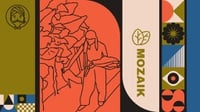tirto.id - Berita pahit itu akhirnya diterima Hardi. Ia sebenarnya sudah mengetahui rencana tersebut sepekan sebelumnya. Namun, pernyataan itu tetap mengguncang 7 anggota DPP yang hari itu dipecat dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Pemecatan diambil secara aklamasi oleh pertemuan DPP Pleno, 4 Agustus 1965. Tekanan untuk menempuh pemecatan sebenarnya lebih banyak datang dari luar partai, termasuk dari Presiden Sukarno yang blak-blakan mengecam PNI karena tidak menindak marhaenis gadungan dan plintat-plintut.
“Inilah tindakan pembersihan besar-besaran pertama sepanjang sejarah PNI, yang merupakan puncak pertikaian panjang antara sayap kiri dan kanan,” catat J. Eliseo Rocamora dalam Nasionalisme Mencari Ideologi: Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946-1965 (1991, hal. 415).
Ketujuh orang yang dipecat itu adalah Hardi, Mohammad Isnaeni, Mhd. Achmad, Sabillal Rasjad, Osa Maliki, Hadisoebeno Sosrowerdojo, dan Karim Mohammad Durjat. DPP mengklaim bahwa mereka dipecat karena melanggar disiplin partai selama lima tahun terakhir. Hardi menilai alasan itu tidak masuk akal, bahkan meyakini pemecatan sudah direkayasa.
“Alasan formal yang dipakai [untuk] pemecatan massal itu sebenarnya hanya soal kecil dan ternyata dibikin-bikin,” tukasnya dalam Api Nasionalisme: Cuplikan Pengalaman (1983, hal. 28).
Langkah pertama Hardi setelah pemecatan adalah menghimpun dukungan yang dinilai mampu melancarkan counter-attack terhadap putusan DPP. Ia menggandeng Hadisoebeno, Ketua Dewan Partai Daerah Jawa Tengah, mantan Gubernur Jawa Tengah, dan sejak awal mengkritisi garis politik Ketua Umum Ali Sastroamidjojo dan Sekretaris Jenderal Surachman.
Enam belas hari sesudah pemecatan “marhaenis-marhaenis gadungan” diumumkan, pengikut setia dan beberapa pimpinan cabang PNI Jawa Tengah yang pro-Hadisoebeno segera mengorganisasi sebuah pertemuan di Banyudono, Boyolali, untuk merumuskan sikap terhadap pemecatan sepihak 4 Agustus 1965. Sebuah surat ditulis dan ditujukan langsung pada Sukarno, memohon intervensi agar kepemimpinan Ali-Surachman dibekukan sementara waktu. Tanggal 22 Agustus 1965, beberapa eksponen PNI Jawa Barat juga menggelar pertemuan di Subang dan mendesak agar kongres luar biasa segera dihelat.
Dua kelompok ini ditambah kelompok kecil lainnya dari Jawa Timur, kemudian bertemu pada 13 September 1965 di Bandung untuk merumuskan strategi bersama. Meski kecil, tetap saja faksi semacam ini membuat pimpinan PNI jengkel. Sebuah tim pengawas internal partai segera dibentuk dan dikirim ke daerah untuk meneliti siapa saja yang terlibat dalam “kelompok Banyudono” dan “kelompok Subang”. Mereka yang kedapatan akan dipecat secara tidak hormat. Hasilnya: lebih dari 150 pimpinan cabang partai di Indonesia ikut dipecat.
Mereka yang dipecat menerima bermacam stigma dan dipersulit dalam berbagai bentuk. Dalam bahasa Jawa, Hardi menyebut orang-orang pecatan PNI sering dikuyo-kuyo, baik oleh bekas partainya, surat kabar, sampai Kapolri yang ikut memerintahkan jajarannya membubarkan kegiatan-kegiatan marhaenis gadungan—pengucilan yang menaruh pecatan-pecatan PNI itu sebagai persona non grata dalam bidang politik, setidaknya sampai 1 Oktober, kala arus balik terjadi secara mendadak dalam sejarah republik.
Birokrat Menyambi Politikus
Dalam ketegangan politik tersebut, nama Hadisoebeno muskil dilepas dari Hardi. Kedua sosok yang dikategorikan sebagai “kubu konservatif” ini merupakan pentolan PNI yang sedari awal menyatakan haluan mereka sebagai nasionalis kanan yang tak ragu memasang kuda-kuda dalam menghadapi manuver Partai Komunis Indonesia (PKI), baik di pusat maupun di daerah. Sikap ini tentunya tidak lahir sekonyong-konyong, melainkan dapat dilacak sejak PKI kembali menyusun kekuatan pada paruh pertama dasawarsa 1950-an, kurun yang sama saat PNI tengah menikmati posisinya di puncak pentas politik nasional.
Sementara Hardi memiliki pamor sebagai anggota DPR fraksi PNI sebelum menjadi Wakil Perdana Menteri I Kabinet Karya, sosok Hadisoebeno tidak terlalu populer dan dikenal terbatas di kalangan partai saja. Menurut Rocamora, Hadisoebeno Sosrowerdojo dilahirkan di Nglorog, Pacitan, 11 Februari 1912 dan menempuh pendidikan MULO dan AMS, sebelum melanjutkan ke Middelbare Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA) Magelang. Dengan menempuh jalur pendidikan itu, jelas Hadisoebeno memilih mata pencaharian sebagai birokrat. Menurut situs Konstituante, birokrat adalah satu-satunya pekerjaan Hadisoebeno yang ia tekuni sejak ia lulus dari MOSVIA pada 1938.
Macam-macam kedudukan yang ia peroleh, mulai dari pegawai negeri biasa hingga mantri polisi. Area kerjanya terbatas di Jawa Tengah, mulai dari Semarang, Weleri, Kendal, Rembang, dan Kudus. Pada 1 Maret 1946 ia menerima penugasan untuk mengepalai jawatan perdagangan dan perusahaan di Pekalongan, merangkap pegawai Kementerian Kemakmuran RI yang kala itu dikepalai Ir. Darmawan Mangoenkoesoemo. Dari sini karier Hadisoebeno naik. Dia diangkat menjadi Wali Kota Semarang pada tahun 1951, wakil ketua PNI Komisariat Jawa Tengah di tahun yang sama, dan resmi menjadi wakil ketua Dewan Partai Daerah Jawa Tengah pada 1953, mendampingi Sarino Mangoenpranoto sebagai ketua.
Pada tahun-tahun sewaktu Hadisoebeno merintis kariernya sebagai birokrat-cum-politikus, keadaan PNI di tingkat nasional sudah mulai mengalami keretakan. Ketika itu, PNI yang diketuai Sidik Djojosukarto ditengarai sebagai partai dengan reputasi buruk, kader-kadernya di pemerintahan terlibat penyelewengan dan korupsi. Lain itu, saling-silang di tubuh partai mengemuka antara faksi nasionalis-radikal yang memusuhi Masyumi dan PSI dengan faksi konservatif yang menganjurkan kerja sama PNI-Masyumi-PSI dalam upaya menghadapi kebangkitan PKI. Faksi nasionalis-radikal yang dipimpin Sidik menyetir PNI agar memajukan program-program antikapitalis dan pro buruh—yang terbukti efektif dipergunakan PKI dalam membangun, memperluas, dan memperkuat basis massa di akar rumput.
Setelah Pemilu 1955, perseteruan antar-faksi makin menguat dan berujung pada percepatan Kongres PNI ke-8 yang seharusnya digelar Desember 1956 menjadi Juli 1956, dengan agenda utama menggeser kedudukan faksi nasionalis radikal, yang saat itu dicerminkan kepemimpinan Sarmidi Mangunsarkoro.
Hadisoebeno yang terpilih sebagai Ketua DPD Jawa Tengah pada Maret 1956, memajukan dukungannya pada faksi konservatif yang kala itu diwakili Wilopo dan Soewirjo. Wilopo dianggap lebih menampakkan kesan “politikus intelektual” yang bergerak di balik layar, sementara Soewirjo mempunyai citra seorang negarawan kawakan yang mengalami jatuh bangun PNI sejak tahun 1930-an.
Lewat pemilihan dalam kongres, 2.655 suara menjatuhkan pilihan kepada Soewirjo selaku ketua umum. Naiknya Soewirjo membuka jalan bagi Hadisoebeno menaiki jenjang kepemimpinan partai sebagai anggota DPP, bersama unsur pimpinan cabang PNI daerah lain.
“Masuknya pemimpin-pemimpin daerah yang kuat seperti Hadisoebeno dan Osa Maliki ke dalam DPP, dan sejumlah wakil daerah yang lebih banyak di Badan Pekerja Kongres menandai puncak perkembangan PNI sejak 1953,” tulis Rocamora (1991, hal. 191).
Menghalau PKI
Menggunakan kapasitasnya sebagai Wali Kota Semarang, kepemimpinan Hadisoebeno di Jawa Tengah sangat kuat dan solid. Corak kepemimpinan ini berkat jejaring PNI yang diperkuat di kalangan birokrat serta konsolidasi PNI di kalangan elite pengusaha dan tuan-tuan tanah yang menyebabkan pendanaan PNI Jawa Tengah relatif stabil dan mapan.
Kendati demikian, corak kepemimpinan tersebut menyebabkan DPD Jawa Tengah cenderung elitis dan kurang memperkuat ormas-ormas yang bernaung di bawah bendera PNI. Kecenderungan ini jelas berbeda dengan PKI, yang selain memperkokoh agen partai di daerah, juga menyuburkan pengaruh lewat ormas maupun organisasi lain yang terafiliasi dengannya.
Dampak langsung kepemimpinan Hadisoebeno yang mengandalkan jejaring elite sebagai penopang partainya baru benar-benar terlihat saat PNI Jawa Tengah harus menelan kekalahan dalam Pemilihan Umum 1957 yang memperebutkan kursi DPRD Jawa Tengah. Dalam analisis Rocamora, setidaknya ada tiga alasan: kampanye yang lesu dan kurang menarik perhatian; rasa puas diri akibat kemenangan PNI dalam pemilihan DPRD Jakarta; dan pemimpin PNI di Jawa Tengah yang tidak berusaha keras karena yakin bahwa PNI akan meraih kemenangan dengan mudah seperti di Jakarta.
Analisis tersebut berbeda dengan penjelasan kekalahan menurut Hadisoebeno. Alih-alih mengintrospeksi dan membuat evaluasi, ia menyalahkan dan menyerang sengit taktik “main kotor” PKI yang dalam kampanye selalu menggambarkan PNI sebagai partai korup dan partai tuan tanah.
Hadisoebeno juga menuding dan menggugat sumber dana PKI yang menurut dugaannya berasal dari “pedagang-pedagang Cina pro-Peking”, “kader-kader yang mempunyai gaji tinggi”, hingga ikut menumpang publikasi dengan meliput kunjungan Presiden Uni Soviet, Kliment Voroshilov. Ia juga menyitir sistem pemilihan umum yang dianggap tidak fair yang menyebabkan orang-orang buta huruf mempunyai hak untuk memilih. Padahal, menurut Hadisoebeno, orang-orang inilah yang “paling mudah dibodohi janji PKI”.
Hadisoebeno kemudian merapatkan barisan dan segera mengeluarkan resolusi dalam Musyawarah Daerah PNI Jawa Tengah pada 31 Agustus 1957. Mulai saat itu, PNI Jawa Tengah tidak bersedia bekerja sama lagi dengan PKI. Langkah ini diikuti keputusan Hadisoebeno menggalang koalisi dengan Masyumi dan Nahdlatul Ulama. Hasilnya, pos-pos strategis dalam kekuasaan legislatif dan eksekutif di Jawa Tengah berhasil diduduki oleh koalisi PNI-Masyumi-NU.
Hadisoebeno meraih posisi Gubernur Jawa Tengah, sedangkan Imam Sofwan dari NU duduk di kursi ketua DPRD. “Aliansi PNI-Masyumi-NU juga berhasil menekan jumlah wakil-wakil PKI di DPRD hingga batas paling rendah,” imbuh Rocamora (1991, hal. 242).
Pendirian pimpinan cabang PNI di daerah-daerah ini, anehnya, bertentangan dengan sikap pemimpin PNI di pusat. Soewirjo yang sejak awal dianggap sebagai pemimpin moderat yang berdiri di luar pertentangan faksi radikal kontra faksi konservatif, nyatanya tak dapat dipegang dalam pendirian terhadap PKI. Suara dari daerah, seperti Hadisoebeno, yang selalu mendukung agar Kabinet Karya memperluas koalisi PNI-NU-Masyumi dalam menghadapi PKI, ditanggapi acuh tak acuh.
Di lain waktu, pendapat Sekretaris Jenderal I.B.P. Manuaba, yang menyerang PKI dan menyatakan PNI siap kerja sama dengan Masyumi, dibantah oleh Soewirjo yang justru menegaskan PNI siap bekerja sama dengan partai manapun, termasuk PKI, apabila dibutuhkan.
Perbedaan sikap pusat dan daerah ini sejatinya mencerminkan persepsi PNI yang terjebak ambivalensi dalam berelasi dengan PKI. “PKI adalah ‘bajingan’ sekaligus ‘pahlawan’, musuh sekaligus sang bijak bestari yang ditakuti sekaligus ditandingi. PKI dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan PNI dan pada saat yang sama, juga sebagai sekutu untuk melawan musuh bersama,” jelas Rocamora (1991, hal. 395-396).
Keadaan menjadi pelik saat PNI yang memasang kuda-kuda untuk melawan PKI, dipaksa satu selimut dengan rivalnya itu dalam politik Nasakom yang mulai digencarkan Sukarno sesudah mengumandangkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, disusul dengan masuknya Indonesia ke dalam periode Demokrasi Terpimpin. PNI yang menyadari kuatnya pengaruh PKI di tingkat pusat, tertatih-tatih mendukung arah baru pemerintahan Sukarno yang mengharuskan pimpinan partai yang konservatif menenggang perasaan demi keselamatan partai dan kepuasan Sukarno.
Kepemimpinan Soewirjo kurang mampu memainkan keseimbangan semacam ini, sehingga ia harus tersingkir dari kursi ketua yang kini diduduki kawan lama Sukarno, Ali Sastroamidjojo berdasarkan pilihan Kongres PNI ke-9, 25 Juli 1960. Hadisoebeno pun terpaksa menelan kekecewaan dengan tergusurnya Soewirjo dari kursi ketua umum.
Sebagai langkah perlawanan, ia memastikan PNI Jawa Tengah menjaga kewaspadaan dengan tidak serta-merta mendukung Ali—langkah yang cukup menyulitkan Ali, mengingat PNI Jawa Tengah memiliki basis massa yang cukup besar. Pilihan ini diambil, mengingat pada tahun Ali diangkat sebagai ketua, Hadisoebeno melepas jabatan gubernurnya untuk digantikan Mochtar, brigadir jenderal KKO yang dianggap lebih menenggang politik Sukarno. Momentum ini juga menandai akhir pengabdian Hadisoebeno sebagai seorang birokrat.
Langkah perlawanan lain yang dilakukan Hadisoebeno dan kelompoknya adalah tindakan simbolik menolak keanggotaan DPR-GR, mendukung sikap netral terhadap Liga Demokrasi, dan diam-diam mendukung Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS)--kelompok aliansi surat kabar yang mendukung tafsir Sukarnoisme menurut Sajuti Melik, dalam polemik panjang melawan Harian Rakjat sepanjang 1964 sampai 1965.
Menghamba Dua Rezim
Pendirian antikomunis Hadisoebeno dan pendukung faksi konservatif lain ditengarai oleh Hardi sebagai sebab utama pemecatan sepihak mereka pada 4 Agustus 1965. Upaya perlawanan mereka menemui aral, sementara PNI semakin berani menunjukkan kemesraan dengan PKI, sampai mengusung jargon yang mengamplifikasi hemat Sukarno bahwa ideologi PNI, Marhaenisme, adalah Marxisme ala Indonesia.
Hanya bertahan dua bulan, angin politik yang berubah pasca G30S melenyapkan gemuruh dalam kampanye PNI yang masif mempromosikan kerja sama dengan PKI. Biduk nasionalis pun terancam karam, massa yang mengejar-ngejar simpatisan PKI mulai menyasar juga pendukung-pendukung PNI.
Melihat arus politik yang berubah amat dahsyat, Ali sebagai ketua umum yang terpilih kembali dalam Kongres PNI ke-10 pada 1963 hanya bergeming dan terlalu lama membaca keadaan daripada mengambil sikap. Situasi inilah yang digunakan Osa Maliki dan Usep Ranawidjaja--pemuka faksi konservatif dari DPD PNI Jawa Barat--untuk mengambil kebijakan sepihak dengan menjauhkan PNI dari tuduhan keterlibatan G30S sekaligus menegakkan kembali marwah faksi konservatif yang dikuyo-kuyo sejak insiden pemecatan.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah PNI, kubu konservatif mengambil tindakan terang-terangan membangun DPP tandingan yang mendukung pembersihan PKI dan mencemooh kubu Ali sebagai “PNI A-Su”, sarkasme yang memelesetkan nama duet Ali-Surachman.

Hadisoebeno jelas menyatakan dukungan pada PNI Osa-Usep. Melalui pengaruhnya yang masih kuat di PNI Jawa Tengah, Hadisoebeno menyatakan dukungannya pada rencana seorang tetua partai, Iskaq Tjokroadisurjo, agar PNI melaksanakan “Kongres Persatuan” yang berhasil digelar di Bandung pada 21-27 April 1966. Kongres ini mengambil putusan yang mendongkel kursi ketua dari Ali dan memilih Hardi sebagai Ketua I dan Hadisoebeno sebagai Ketua IV.
Meski nama Osa Maliki tercantum sebagai ketua umum, kepemimpinan partai secara de facto kini berada di tangan Hardi-Hadisoebeno. Tentu seluruh rangkaian “Kongres Persatuan” itu tak lepas dari intervensi Soeharto yang mempertahankan kekuatan nasionalis, tetapi dengan penyesuaian terhadap politik yang kini disetir oleh Angkatan Darat.
“Dalam pidato pembukaan Kongres, Soeharto mengatakan bahwa pandangan partai ‘harus selalu disesuaikan dengan kehendak rakyat’. Kalau tidak, katanya, ‘...akan dikoreksi rakyat, bahkan akan dibunuh rakyat sendiri.’,” catat Harold Crouch dalam Militer dan Politik di Indonesia (1986, hal. 287). Dengan kata lain, Soeharto tidak akan segan-segan menggebuk PNI jika kubu nasionalis itu coba-coba berseberangan dengan Orde Baru atau berbalik mendukung Sukarno.
Berbeda dengan Hardi yang cenderung blak-blakan dalam menyampaikan pandangan dan sikap politiknya, kepribadian Hadisoebeno hati-hati dan tidak konfrontatif menghadapi penguasa. Selain menjaga keseimbangan ke luar, Hadisoebeno pun menjaga keseimbangan ke dalam, yakni agar kader PNI menjaga jarak dengan “kaum sarungan” (partai-partai Islam yang menghimpun kekuatan santri—red) sekaligus tetap menghormati Sukarno yang Hadisoebeno sebut sebagai “anak Indonesia terbaik dan penggali Pancasila”.
Selain itu, Hadisoebeno juga secara terselubung meminta agar pemerintah meninjau kembali kader-kader dan simpatisan PNI yang ikut terjaring pembinasaan 1965-1966—permintaan yang secara tersirat memohon belas kasihan Soeharto agar membebaskan anggota PNI. Semua tindakan kompromis tersebut, selain menjadi taktik menyelamatkan biduk partai, juga karena Hadisoebeno berharap pada pemilihan umum mendatang PNI dapat mendudukkan seorang kadernya sebagai wakil presiden.
Laku politik Hadisoebeno menjadikan pemerintah tak segan mendorong kader-kader PNI di daerah agar mendukung pencalonannya sebagai ketua umum PNI dalam Kongres ke-12 PNI pada April 1970. Dukungan tersebut disampaikan secara terbuka, sampai-sampai harian partai yang pro-Hardi, Suluh Marhaen, menyampaikan keluhan atas briefing anggota-anggota Opsus pimpinan Ali Murtopo. Menurut Crouch, briefing itu cukup singkat, namun mengandung nada ancaman, dengan mengatakan kepada para anggota delegasi bahwa “Boss menghendaki si anu jadi ketua umum” dan “bila si anu tidak terpilih ketua umum, PNI akan sulit untuk terus hidup” (1986, hal. 290).
Dengan operasi belakang layar itu Hadisoebeno berhasil terpilih sebagai ketua umum PNI pada 12 April 1970. Jabatan itu dipangkunya selama 1 tahun 12 hari, sebelum ia wafat pada 24 April 1971, tepat hari ini 51 tahun lalu.
Penulis: Chris Wibisana
Editor: Irfan Teguh Pribadi