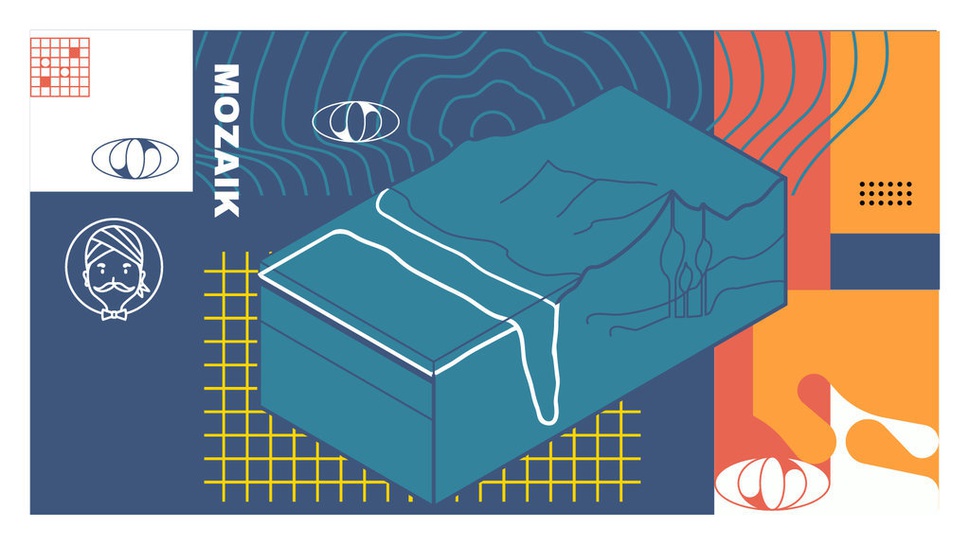tirto.id - 393 tahun yang lalu, tepatnya 1 Agustus 1629 pukul 21.30, sebuah gempa besar dengan magnitudo 8,2 mengguncang Kepulauan Banda, Maluku. Tak hanya membuat tanah retak, gempa ini juga memicu tsunami setinggi 16 meter yang muncul di selat antara Lonthor dan Kepulauan Naira.
Mengutip artikel Unesco, gelombang tersebut sampai ke ke Fort Nassau dan pemukiman di pesisir Banda Neira setengah jam setelah guncangan berhenti.
Meski dilaporkan para nelayan di laut lepas tidak melihat tanda-tanda pasang, kerusakan yang ditimbulkan tidak main-main. Rumah-rumah di pantai hanyut atau hancur. Banyak ikan terlempar ke pantai. Pepohonan tercerabut dari tanah. Benteng Nassau terendam sedalam tiga meter. Pemecah gelombang yang terbuat dari batu hanyut. Bahkan meriam seberat 1,5 ton pun terseret sejauh 11 meter.
Gempa besar ini juga dirasakan sampai Ambon--yang jaraknya mencapai 230 kilometer. Namun di sana tidak dilaporkan adanya tsunami.
Menurut artikel jurnal dari Zac Yung-Chun Liu dan Ron A. Harris, peristiwa ini diikuti oleh setidaknya aktivitas seismik--yang bisa diartikan sebagai gempa susulan--selama 9 tahun. Menurut para peneliti, gempa ini berjenis megathrust dan bersumber dari Palung Seram. Gempa megathrust adalah gempa yang berasal dari zona tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia.
Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 1674, Laut Banda kembali diguncang gempa dangkal--yang juga memicu tsunami setinggi 80 hingga 100 meter. Kala itu, jumlah korban jiwa di Ambon mencapai 2.243 orang.
Sepanjang sejarah, sekitar 67 persen tsunami terjadi di Indonesia timur, dan salah satunya berada di sekitar Laut Banda. Mengapa hal ini dapat terjadi?
Patahan Besar di Laut Banda
Laut Banda memiliki luas sekitar 470 ribu kilometer persegi. Ia terpisahkan dari Samudra Pasifik oleh pulau dan lautan seperti Pulau Ambon, Maluku, Buru, serta Laut Seram dan Halmahera. Di bagian selatannya terdapat Pulau Wetar, Babar, Alor, Timor, dan Tanimbar. Di timur terdapat Pulau Aru. Sementara di barat ada Pulau Wakatobi.
Tempat ini telah lama menarik perhatian para ilmuwan, salah satunya adalah P. M. van Riel. Ia diberi tugas oleh pemerintah Hindia Belanda untuk memetakan dasar lautnya dalam program yang dinamakan Ekspedisi Snellius (1929-1930). Salah satu temuannya adalah palung sedalam 7.440 meter dengan luas 50 ribu kilometer persegi, yang kemudian diberi nama Palung Weber. Ditemukan pula beberapa lubuk seperti Lubuk Banda Utara (kedalaman 5.800 meter) dan Lubuk Banda Selatan (5.400 meter).
Jika palung layaknya jurang, lubuk berbentuk cekungan yang sangat luas.
Para peneliti asal Denmark juga pernah meneliti Laut Banda lewat Ekspedisi Galathea yang dilakukan pada 1951. Dari sampel yang diambil di kedalaman 7.280 dan 6.580 meter, mereka menemukan berbagai jenis teripang, cacing, krustasea, dan hewan-hewan lain. Mereka semua hidup dalam gelapnya palung laut.
Dari 1973 sampai 1988, sebuah proyek raksasa bernama SEATAR menyimpulkan bahwa perairan bagian timur Indonesia secara umum punya bentang topografi yang kompleks. Ditemukan bahwa Lempeng Pasifik terus bergeser ke arah barat dan membentur Pulau Halmahera dan Sulawesi, membuat dasar laut menampilkan wajah beragam, mulai dari laut dangkal, palung, hingga gunung api bawah laut.
Setelahnya para peneliti terus berusaha menguak misteri tempat tersebut, terutama Palung Weber. Palung Weber menarik karena meski telah ditemukan sejak puluhan tahun belum ada satu pun yang berhasil menjawab mengapa ia bisa begitu dalam.
Selain itu Palung Weber juga unik. Palung laut biasanya terbentuk di zona subduksi, yaitu tempat dua lempeng besar kerak samudra bertabrakan. Satu kerak ditarik ke bawah, ke dalam mantel bumi. Proses ini membuat palung cenderung menyerupai huruf v. Tapi Palung Weber justru berada di lembah cekungan raksasa dengan bentuk seperti busur.
Pertanyaan besar tersebut baru terjawab pada 2016 lalu oleh penelitian yang dilakukan tim gabungan dari Australian National University (ANU) dan Department of Earth Sciences Royal Holloway University of London. Riset geolog Jonathan M. Pownall, Robert Hall, dan Gordon S. Lister ini diterbitkan di jurnal Geological Society of America dengan judul "Rolling open Earth’s deepest forearc basin" (2016).
Lewat analisis terhadap peta resolusi tinggi Laut Banda, peneliti menemukan bahwa pada bebatuan di dasar laut itu terdapat luka dengan pola lurus dan paralel. Mereka kemudian membangun hipotesis bahwa luka itu adalah bukti bahwa Palung Weber terbentuk ketika sepotong kerak bumi koyak. Mereka menyebut kerak yang koyak itu lebih besar dari wilayah Belgia.
Tempat robekan-robekan itu ditemukan kemudian disebut "Detasemen Banda". Detasemen diperkirakan mewakili robekan seluas lebih dari 60 ribu kilometer persegi.
Bahkan saat tim berlayar di wilayah Laut Banda, mereka mengidentifikasi bentang alam yang menonjol di air sebagai bagian dari patahan Detasemen Banda. "Saya tertegun melihat bidang patahan yang dihipotesiskan. Kali ini bukan di layar komputer, tetapi menyembul di atas ombak," kata Pownall dari ANU.

Dengan bantuan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), para peneliti dari Institut Teknologi Sepuluh November pernah melakukan studi tentang perkiraan dampak tsunami di sekitar Palung Weber.
Menurut penelitian tersebut, bila terjadi gempa yang bersumber pada aktivitas di Palung Weber, daerah paling awal yang terkena gelombang tsunami adalah Seram bagian Timur. Gelombang tsunami kemudian menjalar sampai sekitar wilayah Maluku. Gelombang besar diperkirakan menyapu daerah sekitar Kabupaten Tual dengan ketinggian 7,71 meter.
Perbedaan tinggi dan penjalaran gelombang masing-masing dipengaruhi oleh jarak pusat gempa.
Berbagai penelitian mengenai potensi gempa besar dan tsunami dari dasar Laut Banda tentu saja perlu direspons secara aktif. Pemerintah harus membuat program mitigasi bencana dan mempersiapkan segala kemungkinan agar jumlah korban jiwa bisa ditekan sekecil mungkin.
==========
Artikel ini terbit pertama kali pada 5 Oktober 2018 dengan judul "Gempa & Tsunami Dahsyat Mengintai dari Patahan Dasar Laut Banda". Redaksi melakukan penyuntingan ulang dan menayangkannya kembali untuk rubrik Mozaik.
Editor: Windu Jusuf & Rio Apinino