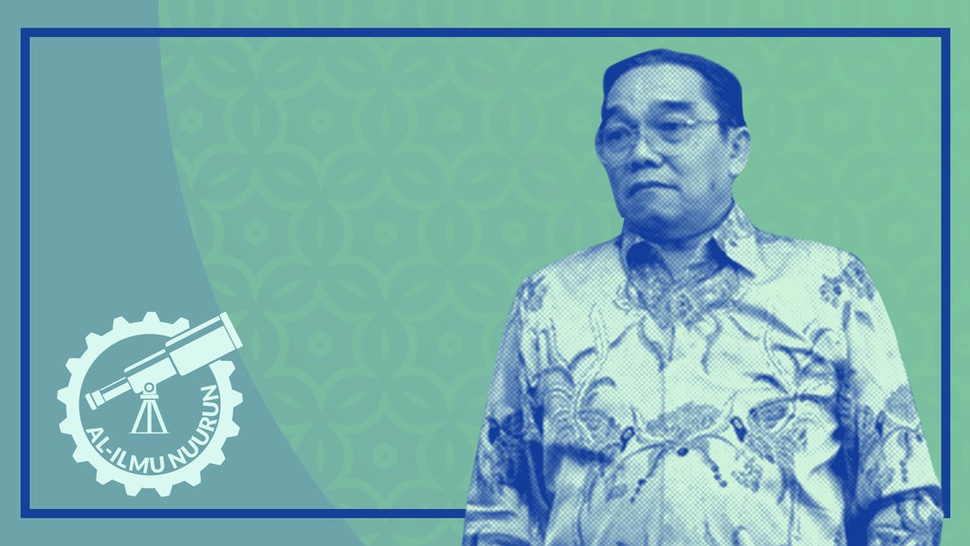tirto.id - Tak ada yang lebih membuat Djohan Effendi bersedih, kecuali pertentangan dan konflik atas nama agama di Indonesia. Di tanah kelahirannya, tempat ia tumbuh dan berkembang dalam spektrum identitas yang luas—termasuk keragaman di lingkup keyakinan yang Djohan pegang sejak akil balig: Islam.
Ia kecewa sekaligus marah dengan aksi penyerangan pemukiman komunitas Ahmadiyah di Lombok timur hingga utara, pada akhir tahun 1998 dan pertengahan 2001. Kasus-kasus serupa juga terjadi di Parung, Bogor (2005) dan Sukabumi (2008). Ada yang meninggal, banyak yang luka-luka.
Sementara itu, pada 29 Juli 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kian memperkeruh situasi dengan kembali mengeluarkan fatwa sesat untuk aliran Ahmadiyah.
Djohan menuangkan kegelisahannya dalam esai yang diunggah ulang di laman Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) pada April 2009. Tulisan tersebut awalnya ditulis di laman A. Umar Said. Ia mengutip jeritan penderitaan warga Ahmadiyah Lombok, selaku bagian dari penduduk Republik Indonesia, yang harus terusir dari kampung halaman demi sepotong rasa aman.
Ia secara tegas menyebutnya sebagai “tragedi kemanusiaan”. Sebagai salah satu pegiat Islam inklusif, plural, dan liberal paling konsisten di tanah air, ia mengkritik negara yang gagal melindungi para korban. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilanggar, juga hak-hak sipil warga Ahmadiyah selaku warga negara.
“Larangan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing sangatlah memerihkan hati seorang penganut agama dan kepercayaan apapun. Larangan seperti ini adalah sebuah pemerkosaan hati nurani yang menyebabkan derita batin yang tak terperikan.”
Lintas Organisasi dan Pemikiran
Luthfi Assyaukanie dalam bukunya Islam and the Secular State in Indonesia (2009) mencatat Djohan sebagai salah satu pelopor gerakan pembaruan Islam sejak dekade 1970-an bersama intelektual lain seperti Nurcholis Madjid, M. Dawam Rahardjo, dan Ahmad Wahib. Keempat sosok tersebut tergabung sebuah kelompok diskusi bernama Limited Group yang berbasis di Yogyakarta.
Mereka membicarakan masalah-masalah yang berkait an dengan agama, budaya dan masyarakat. Kawan lain yang kerap ikut diskusi adalah Kuntowidjojo, Syu'bah Asa, Kamal Muchtar, Wadjiz Anwar, Saifullah Mahyuddin, Djauhari Muhsin, Simuh dan Muin Umar.
Anggota-anggota kelompok Limited Group ini juga yang menjadi poros utama pemikiran-pemikiran progresif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Tengah. Djohan aktif menggodok pemikiran tokoh-tokoh muslim hingga yang sekuler di kelompok tersebut selama berkuliah di IAIN Sunan Kalijaga.
Djohan bergabung dengan HMI pada awal tahun 1965, era di mana politik elite maupun akar rumput Indonesia sedang panas-panasnya. Mulanya karena simpati sebab HMI getol diserang oleh CGMI (underbow PKI) dan GMNI (underbow PNI). Ia terpanggil untuk membela kawan-kawannya.
HMI adalah organisasi yang kian mematangkan pemikiran Islam yang bercorak plural dan liberal ala Djohan. Namun karakternya yang terbuka, toleran serta berani membela kelompok minoritas yang tertindas juga dibangun berkat persinggungan dengan beragam organisasi ke-Islam-an lain sejak usia remaja.
Ahmad Gaus A.F. mengulasnya dengan cukup komprehensif dalam buku yang jadi salah satu rujukan utama memahami isi kepala Djohan, Sang Pelintas Batas: Biografi Djohan Effendi (2009).
Djohan lahir pada tanggal 1 Oktober 1939 di Kandangan, sebuah kecamatan sekaligus ibukota kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berjarak sekitar 135 km di sebelah utara Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Sejarah mencatat orang Banjar selalu dikaitkan dengan pemberontakan seorang tokohnya, Ibnu Hajar, yang ingin mendirikan negara Islam. Djohan memahami hal ini, tetapi juga tidak larut karena juga menyerap beragam pemahaman tentang Islam yang lahir di Jawa maupun Sumatera yang lahir pada masa pergerakan kebangsaan.
Organisasi Islam pertama yang membuat Djohan kecil kagum adalah Masyumi. Jelang Pemilu 1955, misalnya, ia aktif mengikuti pawai Masyumi. Namun, ia juga tetap memuliakan tokoh-tokoh nasionalis, seperti menyimak pidato-pidato Soekarno di rapat-rapat umum yang berisi ajakan menentang pendirian negara Islam.
Memasuki masa remaja, Djohan berganti simpatik pada PERSIS sebab kagum saat membaca buah-buah pemikiran salah satu tokohnya, Ahmad Hassan Bangil atau A. Hassan Bandung. Saking tertariknya, ia sempat menghubungi PERSIS dan mengajukan permohonan jadi anggota. Sayangnya rencana ini tak menemui realisasi lanjutan.
Ketertarikannya pada PERSIS berkurang usai Djohan menamatkan pendidikan di PGAP Banjarmasin pada tahun 1957 dan berangkat ke Yogyakarta untuk studi lanjut di Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN).
Djohan yang mulai bertemu dengan ilmu-ilmu lain, termasuk sains dan terutama filsafat mengalami perubahan pemikiran. Ia mulai berpandangan bahwa segala sesuatu “harus disertai kearifan, dan itu berkaitan dengan konteks sosial, ruang, dan waktu yang lentur". Djohan makin cair dan mengalir dan tak mau terkungkung oleh pandangan tertentu mengenai agama. Sebab menurutnya, “agama bukan penjara, agama adalah sarana evolusi diri mencapai pencerahan tanpa batas.”
Sekembalinya ke Kalimantan Selatan, ia tak hanya aktif bekerja di Kerapatan Qadhi, tetapi juga mengajar SMA Negeri Amuntai. Di sekolah menengah itu ia dekat dengan para siswa, hingga akhirnya dimintai bantuan saat mereka ingin mendirikan Pelajar Islam Indonesia (PII) cabang Amuntai. Ia menjadi penasihat organisasi tersebut.
PII otomatis menjadi organisasi kesekian yang dijajaki Djohan. Ia kemudian turut aktif dalam kepengurusan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), underbow Masyumi, hingga akhirnya dibubarkan menyusul pembubaran Masyumi oleh Soekarno.

Tak Kenal Maka Tak Sayang Ahmadiyah
Mengenai Ahmadiyah, Djohan memang sudah lama mengenalnya dengan baik. Perkenalan pertama terjadi saat Djohan masih menempuh PHIN. Ia sempat belajar filsafat, khususnya perdebatan antara Ibnu Rusyd dan AL-Ghazali. Efeknya pernah mencapai tahap yang signifikan: Djohan hampir jatuh ke jalur agnotisisme—dan Ahmadiyah menyelamatkannya.
“Dalam suasana batin yang terombang-ambing Djohan menemukan bahan-bahan bacaan yang diterbitkan oleh Ahmadiyah yang—terlepas dari doktrin keahmadiyahannya—menawarkan pendekatan yang memadukan penafsiran rasional dan penghayatan spiritual dalam keberagamaan,” tulis Ahmad Gaus.
Buku-buku yang Djohan baca membuatnya tersadar bahwa selama ini ia hanya tahu tentang Ahmadiyah dari buku-buku polemis yang dibuat oleh kalangan yang menentangnya. Pandangannya mengenai isu-isu yang menjadi materi polemik pun menjadi tidak seimbang dan lebih berpihak secara buta.
“Di Yogyakarta, ia punya kesempatan untuk membaca sendiri literatur Ahmadiyah dari sumber primer. Lebih dari itu Djohan juga bergaul dengan pemuka-pemuka Ahmadiyah dan menyaksikan kehidupan mereka yang religius, tulus dan bersih. Yogyakarta waktu itu merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya Ahmadiyah secara pesat.”
Salah satu alasan utama yang membuat Djohan suka membaca literatur dari tokoh Ahmadiyah adalah semangat dan gaya tulisannya tidak melulu romantisme akan masa lalu, tetapi cenderung apologis serta menunjukkan kelebihan Islam dibanding agama-agama dan ideologi-ideologi modern.
Perkenalan kedua terjadi pada awal 1960-an, ketika Djohan kembali melanjutkan studi di UIN Suka. Djohan memilih sering titip absen, lalu pergi ke berbagai perpustakaan di Yogyakarta. Di sana ia mereguk lebih banyak lagi pemikiran tokoh-tokoh Ahmadiyah.
Kekagumannya kian tumbuh dengan mengikuti pengajian tafsir Alquran tiap minggu pagi yang diampu oleh Muhammad Irshad, tokoh Ahmadiyah Lahore. Djohan simpatik sebab pengantarnya memakai bahasa Inggris, sehingga terasa lebih modern.
Meski mendalami betul, Djohan tidak tertarik dan menganut teologi Ahmadiyah berkaitan dengan paham kedatangan Isa al-Masih dan Imam Mahdi yang menjadi akar tunjang dari keahmadiyahan baik Qadyan maupun Lahore. Ia lebih banyak menyerap saripati nilai-nilai kebaikan yang mewujud dalam Islam yang inklusif dan punya dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Persinggungannya dengan Ahmadiyah membuatnya mampu “mengembangkan keberagamaan yang seimbang antara penalaran dan penghayatan” dan “komitmen kepada nilai dan bukan kepada lembaga”. Ia makin arif terhadap bagaimana menjalankan keyakinan sendiri, juga bagaimana kontak dengan penganut keyakinan lain seharusnya tidak berakhir dengan petaka.
Mengapa?
Sebab Djohan “memandang komunitas-komunitas keagamaan, apapun, mengandung nilai-nilai positif yang bisa dijadikan pelajaran. Bagi Djohan, semua agama dan keyakinan hidup adalah mata air kearifan untuk mencapai pencerahan kehidupan manusia.”
Djohan meninggal di Geelong, Australia, pada 17 November 2017, pada usia 78 tahun. Cita-citanya ingin meninggal di Indonesia tak kesampaian.
Meski telah tiada, idenya tentang Islam yang inklusif dan toleran masih bergerilya. Ia pun menginspirasi generasi muslim baru yang memandang perdamaian antar-umat beragama di tanah air adalah segala-galanya.
====================
Sepanjang Ramadan hingga lebaran, redaksi menyuguhkan artikel-artikel yang mengetengahkan pemikiran para cendekiawan dan pembaharu Muslim zaman Orde Baru dari berbagai spektrum ideologi. Kami percaya bahwa gagasan mereka bukan hanya mewarnai wacana keislaman, tapi juga memberi kontribusi penting bagi peradaban Islam Indonesia. Artikel-artikel tersebut ditayangkan dalam rubrik "Al-Ilmu Nuurun" atau "ilmu adalah cahaya".
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti