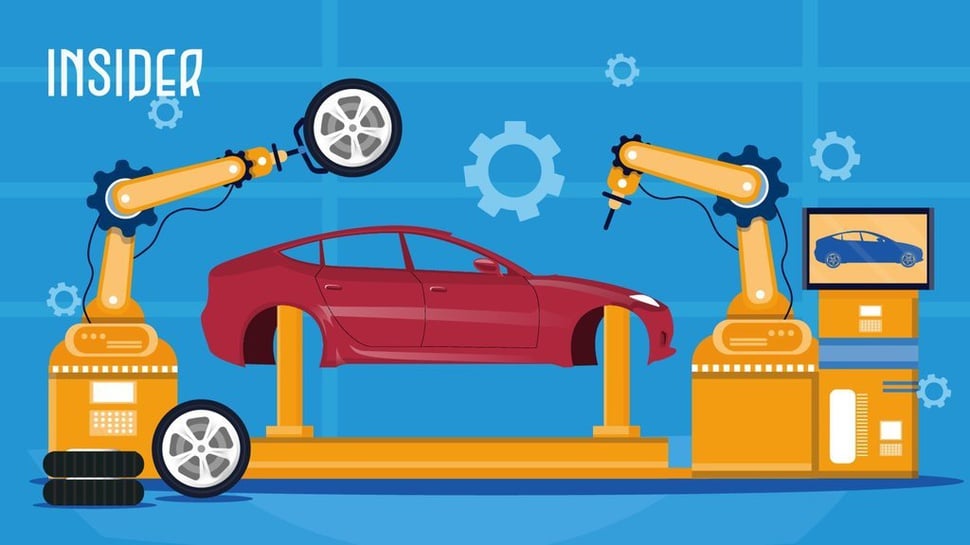tirto.id - Dalam lima tahun terakhir, industri otomotif bergeliat dengan kehadiran beberapa pemain baru. Ketertarikan para pemain tersebut didorong oleh biaya tenaga kerja yang murah dan rasio kepemilikan kendaraan di Indonesia yang cukup rendah, yakni 99 unit per 1.000 penduduk. Sementara itu, Malaysia di angka 490 unit, Thailand 275 unit, dan Singapura 211 unit per penduduk.
Dari sisi ekspor, produk otomotif juga tergolong komoditas “seksi” dan vital bagi pertumbuhan ekonomi Tanah Air. Musababnya, dengan volume ekspor yang kecil, nilai yang disumbangkan cukup signifikan. Hal inilah yang mendorong otomotif masuk ke dalam sektor prioritas pada Rencana Pertumbuhan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Otomotif termasuk produk ekspor non-migas yang masuk kategori 5 besar,” ungkap Rospitawati dari Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur Kementerian Perdagangan dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Indonesia Auto Dynamics yang diselenggarakan Tirto.id di Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Mirisnya, geliat positif tersebut tidak tercermin pada data penjualan. Selama hampir satu dekade, industri otomotif justru “sendu” karena sejak 2013 penjualan mobil domestik bertahan di angka 1 juta unit per tahun.
Tahun 2024, bahkan capaiannya diprediksi menurun dibandingkan tahun 2023. Tak hanya itu, target pemerintah untuk mencapai penjualan tahunan di angka 2 juta pada 2030 sepertinya akan terhambat.
Stagnasi ini timbul sebagai buah dari infrastruktur regulasi yang belum optimal untuk menopang pertumbuhan industri otomotif. Regulasi yang ada saat ini umumnya berfokus untuk mendukung sektor hulu dan melindungi hilir. Akan tetapi rantai pasok di tengah, kurang cukup mendapat perhatian dan perlindungan.
Salah satu dampak dari minimnya atensi tersebut adalah kasus-kasus pembatasan distribusi dengan dalih perjanjian eksklusifitas (keagenan). Dalam beberapa tahun terakhir pemain retail di industri otomotif menyebut bahwa terdapat klausul eksklusivitas dalam perjanjian.
Klausul ini melarang investor untuk mendirikan usaha sejenis yang menjual merek berbeda. Kondisi ini tentu berbeda dengan praktik dahulu yang mendorong persaingan sehat dan membuka peluang kerjasama dengan berbagai merek.
Praktik ini diamini oleh salah satu distributor mobil yang menyebut bahwa pada periode dahulu, distributor tidak dikekang dan diberikan kebebasan untuk distribusi merek apapun. Namun kini, pola yang diterapkan adalah eksklusif hanya mendistribusi satu merek saja. Bahkan, limitasi tersebut hingga membatasi pemegang saham dari badan usaha distribusi untuk mendirikan badan usaha distribusi yang menjual merek lain.
“Dealer agreement-nya beda dengan yang sekarang kalau yang sekarang sama sekali gak boleh,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya kepada Tirto.id pada Rabu (4/9/2024).
Pandangan yang sama juga disampaikan oleh pihak pemegang merek yang mengiyakan bahwa perjanjian eksklusifitas memang dipilih untuk mengembangkan usaha mereka.
“Kalo dari sisi APM (agen pemegang merek) memang maunya kan eksklusif. Semua potensi larinya ke brand kita, semua penginnya gitu untuk mengembangkan usaha masing-masing,” jelas sumber yang enggan disebutkan namanya kepada Tirto.id pada Rabu (4/9/2024).
Keterbatasan Kebijakan
Pembatasan ini tentunya berlawanan dengan asas kompetisi yang sehat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999).
Pasal 19 menyebut pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:
menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
Ironisnya, ketika situasi pembatasan usaha ini muncul dalam perjanjian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkesan tidak dapat langsung bertindak sebagai mediator.
“Jadi memang saat ini, salah satu kelemahan dalam penerapan persaingan usaha di Indonesia adalah beleid dan dasar tindakan KPPU yang lebih berpedoman pada kepentingan masyarakat,” jelas Mulyawan Ranamanggala, Direktur Ekonomi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pada Rabu.
Lebih lanjut, Mulyawan mengakui indikasi atau praktik anti-kompetitif yang tidak terbukti merugikan kepentingan umum belum cukup kuat untuk membuat KPPU bertindak.
“Kalau misalnya ternyata dari perjanjian eksklusivitas itu sebenarnya tidak merugikan kepentingan umum, masyarakat tidak dirugikan, tidak jadi concern bagi KPPU,” imbuh Mulyawan.
Meskipun demikian, distributor yang merasa dirugikan tetap didorong untuk memberikan laporan ke KPPU sebagai bentuk informasi awal. Laporan tersebut kemudian akan masuk tahap penelitian dan pengkajian. Namun, ini membutuhkan waktu yang cukup lama.
“Yang akan jadi kendala itu adalah waktu, karena memang kalau penelitian atau kajian itu bisa lama sekali. Bisa bertahun-tahun, bisa berbulan-bulan,” ujar Mulayawan.
Pandangan minimnya keberpihakkan KPPU pada pelaku usaha turut disampaikan oleh Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Ikhwan Primadani.
“KPPU juga harus memahami POV (point of view) pelaku industri, supaya dia ngerti. Dia harus menggunakan mindset pelaku pasar,” tegas Ikhwan.
Pembentukan UU No. 5/1999 pada dasarnya mengusung prinsip persaingan yang sehat, adil, dan tidak monopolistik. Namun sayangnya, pengimplementasiannya belum optimal, padahal undang-undang ini seharusnya menjadi payung hukum yang dapat melindungi para pelaku usaha dalam persaingan bisnis yang setara.

Perlindungan Usaha di Negara Lain
Berbeda dengan Tanah Air, aturan persaingan usaha di negara-negara asal produsen mobil kenamaan dunia memiliki aturan yang tegas, seperti Jepang dan Uni Eropa.
Di Negeri Sakura, Japan Fair Trade Commission (JFTC) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan aturan persaingan usaha berdasarkan Anti-Monopoly Act (UU Anti-Monopoli). Undang-undang ini melarang praktik-praktik yang membatasi persaingan, termasuk perjanjian eksklusivitas yang menghalangi peluang distribusi bagi pesaing dan mempersempit ruang masuk pasar bagi pemain baru.
Jika perjanjian eksklusivitas dinilai menghambat kompetisi dan merugikan pasar, tindakan tegas akan diambil oleh JFTC untuk melindungi kepentingan bisnis yang lebih luas, termasuk pemain kecil di rantai pasok. Dengan pendekatan ini, Jepang memastikan adanya perlindungan di setiap tingkatan rantai distribusi, termasuk dari potensi dominasi pemain besar.
Sementara itu di Uni Eropa merujuk pasal 101 ayat 1 dari Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) disebutkan mengenai pelarangan perjanjian antara perusahaan yang berpotensi memengaruhi perdagangan antara negara anggota.
Kemudian jika perjanjian tersebut mencegah, membatasi, atau mendistorsi persaingan dalam hal harga jual dan beli, pembatasan produksi, investasi, pangsa pasar dan pasokan. Jika kondisi ini terbukti, maka perjanjian akan secara otomatis dibatalkan.
Japan External Trade Organization (JETRO) dan Eurochamber menjadi organisasi yang berperan memfasilitasi investasi dan perdagangan antara perusahaan/institusi dari Indonesia dengan Jepang dan Eropa. Kedua organisasi tersebut juga mengadvokasi regulasi yang efisien untuk menciptakan kerjasama yang lebih efisien.
Terkait dengan penerapan UU persaingan usaha lintas negara, baik pihak JETRO dan Eurocham enggan memberikan tanggapan. Pihaknya beralasan bahwa lembaga mereka bukanlah pihak otoritas yang tepat untuk dimintai keterangan, karena di luar kewenangan utama mereka.
Lebih lanjut, sejatinya baik di Jepang maupun Eropa, regulasi yang ada menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis besar dan perlindungan bagi pelaku usaha kecil serta konsumen. Pembatasan perjanjian eksklusivitas menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap entitas dalam rantai pasok mendapatkan kesempatan yang adil, sekaligus mencegah praktik-praktik yang dapat menimbulkan dominasi di pasar.
Belajar dari Jepang dan Uni Eropa, pemerintah Indonesia tampaknya perlu tegas melakukan penegakan terhadap peraturan perundangan yang telah berlaku. Aturan dasar persaingan usaha, yakni UU No.5/1999 khususnya pasal 19, dengan jelas telah melarang pemaksaan pembatasan usaha yang dapat membatasi aktivitas penjualan dan dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
Jika ditilik lebih lanjut, diberlakukannya perjanjian eksklusivitas oleh para pemegang merek di Indonesia merupakan sebuah ironi. Pasalnya di negara asalnya, pemberlakuan perjanjian eksklusivitas justru sangat ditentang, sehingga pihak-pihak yang tidak tunduk kepada larangan tersebut dapat ditindak dengan tegas.
Sama halnya dengan yang dilakukan pada Jepang dan Uni Eropa, dasar aturan ini harusnya sudah mampu untuk melarang pihak pelaku usaha melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat, terutama yang berkaitan dengan perjanjian eksklusivitas di industri otomotif.
Pemerintah, KPPU, dan unsur lainnya harus bersinergi untuk mengamankan persaingan usaha, tidak hanya soal konsumen, tetapi juga pelaku usaha dari hulu hingga hilir.
Di sisi lain, juga terdapat kebutuhan untuk lembaga baru, setingkat Badan, yang memang khusus mendampingi pelaku usaha sebagai integrator yang menghubungkan para pemangku kepentingan.
“Dibutuhkan lembaga baru (setingkat Badan) yang memang khusus mengurus industri otomotif mendampingi Gaikindo dan AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia), seperti halnya SKK Migas atau BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol). Lembaga baru ini tidak hanya diisi oleh pemerintah, tapi juga pelaku industri dan stakeholder otomotif,” ungkap Andrea, dari APINDO, pada Rabu.
Industri otomotif adalah sektor yang penting dan strategis, dengan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang kuat, konsisten, berjangka panjang, holistik, berkelanjutan, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pasar
Editor: Tim Media Service