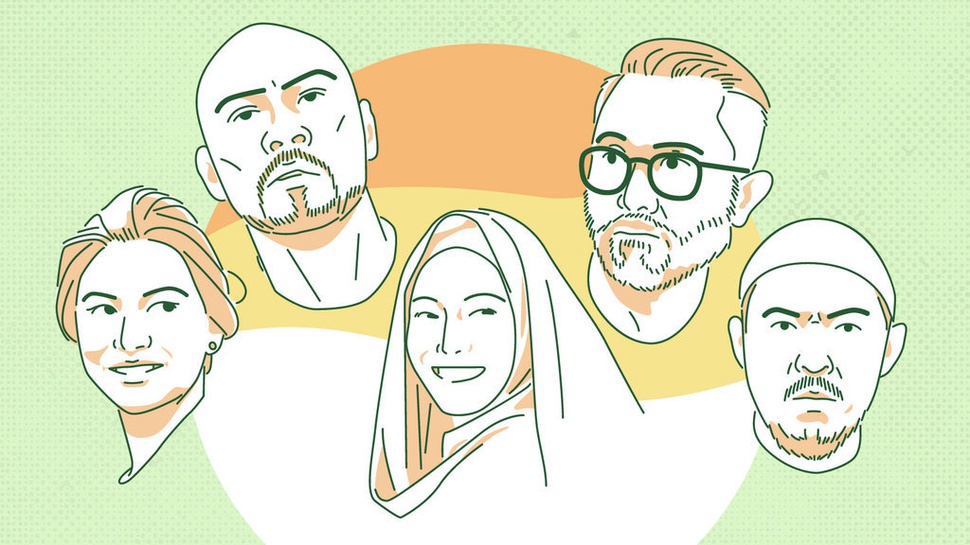tirto.id - “Apa yang paling sering disalahpahami orang Indonesia tentang Buddhisme?” tanya saya.
“Konsep Ketuhanannya. Sering kali orang-orang ketika mengkaji konsep ketuhanan Buddhisme masih sering membawa konsep tuhan Samawi, konsep tuhan Abrahamik, yang sangat personal. Jelas enggak masuk,” jawab El, aktivis pembela kelompok rentan di Yogyakarta, yang pindah ke Buddhis dari Islam pada 2017.
Penganut Buddhisme, sederhananya, tidak percaya konsep Tuhan yang memiliki sosok seperti pada agama Abrahamik.
“Kami mengaku ada ketuhanan. Kami mengakui suatu energi besar di mana kami harus kembali ke situ. Kami mengakui ada sesuatu yang kekal, mengakui ada sesuatu yang tidak tercipta, mengakui ada sesuatu yang beyond everything,” jelas El. “Tapi bukan berarti Dia mengatur, bukan berarti Dia menciptakan, bukan berarti Dia sosok yang kita sembah.”
Pindah agama dari kelompok agama mayoritas ke kumpulan minoritas membikin El mafhum rasanya disalahpahami. Di Indonesia, Buddha termasuk “agama resmi” yang penganutnya sedikit, cuma 0,16 persen atau 1,5 juta jiwa dari total penduduk, menurut sensus agama terakhir pada 2010.
Meski tak ada data resmi, kebanyakan anak-anak Buddhis belajar tentang agamanya di rumah sendiri sebab minim diajarkan di sekolah, tak seperti pendidikan Islam atau Kristen. Wajar belaka jika serba-serbi muslim lebih sering menjadi pengetahuan umum ketimbang Buddhisme.
Menjadi minoritas juga mengajari El untuk bersikap lebih kompromi.
Pernah satu kali wihara tempatnya beribadah didatangi seorang bapak, tetangga di lingkungan sekitar, yang mengamuk dengan dalih mobilnya baret, menuduh pelakunya adalah salah satu jemaat wihara. Terjadi cekcok. Si tetangga itu membawa pukulan besi. Salah satu kawan El terluka tangannya.
Singkat cerita, tuduhan itu tak bisa dibuktikan tapi Pak RT yang melerai meminta wihara memberi uang ganti rugi dan memasang CCTV agar kejadian serupa tak terulang. Alasan Pak RT, “pihak wihara mengalah saja daripada ribut-ribut.”
Dari lubuk hati, El tahu penyelesaian itu tidak adil. Tapi, kebanyakan kawannya dan jemaat akhirnya setuju dan legawa. “Seringkali teman-teman itu beranggapan, ‘Sudahlah enggak usah macam-macam. Kita minoritas ini’.”
“Kebanyakan juga takut berujung kayak kasus Ibu Meiliana yang di Sumut itu, takut wihara sampai dibakar,” kenang El merujuk peristiwa kekerasan berbalut agama di Tanjungbalai pada 2016.
Lantas, apakah perasaan inferior ini muncul karena tekanan mayoritas? Muncul sebagai siasat bertahan?
“Bisa jadi memang konsep inferior dan enggak umbar-umbar itu karena tekanan mayoritas. Aku enggak bisa bilang gitu karena aku enggak punya data banyak. Tapi, ada potensi itu. Bisa jadi,” terka El.
Situasi mementingkan harmoni dan mengorbankan banyak hal membikin El masih merahasiakan identitasnya sebagai Buddhis kepada keluarga. “Aku enggak mau menciptakan chaos. Karena kabar itu pasti akan jadi chaos di keluargaku,” tambahnya.
Menurut El, diskusi tentang mayoritas dan minoritas itu seharusnya bisa ditengahi media dengan cara lebih dingin. “Media kita belum banyak yang bijak meliput topik begini, makanya kelompok minoritas makin inferior, bahkan cenderung enggak merasa aman,” ujarnya.
Salah satu faktor yang membuat situasi macam itu langgeng adalah logika mayoritas yang sering kali dipakai media untuk menghakimi kelompok minoritas, menurut El.
Menulis Sensasional
Dua bulan belakangan isu pindah agama kembali jadi kepala berita. Dua selebritas menjadi pemantiknya. Pembawa acara Deddy Corbuzier masuk Islam, tak lama kemudian selebgram Salmafina Sunan dikabarkan memeluk Kristen.
Akun @_jadigini dan peneliti media Wisnu Prasetya melakukan riset kecil-kecilan terkait pemberitaan pindah agama itu. Sampelnya 10-15 berita yang diambil secara acak selama sepekan.
Temuannya, media-media daring memberitakan Salmafina dengan kata kunci “kontroversi”, “terbongkar”, dan “pengakuan”. Salmafina digambarkan negatif seakan tindakannya keliru, bahkan masa lalu dan pilihannya melepas jilbab jadi sorotan.
Sementara Corbuzier digambarkan sosok yang “mendapatkan hidayah” bukan karena pengaruh orang lain dengan kata kunci “orang baik”,“hidayah”, dan “bela kaum marjinal”. Ia dibingkai sebagai orang merdeka dan berhak menentukan pilihannya sendiri.
Dugaan Wisnu, media sengaja menjual sensasi dari berita itu karena selalu berhasil mengundang jumlah trafik.
“Isu agama sedang dan masih lama akan jadi isu sensitif di Indonesia,” kata Wisnu. “Menulis berita pindah agama dengan cara sensasional hanya akan memberikan amunisi bagi kelompok-kelompok konservatif agama.”
Dampak dari pemberitaan macam itu bisa besar, menurut Wisnu. Berita pindah agama yang sensasional “meskipun bisa jadi tidak politis dan hanya menulis for the sake of sensationalism itu sendiri” bisa menjadi lahan kering yang mudah dibakar, tambahnya.

Media Memberitakan Pindah Agama: Boleh atau Tidak?
Lalu, apakah solusinya media dilarang menulis cerita pindah agama?
Komisi Penyiaran Indonesia melalui Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran mengatur agar media tidak menyiarkan berita soal alasan kepindahan agama seseorang. Pasal 7d berbunyi: Tidak menyajikan alasan perpindahan agama seseorang atau sekelompok orang.
Aturan itu berlaku buat media televisi dan radio. Sementara untuk media cetak/daring belum diatur di Dewan Pers, sebatas menyangkut SARA: Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan SARA serta menganjurkan tindakan kekerasan.
Wakil Ketua KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran Nuning Rodiyah mengingatkan tayangan soal pindah agama harus mengedepankan penghormatan terhadap pelbagai agama di Indonesia. Plus, penghormatan terhadap ruang asasi setiap individu untuk beragama.
“Jika ada program siaran dengan materi proses perpindahan agama harus menyesuaikan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pedoman,” ujarnya.
Berita yang terlalu detail mengungkap perpindahan agama seseorang berpotensi mendiskreditkan agama sebelumnya, kata Wakil Ketua KPI Pusat Sujarwanto Rahmat Arifin. “Larangan ini berlaku untuk semua perpindahan agama,” ujarnya.
Menurut KPI, ketika media berlebihan menyorot keputusan seseorang pindah agama, muncul risiko sikap membandingkan antara agama satu dan lainnya dari pemirsa.
Wisnu Prasetya memandang bahwa wajar saja media memberitakan topik ini apalagi yang diberitakan memang tokoh. “Problemnya,” ia menegaskan, “ada pada bagaimana cara memberitakannya.”
Menurutnya, memang agak susah untuk mematok batasan atau sekat-sekat definitif. Namun, kode etik jurnalistik dan Pedoman KPI sudah cukup, meski sangat normatif. Beberapa batasan yang perlu diperhatikan media adalah menghormati privasi, tidak mengangkat hal-hal sensasional, dan sebagainya.
“Di kode etik jurnalistik sebenarnya sudah cukup jelas, seperti di pasal 3, 8, dan 9,” kata Wisnu.
Pasal-pasal dalam kode etik itu memuat, di antara hal lain, wartawan tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi (pasal 3), tidak menyiarkan berita berbasis prasangka atau diskriminasi atas dasar perbedaan agama (pasal 8), menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya (pasal 9).
Selain aturan dan pemantauan yang perlu diperketat, Wisnu menilai pelatihan kepada jurnalis juga penting mengenai isu agama yang memang butuh kepekaan tersendiri.
Namun, dalam isu pindah agama, Wisnu menilai media tidak kekurangan wartawan yang memiliki wawasan menulis, melainkan berita itu, apalagi jika menyangkut subjek selebritas, dianggap seksi dan menjual.
Kasus ini tak cuma di Indonesia. Perkara sensitif orang pindah agama—perkara yang sebetulnya sangat privat—juga jadi perhatian di media Amerika Serikat. Problemnya soal keberagaman di level editor dan reporter.
Kebanyakan editor dapur redaksi di AS adalah laki-laki dan berkulit putih sehingga besar pengaruhnya terhadap suara orang-orang minoritas yang sering tenggelam di media arus utama.
“Homogenitas adalah masalah besar dalam industri yang ambisinya untuk melayani dan menginformasikan masyarakat yang semakin beragam,” kata wakil editor The Atlantic Gillian B. White, perempuan Afrika-Amerika.
Salah satu cara untuk mengatasi masalah itu adalah memperbanyak wartawan dari pelbagai latar belakang, ujarnya. Minimnya wartawan yang beragam bisa berdampak bahaya, bukan cuma pada perusahaan media tapi juga masyarakat.
“Hal itu bisa menghasilkan liputan tidak lengkap, buta-tuli, dan bias,” tulis White. Media yang demikian bukan cuma gagal melayani publik tapi juga menyumbang kerusuhan karena ketiadaan suara minoritas.
Penulis: Aulia Adam
Editor: Fahri Salam