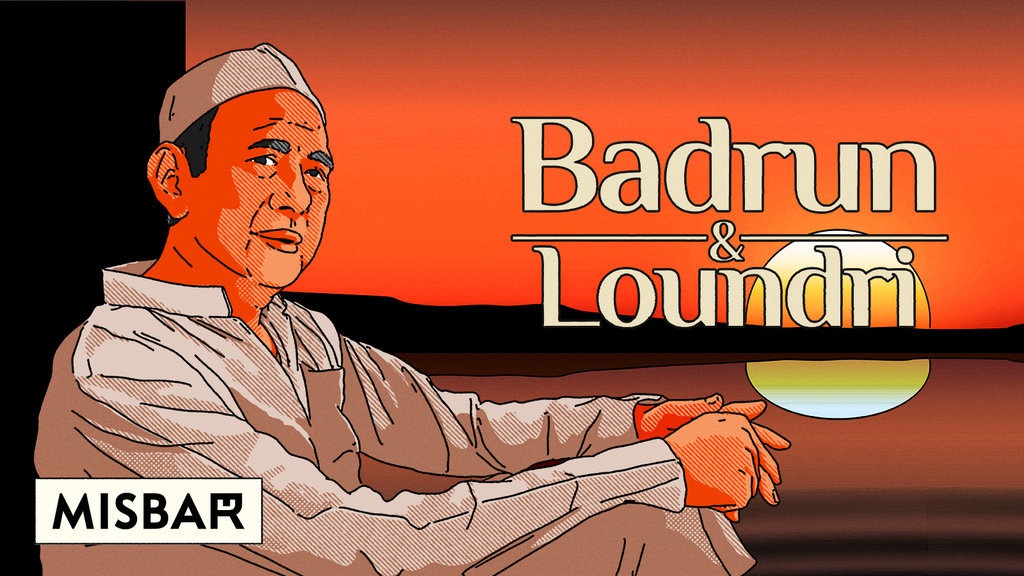tirto.id - Kita mesti mengakui bahwa masyarakat kita masih sangat gampang terpukau oleh pesona gelar, baik gelar akademik, religius, militer, maupun gelar sosial. Terlepas dari kualitasnya, orang-orang yang menyandang gelar biasanya lebih dihormati dan didengar. Pun mereka masih menikmati privilese karena dianggap berstatus kelas atas.
Ada banyak cara merengkuh gelar, mulai dari yang halal hingga yang tabu di mata hukum maupun norma adat. Beberapa mencoba meraihnya dengan cara jujur dan terhormat. Namun, lebih banyak lagi yang menghalalkan segala cara.
Reputasi gelar pun bermacam-macam. Ada yang sangat terhormat, seperti cendekiawan atau pemuka agama. Ada pula yang berprestise darah biru lantaran keturunan. Pun ada yang sekadar berupa julukan, sebagai konsekuensi dari rasa takut yang dipelihara oleh si pemegang gelar.
Guna memudahkan identifikasi, masing-masing gelar umumnya mempunyai ciri spesifik. Seragam militer dengan emblem pangkat, pakaian ulama, sampai busana kebesaran dan senjata pusaka milik anggota keluarga monarki.
Jarang sekali ada khalayak yang peduli mengenai proses seseorang memperoleh gelar yang disandangnya. Dan hal paling penting adalah dampak dari gelar itu, terhadap si individu pemegangnya maupun bagi sekelilingnya. Itu pun belum mempertimbangkan latar belakang dan kelayakan si individu atas gelar.
Maka ketika seorang asing datang ke suatu lingkungan sosial sembari mengenakan atribut-atribut yang merupakan ciri khas gelar tertentu, niscaya dia akan segera diperlakukan istimewa tanpa prasangka buruk.
Lantas, bagaimana jika segala atribut yang dikenakan itu ternyata hanya strategi kamuflase belaka demi menangguk keuntungan pribadi sebesar-besarnya dalam tempo sesingkat-singkatnya?
Demikianlah poin-poin yang tersirat di benak saya seusai menonton Badrun & Loundri. Ia merupakan film panjang anyar karya sineas kawakan Garin Nugroho. Film ini merupakan bagian dari line-up Jakarta World Cinema Week (JWCW) 2023. Lain itu, ia dapat pula disaksikan secara daring melalui kanal tontonan berbayar Klik Film.
Musim Pencitraan
Badrun (Arswendy Bening Swara Nasution) muncul sebagai seorang PNS yang tengah menyiapkan diri menjelang masa pensiun. Suatu hari, dia berteduh dari hujan deras di pelataran sebuah kios laundry yang sudah tutup.
Lalu, datanglang seorang pelanggan yang mengira Badrun sebagai pemilik kios penatu tersebut. Dia lantas menitipkan tas berisi sejumlah pakaian kotor kepada Badrun. Untuk alasan-alasan tertentu, Badrun memutuskan mengenakan beberapa pakaian yang dia temukan setelah menyisir isi tas itu.
Tatkala dia memakai sorban, penduduk setempat menyangka dia adalah penyiar agama yang sedang bersafari lintas daerah. Dalam waktu singkat, warga pun berbondong-bondong menyambanginya seumpama manusia awam melihat nabi.
Badrun menjadi imam salat berjamaah, memberi petuah dan nasehat, serta membuka jasa konsultasi iman. Warga pun mulai memberi imbalan tanpa sedikit pun ragu atas latar belakang Badrun.
Lain waktu, Badrun berganti busana menjadi seragam aparat kepolisian. Persepsi komunitas yang dia datangi lain lagi. Kepada preman lokal, Badrun menawarkan perlindungan dengan imbalan gratifikasi.
Garin terang sedang bermain-main dengan simbol di film terbarunya ini. Adagium “atribut adalah kunci” ditunjukkan begitu gamblang. Personifikasi Badrun secara otomatis mengikuti busana yang sedang dia kenakan—sungguh banal, pragmatis, dan oportunis sekaligus.
Simbol busana dan pencitraan digunakan untuk menyetir persepsi publik. Persepsi umum yang telah terkondisikan dengan sendirinya akan membentuk opini publik. Lalu, opini kolektif yang lahir akan berekspansi sampai muncul antitesa yang bersifat fatal.
Bila opini dimaksud bertahan cukup lama, akibatnya muncul stigma yang kemudian memicu bias. Pada ujungnya, bias menihilkan daya kritis seseorang atau sekelompok orang dalam memahami realitas dihadapannya.
Demikianlah Badruan begitu leluasa mengubah citra diri dan menikmati dampaknya. Dia tak ubahnya seekor bunglon yang beradaptasi dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Dia seakan menjadi cerminan bagi situasi ruang publik kita dewasa ini yang begitu sesak menjelang pemilu.
Musim pencitraan massal hadir lima tahun sekali di Republik ini. Opini publik dapat berubah dalam hitungan hari, bahkan jam. Polanya sangat dinamis dan fluktuatif, mengalahkan chart flow saham di bursa efek.
Pertarungan pengendalian persepsi pada tataran massal semacam ini membuat orang susah percaya. Kita makin kesulitan membedakan mana yang otentik dan mana yang penuh dempul make-up.
Aspek berikutnya yang cukup nyeleneh dan menggelitik dari film ini adalah soal “kebersihan”. Seluruh atribut yang dikenakan Badrun sejatinya adalah pakaian kotor. Itu sebuah metafora bahwa pencitraan yang dia bangun bertumpu pada suatu niat dasar yang tidak steril.
Sialnya, penduduk setempat gagal mencium aroma tidak sedap dari pakaian-pakaian yang melekat pada tubuh Badrun. Mereka lebih memilih terbuai dalam sensasi kedamaian sesaat dari kuasa semu yang ditawarkan oleh busana itu.
Diam-diam, saya nyengir tatkala mengimajinasikan situasi saat Badrun telanjang bulat. Tanpa busana dan simbol-simbol yang melekat, siapakah dia? Apakah orang-orang akan memberi perhatian yang sama seperti ketika ia memakai busana tertentu? Akankah dengan begitu dia kembali suci atau justru itu semata bentuk kreatif dari manipulasi?
Kritik Politik
Enam bulan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, Garin merilis sepasang film yang sangat kental mengusung topik demokratisasi. Film pertama, Kejarlah Janji, adalah produk kolaborasi dengan KPU RI. Ia tayang terbatas di berbagai layar alternatif serta bioskop-bioskop arus utama terpilih.
Badrun & Loundri adalah yang kedua. Menonton keduanya seakan diingatkan untuk selalu mawas terhadap gimik-gimik politik dan tentu saja perilaku para politikus. Pesan-pesan itu semestinya tak hanya digaungkan di kota besar, tapi juga ke pelosok-pelosok jika memungkinkan.
Untungnya, pemutaran film Badrun & Loundri tak bakal berhenti di perhelatan JWCW. Lepas itu, ia akan bertamasya ke Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) sehingga makin banyak penonton luar Jabodetabek berkesempatan menontonnya.
Menurut saya, motivasi serta pilihan estetis Garin belakangan ini tengah diselimuti oleh nuansa politis. Ada semacam keresahan atau mungkin pernyataan politik yang ingin dia sampaikan melalui film-filmnya, terutama pasca penayangan Puisi Cinta yang Membunuh.
Masih sulit untuk menerka apakah ke depan Garin akan semakin larut dalam tema besar yang sama. Bisa jadi preferensinya saat ini semata menyesuaikan momentum berkala yang tengah menanti di depan mata 200 juta lebih pemilik hak suara nasional.
Terlepas dari pesanan institusi atau bukan, pun mengesankan tendensi keberpihakan politis atau tidak, sepasang film Mas Garin pada paruh kedua tahun ini mengandung kritik pedas kekinian yang sukar untuk diabaikan.
Kritik tersebut secara esensial tidak hanya berbicara tentang dinamika politik, melainkan turut mengomentari branding dalam beragam bidang kehidupan. Gerakannya liar dan meluas sehingga berpotensi menumbuhkan otokritik atau bahkan metakritik.
Karakter Badrun bisa merujuk pada siapa saja, bahkan Garin sendiri. Toh, tahapan pembuatan hingga ekshibisi film juga merupakan proses politik. Masalahnya, apakah kita semua siap ditelanjangi atau menempuh jalan pintas bernama klarifikasi?
Penulis: Jonathan Manullang
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id