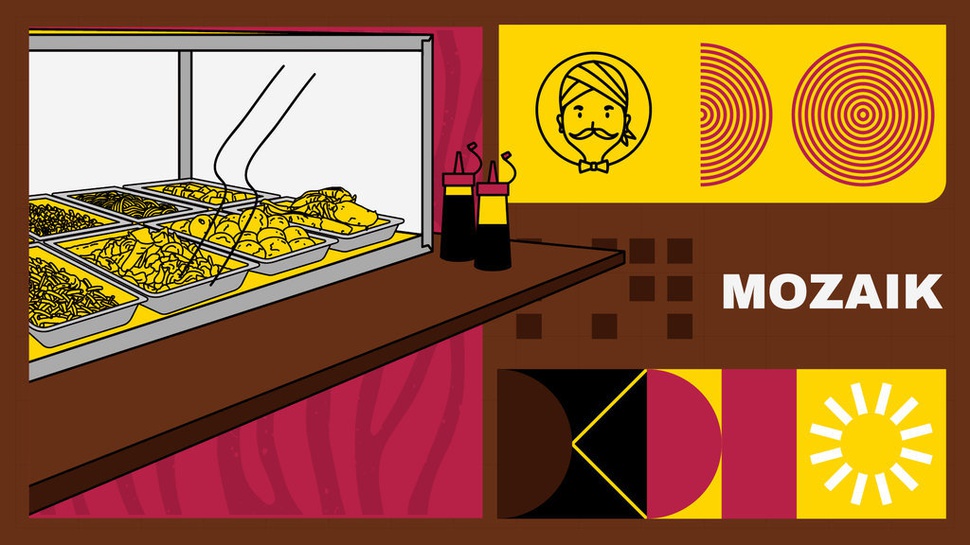tirto.id - Ketika baru menapakkan kaki di Jakarta 2010 lalu, saya tidak menyadari bahwa warteg alias warung Tegal akan menjadi sahabat paling setia di kala lapar. Selain menu sajiannya yang identik dengan masakan rumah, juga karena harganya yang murah dan porsi nasinya yang mengenyangkan.
Selain warteg, warung nasi Padang sebenarnya juga pilihan. Namun bagi karyawan kasta sudra seperti saya, makan di warung nasi padang tidak bisa dilakukan tiap hari. Di samping sayurnya yang kurang variatif, juga karena harganya yang agak mahal.
Warteg merupakan fenomena urban. Tampilan bangunannya yang sederhana dan segmen pasarnya yang membidik kelompok ekonomi bawah kerap mengaburkan status sosial pemiliknya sebagai pengusaha kuliner yang sukses.
Meski memulai bisnis dari bawah, banyak pemilik warteg yang kemudian berhasil meningkatkan taraf hidup keluarganya di kampung halaman. Kerja keras, keuletan, dan tahan banting adalah sebagian kuncinya.
Warteg Naik Kelas
Sejak menjamur pada warsa 1950-an, warteg lekat dengan citranya yang murah, mengenyangkan, dan tata ruang yang seadanya. Namun, sepuluh tahun terakhir mudah didapati warteg di kota-kota besar bertransformasi.
Wahteg contohnya. Meski menu yang disajikan sama dengan warteg pada umumnya tapi desain tata ruang dan perabot yang digunakan mengusung tema vintage yang menarik. Untuk memikat segmen pasarnya yaitu kaum menengah perkotaan, warung makan tersebut dilengkapi AC, smooking room, stop contact, dan akses wifi gratis.
Contoh lain adalah Warteg Hipster. Tempat makan yang berlokasi di Pasteur, Bandung ini berdiri sejak 2016. Sebagaimana Wahteg, Warteg Hipster juga dilengkapi AC dan layanan wifi gratis. Hal menarik lainnya, warteg ini menyediakan tiga minuman gratis yang bisa diisi ulang, yaitu air mineral, teh tawar, dan infused water.
Sour Sally Group yang sudah 11 tahun berpengalaman dalam bisnis waralaba Food and Baverage (F&B) juga menawarkan konsep warteg milenial dengan jenama Wowteg. Selain menawarkan menu masakan sehari-hari sebagaimana lazimnya warteg, Wowteg juga menyediakan menu kekinian, seperti nasi telur Pontianak dan butter rice telur ala Korea.
Di luar negeri, warteg juga sudah mulai “menginvasi”. Yannie Kim, yang banyak dikenal publik Indonesia sebagai influencer, membuka Warteg Gembul di Korea Selatan. Dalam sebuah lawatan ke negeri ginseng itu, Presiden Jokowi sempat mengunjunginya.
Warteg lain yang dibuka di luar negeri adalah Warteg Bahari yang juga berada di Korea Selatan, Warteg Nusantara di Berlin, Warteg Monggo Moro di Jepang, dan Warung Tegal di Saudi Arabia. Meski disebut warteg, pemilik warung makan tersebut tidak semuanya berasal dari Tegal.
WKB: Sebuah Terobosan
Wahteg, Warteg Hipster, dan Wowteg jelas bukan tempat makan favorit konsumen kelas bawah seperti warteg kebanyakan. Dilihat dari tata ruang, fasilitas, dan harga makanannya pun warung-warung itu lebih mirip kafe atau tempat makan untuk segmen pasar yang lebih tinggi.
Fakta tersebut membuat supremasi warteg di seantero Jabodetabek tidak tergoyahkan, di samping jumlahnya yang mencapai 35 ribu sulit dilawan. Terlebih Wahteg yang memiliki outlet di Tanjung Duren (Jakarta Barat) dan Bekasi tutup sejak 2020 lalu. Sementara Warteg Hipster yang semula memiliki lima cabang kini hanya tinggal punya satu outlet.
Di tengah ramainya tempat makan kekinian yang mengusung konsep masakan ala warteg, transformasi yang sesungguhnya lahir di kalangan pengusaha warteg konvensional. Adalah Sayudi (50), seorang lulusan SD, yang memulai perubahan besar itu.
Pria yang pernah menjadi pedagang asongan tersebut punya segudang pengalaman dalam bisnis warteg, mulai warungnya yang hampir digusur dan bangkrut hingga berhasil memiliki tiga cabang. Setelah jatuh-bangun menjalankan bisnis kuliner khas Tegal itu, ia mencoba peruntungan dengan membuka kemitraan atau waralaba.

Nama Warteg Kharisma Bahari (WKB) Group pun digunakan sebagai jenama bisnis waralabanya. Tanpa diduga, usaha tersebut berkembang, bukan hanya di Jabodetabek tapi juga di kota-kota lain. Ekspansi bisnis milik Sayudi semakin agresif, terlihat dari semboyan “Siap mewartegkan Jabodetabek” yang berubah menjadi “Siap mewartegkan Indonesia”.
WKB Group menawarkan tiga kategori warteg berdasarkan nilai modal dan ukuran warungnya, yaitu skala kecil, reguler, dan besar. Modal untuk warteg skala kecil (40 meter persegi) sekira Rp135 sampai Rp165 juta, skala reguler (60 meter persegi) Rp200 juta sampai Rp300 juta, dan skala besar (90 meter persegi) Rp300 juta sampai Rp400 juta.
Modal tersebut sudah termasuk biaya renovasi warung, penyediaan alat dapur dan kamar mandi, fasilitas seperti meja dan lemari es, serta stok awal bahan baku masakan. Tak hanya itu, mitra juga akan diberi panduan pengelolaan, laporan keuangan, dan estimasi pengeluaran bulanan sekaligus omzet atau pemasukan.
Kiwari WKB Group memiliki 100 mitra terdaftar dengan lebih dari 1.000 warteg di seluruh Indonesia. Selain di Jabodetabek, gurita waralaba itu juga merambah Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Palembang, dan sejumlah kota lain.
Meski tak semewah kafe-kafe berkonsep warteg, WKB Group mengubah tampilan warteg konvensional yang terkesan kusam menjadi lebih menarik. Jika dulu warteg identik dengan warna biru, konon melambangkan Kabupaten Tegal yang merupakan daerah pesisir, kiwari warna-warna terang lebih dominan.
Lain itu, jendela dibuat berukuran besar dan pencahayaan ruangan lebih terang. Identitas warteg pun ditulis dalam ukuran besar di kaca jendela. Semua dimaksudkan untuk menciptakan kesan bahwa warteg telah naik kelas.
Bermula Sejak Orde Lama
Warteg memiliki sejarah yang panjang. Kemunculannya turut menandai arah baru kebijakan politik Presiden Soekarno pada warsa 1950 hingga 1960-an yang mencanangkan pembangunan besar-besaran terhadap ibu kota Jakarta. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pemindahan ibu kota dari yang sebelumnya berada di Yogyakarta.
Seturut Rahadian Ranakamuksa Candiwidoro dalam “Menuju Masyarakat Urban: Sejarah Pendatang di Kota Jakarta Pasca Kemerdekaan (1949-1970)” (2017:6), sebagai ibu kota negara, Jakarta menjadi pusat pembangunan dalam skala yang lebih besar dibanding kota-kota lainnya di Indonesia.
Ini bisa dimengerti, sebab saat itu pembangunan infrastruktur seperti gedung-gedung pemerintahan sangat mendesak. Itu sebabnya, hampir dua pertiga dari total utang Pemerintah Indonesia pada 1956 dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Jakarta.
Pembangunan yang masif di Jakarta merupakan salah satu sebab terjadinya arus urbanisasi ke kota tersebut. Pada 1950, penduduk Jakarta berjumlah 1,6 juta jiwa. Satu dekade kemudian angkanya melambung menjadi 2,9 juta jiwa. Angka ini terus membengkak hingga lebih dari 4 juta jiwa pada akhir warsa 60-an.
Karena kebutuhan terhadap kuli bangunan, banyak pekerja dari berbagai wilayah di Jawa berbondong-bondong menuju Jakarta untuk melamar. Jarak Kabupaten Tegal yang hanya 4 jam perjalanan darat ke Jakarta membuat banyak warganya, terutama yang berasal dari Desa Krandon, Sidapurna, dan Sidokaton, mengadu nasib ke kota tersebut.
Banyaknya pekerja kasar yang mencari peruntungan di Jakarta menciptakan peluang bisnis tersendiri. Peka dengan peluang itu sejumlah warga Tegal yang lain menjual nasi ponggal yang murah untuk mencukupi kebutuhan makan para pekerja tersebut. Sebagian di antara penjual nasi itu tidak datang sendiri melainkan bersama anak dan istri mereka.
Dari awalnya menjajakan dagangan di tempat-tempat yang banyak dihuni para kuli bangunan, para penjual nasi itu selanjutnya membangun warung makan semi permanen di dekat lokasi proyek. Seiring berjalannya waktu, warung yang mempertemukan sesama perantau dari Tegal itu dikenal dengan warteg.
Sebagai warung yang melayani konsumen kelas bawah, tidak banyak perubahan dilakukan pemilik warteg terhadap menu masakannya. Menu seperti sayur asam, cah kangkung, sayur santan, atau lauk-pauk seperti tempe, tahu, dan telur dadar seperti sebuah template di warteg mana pun dan tahun berapa pun.
Meski begitu, daya tarik warteg yang menyediakan makanan dengan harga murah dan porsi nasi yang mengenyangkan tak pernah surut. Konsumen mereka yang semula para kuli bangunan dan sesama perantau dari Tegal pun berkembang, bukan hanya perantau dengan latar belakang pekerjaan dan asal daerah yang beragam tapi juga penduduk asli Jakarta.
Penulis: Firdaus Agung
Editor: Nuran Wibisono