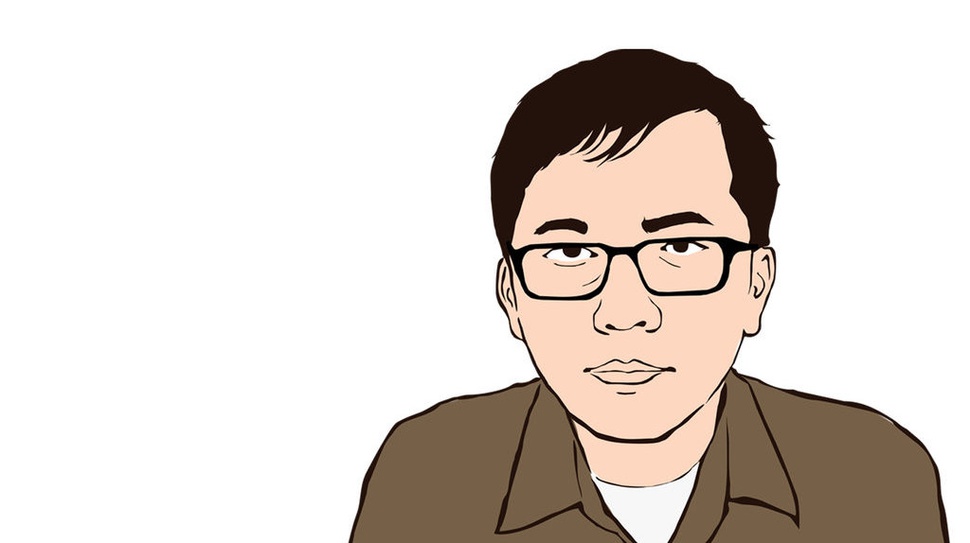tirto.id - Pergantian Panglima TNI berjalan cepat pekan lalu. Sejak Presiden Joko Widodo mengusulkan Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf TNI AU, pada 4 Desember, empat hari kemudian ia dilantik. Esoknya, 9 Desember, serah terima secara kemiliteran di Mabes TNI, Cilangkap, digelar.
Disaksikan oleh sejumlah perwira tinggi TNI, para politisi dari Komisi I DPR, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, di tengah lautan prajurit, Jenderal Gatot Nurmantyo menyerahkan tongkat komando kepada Tjahjanto. "Selamat mengemban tugas sebagai Panglima TNI," ujar Gatot.
Pergantian ini tidaklah mengejutkan, meski menimbulkan tafsir macam-macam. Gatot sendiri akan memasuki masa pensiun pada April mendatang. Syarat menjadi Panglima TNI pun sudah diatur oleh UU TNI 2014, salah satunya: calon panglima pernah menjabat kepala staf angkatan. Mungkin yang menarik dari pergantian ini adalah kecenderungan Jokowi terhadap lingkaran orang-orang yang pernah bertugas di Solo, termasuk Tjahjanto yang pernah menjabat Komandan Lanud Adi Soemarmo.
Pekerjaan rumah TNI sebagai institusi yang menghormati supremasi sipil masih terus jadi sorotan, sekalipun mereka sudah melakukan sejumlah langkah reformasi pasca-Orde Baru. Salah satunya soal tuntutan proses pengadilan sipil terhadap pelaku militer yang melakukan tindakan kriminal, plus pertanggungjawaban komando atas indikasi pelanggaran hak asasi manusia. Belum lagi soal desakan keterbukaan atas bisnis-bisnis tentara.
Selama dua tahun TNI di bawah panglima Jenderal Gatot Nurmantyo (2015-2017), yang muncul ke publik justru pandangan politisnya yang anti-sipil, misalnya saja propaganda dia dengan isu proxy war. Di akhir masa jabatan, ia juga terkesan mencari panggung di antara histeria massa "Aksi Bela Islam" dalam palagan Pilkada DKI Jakarta yang brutal.
Pada September lalu, Gatot juga memobilisasi jajaran teritorial agar mengajak masyarakat sekitar menonton film Gerakan 30 September. Ia juga menjadi pusat polemik saat menyampaikan selentingan soal pembelian senjata di luar TNI.
Dalam urusan pertanian dan ketahanan pangan, di bawah kepemimpinan Gatot, TNI bekerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk mencetak sawah hingga urusan jual beli beras. Kampanye mengenai "kedekatan TNI bersama rakyat" selalu digaungkan Gatot, yang membuatnya populer sampai-sampai namanya mencuat dalam bursa calon wakil presiden 2019 mendatang.
Terakhir, menjelang serah terima jabatan, Gatot melakukan rotasi terhadap 85 perwira tinggi, yang dianggap oleh pengamat militer sebagai langkah Gatot menanam "pengaruh secara tidak langsung" saat dia pensiun.
Namun, di balik sepak terjang politis ini, bagaimana sebenarnya kinerja Jenderal Gatot Nurmantyo, serta reformasi TNI yang terkesan mandek?
Muhamad Haripin, Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan penulis Reformasi Sektor Keamanan Pasca Orde Baru: Melacak Pandangan dan Komunikasi Advokasi Masyarakat Sipil (2013), berpendapat bahwa selama dua tahun menjabat, ada hal positif dan negatif yang dilakukan Jenderal Gatot Nurmantyo. Menurutnya, kemampuan personel TNI mulai meningkat.
“Misalnya, kita menang di beberapa kompetisi menembak. Bukan pengalaman kombat langsung, tapi bisa tercermin dari prestasi itu,” kata Haripin pada redaksi Tirto, awal Desember lalu.
Sisi negatifnya, kebijakan keluar Gatot sebagai panglima kerap offside, yang dinilai Haripin sebagai "kecenderungan jenderal Angkatan Darat sebelumnya". Langkah Gatot yang punya tendensi politis ini, mau tak mau, berimbas pada lambatnya reformasi TNI secara menyeluruh.
Apa saja yang sudah dilakukan Gatot selama ini? Bagaimana nasib reformasi TNI selama dan sesudah Gatot menjabat? Berikut wawancara Haripin dengan Mawa Kresna.
Bagaimana evaluasi Anda atas kinerja Gatot Nurmantyo?
Dari 2015 sampai sekarang, kalau dari evaluasi, [Pusat Penelitian Politik - LIPI] kita bisa lihat kebijakan ke dalam dan keluar. Dari internal, kelihatannya dia memang melanjutkan dari kebijakan panglima sebelumnya, Moeldoko (2013-2015). Zaman Moeldoko, di bawah [Presiden] Susilo Bambang Yudhoyono, membuat kebijakan MEF (Minimum Essential Force). Kebijakan itu intinya ingin memperkuat kapabilitas teknis dan manajerial TNI.
Kami ingin membenahi kemampuan personel—ada rekrutmen, pelatihan, bagaimana promosi dan rotasi personel dirapikan. Kedua, dari segi struktur, bagaimana Komando Teritorial Angkatan Darat, armada barat dan armada timur Angkatan Laut dan Angkatan Udara disinergikan. Dari segi alutsista (alat utama sistem senjata)—ini yang lebih banyak ditekankan dan diberitakan.
Kondisi alutsista memang sudah ketinggalan zaman. Tingkat ketersediaan alutsista pun masih rendah. Misalnya, kesiapan AD baru 60 persen, AU 70 persen, dan AL 40 persen.
[Baca juga:Kekuatan TNI Gagap Menghadapi Ancaman Perang Modern]
Kebijakan ini terus berlangsung ke zaman Jokowi. Jokowi secara eksplisit memiliki prioritas yang kurang lebih sama: harus memperkuat alutsista, menjadikan TNI sebagai tentara yang modern dan profesional, plus poros maritim global. Gatot naik pada Juli 2015 dengan melanjutkan misi ini, ditambah pandangan dia sebagai orang dalam.
Selama dua tahun ini, secara internal, itulah yang kini diperbaiki oleh Gatot.
Secara umum, ada positif dan negatif. Secara personel, zaman Pak Gatot, tingkat kemampuan unit, individunya, semakin meningkat. Misalnya kita menang di beberapa kompetisi menembak. Bukan pengalaman kombat langsung, tapi bisa tercermin dari prestasi itu.
Kalau kebijakan keluar bagaimana?
Ya memang Gatot mengikuti kecenderungan jenderal AD sebelumnya. Domain melebar, ikut-ikut dalam perbincangan politik. Terutama yang terlihat sekali doktrin dia soal proxy war: dari ancaman kemiskinan, pornografi, LGBT, narkoba, dan sebagainya. Yang menarik, kan, ada rencana untuk membuat struktur komando gabungan wilayah. Jadi, tiga matra dijadikan satu tempat, dan mereka menjadi kekuatan militer terpadu. Sampai sekarang itu masih digodok.
Tapi memang untuk urusan keluar, Gatot banyak membuat gaduh, soal proxy war, pembelian senjata polisi, misalnya.
Kenapa jarang terdengar Panglima TNI bicara soal masalah eksternal seperti Laut Cina Selatan dan lainnya? Bagaimana pandangan Gatot soal ancaman dari luar seperti itu?
Misalnya Cina Selatan. Ini isu sangat sensitif. Ada dinamika. Posisi Indonesia dari zaman Orba dan awal reformasi, tidak punya masalah teritorial di wilayah yang dipersengketakan antara para pihak, antara Filipina dan negara-negara lain. Itu masih dipertahankan sampai sekarang.
Dulu zaman Pak Moeldoko, tahun 2014, dia mengeluarkan pernyataan keras soal Laut Cina Selatan. Dia bilang, Indonesia akan menggunakan pendekatan lebih tegas menyangkut kedaulatan di wilayah itu. Ternyata di dalam negeri jadi backlash. Dia dapat kritik dari kementerian luar negeri, dari DPR, dari presiden. Tidak sepatutnya Panglima TNI mengeluarkan pernyataan seperti itu. Ini yang agaknya dipegang Gatot.
Soal ancaman dari luar ini, Pak Gatot juga pernah bikin blunder saat bilang memutuskan kerja sama dengan Australia. Itu, kan, urusan government-to-government. Dari pernyataannya, dari dokumen Kementerian Pertahanan, memang tidak spesifik ancaman dari luar kita itu dari mana. Tapi, kalau dilihat dari latihan-latihan perang yang kita laksanakan, TNI itu melihat ancaman datang dari utara. Ini wajar karena di wilayah utara jauh lebih banyak negara.
Soal doktrin, sampai sekarang TNI masih membawa isu PKI, isu yang sudah usang. Lalu ada pembubaran diskusi dan lainnya. Apakah ini jadi indikasi belum rampung proses reformasi di tubuh TNI?
Kalau dari posisi saya, reformasi TNI ini masih jauh dari selesai. Proses reformasi TNI terlihat progresif dari 1999 sampai 2004: UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, UU 34/2004 tentang TNI. Ada paradigma baru. ABRI tidak lagi di MPR, polisi pisah dari ABRI. Tapi, sejak 2004 berjalan lebih bertahap. Dan di dalam internal pun, yang saya pahami, baik dari angkatan 1970-an, zaman Pak SBY (lulusan Akademi Militer tahun 1973), Agus Widjojo (lulusan 1970), Luhut Panjaitan (lulusan 1970), sampai Pak Hadi Tjahjanto sekarang, memang kita sudah melakukan reformasi TNI: ABRI sudah pisah dari polisi, sudah tidak lagi ikut dalam politik praktis.
Menurut pandangan mereka, sepengetahuan saya, tidak boleh, jangan coba-coba mengotak-atik identitas asli, bahwa "kita adalah tentara rakyat, urusan kita itu tidak seperti militer seperti negara Barat, kita ini tidak bisa sepenuhnya profesional, karena kita ini lahir dari rahim rakyat."
Dan itu identitas yang terkait dengan materi training ketika di Akademi Militer: bagaimana mereka ditempa angkatan, Seskoad (Sekolah Staf dan Komando AD), Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional). Jati diri itu yang terus menerus dirawat oleh tentara sampai sekarang.
Banyak yang bilang mereka mau kembali ke Orde Baru. Sebenarnya, di internal sendiri, mereka tidak membayangkan bisa kembali seperti zaman Orde Baru, tapi mereka melihat masih memiliki dua peran: sosial politik dan sosial kemasyarakatan.
Misalnya, ketika saya wawancara dengan mereka, [mereka berkata] ketika tsunami Aceh 2004, gempa Yogyakarta 2006, dan erupsi Merapi 2010, yang pertama kali turun adalah TNI, bersama rakyat. Melihat di lapangan, kan, tidak memungkinkan izin dulu ke DPR. Tapi, sebenarnya, enggak juga. Karena itu tertera dalam UU TNI.
Misalnya juga isu terorisme. Mereka mau masuk. Mereka beranggapan [isu terorisme] juga urusan NKRI.
Identitas jati diri—ini retorika yang digunakan oleh Presiden Jokowi, agar TNI menjadi tentara yang modern, berjuang bersama rakyat. Ini retorika yang dipakai terus sampai sekarang.
Ini jadi problem untuk reformasi di tubuh TNI?
Kalau dari segi profesionalisme, kita mau mengejar efektivitas militer, ya kita kembali saja MEF yang sudah dibuat TNI. Itu sudah jelas: tugas tentara berperang. Memang mereka punya doktrin yang beda dengan sipil. TNI berlatih untuk mengalahkan musuh, dan melindungi teritori negara dan masyarakat.
Sekarang, kalau tugas itu tidak diiringi dengan tugas yang tidak kalah rumit dan banyak—penyuluhan pertanian, misalnya—tentu saja itu mengganggu dan itu disampaikan oleh kalangan internal. Ada yang bilang kepada saya: bagian teritorial di Kodam Jaya (meliputi DKI, Tangerang, dan Bekasi) berkata, 'Setiap pagi saya menerima laporan harga cabai karena kita harus memantau harga sembako."
Itu sudah bukan ranah militer. Sudah ada kerjaan orang lain. Tapi, ia diperintahkan atasan dan menjadi bagian dari pembinaan teritorial. Ini bisa mengganggu proses reformasi juga.
Apakah sistem 'pertahanan keamanan rakyat semesta' tidak bisa berubah seperti tentara Amerika Serikat, misalnya?
Aspek identitas dan norma internal masih tertanam di tubuh TNI sekarang. Itu hanya satu aspek mengapa TNI tidak bisa berubah. Soal kelembangaan juga menjadi masalah. Ini ada banyak personel yang perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati) yang nonjob. Ada teman yang riset: selama ini rotasi hanya bersifat horizontal, tidak vertikal. Dari aspek moral, personel juga terganggu: 'Kenapa saya tidak naik-naik pangkat? Apakah proses promosi betul? Apakah atasan memilih teman sendiri?'
Kenapa yang nonjob masih banyak?
Karena waktu angkatan 1970-an dan 1980-an memang merekrut banyak orang. Kita punya Undang-Undang No. 20/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang berlaku pada zaman Jenderal Benny Moerdani. Dampaknya sampai sekarang masih terasa. Dulu memang di zaman Orde Baru, seorang TNI itu bukan cuma disiapkan untuk tugas kemiliteran, tapi untuk kekaryaan. Kalau orang masuk Akademi ABRI bisa jadi gubernur, bupati, walikota, jadi lurah. Jadi ada banyak personel bisa dipasang di jabatan sipil. Saya pikir juga orang yang baru sekarang ketika melamar menjadi TNI tidak akan berpikir menjadi bupati. Yang dipikirkan adalah meniti karier di kemiliteran.
Kalau mau jadi tentara profesional sudah ada MEF, dan ini tinggal dijalankan. Masalahnya, ini tidak konsisten dijalankan, misalnya pembelian persenjataan, ketika beli F-16, beli Leopard, tidak sesuai MEF. Tapi karena ada pertimbangan politik dan ekonomi jangka pendek, semua masuk.
Seberapa pengaruh peran Panglima TNI dalam percepatan reformasi?
Tentu berpengaruh. Kepemimpinan setiap panglima mencerminkan pilihan presiden sebagai pemimpin sipil. Jokowi dalam bidang pertahanan ingin menjadi militer yang modern dan profesional—ini yang ingin dia wujudkan dengan mengangkat Marsekal Hadi Tjahjanto. Dia dari AU, dan selama ini persepsi publik, AU ini punya perspektif yang berorientasi keluar, mereka lebih terbuka atas ide yang baru. Semoga dengan panglima dari AU jauh lebih baik. Itu dari sisi profesionalnya.
Tapi kita tahu juga presiden punya kebijakan politik. Kalau saya tandai, sejak Jokowi naik, kemudian Gatot diangkat, TNI tidak pernah absen mengurusi masalah ketahanan pangan. Padahal ini tidak boleh. TNI tidak boleh secara permanen terus mengurusi itu. Dan ini terkait juga dengan kebijakan pemerintah.
Memang, secara aturan ada, kalau dilihat dari pertimbangan Jokowi tahun pertama fokus konsolidasi politik; dia mengerti tidak punya partai, tahun kedua lebih pada infrastruktur, lanjut sampai tahun ketiga. Tahun keempat, banyak proyek yang direncanakan selesai pada tahun depan. Dan itu tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit dan personel yang banyak. Nah, yang paling mudah adalah memobilisasi tentara, dan di undang-undang memang diberikan celahnya. Itu yang diikuti oleh Jenderal Gatot.
Artinya sampai sekarang reformasi TNI masih jalan bertahap?
Mereka juga mengakui bahwa reformasi ini masih jalan. Mereka berharap pemerintah bisa memberikan anggaran yang lebih bisa untuk lebih profesional. Karena sarana latihan mereka sudah jelek, alutsista mereka juga sudah tua. Padahal anggaran mereka juga sudah besar, tapi habis untuk belanja pegawai karena masih ada komando teritorial (koter).
Kenapa masih ada komando teritorial? Itu dilikuidasi saja, dirampingkan. Yang saya baca, konsepsi mereka soal demokrasi, soal reformasi ini berhenti pada tidak lagi berpolitik dan tidak lagi memihak Golkar.
Itu yang dipahami tentara kita sekarang?
Iya. Tapi perlu dibedakan. Identitas tentara dengan kekaryaan. Kalau mereka bilang, 'Kita itu tentara rakyat. Ini yang sudah dari awal tumbuh dalam diri kita.' Itu sebabnya mengapa kita mengurusi bikin toilet—itu bagian dari tugas karena tentara bagian dari rakyat yang sedang membangun rakyat.
Apa doktrin itu tidak menjadi alibi? Misalnya, kita bisa lihat kasus TNI bikin klub sepakbola, main di liga profesional. Ada korban sipil.
Iya, itu tentu apologi. Tapi dilihat dari internal dari interaksi saja: ada perubahan generasi 1970-an yang dididik pada masa Orde Baru dengan generasi yang baru. Misalnya, anaknya SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan pada pendidikan. "Kita itu harus menjadi intellectual soldier," kata dia. Enggak dia saja. Ada beberapa orang seperti dia, pangkat letkol, kolonel, yang usianya masih 40 sampai 45 tahun. Mereka lebih berpikir bagaimana ancaman cyber kaitannya dengan intelijen militer? Bagaimana pertahanan kita menghadapi makin padatnya Selat Malaka?
Jadi diskusi teknis, soal kemiliteran, lebih bisa diajak bicara dengan generasi muda ini. Kalau yang tua itu bicara soal pembangunan nasional—tapi bukan berarti tidak bisa diajak diskusi.
Penulis: Mawa Kresna
Editor: Fahri Salam