tirto.id - Kasus pelecehan seksual yang dialami Agni (bukan nama sebenarnya) saat menjalani program Kuliah Kerja Nyata (KKN) berujung tidak baik. Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Panut Mulyono menegaskan Agni dan HS (pelaku pelecehan seksual) sepakat menyelesaikan kasus secara non-litigasi.
Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan pada Senin (04/02/2019) lalu oleh tiga pihak: Agni, HS, dan Panut, yang disaksikan Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Purwanto; Dekan Teknik UGM Nizam; ayah HS; serta pengacara korban Sukiratnasari.
“HS menyatakan menyesal, mengaku bersalah dan memohon maaf atas perkara yang terjadi pada Juni 2017 kepada pihak saudari AN disaksikan pihak UGM. Saudara HS, AN, dan UGM menyatakan perkara ini sudah selesai,” kata Panut di UGM.
Panut mengatakan, dalam kesepakatan, termaktub kewajiban bagi HS untuk menjalani mandatory counseling dengan psikolog klinis yang ditunjuk UGM, atau yang dipilihnya sampai dinyatakan selesai.
Sementara Agni diwajibkan mengikuti konseling trauma dengan psikolog klinis yang ditunjuk atau yang dipilihnya sampai dinyatakan selesai oleh psikolog yang menanganinya.
Selain dua kewajiban itu, UGM menanggung biaya konseling, pendidikan, dan biaya hidup untuk Agni yang setara dengan komponen dalam beasiswa Bidikmisi.
Panut juga menugaskan Fakultas Teknik dan Fisipol untuk mengawal studi HS dan AN, sehingga keduanya bisa menyelesaikan studi dan lulus pada Mei 2019, dengan catatan sudah menjalani persyaratan yang diwajibkan.
Yale juga Sama Saja
Pada 12 Desember 2016, DKE, salah satu perkumpulan mahasiswa di kampus Yale yang sangat bergengsi dan elite itu, mengadakan pesta tahunan bertajuk “DKEmas”. Pesta ini diadakan secara eksklusif, hanya mahasiswa tertentu yang bisa ikut dalam pesta.
Beth, bukan nama sebenarnya, termasuk orang yang memperoleh undangan pesta. Pada pengalaman pertama itu Beth datang bersama temannya, mahasiswa junior di Yale. Di tengah pesta, ia berkenalan dengan Luke, salah satu anggota DKE. Perkenalan itu rupanya berujung pada lahirnya kasus yang menyedihkan: Luke memperkosa Beth.
Versi cerita pihak Beth, simpulan “pemerkosaan” muncul setelah Luke melanggar konsensus yang sudah disepakati perihal pemakaian kondom ketika berhubungan seks. Menurut pengakuan Beth, ia berkali-kali meminta Luke memakai kondom. Tapi Luke bersikeras menolak.
Keesokan hari, Beth bangun dengan perasaan tak menentu. Sedih, kecewa, dan marah. Ia menilai batasan konsensual dilanggar. Tak lama berselang, Beth memberitahu keluarganya bahwa ia diperkosa. Bersama sang kakak, Beth pergi ke Rumah Sakit Yale di New Haven guna menjalani pemeriksaan medis kekerasan seksual.
Sementara versi pihak Luke menyatakan keduanya memang sempat membahas penggunaan kondom. Akan tetapi, pembahasan itu hanya muncul di awal perbincangan. Setelahnya, mereka tetap melanjutkan aktivitas intim. Luke percaya bahwa apa yang dilakukannya sudah berdasarkan kesepakatan antara dia dan Beth.
Beth melaporkan kasus ini ke Komite Pelanggaran Seksual Universitas (UWC). UWC, yang menerapkan standar bukti berbeda serta lebih rendah dari penegakan hukum pidana, menjatuhkan vonis bersalah terhadap Luke karena “melakukan penetrasi seksual tanpa persetujuan”, berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan selama lima bulan.
Namun, alih-alih dijatuhi hukuman lebih berat--misalnya, dengan dikeluarkan dari kampus--Luke ‘hanya’ diskors selama tiga semester.
Ini bukan pertama kali Yale bersikap lunak terhadap mereka yang dianggap melakukan kekerasan seksual.
Berdasarkan temuan Business Insider, ada lebih dari 60 laporan kekerasan seksual yang masuk ke meja UWC sejak 2011. Dari 60 kasus itu, 15 kasus ditetapkan oleh Yale sebagai bentuk “penetrasi tanpa persetujuan”, “seks non-konsensual”, maupun “seks tanpa persetujuan”.
Vonis terhadap belasan kasus itu berbeda-beda: lima orang dikeluarkan, tapi sisanya cuma menerima penangguhan, masa percobaan, serta teguran tertulis.
Banyak pihak menilai bahwa masih memungkinkan pelaku kekerasan seksual kembali menimba ilmu di kampus adalah gambaran betapa tidak jelas (atau mungkin lemah) pola penerapan hukuman di Yale.
Kendati demikian, Yale bersikukuh telah menerapkan standar tinggi dalam mengusut kasus kekerasan seksual di lingkup kampus.
Diselesaikan Pengadilan atau Internal Kampus?
Pada 1972, Presiden Richard Nixon menandatangani regulasi bernama “Title IX.” Aturan ini, pada dasarnya, melarang ada diskriminasi gender dalam program atau seluruh kegiatan pendidikan yang didanai oleh pemerintah federal, termasuk di lingkup universitas.
Seiring waktu cakupan "Title IX" diperluas. Semasa pemerintahan Barack Obama, "Title IX" dipakai untuk mengatasi masalah kekerasan seksual di kampus-kampus.
Alasan Obama, terlalu banyak korban kekerasan seksual yang suaranya tidak didengar dan terlalu banyak pelaku yang lolos dari jerat hukum. Lagipula, tegas Obama, kekerasan seksual merupakan bagian dari diskriminasi gender, sebab sebagian besar korban adalah perempuan.
Di bawah pemerintahan Obama, hampir semua orang di kampus-kampus AS diminta untuk melaporkan segala sesuatu yang punya indikasi pelanggaran seksual, sekalipun masih sebatas rumor dan kabar angin.
“Lihat, dengar, ketahui, dan laporkan!” adalah jargon yang kira-kira diusung pemerintahan Obama waktu itu.
Selain meminta pihak-pihak di kampus untuk aktif jemput bola, pemerintahan Obama mendorong kampus mengubah standar penyelidikan dengan menurunkan jumlah bukti yang diperlukan agar kasus bisa diusut dengan cepat.
Segera, catat The Atlantic, implementasi aturan "Title IX" pada era Obama memantik kritik dari khalayak.
Pertama, aturan ini telah mengakibatkan penangkapan yang “berlebihan” di lingkungan kampus. Mereka yang sudah dicap sebagai pelaku tetap dijatuhi hukuman meski tanpa ada korban.
Kedua, jumlah bukti minimal untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dianggap tidak sesuai aturan hukum pidana AS (Baca: terlalu rendah). Hitung-hitungannya, untuk bisa menjadikan seseorang tersangka, penyidik kasus harus mengantongi minimal 75 persen barang bukti. Ini berbeda dari aturan Obama yang cuma menetapkan angka pada kisaran 50 persen.
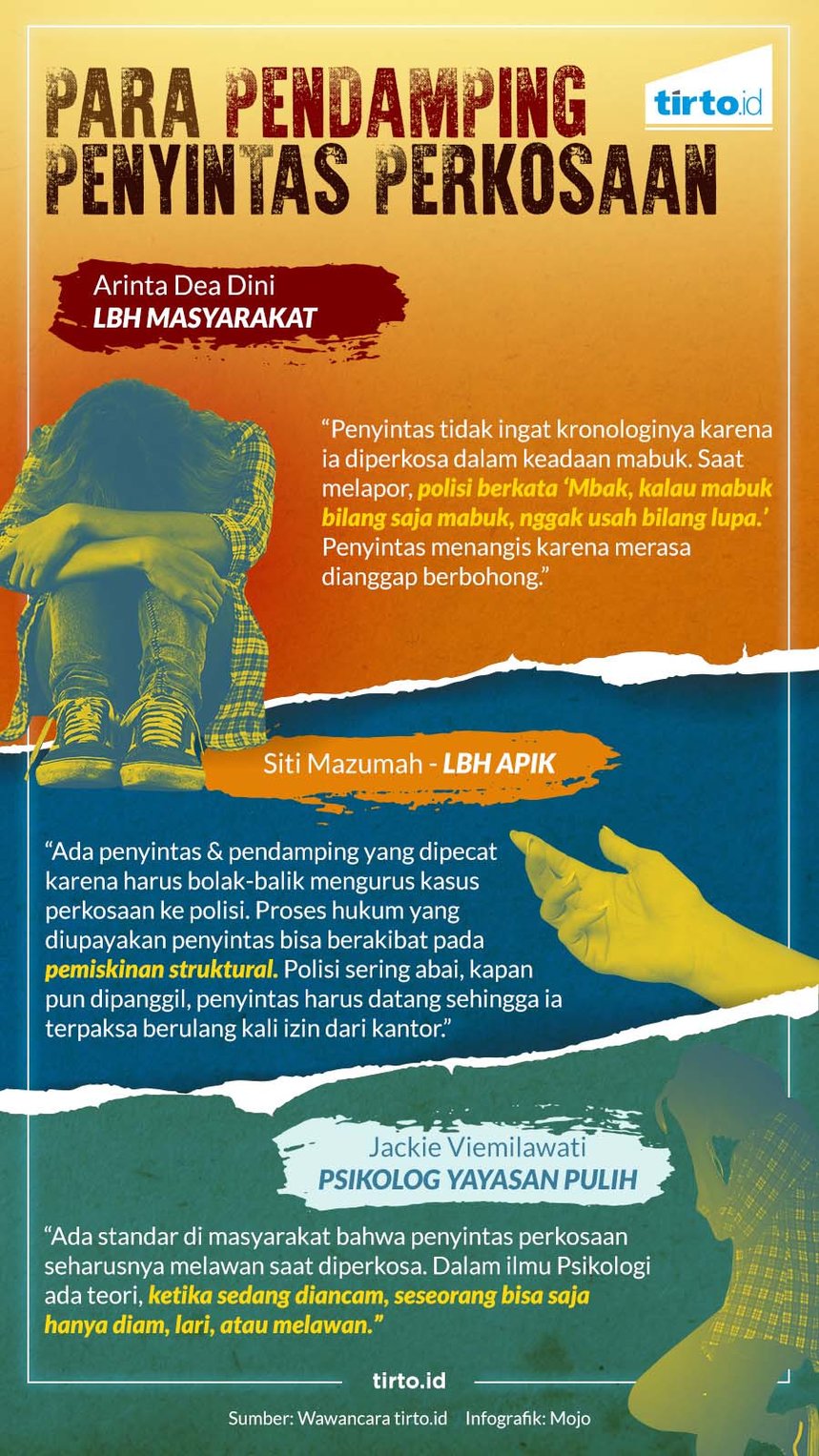
Betsy DeVos, Sekretaris Departemen Pendidikan AS saat itu, menilai sistem yang diterapkan pemerintahan Obama cukup mendiskriminasi kelompok laki-laki. Ia berpendapat yang semestinya menyelidiki dan mengadili kasus kekerasan seksual adalah kepolisian, bukan lembaga akademik.
Langkah berkebalikan diambil pemerintahan Donald Trump. Aturan yang ditetapkan Obama dianulir dan digantikan regulasi yang baru.
Dalam aturan baru itu, pemerintahan Trump mempersempit definisi “kekerasan seksual” di kampus dengan mengadopsi definisi yang ditulis Mahkamah Agung: “Kekerasan seksual merupakan perilaku seks yang parah dan menyinggung orang secara obyektif.”
Kemudian, pemerintahan Trump meminta kampus sekadar jadi tempat penerima keluhan. Untuk tindakan lebih lanjut, akan dipegang oleh pihak berwenang, termasuk dalam memutus perkara lewat mekanisme pengadilan.
Tujuan pemerintahan Trump, atau dalam hal ini Betsy, merevisi aturan yang berlaku di era Obama adalah untuk menyediakan keadilan yang setara bagi korban dan terdakwa.
Lalu, aturan yang baru juga dibikin untuk meminimalisir banyak aksi tangkap yang dinilai “berlebihan” serta membuka kesempatan ada mediasi antara kedua belah pihak (korban dan tersangka).
Gambaran dari implementasi aturan baru tersebut bisa diambil dari kasus Saifullah Khan, mahasiswa Yale, yang dituduh memerkosa teman satu kampusnya pada malam Halloween 2015.
Beberapa waktu silam, ia disidang secara terbuka oleh Pengadilan New Haven atas kasus itu. Khan pada akhirnya diputus tidak bersalah.
Tidak ada catatan resmi mengenai berapa banyak kasus kekerasan seksual di kampus yang dibawa sampai tingkat pengadilan tiap tahun. Departemen Kehakiman AS, sebagaimana dilaporkan The New York Times, memperkirakan korban yang melaporkan kasus kekerasan seksual ke pihak berwenang tak lebih dari 20 persen. Dari angka itu, hanya sebagian kecil yang mengarah ke penangkapan pelaku, apalagi persidangan.
Persidangan Khan tak dapat dipungkiri membelah opini publik. Mereka yang mendukung beranggapan pengadilan adalah cara dan medium tepat untuk menentukan kebenaran dalam mengusut kasus kekerasan seksual.
Pengadilan, pada saat bersamaan, juga menjadi jawaban atas ketidakmampuan pihak kampus dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Pihak kampus dianggap bertele-tele, sarat kepentingan, dan cenderung menutup rapat kasus yang ada karena dinilai berpotensi merusak citra institusi.
Sementara bagi yang menolak, berdiri pada pendapat bahwa pengadilan, dengan segala mekanismenya, hanya tambah membuat korban menjadi trauma.
Dalam kasus Khan, misalnya, beberapa kali pengacara Khan mencecar pertanyaan yang menyudutkan korban (soal pakaian dan sebagainya). Hal itu disebut-sebut sebagai preseden buruk terhadap perlindungan korban.
Untuk kasus Agni di UGM, terlepas dari motif "kesepakatan penyelesaian" yang diambil di belakang meja, ini adalah bukti kegagalan institusi pendidikan dan kepolisian dalam mengusut kasus kekerasan seksual.
Bukan tak mungkin jika kasus Agni adalah permulaan dari penyelesaian kasus-kasus serupa di kampus lain, yang pada akhirnya mengambil jalan pintas "perdamaian", mengabaikan seberapa berat trauma yang dialami oleh korban.
Editor: Nuran Wibisono












