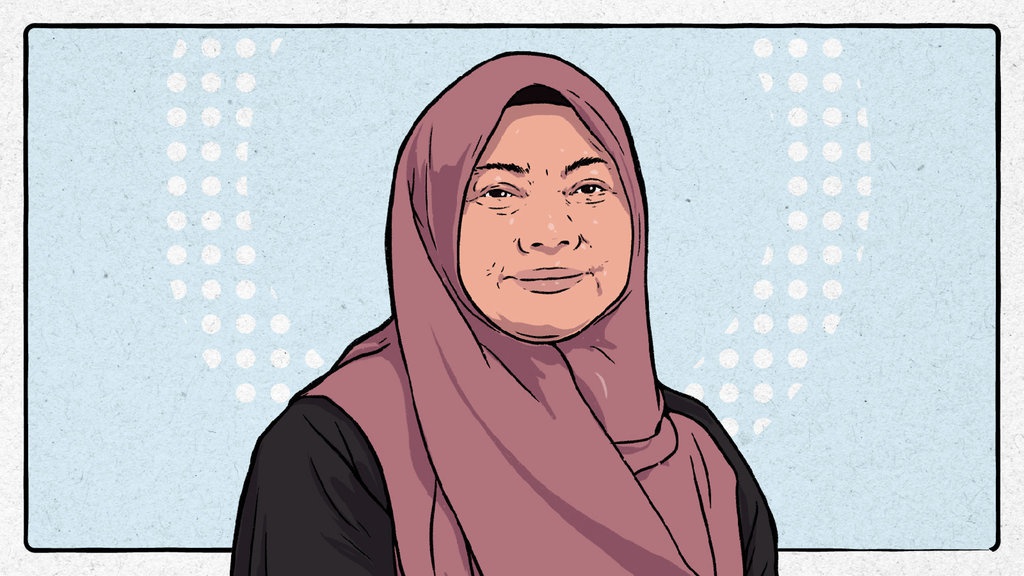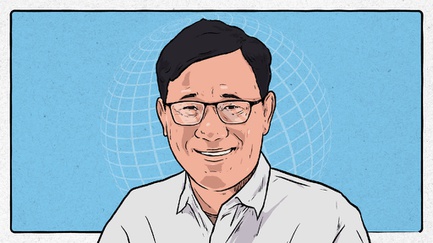tirto.id - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 setidaknya menjadi kado awal tahun bagi demokrasi atau pemilu di Indonesia. Pasalnya, lewat putusan tersebut, MK akhirnya mengabulkan permohonan gugatan terkait penghapusan ketentuan presidential threshold 20 persen bagi pencalonan presiden dan wakil presiden.
Permohonan perkara itu diajukan empat mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, yaitu Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna.
Sikap MK mengabulkan seluruh gugatan pemohon yang menguji norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu kali ini menjadi momen titik balik bagi MK. Terlebih, secara keseluruhan, setidaknya sudah ada sekitar 32 permohonan uji materi serupa ke MK danseluruhnya tidak membuahkan hasil.
"Jadi, ini luar biasa nih. Saya saja yang sudah tiga kali menguji ke Mahkamah Konstitusi itu terkejut. Tidak menyangka karena sudah biasa ditolak," kata pegiat kepemiluan sekaligus dosen Hukum Pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, dalam podcast For Your Politics, di Kantor RedaksiTirto, Jakarta.
Titi mengatakan bahwa pasal presidential threshold 20 persen memang sudah selayaknya dihapuskan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
"Saya melihat ya ini terlepas dari apa pun yang harus kita apresiasi, kita rayakan. Meski, banyak pekerjaan rumah yang juga menunggu dan saya bilang bahwa ini bukan panasea atau obat bagi semua penyakit pemilu kita. Jadi, ini baru awalan dari sebuah perjuangan panjang yang memang harus kita tuntaskan," jelas dia.
Kepada Tirto, Titi juga menceritakan bagaimana perannya dalam menggugat Pasal 222 UU Pemilu di MK. Berikut petikan wawancara kami dengan Titi.
Bagaimana Anda menilai putusan MK terkait dengan presidential threshold?
Dalam konteks itu, kita bersyukur. Meskipun, memang butuh waktu dan pengorbanan yang panjang untuk menggugah iman Mahkamah Konstitusi.
Jadi, di tanggal 2 Januari 2025 itu ada empat perkara. Pertama, Perkara Nomor 62 Tahun 2024 yang dimohonkan oleh empat mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Kedua itu Perkara Nomor 87 Tahun 2024, pemohonnya dosen dari Unsulbar dan Unhas.
Ketiga perkara saya. Kebetulan saya tidak atas nama Perludem karena sekarang saya dosen di FHUI bersama Pak Hadar Nafis Gumay. Perkara Nomor 101 Tahun 2024. Dan yang terakhir ada Perkara Nomor 129 Tahun 2023.
Nah, di antara empat perkara ini, yang memang minta agar ambang batas pencalonan presiden itu dibatalkan dan dinyatakan inkonstitusional sepenuhnya ya empat teman-teman mahasiswa ini. Sementara, tiga permohonan lainnya lebih moderat, mencoba meminta rekonstruksi ambang batas yang lebih mudah. Istilahnya mungkin mau merayu MK supaya MK itu tidak lagi menolak.
Tapi, ternyata justru “kadonya” luar biasa progresif dengan dibatalkannyaPasal 222 Undang-Undang Nomor 7/2017 yang mensyaratkan bahwa kalau ingin mencalonkan presiden harus punya minimal 20 persen kursi atau 25 persen suara sah dari pemilu DPR yang terakhir.
Jadi, ini luar biasa nih. Saya saja yang sudah tiga kali menguji ke Mahkamah Konstitusi itu terkejut. Tidak menyangka karena sudah biasa ditolak.
Secara keseluruhan, yang menguji ke Mahkamah Konstitusi sebelum ada putusan yang dikabulkan itu sudah 32. Ditambah yang empat di tanggal 2 Januari 2025, berarti total 36 ya.
Dari 32 permohonan uji materi itu, kami petakan bahwa 24 itu tidak dapat diterima. Persoalannya apa? Persoalannya legal standing. Jadi, dari aspek kedudukan hukum, MK menganggap mereka enggak punya kepentingan langsung terhadap apa yang diujikan.
Menurut MK, yang punya legal standing harusnya partai politik atau orang yang punya hak untuk dipilih dan dicalonkan oleh partai. Artinya, dia adalah orang yang dapat tiket dari partai, tapi kemudian tidak bisa mencalonkan karena tidak terpenuhinya syarat ambang batas. Itulah yang dianggap punya legal standing.
Sementara itu, enam perkara lain ditolak karena dalil yang dikemukakan tidak beralasan. Jadi, dalil mereka tidak terbukti menurut MK. Lalu, dua perkara lain itu ditarik kembali oleh pemohonnya, yang pertama Ki Gendeng Pamungkas karena meninggal dunia dan yang kedua Jaya Suprana.
Barulah empat permohonan yang terbaru ini beragam. Perkara Nomor129/2023 itu diajukan oleh advokat Gugum Ridho. Dia minta agar ada ambang batas maksimal. Kata dia oke enggak apa-apa ada ambang batas minimal yang 20 persen kursi atau 25 persen suara sah. Tapi, koalisi pencalonan itu enggak boleh lebih dari 40 persen atau 50 persen dari total kepemilikan kursi atau suara.

Permohonan saya dan Pak Hadar serta dosen Unsulbar dan Unhas itu mintanya peninjauan syarat ambang batas itu. Kami mengajukan demikian bukan karenahopeless sudah 30 kali ditolak ya. Kami cari cara supaya pilpres kita itu lebih inklusif dan beragam.
Akhirnya, dengan studi dan membangun argumentasi berdasarkan perkembangan putusan MK sebelumnya, saya dan Pak Hadar itu minta agar semua partai parlemen punya hak untuk mencalonkan.
Sementara, partai nonparlemen diatur ambang batasnya oleh pembentuk undang-undang. Persyaratannya seperti apa, nanti diputuskan oleh pembentuk undang-undang.
Ternyata, luar biasa MK justru menjawab permohonan yang substansinya selama ini 30 kali ditolak. Dan kalau kita baca isi putusan MK, sebenarnya terus terang, dengan segala apresiasi kepada MK, tidak ada yang baru argumennya. Yang membedakan adalah MK sekarangmelakukan penilaian atas praktik penerapan syarat ambang batas minimal selama ini.
Sebelumnya, syarat pencalonan itu selama ini dikatakan merupakan kewenangan hukum pembentuk undang-undang. Syarat itu boleh ada juga boleh tidak ada. Maka ketika pembentuk undang-undang membuat persyaratan ambang batas 20 persen kursi atau 25 persen suara sah, MK mengatakan itu konstitusional.
Sekarang, MK itu pasang rambu-rambu openlegal policy.Rambu pertama itutidak boleh melawan atau melanggar moralitas. Kedua, tidak boleh melanggar rasionalitas. Yang ketiga, tidak boleh mengandung perbuatan atau kebijakan yang memuat ketidakadilan yang intolerable atau tidak dapat ditoleransi.
Berikutnya adalah tidak boleh menghilangkan hak politik warga dan hak politik peserta pemilu. Dan yang terakhir itu tidak boleh bertentangan dengan kedaulatan rakyat.
Ternyata, MK selama ini, di dalam permohonan-permohonan terdahulu, belum menilai openlegal policyitu. Barulah setelah tujuh tahun lebih Pasal 222 UU Pemiluberlaku, MK—dalam bahasa saya—siuman. Atau lebih ekstremnya, bertobat.
Latar belakang Andamenggugat presidential threshold apa?
Ambang batas pencalonan presiden itu bukan hal baru. Saya ikut pilpres itu sejak 2004 karena memang itu pilpres pertama. Pilpres 2004 itu kita punya lima pasangan calon dan kompetisinya itu semarak. Partai berusaha betul untuk menemukan kader-kader terbaik mereka.
Pada waktu itu, ambang batas pencalonannya itu 3 persen kursi atau 5 persen suara sah hasil pemilu DPR. Di Pemilu Presiden 2009, ambang batas itu naik menjadi 20 persen kursi atau 25 persen suara sah yang sama dengan isiPasal 222 Undang-Undang Nomor 7/2017.
Pada waktu itu, apakah ada yang menggugat ke MK? Ada. Misalnya, Pak Saurip Kadi, lalu partai-partai kecil seperti PBB, Hanura, PPRN, Republikan. Jadi, bukan ketika Undang-Undang Nomor 7/2017 saja [mulai digugat].Dari dulu, juga sudah ada yang menggugat.
Tapi, MK ya selalu mengatakan itu kewenangan hukum pembentuk undang-undang. Mau ada atau tidak ada [ambang batas itu], ya kewenangan pembentuk undang-undang. Itu terus dilanggengkan sampai 2014. Pilpres 2014, Pilpres 2019, dan Pilpres 2024.
Saya pertama kali menguji ke MK bersama Pak Hadar Nafis Gumay itu tahun 2017 dengan Perkara Nomor 71 Tahun 2017. Segera setelah Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7/2017 [berlaku] saya dan teman-teman lain—waktu itu saya masih Direktur Eksekutif Perludem—menggugat ke MK.
Karena kenapa? Pertama, ketentuan tersebut tidak sesuai dengan UUD1945. Pasal 6A Ayat 2 UUD 1945 mengatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Artinya, partai bisa bertindak sendiri atau bertindak bergabung dengan partai lain.
Jadi, keberadaan syarat harus punya 20 persen kursi atau 25 persen suara kan bisa menghilangkan hak partai untuk sendiri mengusulkan. Dia tersandera oleh syarat 20 persen kursi atau 25 persen suara. Nah, itulah alasan yang paling mendasar: basis konstitusi.
Kedua, sebagai warga negara, saya ingin setiap anak bangsa punya peluang jadi kepala daerah, jadi presiden atau wakil presiden. Kita ini kan populasinya ratusan juta, ragam suku, ragam etnis, ragam agama, sosial, budaya. Jadi, ruang-ruang kontestasi itu harusnya dibuka lebih inklusif.
Terakhir, menurut kami pada waktu itu pasal ambang batas pencalonan presiden itu melemahkan eksistensi partai politik sebagai institusi kaderisasi, rekrutmen politik, dan regenerasi politik.
Partai sudah susah-susah jadi peserta pemilu, melakukan kaderisasi, tapi kemudian tidak bisa mempromosikan kader terbaiknya dan harus dipaksa berkoalisi yang dalam banyak hal tidak alamiah.
Itu bahkan membuka ruang-ruang politik transaksional. Partai yang punya suara dan kursi besar posisi tawarnya lebih tinggi, sementara partai yang belum punya kursi atau partai baru kan akhirnya posisi tawarnya menjadi lemah.
Dengan pertimbangan itu, kayaknya semua yang didalilkan MK dalam putusan yang mengabulkan, kayaknya sudah pernah didalilkan dalam putusan yang 30 ditolak.
Akhirnya, di Putusan MK Nomor 62/2024 momentum itu datang setelah 7 tahun lebih setelah 2017. Dan tampaknya, memang harus melalui tangan-tangan teman-teman mahasiswa.

Apakah permohonan uji materi oleh mahasiswa itu jadi strategi juga? Karena teman-teman mahasiswa ini kan polos, mungkin mereka juga lebih peduli...
Kalau menurut saya, mereka otentik. Mereka itu resisten dalam perjuangan. Kalau kami, mencoba memahami realitas politik di dalam permohonan yang kami ajukan. Karena sudah 30 kali ditolak, setidaknya kan harus ada solusi ya.
Jadi, ketika kami mengajukan skema seperti yang kami mohonkan, itu sebenarnya juga bertentangan dengan keyakinan konstitusi yang kami miliki. Di dalam dua permohonan sebelumnya kami mintanya dihapus. Berkaca dari 30 putusan yang ditolak, kami ingin mencari solusi setidaknya jangan sampai MK menolak lagi.
Tapi, teman-teman mahasiswa ini memang menunjukkan resistensi dan sikap yang otentik. Jadi, terlepas sudah 30 yang ditolak, ketika keyakinan akademik dan konstitusi mereka bahwa memang ambang batas itu inkonstitusional, kepercayaan diri itu yang mereka bangun.
Kalau Almas Tsaqibbiru saja bisa, kenapa mereka tidak bisa menggugah MK? Di kasus Almas, MK juga mengubah pendiriannya soal usia.
Dan itu insentifnya kan dirasakan cuma satu orang. Tapi, ini [penghapusan presidential threshold 20 persen] insentifnya kan untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk semua partai. Tidak ada yang dirugikan dan semua diuntungkan, masyarakat merasakan manfaatnya. Jadi, ya memang otentisitas itu yang dimiliki oleh teman-teman mahasiswa ini.
Menurut Anda, kenapa akhirnya MK memutuskan untuk “bertobat”?
Terakhir MK itu memutus perkara ini adalah di tahun 2023. Saat itu, MK masih tetap menganggap ambang batas pencalonan presiden itu sebagai kewenangan hukum pembentuk undang-undang atau openlegal policy ya.
Lalu, kenapa MK bisa berubah? Itu tidak terlepas dari pemikiran MK sendiri. Walaupun itu open legal policyyang merupakankewenangan pembentuk undang-undang, bukan berarti MK tidak bisa menilai konstitusionalitasnya.
Kalau open legal policy atau kewenangan pembentuk undang-undang itu dieksekusi dengan cara-cara melanggar moralitas, rasionalitas, mengandung ketidakadilan yang intolerable, bertentangan dengan hak politik dan juga kedaulatan rakyat, MK bisa melakukan penilaian dan mengubah pendirian hukumnya.
Itulah yang dilakukan oleh MK. Akhirnya, MK mengatakan bahwa rezim ambang batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden itu bertentangan dengan UUD 1945 dan inkonstitusional.
Jadi, rezim ambang batasnya itu yang enggak boleh. Eggak boleh lagi kita nyebutnol persen karena nol itu pun masih angka.
Kembali ke pertanyaan kenapa MK bisa begitu? Pertama, MK meneguhkan kembali original intent ketika UUD diamandemen. Enggak ada omongan soal ambang batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden saat konstitusi itu diamandemen antara 1999 sampai 2002. Kan empat kali kita mengamandemen UUD 1945.
Kedua, ternyata MK melihat praktiknya. Ada kecenderungan bahwarezim ambang batas ini menguntungkan hanya partai-partai besar. Dan kecenderungan untuk hanya menghadirkan dua pasangan calon di beberapa pilpres terakhir.
Kalau dibiarkan, kata MK, itu bisa mengakibatkan terjadinya calon tunggal di pilpres seperti halnya fenomena pilkada bercalon tunggal atau pilkada dengan kotak kosong di beberapa waktu terakhir.
Kata MK itu tidak sesuai dengan semangat amandemenUUD 1945 yang ingin memperkuat kedaulatan rakyat melalui pilpres langsung. MK ingin kedaulatan rakyat itu diwadahi, bukan hanya hak untuk memilih, tapi juga hak untuk dipilih yang lebih beragam, lebih inklusif.
Dan sebenarnya, argumen MK tidak baru juga kalau menggunakan syarat perolehan kursi atau suara pemilu DPR. Syarat itu mengaburkan sistem presidensial dan membuat sistem presidensial dalam bayang-bayang parlementer.
Sistem presidensial sumber legitimasinya itu bukan dari calon presiden, bukan juga dari parlemen, tapi dari rakyat. Karena, presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Kalau di dalam sistem parlementer kan tidak ada pilpres. Karena, partai pemenang pemilu di parlemen—dengan syarat membentuk koalisi—otomatis akan bisa mengajukan tokohnya sebagai perdana menteri. Tidak perlu ada pemilihan.
Karena itu, akan mengherankan bila kita pakai sistem presidensial, tapi pencalonan kandidat kepala negara sekaligus kepala pemerintahan kok bergantung pada kekuatan parlemen.
Lalu, MK juga menemukan ternyata dalam praktik penerapan ambang batas minimal itu tidak berkorelasi dengan penyederhanaan partai politik di parlemen. Jadi, kata MK, ternyata enggak ada hubungannya itu antara ambang batas pencalonan presiden dengan penyederhanaan partai politik peserta pemilu.
Hal-hal seperti itu udah pernah dilihat MK belum sih di penolakan-penolakan sebelumnya?
Terus terang saja ya, semua argumen MK itu pernah diargumenkan oleh para pemohon yang 30 permohonannya ditolak. Jadi, tidak ada yang baru.
Kalau saya sih menyebutnya ya MK tersadarkan. Titik baliknya, dugaan saya, adalah ketika MK memutus soal ambang batas pencalonan kepala daerah. Saat itu, ambang batas pencalonan kepala daerah diturunkan dari 20 persen kursi atau 25 persen suara DPRD menjadi 6,5 sampai 10 persen.
Ternyata, itu disikapi [partai-partai] dengan upaya membangun dominasi pencalonan. Akhirnya, semangat untuk [membuat] akses kepada pencalonan yang lebih inklusif itu malah justru tidak terjadi.
Istilahnya itu dilakukan semacam blocking-blocking politik atau praktik borong partai.
Saya menduga titik balik MK adalah implementasi atas Putusan 60 dan praktik pada pilpres antara 2014, 2019, dan 2024 yangpunya kecenderungan untuk melegitimasi dan mendominasi kekuatan politik itu makin kuat.
MK itu kan tidak bisa dibilang bekerja di ruang hampa. Realitas politik ketatanegaraan, kebuntuan dalam sistem politik dan ketatanegaraan pasti menjadi pertimbangan MK.
Kecenderungan untuk hanya menghadirkan dua pasangan calon dalam pemilu itu, berdasarkan penalaran yang wajar, itu menjadi basis bagi MK [memutuskan] bahwa ada moralitas politik dan demokrasi yang terlanggar. Ada ketidakadilan yang intolerable yang sudah terjadi.
Nah, di 2024 ada apa? Ada pilpres dan ada pilkada karena MK juga menyebut soal fenomena calon tunggal atau pilkada kotak kosong di 2024. Artinya, MK membaca itu semua. MK juga menyebut bahwa ambang batas pencalonan presiden itu berkontribusi pada polarisasi di masyarakat karena keterbatasan pilihan.
Tapi, bagaimanapun kan ini momentumnya sekarang. Dalam sebuah tulisan saya di media, saya bilang bahwa evaluasi MK atas praktik open legal policy pembentuk undang-undang puncaknya itu di Pemilu dan Pilkada 2024. Itu bertemu momentumnya dengan permohonan teman-teman dari UIN.
MK memang sudah sangat gelisah dengan dinamika ketatanegaraan kita yang dirasa makin jauh dari tujuan perubahan konstitusi dan juga tujuan reformasi.
Jadi, terlepas dari apa pun, keputusan kali ini harus kita apresiasi, kita rayakan. Meski banyak pekerjaan rumah yang juga menunggu dan saya bilang bahwa ini bukan panasea atau obat bagi semua penyakit pemilu kita. Jadi, ini baru awalan dari sebuah perjuangan panjang yang memang harus kita tuntaskan.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id