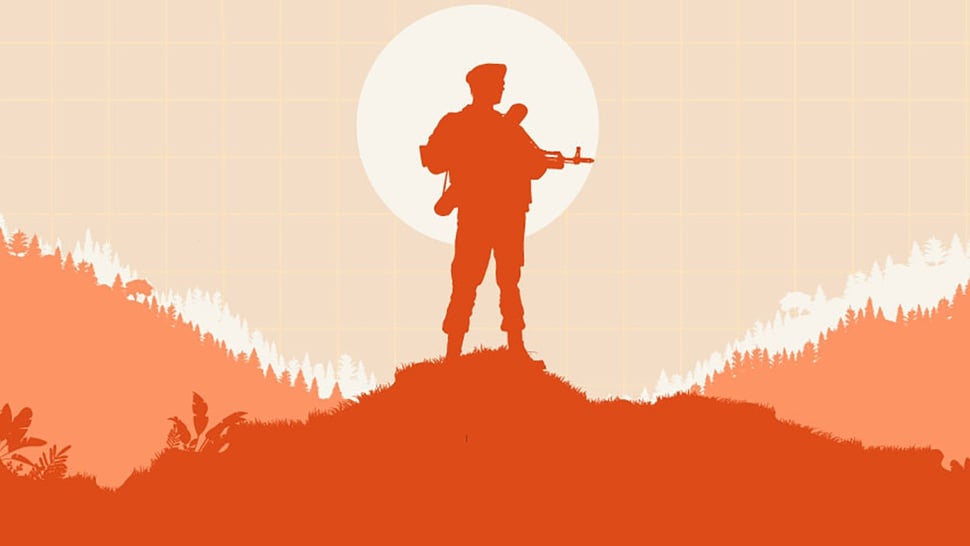tirto.id - Pada 15 Maret 1966, Soe Hok Gie dan Jopie Lasut berangkat ke Bandung. Mereka berdua ditugaskan untuk memastikan kebenaran informasi yang menyebut Panglima Kodam Siliwangi Mayor Jenderal Ibrahim Adjie membelot dari Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Dua Jenderal lain, Brigadir Jenderal Dharsono dan Brigadir Jenderal Suwarto—yang berkedudukan di Bandung, kemudian membantah tuduhan tersebut.
“Kami datang ke sini bukan wakil KAMI (Komite Aksi Mahasiswa Indonesia). Sepanjang pengetahuan saya, para mahasiswa tidak akan mempertahankan kerja sama dengan ABRI jika jenderal-jenderalnya masih hidup mewah-mewahan,” kata Soe Hok Gie seperti diingat dan ditulis Jopie dalam buku Soe Hok Gie Sekali Lagi (2010, hlm. 411).
Menurut Jopie, Dharsono menganggap tuduhan itu sebagai keganjilan. Namun, Suwarto—yang agaknya lebih paham kemauan mahasiswa—setuju dengan Hok Gie.
“Yah, tapi jangan dimasukan jenderal-jenderal seperti kita-kita ini, dong. Kami masing-masing hanya memiliki satu mobil pribadi yang kami bawa dari luar negeri. Itu pun untuk modal penyambung hidup,” kata Suwarto dengan penuh keakraban.
Dalam film Gie (2005), sosok Suwarto dihadirkan sebagai perwira yang dekat dengan mahasiswa. Dia ditemui Hok Gie dan kawan-kawan pada malam hari.
Di medio 1960-an, Suwarto adalah Wakil Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Bandung. Menurut Jopie, Suwarto mengaku telah mengubah kurikulum di lembaga pendidik para calon jenderal tersebut. Suwarto beranggapan siswa Seskoad haruslah mendalami persoalan masyarakat dengan berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Yang dibutuhkan sekarang ini adalah kader-kader pembangunan dan bukan kader-kader perang. Perang itu masih jauh, sedangkan kemiskinan sudah di depan mata kita,” kata Suwarto waktu itu.
Tak sekadar asal bicara, Suwarto menang dikenal sebagai jenderal yang cukup dekat dengan dunia kampus. Dia jugalah yang menjembatani hubungan antara kampus dan militer.
“Kerja sama dan hubungan baik antara universitas dengan Angkatan Darat sebenarnya dirintis oleh Suwarto,” tulis Hok Gie dalam artikelnya “Kuli Penguasa atau Pemegang Saham” yang terhimpun dalam Zaman Peralihan (1995, hlm. 56).
Menurut Hok Gie, Mayor Jenderal Suwarto berpikir bahwa tentara bukan sekedar alat pertahanan saja. Karenanya, Suwarto kerap mengundang para pemikir dan tokoh-tokoh universitas untuk ikut mengajar di Seskoad. Seskoad bahkan berani mengambil opini berbeda dari Presiden Sukarno. Seskoad, misalnya, berani mempekerjakan Mochtar Kusumaatmadja yang dipecat dari Universitas Padjadjaran karena kritis pada pemerintahan.
Pada awal 1966, kala demonstrasi mahasiswa menghebat, Suwarto sempat terlihat hadir di sekitar Senayan. Menurut Jopie, dia sengaja datang ke Jakarta supaya dapat bertindak sebagai katalisator antara para mahasiswa dan tentara (Siliwangi, RPKAD, Kavaleri). Padahal, Suwarto saat itu dalam kondisi sakit-sakitan.
Alumnus Amerika di Seskoad
Suwarto yang lahir di Semarang, 5 Desember 1921, termasuk dalam jajaran perwira yang sempat mencicipi pendidikan militer Amerika Serikat. Beberapa jenderal Angkatan Darat yang juga pernah sekolah militer tingkat lanjut di Amerika di antaranya adalah Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani, M. Jusuf, dan arwo Edhi Wibowo.
Yani dan Suwarto pernah belajar di US Army Command and General Staff di Fort Leavenworth, Kansas. Suwarto belajar di sana pada 1959.
Sejak 1 Juni 1966, Suwarto diangkat menjadi Komandan Seskoad menggantikan Mayor Jenderal Raden Soedirman—ayah dari mantan Gubernur Jawa Timur Basofi Soedirman.
Pada 25-31 Agustus 1966, Seskoad mengadakan Seminar Angkatan Darat Kedua di Graha Wiyata Yudha. Seperti sebelum-sebelumnya, Suwarto pun turut menghadirkan para pakar politik dan ekonomi ke seminar tersebut.
Terkait seminar itu, Ulf Sundhaussen dalam Politik Militer Indonesia 1945-1967 (1986, hlm. 422) menyebut, “Dengan seksama dipimpin oleh Brigadir Jenderal Suwarto, dalam kesimpulannya mengulangi tema yang sudah tidak asing lagi bahwa Angkatan Darat, yang lahir dalam revolusi dan dengan demikian mempunyai hak dan kewajiban untuk memikul tanggung jawab di luar militer, telah terpaksa memperluas kegiatan non-militernya.”
Menurut Sundhaussen, kesimpulan itu bahkan melampaui gagasan Nasution tentang peran ABRI. Setelah Soeharto jadi presiden, kesimpulan seminar itu ditafsir dan diwujudkan menjadi Dwifungsi ABRI.
Implementasi dari kesimpulan seminar itu pun meluas ke ranah kebijakan pembangunan nasional. Sayidiman Suryohadiprodjo dalam Kepemimpinan ABRI (1996, hlm. 327) menulis, “Pembangunan nasional yang dimulai pada 1 April 1969 berpangkal pada Seminar TNI-AD ke-2 dalam tahun 1966.”

Perjalanan Karier Suwarto
Suwarto adalah tentara yang terdidik. Dia lulusan SMA bagian B pada zaman Hindia Belanda dan sempat kuliah teknik di sekolah tinggi teknik kolonial yang sekarang jadi Institut Teknologi Bandung (ITB).
Jelang kedatangan serdadu Jepang ke Indonesia, Suwarto muda bersiap. Menurut Benjamin Bouman dalam Van driekleur tot rood-wit: de Indonesische officieren uit het KNIL, 1900-1950 (1995, hlm. 395), dia sempat mendapat pelatihan artileri dalam kesatuan milisi pribumi.
Sebagai pemuda terpelajar, Suwarto punya peluang jadi perwira bila Hindia Belanda mampu bertahan dari serangan Jepang. Namun, kenyataannya Hindia Belanda menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942. Di zaman Jepang, Suwarto adalah golongan yang sulit diterima militer Jepang untuk jadi perwira PETA, meski dia lebih terpelajar daripada kebanyakan perwira PETA.
Setelah Indonesia merdeka, Suwarto ikut Republik. Sundhaussen (hlm. 22) menyebut Suwarto sempat memimpin tentara pelajar di sekitar Bandung. Harsya Bachtiar dalam Siapa Dia? Perwira Tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (1988, hlm. 423) menyebut dia pernah menjadi Kepala Staf Batalyon Nasuhi dan Wakil Komandan Brigade Nasuhi di masa revolusi.
Pada 1950 dia adalah Komandan Batalyon di Jawa Barat, lalu Komandan Resimen 11 di sisi timur Jawa Barat. Mayor Suwarto yang orang Jawa, menurut Sundhaussen (hlm. 172), adalah perwira yang tidak menyukai Sukarno. Menurutnya, Sukarno mengambil langkah terlalu lembek kala Yogyakarta diserang Belanda pada 1948 sehingga dia menjadi tawanan Belanda.
Suwarto juga tidak suka dengan inefisiensi kabinet parlementer era 1950-an. Karena itu, dia melibatkan diri dalam gelombang Peristiwa 17 Oktober 1952 yang menuntut eksekutif sipil tak ikut campur dalam urusan kemiliteran. Dia sempat dipecat gara-gara terlibat, meski kemudian diterima berdinas kembali setelah masalah mereda.
Sewaktu bertugas di Jawa Barat, Suwarto berjibaku melawan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pimpinan Kartosuwiryo. Seperti dicatat Sundhaussen (hlm. 242-243), Suwarto menerapkan strategi militer yang dibarengi strategi ekonomi dan sosio-politik untuk mengucilkan para pemberontak dari masyarakat umum.
Pada akhir 1950-an, Suwarto yang sudah berpangkat kolonel ikut terlibat dalam Dewan Perancang Nasional. Dia didapuk sebagai perwakilan Angkatan Darat dan ditunjuk pula menjadi Wakil Ketua dewan itu. Suwarto kemudian mengusulkan agar perang teritorial dijadikan doktrin pertahanan resmi. Menurutnya, langkah itu relevan karena saat itu Indonesia belum mempunyai Angkatan Udara dan Angkatan Laut yang mumpuni sebagai tameng serangan dari luar.
Karena itu pula, kedua angkatan tersebut kemudian mulai diperkuat sejak awal 1960-an. Indonesia secara khusus mendatangkan alutsista canggih yang kebanyakan berasal dari negara Blok Timur (negara-negara komunis).
Setelah sekolah di Amerika, dia ditempatkan di Seskoad. Mayor Jenderal Suwarto hanya menjadi komandan Seskoad hingga 28 September 1967—kala dia wafat karena sakit yang dideritanya. Setelah meninggal dunia, dia mendapat kenaikan pangkat menjadi Letnan Jenderal Anumerta.
Editor: Fadrik Aziz Firdausi