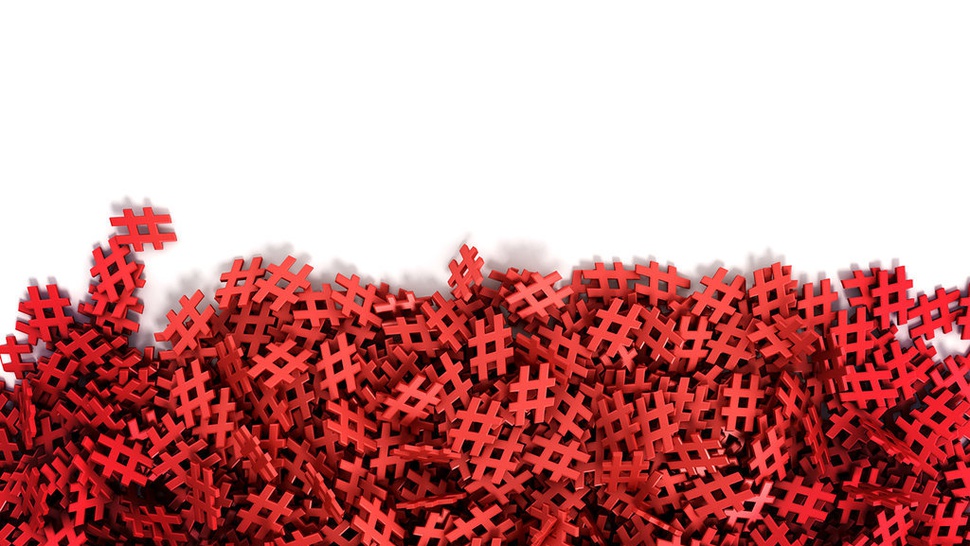tirto.id - Dalam sepekan terakhir, dua kasus menyita banyak perhatian. Pertama, kasus tertangkapnya Tora Sudiro dan Mieke Amalia terkait psikotropika Dumolid. Kedua, perkara tuduhan pencemaran nama baik Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan fitnah pasal 310-311 KUHP yang dilayangkan PT Duta Paramindo Sejahtera (pengelola Apartemen Green Pramuka City/APG) kepada Muhadkly "Acho".
Baca juga:
- Tora Sudiro dan Mieke Amalia Ditangkap Karena Narkoba
- Menagih Hak Acho Sebagai Konsumen di Kasus Green Pramuka
Baik dari kasus Tora maupun Acho, lahir suatu aksi kepedulian melalui tagar di media sosial. Mereka yang memberi dukungan moral terhadap Tora menggunakan tagar #sayabersamatora. Sampai tanggal 8 Agustus di Instagram, tagar ini telah digunakan 3.464 kali, sementara di Twitter, terdapat 1.955 cuitan yang menggunakan tagar ini. Lain lagi dengan tagar #AchoGakSalah. Aktivisme yang bertujuan membela hak Acho sebagai konsumen ini digunakan di Instagram sebanyak 597 kali dan di Twitter sebanyak 1.931 kali.
Penggunaan tagar sebagai wujud kepedulian atau aktivisme mendukung pihak-pihak atau isu tertentu memang telah dimanfaatkan warganet beberapa tahun belakangan ini. Ada alasan mengapa media sosial dan tagar dipilih untuk melakukan aktivisme. Popularitas media sosial di berbagai kalangan membuat pesan aktivisme lebih mudah disebarkan ke banyak orang dan dalam waktu yang lebih singkat. Menurut data dari The Cultureist pada 2013, sekitar 175 juta cuitan dipublikasikan setiap harinya, sedangkan jumlah foto yang diunggah di Instagram mencapai 40 juta per hari.
Tagar memang bisa menjadi alat yang ampuh untuk mengumpulkan solidaritas massa karena merupakan suatu simbol sederhana yang mudah melekat di benak orang-orang. Saat terjadi aksi terorisme di Paris misalnya, ramai-ramai warganet dari berbagai penjuru dunia menyematkan tagar #prayforparis dalam status, cuitan, maupun gambar yang diunggah di media sosial.
Ada beberapa hal yang membuat aktivisme di media sosial membuahkan hasil positif di kehidupan nyata. Merlyna Lim (2013), dalam jurnalnya yang berjudul Many Clicks, But Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia mengatakan bahwa terdapat beberapa kriteria yang mendorong kesuksesan suatu aktivisme digital: narasi yang sederhana, kongruen dengan narasi dominan, cenderung berisiko kecil, serta penggunaan simbol-simbol tertentu.
Ketika orang awam dengan mudah memilah mana pihak yang baik dan mana pihak yang berintensi buruk, kemungkinan sukses suatu aktivisme akan makin besar. Kasus Prita Mulyasari yang sempat dituntut RS Omni Batavia pada 2008 lampau misalnya, berhasil menarik perhatian dan dukungan khalayak lantaran ia dipandang sebagai sosok ibu tak bersalah ketika menyampaikan keluhannya sebagai konsumen, serupa tapi tak sama dengan Acho.
Lain halnya jika berbicara tentang aktivisme untuk membela hak-hak kaum LGBT. Lantaran narasi dominan di Indonesia masih berpondasi pada nilai-nilai agama dan heteronormativitas, tentunya tidak mudah bagi para aktivis LGBT untuk meraih kesuksesan. Strategi yang sama dengan aktivisme-aktivisme lain di media sosial pun tak bisa sepenuhnya diandalkan untuk menciptakan kesadaran penerimaan perbedaan orientasi seksual dan kesadaran pemenuhan hak azasi kaum LGBT sebagaimana orang-orang heteroseksual.
Begitu suatu wacana ramai diperbincangkan di media sosial, potensi diangkatnya wacana ini di media-media lain seperti televisi, radio, dan surat kabar pun akan meningkat, demikian pendapat Bonilla & Rosa (2015) yang meneliti soal aktivisme tagar #Ferguson sebagai wujud solidaritas terhadap remaja kulit hitam di AS yang ditembak polisi. Senada dengan Lim, Bonilla & Rosa menyatakan, penggunaan simbol tertentu mampu memompa keberhasilan suatu aktivisme. Tak hanya dengan tagar, aksi dan gambar pun bisa dilibatkan dalam suatu aktivisme di media sosial untuk menarik lebih banyak lagi simpati khalayak. Dalam jurnal mereka dicantumkan sebuah gambar sekelompok mahasiswa Howard University yang terlihat mengangkat tangan. Gambar tersebut dipublikasikan di Twitter oleh David Flores pada 16 November 2014 dengan dibubuhi tagar #100DaysOfInjustice, #Ferguson, #HandsUpDontShoot.
Penggunaan gambar bersamaan dengan tagar ini juga tampak dalam aktivisme #sayabersamatora di Instagram dan Twitter. Ribuan gambar yang menampilkan sosok Tora Sudiro diekori dengan cerita singkat pengalaman dan persepsi terhadap aktor tersebut dengan mudah ditemukan begitu seseorang menekan tagar tersebut. Meski Tora dinyatakan sebagai tersangka atas kepemilikan psikotropika secara ilegal, mereka yang mengunggah gambar dengan tagar #sayabersamatora tidak ragu untuk memberi dukungan moral terhadapnya. Mereka percaya Tora adalah sosok baik yang tengah tertimpa kemalangan. Alih-alih ditinggalkan, justru ia perlu diberikan semangat meski tak melulu secara langsung.

Meski aktivisme tagar jamak ditemukan di media sosial, beberapa pihak menganggap hal ini potensial berhenti di kegiatan mengeklik saja alias clicktivism, atau dalam bahasa Lim, slacktivism. Artinya, warganet yang memublikasikan konten bertagar tertentu hanya sekadar meneruskan aktivitas orang-orang di lingkarannya atau sesuatu yang sedang trending. Sejenak kemudian, kepedulian mereka dianggap akan menguap dan tidak menyisakan tindak lanjut di masa depan.
Namun, benarkah aktivisme tagar merupakan hal remeh temeh? Memang tidak bisa dimungkiri, proses hukum di Indonesia tidak akan terintervensi oleh adanya aktivisme dalam macam-macam bentuk. Kendati demikian, dampak lain yang tak bisa diabaikan pun bisa terjadi akibat aktivisme yang mencuat di media sosial ini. Tengok saja kasus kriminalisasi Ahok yang memicu aktivisme tagar #lilinforAhok. Masifnya aktivisme ini tak pelak mengundang media-media asing untuk menyoroti situasi sosial politik di Indonesia. Beberapa negara yang tergabung dalam PBB bahkan mendesak Indonesia untuk mencabut regulasi tentang penistaan agama seiring dengan kasus penahanan Ahok silam.
Terkait dengan efektivitas aktivisme di media sosial, Tirto mewawancarai Dhyta Caturani, aktivis yang mendirikan PurpleCode Collective, sebuah komunitas yang terdiri dari para pemerhati isu gender dan teknologi. Dhyta mengungkapkan, suatu aktivisme bisa dibilang efektif atau tidak, tergantung kepada tujuan dibuatnya hal tersebut.
"Kadang kala tagar memang dibuat dengan ekspektasi tujuan yang paling realistis dan itu sering kali terbukti efektif. Tetapi terkadang, aktivisme tagar dibuat dengan ekspektasi yang tinggi dan kemudian tidak terbukti efektif. Yang paling penting untuk diingat adalah popularitas tagar tidak selalu linear dengan keberhasilan gerakan yang dimaksudkan dengan tagar tersebut," jelas Dhyta.
Efektivitas aktivisme di media sosial juga bergantung pada apakah isu yang diangkat menyentuh empati masyarakat atau merupakan isu kolektif. Dhyta mencontohkan fenomena aktivisme Cicak vs Buaya yang meraup perhatian khalayak lantaran hal tersebut merupakan isu kolektif. "Korupsi merupakan kemuakan kolektif, itulah yang menggerakkan orang untuk melakukan aktivisme," kata Dhyta.
Perempuan pemerhati digital rights ini juga menjelaskan kendala melakukan aktivisme di dunia online. Menurutnya, problem terbesar dari aktivisme tagar adalah sering kali aktivisme ini menjadi ilusi bahwa dengan melakukan aktivisme tagar saja sudah cukup, terutama untuk isu-isu yang sebenarnya membutuhkan kerja nyata di dunia offline. "Perasaan kecukupan dengan terlibat dalam gerakan tagar ini kerap membuat orang malas untuk ikut terlibat dalam gerakan secara offline. Problem lain adalah time span yang pendek. Banyaknya isu yang ada dengan keriuhannya masing-masing membuat perhatian orang memiliki time span yang pendek. Memang hal ini tidak selalu terjadi, tetapi mayoritas seperti itu," imbuh Dhyta.
Lantas, bagaimana mengukur kesuksesan aktivisme di media sosial?
Dhyta mengungkapkan bahwa tolok ukur kesuksesan hal ini sangat variatif. Kembali lagi kepada tujuan aktivisme dibuat. "Contoh, bila seandainya tujuannya adalah mengangkat isu dan membuat orang aware terhadap isu tertentu, maka mengukurnya bisa dilihat dari seberapa banyak atau seberapa ramai orang ikut terlibat dalam aktivisme itu dan memperbincangkannya. Kemudian, seberapa besar aktivisme ini menarik perhatian media mainstream untuk memberitakan baik isu maupun gerakannya. Tingkat engaging dalam diskusinya juga harus dilihat. Retweet atau share hanya menunjukkan penyebaran isunya, bukan kesadarannya. Namun, tingkat engagement dalam diskusinya, baik argumen pro dan kontra, bisa dipakai sebagai ukuran atas pemahaman orang terhadap isu tertentu tersebut yang sedikit lebih tinggi. Atau, bila tujuannya adalah untuk memobilisasi gerakan offline, maka kebesarannya bisa diukur seberapa banyak orang yang ikut dalam gerakan offline. Misalnya, aksi demo karena tergerak dari aktivisme online yang berjalan," jelas Dhyta.
Efektivitas suatu aktivisme juga dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan pejabat negara serta kebijakan yang diambil terkait dengan suatu isu. "Salah satu contohnya adalah kasus perkosaan terhadap YY, anak perempuan berusia 14 tahun di Bengkulu. Aktivisme media sosial yang mampu memobilisasi orang-orang untuk hadir dalam ruang-ruang offline dan pada akhirnya 'memaksa' banyak pejabat negara untuk membuat pernyataan dan mengambil kebijakan. Hal ini terlepas dari betapa problematiknya kebijakan yang kemudian diambil, yakni Perppu Kebiri bagi pelaku kekerasan," ucap perempuan yang sempat terlibat dalam kepanitian Belok Kiri Fest. ini.
Dari kacamata Dhyta, sedikit banyak, aktivisme yang tercipta seiring kriminalisasi Ibu Nuril beberapa waktu lalu pun memengaruhi keputusan hakim. Para penegak hukum menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan karena kasus Ibu Nuril diawasi oleh publik. Hal menarik lain bagi Dhyta dari kasus Ibu Nuril adalah betapa bermanfaatnya media sosial dalam menyebarkan isu yang datang dari pelosok negeri hingga menimbulkan suatu kesadaran dan dukungan moral.
Sehubungan dengan kasus Tora Sudiro dan Acho, Dhyta menyatakan bahwa popularitas kedua orang ini memang membantu meluasnya aktivisme, tetapi tidak mutlak.
"Ada alasan di luar popularitas, yakni kedekatan masyarakat dengan isu yang sedang diangkat. Katakanlah kasus Acho, seorang konsumen yang curhat karena merasa diperdaya oleh pengembang dan berharap bisa mengedukasi orang lain untuk lebih berhati-hati. Masyarakat jelas bisa melihat dirinya di posisi Acho karena pada dasarnya kita adalah konsumen yang sering berada di posisi merasa ditipu oleh korporasi. Bila Acho dikriminalisasi karena curhat maka siapapun bisa mengalami hal yang sama. Membela Acho adalah membela diri kita sebagai konsumen. Demikian juga kasus Tora, sudah menjadi rahasia publik bagaimana buruk dan penuh konspirasinya penanganan peredaran narkoba di Indonesia ini bekerja. Ini bikin orang muak dan merasa perlu bersolidaritas dengan Tora. Namun fakta bahwa baik Acho maupun Tora adalah public figure turut membantu isu ini naik dengan lebih mudah dan cepat."
Meski sudah banyak contoh aktivisme di media sosial yang mampu memobilisasi massa, Dhyta menegaskan bahwa orang perlu melihat hal-hal lain yang mendorong kesuksesan suatu aktivisme. "Output yang saya sampaikan tadi faktornya tidak melulu hanya karena gerakan media sosial saja," demikian ditekankan oleh Dhyta.
Dari fenomena-fenomena semacam ini, orang-orang dapat menilai apakah orang-orang yang menggunakan tagar tertentu untuk mengekspresikan keterlibatannya dalam aktivisme hanya sekadar mengeklik, mencuit, dan memublikasikan ulang, atau benar-benar menyiratkan kepedulian terhadap isu di sekitar. Pandangan bahwa media sosial cuma sekadar bagian dari budaya populer yang tidak signifikan terhadap perkembangan situasi sosial politik kini perlu dievaluasi ulang. Beberapa fenomena yang ada justru menunjukkan bukti bahwa media ini bukan sekadar sarana “senang-senang” dan melulu bertujuan untuk pamer diri.
Penulis: Patresia Kirnandita
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti