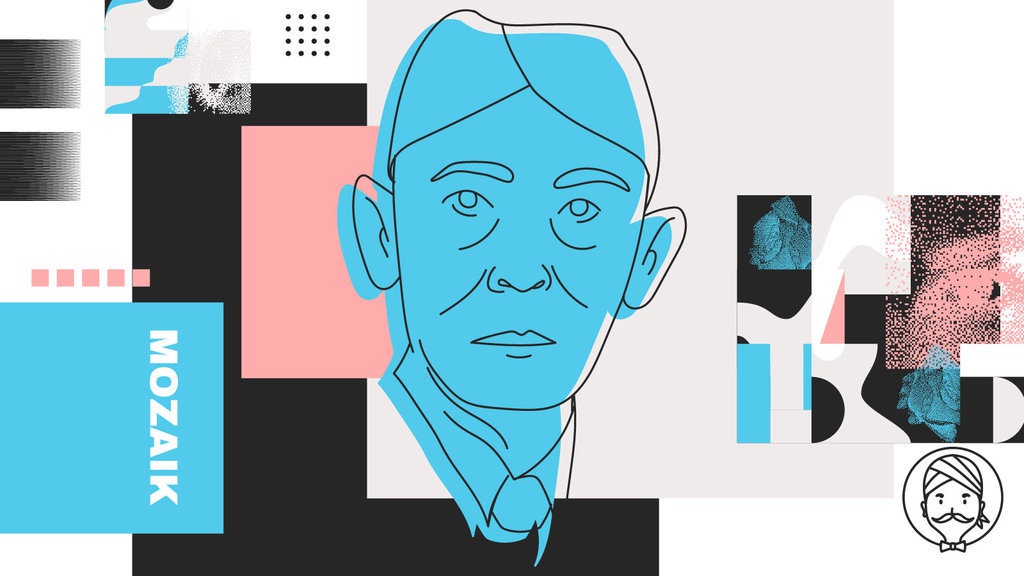tirto.id - Putusan rapat anggota Indonesische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia) hari itu sungguh menampar Noto Soeroto. Sebagai pemrakarsa dan peletak dasar organisasi, ia dikeluarkan secara tidak hormat karena terbukti mengkritik nonkooperasi yang telah disepakati sebagai asas perhimpunan. Dalam memoar Untuk Negeriku: Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi (2014), Mohammad Hatta tahu bahwa kritik Noto tendensius.
“Maksudnya ialah untuk memperoleh simpati dari usahawan Belanda, terutama dari pihak yang memimpin perusahaan Belanda yang bekerja di Indonesia,” tulis Hatta (2014, hal. 220).
Kritik itu dikecam Arnold Mononutu sebagai tindakan yang merendahkan martabat Noto sebagai seorang aristokrat. Citra Indonesische Vereeniging yang dibangun susah payah masa itu seakan dimentahkan lewat suara “orang dalam” yang justru bernada sumbang. Putusan rapat beroleh tepuk tangan forum, dan sebaliknya membuat air muka Noto memberengut. Bukan cuma keputusan rapat yang emoh berkompromi, tetapi juga karena perangai orang di sebelah Noto yang tidak terduga.
Orang itu, mula-mula datang ke rapat tanpa tahu apa yang hendak dibicarakan. Sebelum rapat mulai, ia bahkan sempat ngobrol dan bergurau dengan Noto. Tetapi sesudah mafhum apa yang dirapatkan, orang itu tukar haluan dan menyindir Noto sebagai pangeran yang “perutnya keroncongan” dan tidak bisa hidup jika tak disangu Belanda. Yang paling menyakitkan, orang di sebelah yang mengkritik Noto dengan nada pedas masih sekampung dengannya di Solo, Jawa Tengah. Sesama mahasiswa, tapi lebih tua empat tahun darinya. Sesama priyayi, namun memiliki kepribadian yang berbeda dari ningrat kebanyakan.
Dialah Raden Mas Ngabehi Poerbatjaraka, intelektual organik Jawa yang diberangkatkan pemerintah kolonial untuk mengangsu ilmu kesusastraan Jawa kuno dan Sansekerta ke Belanda, sebelum kemudian ditarik pulang dan menjadi mahaguru Jawa Kuno yang reputasinya merentang hingga tiga zaman.
Lesya, Si Anak Penasaran
Poerbatjaraka lahir dengan nama Lesya pada 1 Januari 1884 sebagai anak kedua Raden Tumenggung Poerbadipura dan Mas Adjeng Semu. Kedua orang tuanya adalah abdi dalem di Keraton Surakarta yang terpilih menjadi orang kepercayaan keluarga raja. Poerbadipura mengasuh Gusti Raden Mas Malikul Kusna sejak bayi, yang di kemudian hari dinobatkan sebagai Pakubuwana X.
Sampai usianya lanjut, Poerbadipura masih dipercaya jadi tangan kanan Pakubuwana X untuk berbagai urusan: dari busana, cenayang pribadi, hingga merawikan kisah dan tembang yang digemari oleh Sang Sunan. Untuk yang terakhir, tentu ia harus menguasai kesusastraan Jawa Kuno, keahlian yang menurun pada Lesya. Kepercayaan Pakubuwana X juga diembankan kepada Lesya, ia ikut mendampingi anak-anak Sunan di sekolah dan menjaga priyayi-priyayi kecil itu supaya tidak diganggu sinyo-sinyo Belanda di kelas.
Saat mendampingi majikannya di sekolah, Lesya gunakan untuk menyerap ilmu yang diajarkan di kelas. “Dasar pinter lagi tekun beladjar, dia sendiri berhasil sampai kelas 6. Lain2nja gagal di djalan,” tulis Jakob Oetama dalam artikel “Dimana sekarang Prof. Dr. R.M. Ng. Poerbatjaraka” yang dimuat majalah Intisari Th. I, No. 4, November 1963.
Namun, kecerdasan Lesya terantuk kebijakan sekolah yang mengeluarkannya di kelas tertinggi itu. Dalih yang digunakan, Lesya terlalu tua. Alasan bikinan ini jelas sukar dipercaya, termasuk oleh adik Lesya, Kodrat. “Bukannja terlalu tua, tapi terlalu pinter. Belanda kawatir, djangan2 nanti dapat melandjutkan ke HBS,” tukas Kodrat saat diwawancarai Jakob.
Karena peluang menempuh sekolah formal tak dapat diraih, Lesya pun menjadi seorang autodidak. Ia, misalnya, melicinkan kefasihan bahasa Belanda yang diperoleh di sekolah dasar dengan bercakap langsung dengan serdadu-serdadu Belanda yang bertugas di tangsi. Bermodal latihan itu, Lesya menyasar koleksi buku ayahnya yang mencapai empat lemari lebih. Dalam waktu luang, ia membuka-buka buku seperti Sanasunu, Angling Darma, dan Ramayana. Minat akan kesusastraan Jawa kuno pun bersemai dalam diri Lesya yang menikmati kisah wiracarita itu, berikut nilai-nilai ajarannya, sambil memperlancar kemampuan berbahasa Belanda.
Dengan usia yang beranjak naik, Lesya mulai dipekerjakan oleh keraton. Macam-macam posisi pernah ia emban, dari mantri pekerjaan umum sampai mengetuai perkumpulan gamelan. Semua itu adalah penugasan Pakubuwana X yang menyadari potensi besar dalam diri Lesya, namun juga kesulitan mementaskan jalan bagi putra punggawa kepercayaannya.
Berkat Krom dan Hazeu
Titik terang bagi Lesya muncul pada 1913. Usianya kala itu 29 tahun dan mendapat nama tua R.M. Ngabehi Poerbatjaraka, gabungan kata “Poerba” dari sang ayah dan “tjaraka”, yakni tiga huruf terakhir dari Hanacaraka. Pada tahun itu, Poerbatjaraka berkesempatan untuk berangkat ke Batavia dan berkonsultasi langsung dengan Dr. Nicolaas Johannes (N.J.) Krom, pakar Jawa kuno dan murid langsung Prof. Hendrik Kern. Kesempatan ini didapatkan Poerba sesudah diseleksi Karesidenan Surakarta, ia mampu mengalahkan seorang kompetitor dari kalangan sastrawan Solo yang tak cakap berbahasa Belanda, sementara Poerba sudah fasih karena berlatih mandiri.
Pengalaman pertama menginjakkan kaki ke jantung kekuasaan Hindia Belanda ini tidak disia-siakannya. Ia memperdalam pengetahuan Jawa kuno dan bahasa Sansekerta langsung dari Krom, yang hanya lebih tua setahun darinya. Bacaan yang melimpah dan diskusi yang intensif menggugah Poerbatjaraka untuk menyelinap masuk ke lingkungan para cendekiawan dengan menuliskan penelitian awalnya dalam tiga artikel ilmiah yang dimuat Tijdschrift voor Bataviaasch Genootschaap van Kunsten en Wetenschappen (TBG), Vol. 56, No. 1-2 dan 3-4 (1914).
Ia menulis artikel “De dood van Raden Widjaja, eerste Koning en stichter van Majapahit” sepanjang 6 halaman, “De naam van Negarakrtagama” sepanjang 1 halaman, dan “Een pseudo-Padjadjaransche kroniek” dengan C.M. Pleyte sepanjang 34 halaman. Saat ia pulang ke Solo ketika Krom cuti ke Belanda, pengetahuannya menjadi yang paling mutakhir dan tak tertandingi sastrawan manapun.
Enggan menjadi pribadi yang pelit ilmu, Poerbatjaraka berinisiatif menghimpun guru-guru Solo yang berminat memperdalam kesusastraan Jawa kuno dan Sansekerta untuk belajar bersamanya. Mula-mula ia menggelar kelas terbuka di Museum Radya Pustaka, tempat ia bekerja sebagai pustakawan sejak 1915. Lantaran diprotes, mereka pindah ke Taman Sriwedari, ia mengajar di bawah pohon seperti Rabindranath Tagore. Lain itu, Poerbatjaraka juga rajin menulis di majalah terkemuka di Solo waktu itu, Sedyatama.
Salah satu kejadian paling menggemparkan adalah ketika Poerbatjaraka mengoreksi penamaan “Sito Danoedjo”, perkumpulan priyayi dan bangsawan Solo. Menurut kamus Jawa Kawi yang dianggit Carel Frederik Winter, nama itu berarti “ksatria terkemuka”. Namun menurut Poerbatjaraka makna sesungguhnya adalah “raksasa kedinginan”. Tak ayal, ia pun dicela sebagai “anak muda sok tahu” atau diolok “masih muda sudah gila”.
Sikapnya yang tak acuh dan cukup eksentrik ini, di samping membuat orang takzim, juga memicu rivalitas antara dirinya dan para sarjana Jawa yang merasa direndahkan. Dalam situasi terkucil di kampung sendiri inilah, Prof. Godard Arend Johannes (G.A.J) Hazeu, seorang pakar Jawa dan penasihat Gubernur Jenderal, bertandang ke Solo.
Kepada Hazeu, Poerbatjaraka menunjukkan terjemahan kitab Smaradhana langsung dari bahasa Sansekerta. Hazeu terpukau karena tidak ada satu pun pakar Jawa yang mampu menerjemahkan teks asli Smaradhana sebagus Poerbatjaraka. Ia pun segera diajak bekerja di Oudheidkundige Dienst di Batavia, yang berkantor satu atap dengan Museum yang dikelola Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
Tawaran ini mula-mula memicu keberatan dari Pakubuwana X yang menganggap Poerbatjaraka tidak tahu terima kasih karena sudah dipekerjakan dan juga disekolahkan keraton. Atas negosiasi Residen Surakarta, F.P. Sollewijk Gelpke, Sunan akhirnya rela melepasnya dengan pertimbangan bahwa di kampung halaman Poerbatjaraka takkan berkembang secara optimal.
Pegawai Museum Jadi Dekan 3 Fakultas
Ucapan Pakubuwana X terbukti benar. Berkarier sebagai pegawai dinas kepurbakalaan adalah habitus Poerbatjaraka yang sesungguhnya. Di bawah bimbingan Krom dan Hazeu, ia diserahi tugas di bidang epigrafi, antara lain menerjemahkan prasasti dan menaksir temuan dan artefak hasil penggalian arkeologi yang jamak dilakukan sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. “Apa jang tak dapat mereka ketahui, saja dapat mengartikannja,” ujarnya mengenang masa kerjanya bersama Krom dan Hazeu.
Sejak mulai bekerja pada 1917, Poerbatjaraka juga prolifik menulis di jurnal ilmiah. Menurut rekapitulasi Sri Timoer dalam edisi khusus Madjalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia tahun 1964, Poerbatjaraka menulis 12 artikel ilmiah yang diterbitkan berkala oleh TBG dan jurnal Oudheidkundige Verslag yang dipublikasikan kantornya.
Pada tahun kelima bekerja di dinas kepurbakalaan, ia memperoleh beasiswa dari Yayasan Kern untuk menempuh studi lanjut ke Universitas Leiden, dengan konsentrasi bidang sastra Jawa kuno dan Sansekerta. Di sana, Poerbatjaraka juga menjadi asisten dosen untuk mata kuliah yang sama dengan konsentrasi studinya. Di luar kampus, ia aktif di Indonesische Vereeniging yang menjadi Perhimpoenan Indonesia pada 1925.
Berkat jejaring yang ia bangun di Leiden pula, tulisannya mulai terbit di berkala prestisius, Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde atau BKI kepunyaan Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde (KITLV). Menempuh studi selama lima tahun, disertasi yang dianggap sebagai magnum opus Poerbatjaraka rampung dan berhasil dipertahankan pada 1926 dengan judul Agastya in den Archipel. Ia pun menjadi anak Hindia kedua sesudah Hoesein Djajadiningrat yang meraih gelar Doktor Sastra Timur dan Filsafat dari Universitas Leiden.

Sepulangnya ke tanah air, karier Poerbatjaraka segera melesat di dinas kepurbakalaan maupun di museum, di samping menerima pengakuan sebagai pakar Jawa kuno dan Sansekerta yang amat disegani. Sebenarnya, kata hatinya mendorong Poerbatjaraka untuk mengajar kesusastraan Jawa kuno di Algemeene Middelbare School di kota kelahirannya. Apa daya, pemerintah kolonial sengaja “mengurung”-nya sebagai karyawan museum dan dinas kepurbakalaan.
“Mereka sengadja takmembiarkan saja mengembangkan kemampuan saja dengan mengadjar,” sesalnya kepada Jakob saat diwawancarai. Menurut intuisinya, kebijakan itu diambil karena sikapnya yang jujur dan selalu terus-terang kurang diapresiasi, bahkan dianggap dingin oleh sejawat akademisi dan sarjana Belanda di bidang yang sama. Karenanya, Poerbatjaraka memilih cara lama membagikan ilmu yang ia punya: menulis.
Warsa 1929 sampai 1941 barangkali menjadi periode emas Poerbatjaraka dalam menulis artikel ilmiah yang terbit di tiga berkala prominen: TBG, BKI, dan Djawa. Yang terakhir disebut ialah majalah ilmiah milik Java Instituut, organisasi penelitian kebudayaan Jawa yang berkantor di Surakarta. Enam tulisannya juga pernah bersanding di halaman majalah Poedjangga Baroe pimpinan Sutan Takdir Alisjahbana. Ia secara khusus mengkritik gagasan pembaratan dan mengingatkan bahaya pemikiran Takdir yang mencoba menghapus jejak sejarah kuno Hindia, semata-mata demi cita-cita Indonesia Merdeka. Kelak, dalam kumpulan Polemik Kebudayaan yang disunting Achdiat K. Mihardja (1954), tulisan-tulisannya ikut dimuat sebagai antitesis ide-ide pembaratan ala Takdir.
Puncak pencapaian Poerbatjaraka adalah saat dipercaya menjadi dekan di tiga fakultas sastra, sekaligus menjadi guru besar yang merangkap pengajar. Ketika Universitas Gadjah Mada dibuka di Yogyakarta pada 1949, ia diminta mengepalai Fakultas Sastra serta mengajar mata kuliah tentang Jawa Kuno. Dua tahun kemudian, Fakultas Sastra Universitas Indonesia pun memintanya menjadi dekan, yang menuntut Poerbatjaraka pindah ke Jakarta.
Pada 1957, Poerbatjaraka pindah ke Bali dan merintis Fakultas Sastra Universitas Udayana. Khusus yang terakhir, ia bahkan menyumbangkan koleksi buku-bukunya untuk mengisi perpustakaan kampus. Selain mengajar, ia juga aktif menulis, memberi bimbingan skripsi, dan menulis artikel di jurnal Penelitian Sedjarah terbitan Jajasan Lembaga Ilmiah Indonesia. Kesibukan yang melelahkan itu dilakoninya sepenuh hati, kendati ia sudah berkepala tujuh.
Dengan pilihannya sendiri, Poerbatjaraka menghabiskan usia tua dengan hidup amat bersahaja. Rumahnya di bilangan Guntur, Jakarta Selatan, masih menggunakan lampu teplok. Sehari-hari, ia tidak pernah memakai busana selain setelan Jawa lengkap, yang pemakaiannya masih harus dibantu orang lain. Jalan ke rumahnya sekitar dua kilometer dari jalan raya, tidak diaspal dan becek kala hujan. “Ik heb geen spijt van mijn leven”, saya tidak pernah menyesali hidup saya; suatu komitmen yang dibawanya sampai tutup usia pada 25 Juli 1964, tepat hari ini 58 tahun lalu.
Penulis: Chris Wibisana
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id