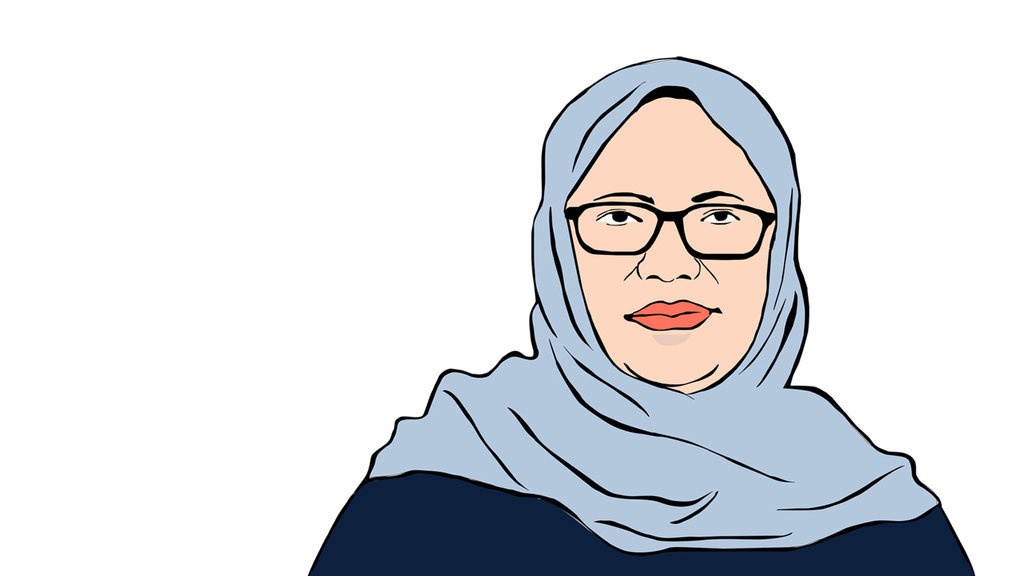tirto.id - Koalisi Perempuan Indonesia masih terus mengampanyekan gerakan 'Stop Perkawinan Anak'. Salah satu daerah yang aktif menyuarakan kampanye ini adalah Indramayu. Meski dari catatan UNICEF bukan daerah dengan angka tertinggi, tetapi eskalasi kasus perkawinan anak di kawasan pantai utara Jawa Barat ini tak bisa diabaikan begitu saja.
Pada 2015, pengadilan agama Indramayu mencatat setidaknya 459 anak meminta dispensasi untuk menikah. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 429 permintaan dispensasi menikah. Ini angka resmi. Belum termasuk yang menikah di bawah tangan atau nikah siri.
Restu Diantina Putri, reporterIndepth Tirto, menemui Yuyun Khoerunnisa, aktivis Koalisi Perempuan Indonesia dari Indramayu, pada akhir November lalu. Ditemani kopi dan sepiring kentang goreng, Enis—sapaan akrabnya—bercerita soal praktik perkawinan anak yang "mengakar kuat" di kampung halamannya.
Seperti apa fenomena perkawinan anak di Indramayu?
Perkawinan anak di sini sebenarnya merupakan fenomena gunung es. Banyak yang tidak terekspos. Penyebabnya, pertama, karena malu. Kemudian Kantor Urusan Agama juga tidak mau mengawinkan secara resmi. Sehingga tidak ada angka resmi perkawinan anak yang tercatat. Biasanya yang seperti itu menikah di pengadilan dengan biaya sekitar Rp4 juta. Itu baru ke pengadilan saja, belum lagi bayar di KUA.
Bagaimana cara pasangan di bawah umur ini mendapatkan legalitas?
Mereka akan meminta dispensasi ke pengadilan, tentu dengan izin orangtua. Tapi karena tetap mengeluarkan biaya yang cukup mahal, banyak orangtua mempelai yang memilih menikahkan secara siri. Di sini ada yang namanya naib atau lebe. Tugasnya membantu proses pernikahan secara resmi ke KUA ataupun siri. Nanti jika sudah cukup umur, pasangan perkawinan anak ini kemudian menikah lagi untuk kedua kali agar tercatat di KUA. Dalam kasus perkawinan anak, lebe berperan memalsukan usia mempelai, kebanyakan perempuan, untuk didaftarkan ke KUA.
Bukankah nikah siri banyak merugikan pihak perempuan? Apa dampak pernikahan siri?
Kasus terbanyak, anak dari hasil perkawinan tidak memiliki akta kelahiran. Padahal sekolah, kan, memerlukan akta. Bisa pakai akta sebenarnya tapi tidak ada nama bapak. Hanya nama ibu. Itu bisa merusak psikologis si anak juga. Terkadang ada juga yang akhirnya ikut dengan kartu keluarga kakek-neneknya.
Apa penyebab angka perkawinan anak masih cukup tinggi di sini?
Banyak hal. Pertama, faktor agama. Pernikahan menjadi jalan keluar ketimbang pasangan bocah itu berzina. Lalu ada juga faktor ekonomi. Saya memiliki kawan waktu SMA. Dia siswa berprestasi. Tapi sebelum lulus, ia sudah dinikahkan oleh bapaknya. Alasannya karena ayahnya terlilit utang. Sebagai pelunasan, ia harus menikahkan anaknya dengan si pemberi utang. Toh, pada akhirnya, perkawinan mereka cuma diisi dengan pertengkaran. Sudah beberapa kali hampir cerai.
Di desa saya, ada yang memang karena pergaulan bebas, kemudian hamil sehingga terpaksa dinikahkan. Ada pula yang hanya karena digerebek. Jadi, saya dapat kabar mereka menikah. Padahal dua-duanya masih anak-anak. Katanya, ketahuan lagi berdua-duaan, jadi digerebek, lalu dipaksa untuk menikah.
Soal pergaulan yang diboboti dengan frasa "bebas"—ini sering jadi alibi sehingga sampai pada kesimpulan: Ya, sudah, nikahkan saja. Kasus-kasus khusus di Indramayu bagaimana?
Sebenarnya bukan bebas. Hanya saja rata-rata orangtua di sini adalah buruh migran. Jadi, peran mengasuh dialihkan ke kakek-nenek mereka yang kebanyakan sudah sepuh. Namanya sudah tua, mulai terbatas untuk mengontrol pergaulan anak. Akhirnya, yang penting kakek-neneknya tahu mereka sekolah saja, selain itu sudah tidak terpantau lagi pergaulannya. Atau, saking dimanjakan, jadi dibelikan telepon genggam oleh neneknya. Jadi, kalau dibilang kurang hiburan, tidak juga. Karena di sini banyak pantai. Ada dampak dari penyalahgunaan teknologi juga. Selain itu, seperti yang saya katakan, ini terkait pola asuh juga. Banyak buruh migran wanita yang kembali membawa laki-laki lain. Hal-hal seperti itu juga memengaruhi psikologis anak.
Selain rumah tangga yang rapuh, apa dampak negatif lain dari perkawinan anak?
Mulai dari kekerasan, karena psikologis suami-istri yang belum stabil. Perkawinan anak juga berkontribusi pada angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Indramayu termasuk yang tertinggi di Jawa Barat. Tahun lalu tercatat, per semester ada sekitar 50 ibu meninggal setelah melahirkan. Ini meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya 30 kasus per tahun.
Selain itu, penyebab tindak pidana perdagangan orang. Modus biasanya dengan menjadikan buruh migran. Dampak lain: meningkatnya angka kriminalitas. Ini faktor tidak langsung, ya. Karena menikah tapi mereka tidak punya keterampilan, misalnya, kemudian jadi pengangguran. Jadilah melakukan kejahatan, begal biasanya.
Bagaimana kasus-kasus perkawinan anak perempuan di sini mendorong eksploitasi?
Biasanya anak perempuan dikawinkan, lalu disuruh pergi ke luar negeri, untuk jadi buruh migran. Jadi terkadang, kan, tidak memenuhi syarat kalau belum kawin. Saat mau menikah, umurnya dipalsukan.
Selain jadi buruh migran, ada pula yang karena frustrasi rumah tangganya berantakan, mereka lari ke pelacuran. Dilacurkan oleh orangtuanya sendiri. Sayangnya, kami belum ada akses ke situ.
Ada pula yang dieksploitasi tenaganya. Ada seorang korban di Desa Pabean (salah satu desa di kawasan pantai Kecamatan Indramayu). Tujuan orangtuanya waktu itu menikahkan sang anak untuk mengurangi beban. Anaknya dinikahkan dengan pengusaha lokal, duda anak satu. Tapi ternyata korban dinikahi hanya untuk menjaga anaknya saja. Dinafkahi pun tidak. Padahal dia masih 15 tahun. Suaminya sering pergi entah ke mana. Perkawinannya hanya bertahan tiga bulan.
Apa yang dilakukan Koalisi Perempuan Indonesia di sini?
Kami melakukan pendampingan dan sosialisasi ke desa-desa. Selain itu pendekatan ke sekolah-sekolah, terutama ke SMP-SMA karena perkawinan anak rentan terjadi pada masa itu. Kalau sekolah-sekolah di Indramayu kota, mereka sudah mulai mengerti, ya. Tapi lain hal kalau kami ke daerah pinggiran. Cukup sulit.
Mengapa?
Karena bahasanya. Mereka berpikir, daripada berzina, lebih baik menikah. Mindset seperti ini yang agak susah diberi pengertian. Kami jelaskan, ada cara lain untuk menghindari zina. Mereka harus buang dulu pikiran soal zina itu. Lucunya, mereka masih ada yang bertanya manfaat menikah di bawah umur. Ya saya bilang tidak ada.
Selain perkawinan anak, kami juga mendampingi sejumlah kasus lain, misalnya tindak pidana perdagangan orang. Tapi, toh, pada akhirnya, semuanya banyak bermula dari perkawinan anak. Kasus-kasus yang melibatkan perempuan kebanyakan awalnya bermula dari sana.
Bagaimana dengan pemerintah?
Baru Koalisi Perempuan Indonesia yang mendobrak untuk isu perkawinan anak. Dari dinas ataupun lembaga di bawah negara belum ada. Kemarin kami bikin kampanye 'Stop Perkawinan Anak'. Ya dinas tidak ada dukungannya. Pemerintah kabupetan juga tidak ada. Kami sudah audiensi dengan bupati juga. Hasilnya nihil. Kami juga mendorong ada peratutan bupati tentang batas usia pernikahan anak. Kami minta disamakan dengan usia laki-laki, yaitu 19 tahun.
Koalisi Perempuan nasional sempat ajukan judicial review soal ini, tetapi gagal. Waktu itu kami minta batas bawah usia perempuan menikah menjadi 18 tahun. Sekarang kami mau coba ajukan lagi dengan usia 19 tahun. Padahal Undang-Undang Perlindungan Anak menyebut, batas bawah usia menikah perempuan 18 tahun ke atas.
Artinya, Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 perlu direvisi?
Ya. Setidaknya yang paling krusial terkait umur. Enam belas tahun itu masih usia anak-anak. Selain itu, banyak perkawinan anak terjadi karena pengadilan memberi dispensasi. Artinya, ada akses yang memudahkan. Kami mendorong segera diamandemen. Jangan sampai ada akses yang menjadi alternatif orangtua dapat menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.
Penulis: Restu Diantina Putri
Editor: Fahri Salam
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id