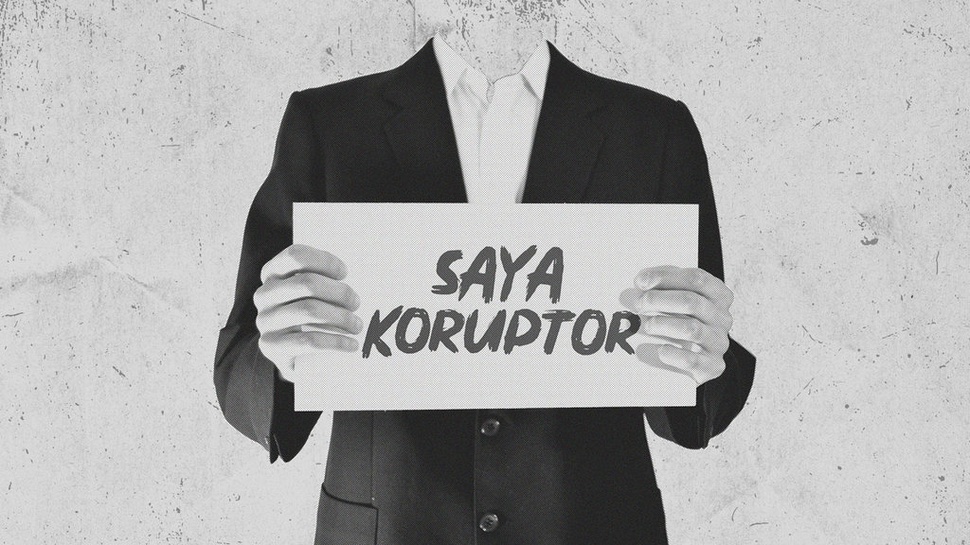tirto.id - Presiden Joko Widodo menang pada Pemilihan Umum Presiden 2019. Di akhir periode pertamanya, pemerintah dan DPR kemudian mengesahkan revisi UU KPK dan ingin menggolkan RKUHP yang baru. Yang terakhir berhasil dicegah, tapi revisi UU KPK tetap diketuk palu kendati di tengah demonstrasi besar bertajuk #ReformasiDikorupsi.
Aturan-aturan dalam UU KPK yang baru ditentang karena dianggap merugikan bagi penegakan korupsi di Indonesia. Alih-alih memperkuat dan memperluas wewenang KPK, aturan ini justru membatasi tindakan KPK untuk memergoki pihak-pihak yang melakukan korupsi.
Misalnya, KPK perlu meminta izin Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan. Hal ini dikhawatirkan mengganggu jalannya operasi tangkap tangan (OTT) yang biasa dilakukan KPK. Namun, DPR beranggapan bahwa KPK di masa depan memang perlu mengedepankan pencegahan daripada penangkapan koruptor.
Kemudian terbukti, OTT menjadi lebih jarang dilakukan. Sepanjang 2020 setelah UU KPK yang baru diterapkan, KPK tercatat hanya melakukan dua OTT. Pada 2021, angka ini mengalami peningkatan menjadi 7 OTT.
Ini jelas suatu penurunan tajam jika dibandingkan OTT pada tahun-tahun sebelum revisi UU KPK. Pada 2018, misalnya, KPK tercatat melakukan 32 kali OTT dan ada 16 OTT—7 di antaranya melibatkan pemerintah kabupaten/kota—pada 2019.
Selain itu, ada pula aturan yang memutuskan bahwa pegawai KPK menjadi bagian dari aparatur sipil negara (ASN). Dengan adanya predikat tersebut, pegawai KPK harus mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang kemudian mengakibatkan 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos.
Padahal, sebagian dari mereka yang terdepak, jika bukan semuanya, punya rekam jejak baik dalam penanganan korupsi.
Dalam catatan dua tahun aksi #ReformasiDikorupsi yang disusun oleh Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK), tren melemahnya KPK makin lengkap dengan terpilihnya Firli Bahuri sebagai pemimpin KPK.
Firli pernah kedapatan melakukan pelanggaran etik selama di KPK dahulu. Setelah menjabat, Firli kedapatan berjalan-jalan menggunakan helikopter mewah yang kemudian juga divonis melanggar kode etik KPK.
“Pasca revisi UU KPK, terlihat berbagai pendekatan dan kebijakan yang seolah memberikan normalisasi pada korupsi. KPK sempat memunculkan gagasan untuk mengubah istilah ‘koruptor’ sebagai penyintas korupsi—meski belakangan dibatalkan. KPK juga sempat hendak mengajak napi korupsi untuk menjadi penyuluh program anti korupsinya ke masyarakat,” catat PSHK.
Bagi PSHK, setelah UU KPK yang baru diterapkan, penegakan korupsi di Indonesia memang problematik.
“Dua tahun pasca aksi #ReformasiDikorupsi, siapapun yang menggunakan akal sehat akan setuju bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia telah menyentuh titik nadir. Minimnya upaya mengoreksi dari cabang kekuasaan lain akan semakin terpuruknya pemberantasan korupsi pasca revisi UU KPK semakin menguatkan pesan bahwa ekosistem hukum kita sedang menuju ke arah jurang yang sama,” masih menurut PSHK.
Bolak-balik Melonggarkan Korupsi
Pada Selasa (6/9/2021), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham mengumumkan 23 narapidana kasus korupsi bebas bersyarat. Mereka berasal dari Lapas Kelas IIA Tangerang, Banten, dan Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung.
Di antaranya ada nama-nama yang tidak asing, seperti mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.
Pembebasan bersyarat ini awalnya diatur pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. PP tersebut tidak mengatur klausul khusus tentang narapidana kejahatan luar biasa, seperti kejahatan hak asasi manusia, terorisme, narkotika, ataupun korupsi.
Aturan ini kemudian mengalami perkembangan atau perubahan pertama dengan terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2006. Isinya ditambahkan dalam perihal remisi. Pasal 34 ayat (3) menyebut narapidana kasus korupsi, narkotika, kejahatan HAM, atau kejahatan transnasional lainnya bisa mendapat pengurangan hukuman apabila berkelakukan baik dan telah menjalani sepertiga masa pidana.
Sedangkan itu, Pasal 43 menyebut bahwa setiap narapidana bisa dibebaskan bersyarat apabila berkelakukan baik dan telah menjalani dua pertiga masa hukumannya dan tidak kurang dari 9 bulan.
Aturan ini kemudian dianggap terlalu menguntungkan bagi koruptor. Sepanjang 2006-2012, banyak koruptor yang mendapatkan remisi dari pemerintah. Meski tidak banyak catatan tentang pembebasan bersyarat, jumlah pemberian remisi kepada napi koruptor tergolong masif.
Pada 2010, misalnya, napi koruptor yang mendapat remisi ada di bawah 300 orang. Kemudian pada 2012, ada 583 koruptor yang diberi remisi, sedangkan 32 lain mendapat pembebasan bersyarat.
"Untuk ke depan, kebijakan tersebut perlu dievaluasi lagi. Kalau remisi itu dua kali, masa hukuman yang dijalani cenderung rendah, sehingga perlu ditinjau ulang," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnaen dilansir dari BeritaSatu.
Menteri Hukum dan HAM kala itu, Amir Syamsudin, berargumen bahwa setiap warga binaan berhak mendapat remisi tanpa dibeda-bedakan. Padahal, korupsi seharusnya termasuk dalam kejahatan luar biasa. Pada 2010, KPK pun sebenarnya berpandangan koruptor seharusnya tak berhak mendapatkan remisi.
Pada November 2012, pemerintah akhirnya mengambil langkah dengan menerbitkan PP Nomor 99 Tahun 2012. PP tersebut merupakan perubahan kedua terhadap aturan pembebasan bersyarat.
Pemberian remisi masih diperbolehkan dengan syarat yang diperketat, di antaranya harus melunasi denda yang ditetapkan oleh pengadilan dan setuju untuk menjadi justice collaborator (JC) untuk membantu negara memecahkan kasus korupsi yang dilakukannya. Hal yang sama berlaku bagi aturan pembebasan bersyarat.
Saldi Isra yang sekarang menjabat sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa aturan untuk memperketat pemberian remisi bagi koruptor ini tidak bertentangan dengan aturan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Dalam Pasal 14 aturan yang dibuat pada masa kejayaan KKN Orde Baru itu, narapidana punya hak untuk mendapat remisi tanpa ada pembatasan spesifik terhadap narapidana jenis kejahatan apapun.
“PP itu tidak menghalangi hak narapidana untuk mendapatkan remisi, hanya adanya pembatasan saja,” ujar Saldi.
Baginya, aturan dalam PP ini sudah baik dan pemerintah diharapkan bisa konsisten bertahan dengan pembatasan remisi dan pembebasan bersyarat ini.
Pada 2013, seorang terdakwa korupsi bernama Rebino dengan kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra menggugat PP 99/2012—yang baru berlaku sekira setahun—ke Mahkamah Agung.
Namun, uji materiil itu dibatalkan oleh Majelis Hakim MA yang terdiri dari M. Saleh, Yulius, Supandi, Artidjo Alkostar, dan Imam Soebechi. Nama pertama adalah hakim ketua dan dia mengetuk palu bahwa PP 99/2012 tidak bermasalah dan tidak bertentangan dengan UU 12/1995.
Hakim Agung kala itu berpendapat perbedaan yang diterapkan kepada kejahatan luar biasa wajar dimaklumi. Apalagi, kejahatan macam korupsi sudah memberikan dampak kerugian besar pada ekonomi negara.
Bukan hanya soal syarat remisi, bahkan pada saat penyelidikan dan penyidikan saja, kasus korupsi memang sudah ditindak secara khusus di luar kasus pidana lainnya.
“Menimbang, bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 memperketat syarat pemberian Remisi agar pelaksanaannya mencerminkan nilai keadilan. Sehingga menunjukkan pembedaan antara pelaku tindak pidana yang biasa atau ringan dengan tindak pidana yang menelan biaya yang tinggi secara sosial, ekonomi, dan politik yang harus ditanggung oleh Negara dan/atau rakyat Indonesia. Dengan demikian, perbedaan perlakuan merupakan konsekuensi etis untuk memperlakukan secara adil sesuai dengan dampak kerusakan moral, sosial, ekonomi, keamanan, generasi muda, dan masa depan bangsa, dari kejahatan yang dilakukan masing-masing narapidana,” demikian bunyi petikan putusan Majelis Hakim MA.
Namun, tantangannya belum selesai. Pada 2021, PP 99/2012 kembali digugat. Meski ada Supandi di deretan Majelis Hakim MA yang dahulu setuju bahwa PP 99/2012 tak bertentangan dengan UU Pemasyarakatan, hasil rembukan hakim MA kali ini memutus bahwa PP 99/2012 tidak sesuai dengan UU 12/1995.
Salah satu dampak aturan ini adalah kebebasan bagi pemerintah atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dari Kemenkumham untuk bisa memberikan remisi bagi napi koruptor.
Belum Beranjak dari Era Orde Baru?
Masalah ini sebenarnya tetap bisa dibenahi dan hukum yang memberi efek jera pada koruptor bisa dikembalikan. Salah satunya adalah dengan revisi UU Pemasyarakatan yang dianggap “tidak diskriminatif” sekali pun pada pelaku kejahatan luar biasa macam koruptor.
Namun, alih-alih memulihkan pengetatan yang hilang, pemerintah dan DPR justru lebih setuju memperingan hukuman bagi koruptor.
Kejadiannya di 2019, ketika DPR mengebut pembahasan RUU Pemasyarakatan yang baru dan ingin mengesahkannya di tahun itu juga. Aturan baru itu diperkirakan justru menguntungkan koruptor karena menghapuskan syarat-syarat tertentu bagi narapidana kasus korupsi mendapatkan remisi.
Menkumham Yasonna Laoly waktu itu berpendapat bahwa syarat-syarat itu melanggar hak asasi manusia, meski targetnya adalah pelaku kejahatan luar biasa.
Namun pengesahan RUU Pemasyarakatan baru itu batal dengan alasan menunggu RKUHP. Omongan pemerintah dan DPR ini konsisten selama setidaknya 3 tahun belakangan.
Pada 2022, pemerintah, melalui Menkumham Yasonna Laoly, dan DPR akhirnya menetapkan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang resmi menggantikan UU 12/1995.
Dan syarat khusus bagi narapidana kejahatan HAM, terorisme, narkotika, korupsi, atau yang dirasa luar biasa benar-benar dihilangkan. Hanya dengan berkelakuan baik, aktif ikut program pembinaan, dan telah menunjukan penurunan tingkat risiko, maka seorang koruptor sekalipun bisa mendapat remisi dan pembebasan bersyarat.
Selain mendapat perlakukan yang sama seperti narapidana kasus lainnya, koruptor di Indonesia kiwarijuga tetap bisa ikut dalam kontestasi pemilu legislatif. Pada Pemilu 2019 saja, ada 81 caleg koruptor yang percaya diri untuk maju.
Seperti catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2021, sejak MA membatalkan PP Nomor 99/2012, “pemberantasan korupsi” di Indonesia “kembali berada di titik nadir”.
Saat itu, ICW sudah mengingatkan agar pemerintah dan DPR “tidak memanfaatkan putusan MA dalam RUU PAS sebagai dasar untuk mempermudah pengurangan hukuman para koruptor”. Namun, peringatan itu sia-sia belaka karena tak digubris.
RUU PAS tetap disahkan dengan memperlakukan korupsi sebagai tindak pidana biasa. Setelah berjarak lebih dari dua dekade Reformasi—yang salah satu cita-citanya adalah memberantas korupsi, aturan hukum di Indonesia sekilas pandang justru tampak tak bergerak dari era rezim Orde Baru kala KKN merajalela.
Editor: Fadrik Aziz Firdausi