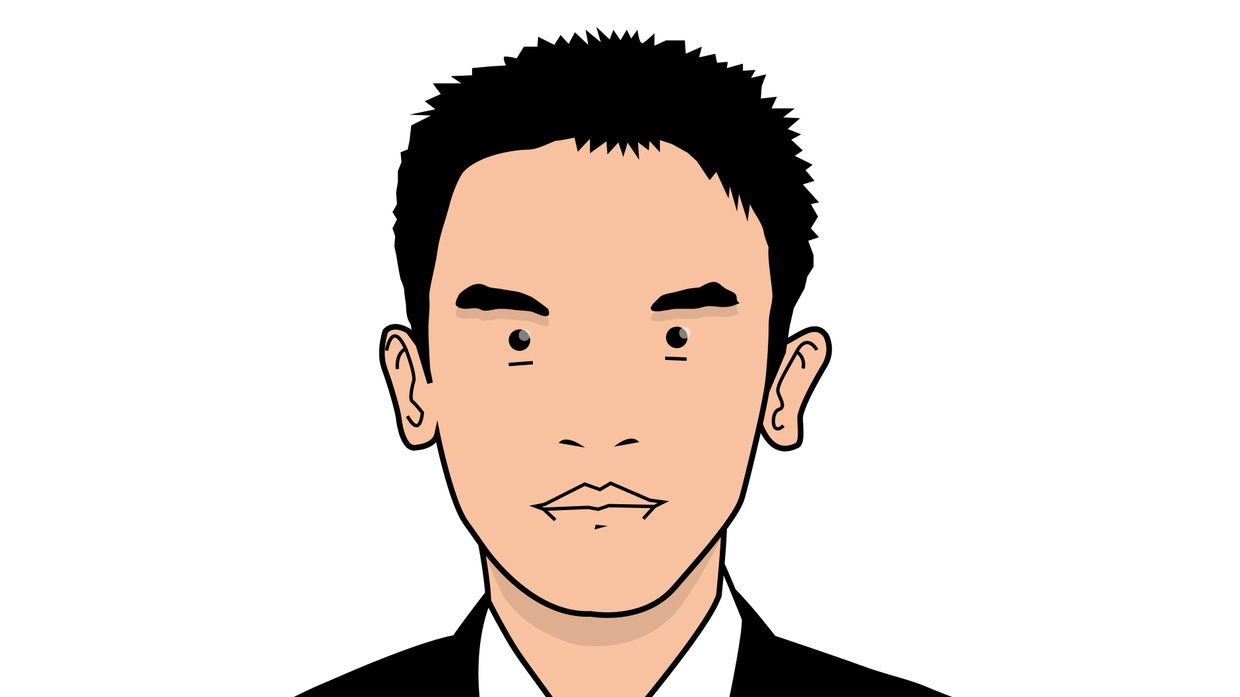tirto.id - Wacana pendaftaran akun media sosial menggunakan KTP yang dilontarkan oleh politikus PDI Perjuangan mencerminkan cara partai politik melihat media sosial.
Di satu sisi, sikap sang politikus menunjukkan pengakuan atas pengaruh media sosial yang besar. Di sisi lain, ia menunjukkan kegagapan karena gagal beradaptasi dengan karakter demokrasi digital yang dibawa media sosial. Kontradiksi ini justru ingin diselesaikan dengan mengontrol media sosial.
Peran media sosial semakin penting seiring meningkatnya pengguna internet di Indonesia. Ada sederet contoh yang bisa diajukan untuk melihat bagaimana platform ini memberdayakan warga, termasuk menunjukkan antusiasme dalam partisipasi politik. Namun, ia juga menjadi ruang paling efektif untuk penyebaran berita palsu dan hoaks yang mendominasi lanskap politik Indonesia beberapa waktu belakangan.
Ironisnya, dalam lanskap politik semacam itu, partai politik belum secara serius menggunakan media sosial sebagai platform yang bisa menyebarkan gagasan-gagasannya.
Yang paling menonjol sejauh ini justru akun-akun pribadi politikus yang punya banyak pengikut di media sosial. Dari partai-partai yang ada di DPR, hanya segelintir yang terlihat serius menggarap lini media sosial. Di antaranya adalah Gerindra yang beberapa hari lalu merayakan ulang tahun kedelapan.
Apa yang dilakukan Gerindra ini menarik untuk dicermati ketika partai-partai Koalisi Merah Putih rontok satu per satu. Bersama PKS, praktis hanya Gerindra yang menjadi simbol kelompok oposisi.
Cermati akun-akun media sosial Gerindra (setidaknya di Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube), Anda akan menyaksikan konten media sosial yang dirancang secara terstruktur dan sistematis. Jauh berbeda jika dibandingkan dari partai-partai lain, khususnya partai pendukung pemerintah.
Sejak pemilihan umum 2014, akun media sosial Gerindra memang jauh lebih rapi dengan pesan kampanye dan sistem komunikasi yang memusat dari atas ke bawah. Materi-materi kampanye bertumpu pada akun-akun resmi partai. Sejauh yang bisa diamati, apa yang dilakukan Gerindra ini setidaknya memiliki dua efek penting.
Pertama, media sosial memungkinkan partai berkomunikasi secara langsung dengan pemilih dan calon pemilih. Setidaknya ia menjadi ruang untuk merawat isu yang selama ini menjadi garis pembeda bagi posisi kelompok oposisi dan pemerintah.
Dengan karakter media sosial yang membuat orang mudah lupa, merawat isu dengan konsisten adalah cara untuk tetap diingat publik. Jejak digital akan diingat—atau diungkit—publik dan bisa digunakan sebagai senjata di masa pemilihan umum. Melihat fakta bahwa partai politik di Indonesia kerap hanya dirasakan kehadirannya ketika musim pemilu, “kehadiran” di media sosial setidaknya menjaga agar isu yang dibawa terus itu dekat dengan publik.
Algoritma media sosial, yang membentuk gelembung filter, sebenarnya akan menguntungkan partai yang bisa terus merawat isu-isu yang coba diusung. Lepas dari pelbagai sisi negatifnya, kecenderungan pengguna media sosial untuk mencari ide-ide yang sesuai pemikirannya, jika dirawat oleh partai, akan “mengeraskan” dukungan terhadap partai.
Kedua, media sosial adalah platform dengan kapasitas yang mampu melampaui peran media arus utama.
Ketika kampanye politik mulai diizinkan di televisi oleh pemerintah Orde Baru pada dekade 1990-an, masing-masing partai hanya mendapatkan jatah terbatas. Artinya, semakin sedikit waktu yang bisa mereka gunakan untuk menjangkau publik melalui media. Bahkan di era pasca reformasi, akses terhadap media akan ditentukan oleh sumber daya milik partai. Partai yang ketuanya adalah pemilik media seperti Perindo (Hary Tanoesoedibjo) dan NasDem (Surya Paloh) tentu mendapat keuntungan sendiri.
Demokrasi digital telah memecah kanal-kanal informasi sehingga tak terpusat di media arus utama. Peran media arus utama sebagai penjaga gawang (gatekeper) berhasil dijebol. Walhasil, partai lebih leluasa membangun citra diri yang diinginkan, tak seperti berita-berita di media arus utama yang akan di-framing sana-sini.
Dengan demikian, partai yang mengeluh diberitakan negatif di media arus utama adalah partai malas. Beragam kanal media sosial bisa menjadi ruang untuk menepis pelbagai berita negatif tersebut. Aneka peristiwa yang muncul beberapa tahun belakangan juga menunjukkan bahwa isu yang diangkat di media sosial bisa mendominasi ruang berita di media arus utama.
Efek kejut penggunaan media sosial akan lebih dahsyat jika partai didukung oleh oligarki media. Kita bisa ambil contoh dari suasana yang begitu panas dan brutal di media sosial selama Pilkada Jakarta tahun lalu. Suasana itu juga dibangun oleh berita-berita di televisi yang berpihak pada kandidat.
Di titik ini, sikap Gerindra yang aktif dan agresif di media sosial bisa dipahami. Ini langkah yang sangat strategis, khususnya jika yang disasar adalah generasi pemilih Milenial dalam pemilu 2019. Sebuah lumbung suara yang strategis, mengingat 34,4 persen penduduk Indonesia adalah generasi Milenial (kelompok usia 17-34 tahun, menurut data Saiful Mujani Research & Consulting).
Artinya, gabungan antara kampanye media sosial dan mesin partai yang sedang punya moral tinggi pasca menang di Pilkada Jakarta bisa membawa kejutan pada Pemilu 2019.
Ruang Politik di Media Sosial
Yang perlu diperhatikan, jumlah pengikut yang besar di media sosial—termasuk popularitas di media—tak selalu bisa diterjemahkan ke kotak suara. Popularitas atau tingkat keterkenalan yang tinggi tidak selalu menjamin tingkat keterpilihan karena ada banyak faktor yang membuat partai dipilih. Namun, mengabaikan media sosial sembari berharap pada kampanye offline belaka juga sebuah kekeliruan.
Selain itu, aktivitas di media sosial akan sia-sia jika gagal mengapitalisasi momen-momen politik. Kita bisa melihatnya pada Gerindra. Meskipun paling agresif di media sosial, selama tiga tahun belakangan publik tidak benar-benar melihat Gerindra sebagai kekuatan oposisi yang tangguh—setidaknya itulah citra yang muncul di media sosial.
Alih-alih kritik dan tawaran alternatif atas pelbagai kebijakan pemerintah, kita justru lebih sering menemukan pesan-pesan nyinyir. Misalnya ketika Fadli Zon, kader Gerindra paling populer di media sosial, menyindir menteri Susi Pudjiastuti dan Sri Mulyani melalui media sosial tanpa berusaha membangun basis kritik yang jelas.
Contoh lain ketika mengampanyekan penolakan terhadap RUU KUHP yang dinilai akan membungkam demokrasi, Gerindra memakai kutipan Wiji Thukul dalam postingan akun Instagram resmi partai. Tapi bagaimana mungkin partai yang ketuanya diduga menghilangkan Wiji Thukul bisa menggunakan kutipan sang penyair?
Pesan oposisi yang yang sebenarnya strategis itu akhirnya menguap.
Dua contoh itu berujung blunder dan justru menuai serangan bertubi-tubi dari warganet. Karakteristik “serangan balik” dari warganet ini memang mesti dipahami sebagai faktor yang melekat dalam kampanye media sosial, betapapun positif kampanye yang coba dibangun.
Meski punya tingkat kejenuhannya sendiri, jumlah pengguna internet dan media sosial di Indonesia terus bertambah. Ruang ini semakin jadi palagan penting dalam pertempuran membentuk opini publik. Artinya, partai politik harus serius menggarap media sosial jika ingin menjangkau para calon pemilih dari kalangan Milenial.
Pengabaian media sosial hanya akan menunjukkan kegagapan untuk beradaptasi dengan teknologi dan terutama dengan anak-anak muda.
Editor: Windu Jusuf
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id