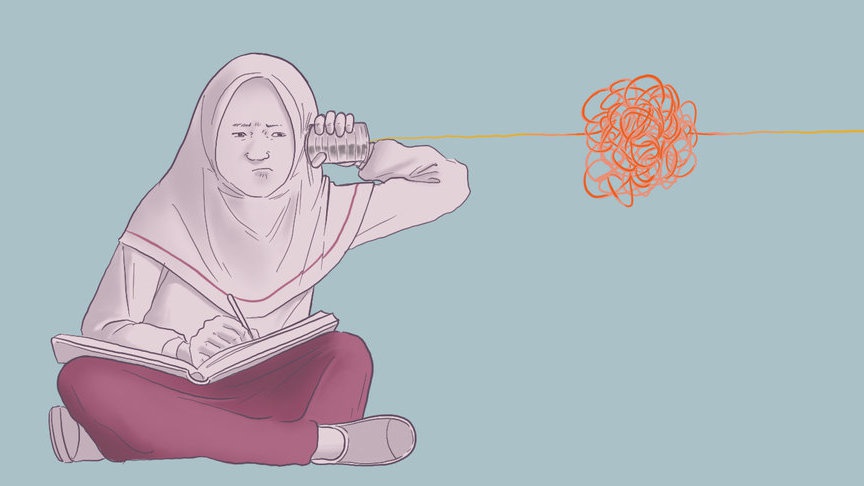tirto.id - Ini bukan cerita baru lagi: para siswa, orangtua, dan guru jungkir balik mengikuti proses belajar jarak jauh via daring selama pandemi COVID-19. Di daerah-daerah terluar dari pusat kekuasaan, bahkan sekalipun di dekat pusat wisata terkenal di Indonesia, para murid harus mencari cara yang tak masuk akal demi mendapatkan sinyal internet. Di tempat lain, ada keluarga-keluarga yang tak punya ponsel sama sekali; ada juga yang bergantian memakai satu ponsel milik orangtuanya. Dan, sekalipun mudah mendapatkan akses internet dan punya ponsel, banyak keluarga yang kerepotan membeli kuota, di saat ekonomi keluarga tergulung pagebluk.
Kondisi-kondisi ini, selama enam bulan terakhir sejak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menerapkan belajar dari rumah pada akhir Maret lalu, menunjukkan ketimpangan pendidikan di negara kepulauan Indonesia.
Anda bisa mendengarkan cerita Imam Aji Subagyo, guru usia 30 tahun, yang mengajar di sebuah sekolah dasar di Kepulauan Riau.
Nama sekolahnya SD Negeri 004 Mantang. Sekolah induknya di Pulau Siolong, sementara tiga sekolah cabangnya di Pulau Sirai, Pulau Telang Kecil, dan Pulau Telang Besar. Keempatnya berada di Kabupaten Bintan, daerah andalan pariwisata, yang dihubungkan lautan.
Menjadi kepala sekolah di SD tersebut, ujar Imam, bak memimpin empat sekolah berbeda karena di tiap pulau punya kelas satu sampai kelas enam.
Tinggal di Pulau Siolong, Imam harus naik perahu selama 30 menit menuju Pulau Sirai; 1 jam menuju Pulau Telang Kecil; dan 1,5 jam menuju Pulau Telang Besar. Di tiga pulau ini, jangankan sinyal internet, sinyal telepon pun bapuk. Warga harus pergi ke pelabuhan jika ingin menikmati sinyal “agak lumayan,” kata Imam.
“Hanya sekolah di Pulau Siolong yang punya sinyal memadai. Itu pun hanya provider IM3,” ceritanya kepada saya via telepon pada awal September lalu. Akhirnya, ia terpaksa menggelar proses belajar tatap muka terbatas di tiga pulau tersebut—yang sebenarnya agak mengkhawatirkan mengingat Kabupaten Bintan pernah menjadi zona merah Covid-19.

Banyak siswa berasal dari keluarga miskin, yang membuat mereka tak punya ponsel, cerita Imam. Kabupaten Bintan, menurut Badan Pusat Statistik tahun 2019, memiliki 10 ribu penduduk miskin atau 6 persen dari total penduduk. Di Pulau Siolong, ada juga SMP Negeri 25 Satu Atap Selat Limau. Kebanyakan siswanya dari keluarga mampu, yang kebanyakan tinggal di Pulau Siolong dan Pulau Sirai.
“Enggak semua anak di Pulau Telang Kecil dan Telang Besar bisa sekolah di SMP itu,” kata Imam. Artinya, ancaman putus sekolah besar sekali.
Keluhan serupa datang dari Ramayana, guru usia 27 tahun untuk SMP Negeri 4 Satap Pulau Komodo. Mengajar Seni Budaya Dasar, ia kesulitan menerapkan belajar daring. Sinyal internet amburadul. Tak semua siswa punya gawai.
Kampung Komodo di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, hanya dialiri provider Telkomel. Total ada 10 rukun tetangga: jaringan internet acak-adut; sekalipun sinyal bagus, banyak siswa tak punya ponsel.
Rama berkata di tempatnya, “kalau mau telepon atau internet, saya mesti ke dermaga. Repot!”
Itu kebalikan dari citra Pulau Komodo, yang digembar-gemborkan oleh pemerintah Joko Widodo sebagai ikon wisata nasional dan dunia, yang menyumbang miliaran rupiah bagi pendapatan provinsi dan nasional setiap tahun. Ada 49,23 ribu penduduk miskin di Manggarai Barat atau 18% dari total penduduk, menurut BPS tahun 2019.
“Setidaknya pemerintah sediakanlah wifi untuk setiap sekolah di Pulau Komodo atau mungkin di titik-titik tertentu sediakan wifi gratis,” saran Rama, getun.
Rama berkata hanya sekitar 25 siswa dari 100-an siswa di sekolahnya yang bisa mengikuti belajar jarak jauh karena mereka memiliki gawai.
“Ada juga siswa punya ponsel, tapi enggak ada pulsa paket,” keluhnya.
Akhirnya, sekolah dia terpaksa memutuskan menjalankan belajar seperti biasa tapi bergantian.

Ketimpangan Pendidikan di Indonesia
Saya mengontak Tri Ari Santi, relawan informal SD Inpres Samenage. Ari, 36 tahun, berasal dari Jawa, yang datang ke Papua demi apa yang disebunya “belajar” bersama anak-anak Papua. Samenage, sebuah distrik di Yahukimo, berada di pegunungan tengah Papua; kawasan dengan medan berat yang bisa dijangkau 15 menit dengan pesawat kecil Pilatus berbiaya Rp10 juta dari Wamena, atau berjalan kaki selama 2-3 hari dari Wamena. Setelahnya, Ari harus berjalan kaki selama dua jam untuk tiba di SD Inpres Samenage. Wamena adalah ibu kota Jayawijaya, pusat bisnis di lembah pegunungan tengah Papua.
Warga Papua dari sembilan kampung di Distrik Samenage hanya menggunakan bahasa daerah lewat dialek Nayak dan Nare, ujar Ari.
SD Inpres Samenage berinduk di Kampung Pona, dua sekolah cabang lainnya di Kampung Samenage dan Kampung Ibelak. Di sekolah itu, ada kepala sekolah, dua guru honorer lulusan SMA, dan tiga relawan pengajar. Total ada 53 siswa dari lima kampung.
Ari berkata jangankan sinyal telepon dan internet, listrik pun tidak ada.
“Distrik dapat bantuan solar cell untuk penerangan pada akhir tahun 2018,” kata Ari via telepon pada awal September lalu saat berada di Jayapura.
Tak cuma ketimpangan akses internet untuk belajar daring, untuk informasi Covid-19 saja serba telat. Saat pemerintahan Jokowi mengumumkan kasus corona, awal Maret lalu, “Kami belajar seperti biasa. Masyarakat ke hutan untuk panen kelapa hutan seperti biasa, kebetulan sedang musim. Kami tahu penyakit ini dari radio saja,” kata Ari.

Hasil riset dari ISEAS-Yusof Ishak Institute, yang dirilis pada 21 Agustus lalu, menjelaskan ketimpangan nyata di dunia pendidikan Indonesia selama musim pandemi Covid-19.
Hampir 69 juta siswa kehilangan akses pendidikan dan pembelajaran saat pagebluk. Namun, di sisi lain, banyak kelompok siswa dari keluarga mapan lebih mudah belajar jarak jauh. Ini implikasi dari ketimpangan, tulis riset itu.
Riset itu mendapati hanya 40% orang Indonesia memiliki akses internet. Ia makin membuka tabir ketimpangan infrastruktur komunikasi, khususnya di luar Pulau Jawa.
Bahkan sekalipun di Jakarta, ketimpangan akses belajar jarak jauh selama pandemi ini kentara.
Khoirin Dava, siswa kelas 1 di SD Negeri 03 Ancol, Jakarta Utara, sempat tak bisa mengikuti belajar daring karena keluarganya tak punya ponsel.
Pada Juli lalu, saat semester pertama, Dava melapor ke guru bahwa ia belum bisa mengikuti sekolah daring. Guru maklum dan menganjurkan Dava meminjam ponsel dari tetangga.
“Bahkan informasi ambil buku ke sekolah saja Dava telat dapat kabar,” kata Siti Masyitoh, ibunda Dava, kepada saya.
Ibu, bapak, Dava dan adiknya tinggal di sebuah rumah kontrakan ukuran 3x3 meter persegi seharga Rp600 ribu per bulan di Kampung Bandan, pinggiran utara Jakarta. Mereka terancam diusir karena sudah tiga bulan menunggak. Ayah Dava, buruh bangunan harian, sudah menganggur sejak awal April. Alat kerja ayahnya, seperti bor, martil, hingga pemotong keramik, sudah dijual demi keluarga itu menyambung hidup selama pandemi.
“Sedangkan saya hanya bisa ngamen sehari-hari di Kota Tua untuk makan sehari-hari,” kata Siti.
Pada medio Agustus lalu, Dava mendapatkan bantuan donasi ponsel gratis serta pulsa dan paket internet dari gerakan para wartawan yang tergabung dalam Wartawan Lintas Media. Dava tinggal menggunakannya saja. Alhasil, Dava sudah bisa belajar daring.
“Tinggal seragam enggak punya karena enggak ada uang. Belajar online teman-temannya pada pake seragam semua, hanya Dava yang tidak,” kata Siti.

Inisiatif Publik Menerabas Krisis Pendidikan
Dari kesehatan hingga pekerjaan, pagebuk semakin memperlihatkan beragam masalah publik di Indonesia. Dan persis ketika masalah ini meluas dan sistematis pada awal corona, ketika pemerintahan Jokowi meremehkan virus ini dan gelagapan menghadapinya, inisiatif publik saling membantu warga muncul lewat penggalangan dana dan donasi.
Dalam krisis pendidikan juga demikian. Gerakan Wartawan Lintas Media adalah salah satu inisiatif warga bantu warga. Gerakan ini menggalang donasi ponsel bekas. Ia juga menggalang dana viaKitaBisa.com, yang nantinya dipakai membeli ponsel pintar dan dibagikan ke para siswa.
Tsarina Maharani, salah satu penggeraknya, berkata inisiatif ini bermula dari salah satu teman bercerita ada pemulung datang ke rumah dan menanyakan apakah ada ponsel bekas atau tidak. Anak si pemulung butuh ponsel untuk belajar daring.
“Dari situ, akhirnya kami mikir … dengan kondisi ini, anak-anak siswa yang enggak punya ponsel itu banyak di luar sana,” kata Rani.
Hingga akhir Agustus, gerakan ini telah mengumpulkan 160-an ponsel bekas, meski tak semuanya bisa digunakan, serta dana lebih dari Rp500 juta.
Setidaknya sudah 270 siswa mengajukan permintaan ponsel bekas ke tim relawan, yang prosesnya diverifikasi oleh tim demi donasi tepat sasaran. Sudah ada 92 siswa menerima ponsel bekas pada gelombang pertama dan kedua. Berikutnya, dalam gelombang ketiga, 75 siswa dalam tahap pengiriman. Para siswa juga mendapatkan paket internet selama tiga bulan terturut-turut.
Di Yogyakarta, muncul gerakan BisaBelajar. Sejak 30 April, gerakan ini menggalang dana untuk disalurkan sebagai subsidi paket internet gratis ke para pelajar "kurang mampu."
Gamma Haezy, salah satu penggerak BisaBelajar, mengisahkan semula gerakan itu dikerjakan dua orang. Saat awal pandemi, publik dibetot perhatiannya berdonasi alat pelindung diri, tapi donasi pendidikan nyaris belum terlihat. “Pendidikan cukup penting dan terdampak karena enggak bisa maksimal,” kata Haezy.
Haezy bercerita timnya rutin berkomunikasi dengan asosiasi, serikat, dan forum-forum guru di Yogyakarta, sehingga gerakan itu bisa mendapatkan target siswa yang dinilai layak menerima donasi. Mereka sudah memberikan donasi paket internet ke 170 siswa. Saat ini, dalam gelombang kedua yang masih berjalan, tim BisaBelajar telah mengumpulkan donasi Rp19,5 juta.

Pada 11 Agustus, setelah enam bulan sekolah menggelar proses belajar daring, Menteri Keuangan Sri Mulyani berkata dalam satu seminar bahwa pemerintah tengah membahas untuk memecahkan krisis pendidikan selama COVID-19.
“Bagaimana kita bisa membantu mereka [yang] tidak bisa sekolah, tidak bisa mengakses melalui pembelajaran secara digital … entah masalah teknologi, masalah tidak memiliki handphone, atau tidak bisa membayar pulsa,” ujarnya.
Pada 27 Agustus, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim akhirnya merilis kebijakan bantuan kuota internet kepada para siswa se-Indonesia, dalam Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
Gamma Haezy menilai surat keputusan itu “telat sekali” setelah sekian lama pemerintah “baru sadar murid-murid butuh kuota.”
“Menteri Nadiem enggak pernah memberikan statement bahwa sekolah harus ini, sekolah harus itu, sekolah harus memberikan bantuan ini-itu. Dia selalu membiarkan sekolah menentukan, terserah murid, terserah guru, terserah sekolah,” kata Haezy.
Rani menilai kebijakan pemberian kuota internet tidak menyelesaikan akar permasalahan.
“Pemerintah ngasih kuota, internet gratis, tapi kalau misalnya enggak ada ponsel dan akses jaringan internet di daerah itu, bagaimana?” katanya.

======
Penyingkapan: Haris Prabowo, wartawan Tirto yang menulis laporan ini, tergabung dalam relawan gerakan Wartawan Lintas Media.
*Pada 11/9 pkl 09:46, Kami mengoreksi detail minor di bagian informasi mengenai inisiatif publik BisaBelajar.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Fahri Salam