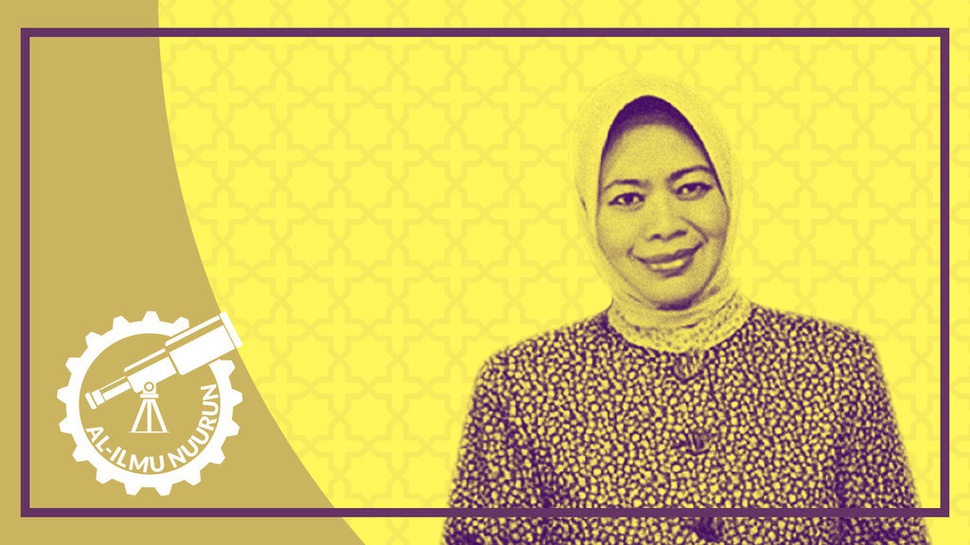tirto.id - Musdah Mulia kerap membatalkan salat berjamaah. Itu ia lakukan apabila mendengar nada sumbang dalam bacaan Alquran sang imam. Baginya, intonasi yang tidak tepat menunjukkan bahwa sang imam tidak kredibel untuk memimpin ibadah. Imam salat berkaitan dengan kompetensi, bukan perkara gender layaknya pandangan umum yang menyebut imam salat sebaiknya adalah pria.
Musdah, yang saya temui pada Rabu (6/6), mengajak saya mengingat Ummu Waraqah, wanita yang diminta Rasulullah untuk memimpin salat bagi umat laki-laki dan perempuan dewasa. Masa-masa itu ialah zaman ketika Rasulullah mengajarkan tentang kesetaraan antara pria dan wanita—konsep dan praktik yang kian luntur sepeninggalnya.
Dua puluh tahun terakhir Musdah mencoba membangkitkan prinsip kesetaraan lewat berbagai penelitian, buku, dan opini-opini yang disampaikan kepada publik. Ia menentang poligami dan pernikahan anak, mendukung pernikahan lintas agama, dan mengingatkan hakikat perempuan dalam Islam.
Sejumlah pemuka agama Islam dan penganut Muslim lain termasuk beberapa anggota keluarganya menentang pemikiran Musdah. Ia dinilai kafir dan murtad. Dalam sebuah khotbah, seorang ustaz bahkan menyiratkan Musdah dengan pandangan negatif: mengajarkan umat Muslim menyembah setan lewat ajakan untuk mendukung aktivitas masyarakat non-Muslim.
“Saya dimaki dan di-bully tapi saya tidak peduli. Walau saya harus jadi martir sekalipun, saya harus melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Saya mendakwahkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang menebar rahmat dan kasih sayang bagi semua makhluk di alam semesta. Yang penting, saya berusaha untuk tidak melakukan hal-hal prinsip yang dilarang agama, seperti berdusta, berlaku curang dan berkhianat, mencederai sesama, berzina, dan menebar hoaks,” kata Musdah.
Emansipasi dan Toleransi
Wanita asal Sulawesi Selatan ini dibesarkan dalam keluarga yang taat menjalankan praktik keagamaan. Ibunya, Buaidah Achmad, ialah wanita pertama yang berhasil menuntaskan jenjang pendidikan pesantren di sebuah desa di Pare Pare, Sulawesi Selatan. Ayahnya, Mustamin Abdul Fatah, pernah menjabat sebagai Komandan Batalyon DI/TII Sulawesi Selatan. Kakeknya adalah seorang ulama.
Musdah selalu mengenyam pendidikan dalam institusi berbasis Islam. Ia adalah doktor perempuan pertama bidang pemikiran politik Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Sepanjang hidup, saya belajar agama. Di rumah, saya tidak pernah dicekoki pandangan fundamentalis. Ibu adalah perempuan gigih yang mengajarkan kesetaraan dan kemanusiaan.”
Tekad untuk memperjuangkan kesetaraan perempuan membulat ketika ia bergabung dengan organisasi Fatayat NU dan mengadvokasi permasalahan perempuan-perempuan pedesaan. Hati Musdah miris melihat mereka yang terperangkap dalam kebodohan akibat ketiadaan akses informasi.
Saat itu ia juga melihat ajaran agama diterapkan sebagai praktik misoginis lewat pandangan terhadap perempuan sebagai obyek seksual dan mesin reproduksi. "Di sana muncul masalah tingkat kematian balita dan ibu melahirkan yang tinggi. Eksploitasi perempuan menjadi buruh migran, pekerja rumah tangga, pelacur, dan sebagian dipaksa menikah dalam usia dini. Akibatnya, muncul tingkat perceraian tinggi, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan perdagangan perempuan anak dan dewasa."
Ia bicara antusias layaknya seorang dosen yang tengah berapi-api menyampaikan materi di kelas. Padahal kami hanya bicara berdua di sebuah ruang kaca berkapasitas kurang dari 10 orang, sesaat setelah ia menguji sidang disertasi seorang mahasiswa.
Ada optimisme besar di balik hal-hal menyedihkan tentang ketimpangan dan intoleransi yang ia ceritakan. Musdah mengaku kecolongan saat mendengar kabar aksi teror di Surabaya beberapa waktu lalu. Perjuangannya puluhan tahun untuk kesetaraan perempuan belum menghasilkan dampak signifikan.
“Ini adalah kemunduran. Kalangan post-truth muncul dan tidak bisa diselamatkan. Pemerintah telah begitu lama membiarkan ruang demokrasi dimanfaatkan oleh kelompok yang berbuat hal bertentangan dengan nilai demokrasi yakni kebebasan, kesetaraan, dan penghargaan. Isu intoleransi menguat. Imbasnya peran perempuan makin direduksi. Poligami diproklamirkan sebagai ajaran Islam. Pernikahan dini diprovokasikan. Ijab kabul digunakan sebagai kamuflase perzinahan,” tutur perempuan pertama yang dikukuhkan LIPI sebagai Profesor Riset bidang Lektur Keagamaan.
Opini Musdah ada di tengah omongan ustaz yang menyatakan poligami ialah takdir perempuan. Pernyataan itu muncul beberapa hari lalu dalam tayangan spesial ramadan yang disiarkan langsung oleh satu stasiun televisi swasta pada jam prime time. Acara mendatangkan narasumber ustaz, ustazah, pria pelaku poligami, dan seorang wanita yang dipoligami. Dalam acara itu, sang ustazah berkata bahwa perilaku tidak adil akibat poligami ialah wajar karena mustahil manusia bersikap adil. “Intinya kita lebih sayang Allah atau suami?” Penonton menyambut khotbah dengan “subhanallah” dan tepukan tangan.
Dalam “Makna Nuzul Al Quran Bagi Perempuan”, Musdah menyatakan bahwa Rasul mengoreksi praktik poligami yang muncul di jaman jahiliyah. Sementara lewat Kemuliaan Perempuan Dalam Islam (2014), ia berpendapat bahwa poligami tidak dibenarkan karena bisa berseberangan dengan esensi sakinah, mawaddah, wa rahmah. “Perlu ada manajemen syahwat. Ayat tidak dibaca secara utuh. Sesungguhnya poligami satu tarikan napas dengan anak yatim,” tutur Musdah.
Berulang kali Musdah menekankan bahwa tidak ada ajaran agama yang berseberangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal seperti saling menghormati, melindungi, dan memberdayakan sesama. Dalam buku yang sama, ia menulis data historis yang menyebut perempuan leluasa mengekspresikan diri dan jadi mediator konflik. Ia mengutip ayat-ayat kitab suci yang mengisahkan perempuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial, punya kebebasan dalam menentukan pilihan pribadi, diimbau untuk menolak kezaliman, dan punya ruang bagi kebebasan berpendapat.
Musdah percaya Islam bukanlah sebuah ideologi yang muncul dari persimpangan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ia meyakini Islam sebagai agama yang harus dipelajari dengan nalar kritis dan dipahami secara kontekstual.

Empati adalah Kunci
Dalam artikel “Ada Apa dengan Buku-Buku Keislaman?” Musdah menulis bahwa Islam ialah agama yang paling vokal bicara soal pentingnya membaca bagi laki-laki dan perempuan. Ia menyayangkan bahwa buku yang diminati ialah buku keislaman normatif yang tidak merangsang pembaca melakukan analisis. “Buku yang banyak beredar hanya mengantarkan pembaca membangun kesalehan individu tetapi sulit menuju kesalehan sosial yang ditandai dengan rasa empati terhadap penderitaan kelompok rentan tertindas.”
Bekal untuk berempati salah satunya ia dapat lewat pengalaman mengikuti dialog antar-umat beragama di berbagai negara. Tahun lalu, Musdah ke Jerman mengikuti konferensi Peace Among The People: Interreligious Action for Peace and Inclusive Communities. Di sana ia mengunjungi sinagoga, gereja, dan masjid yang dipimpin oleh perempuan.
“Di sini anggapan miring tentang perempuan berubah. Aktivitas penuh perempuan dalam gerakan keagamaan, terutama dalam program dialog agama menjadikan rumah ibadah yang biasanya sangat eksklusif menjadi rumah suci yang inklusif, ramah terhadap semua golongan dan fungsional bagi upaya-upaya kemanusiaan. Perempuan justru lebih mengedepankan tujuan hakiki semua agama, yaitu memanusiakan manusia,” tulis penggagas Indonesian Conference on Religion and Peace ini.
Baca juga:
- Haidar Bagir: Tasawuf Akal, Toleransi, dan Pembelaan Terhadap Syiah
- Sepakbola dan Tafsir Alquran dalam Hidup Quraish Shihab
- Djohan Effendi dan Warisan Islam yang Toleran
Pada malam setelah bertemu dengan saya, ia berangkat ke Jerman untuk mengikuti dialog antar-agama. Satu informasi yang bisa jadi bahan diskusi ialah penelitan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatulah terhadap kaum muslim generasi Z, para guru dan dosen tekait pandangan mereka tentang agama, keragaman, negara, dan pendidikan agama sebagai pembentuk cara berpikir. Studi menunjukkan hampir sepertiga responden menanggap perbuatan intoleran terhadap kaum minoritas bukan masalah.
Bagi kaum perempuan yang belum terseret pusaran post-truth, ia berharap agar mereka bisa memahami hak dan kewajiban sebagai individu dalam keluarga dan sebagai warga negara dan memaknai agama sebagai internalisasi nilai-nilai universal. Untuk mereka yang mengalami ketidakadilan, Musdah berpesan agar jangan pernah diam. Seperti Musdah yang terus bergerak melawan mereka yang masih melihat agama sebagai sekat pemisah.
====================
Sepanjang Ramadan hingga lebaran, redaksi menyuguhkan artikel-artikel yang mengetengahkan pemikiran para cendekiawan dan pembaharu Muslim zaman Orde Baru dari berbagai spektrum ideologi. Kami percaya bahwa gagasan mereka bukan hanya mewarnai wacana keislaman, tapi juga memberi kontribusi penting bagi peradaban Islam Indonesia. Artikel-artikel tersebut ditayangkan dalam rubrik "Al-Ilmu Nuurun" atau "ilmu adalah cahaya".
Editor: Ivan Aulia Ahsan