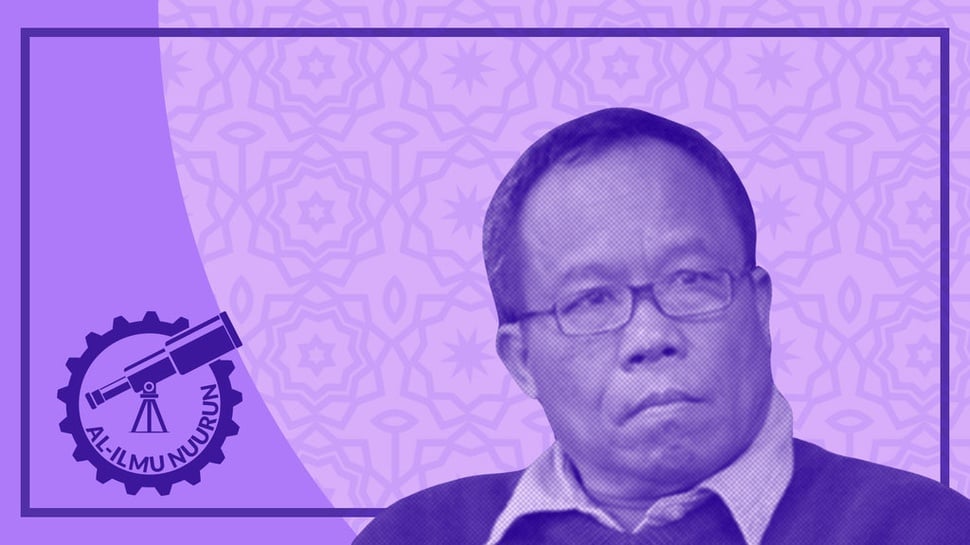tirto.id - Saat berusia sembilan tahun, Mohamad Sobary ditegur sang ayah. “Untuk apa kamu jengkang-jengking (salat)? Tahu apa kamu?” Teguran itu begitu membekas di hati dan ingatannya. Sedih? Tentu saja. Sedikit bocah yang tak sedih ditegur lantaran sedang rajin-rajinnya sembahyang.
Sobary—seperti ia akui sendiri dalam tulisannya berjudul “Ayah dan Pici”—melakoni masa kanak-kanak dalam dunia kecil yang ruwet. Ia lahir pada 7 Agustus 1952 di Bantul, Yogyakarta di desa dengan kultur Muhammadiyah yang kuat. Lantaran menimba ilmu agama di pengajian Muhammadiyah, Sobary selalu mendaku diri sebagai anak Muhammadiyah.
Meski begitu, sang ayah justru seorang abangan yang tidak menjalankan perintah sembahyang. Tapi ia pernah bertapa seperti yang dilakukan Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu kenabian, mengajarkan berhenti makan sebelum terlalu kenyang seperti teladan Kanjeng Rasul, doyan tirakat seperti warga NU di pesantren, makan cuma umbi-umbian, cegah daging, cegah garam, dan melek malam.
“Wisdom-nya: jangan sebut keburukan orang. Lupakan kebaikanmu sendiri. Baginya, agama itu hidup. Kalau kita sudah mengerti makna hidup, baru kita paham apa itu agama,” begitu Sobary mengenang wejangan ayahnya.
Dekade 1960-an adalah masa ketika politik menjadi "panglima". Di zaman itu, menurut Sobary, membincangkan ideologi, politik, dan agama adalah salah satu jalan keluar melupakan kemiskinan yang mencekam. Meski demikian, Sobary mengaku ayahnya tak doyan bicara politik.
“Kami makan bubur. Mungkin lebih tepat minum, sebab terlalu encer. Itu pun kadang kurang. Sering Ayah menahan diri dan tak makan.”
Sobary menapaki dunia pendidikan di bawah bayang-bayang kemiskinan. Saat akan naik ke kelas 6 SD ia berhenti sekolah lantaran tidak bisa beli seragam. Ia baru bisa menamatkan sekolah setelah kedua orang tuanya berhasil mengumpulkan uang. Hal yang sama terjadi saat ia duduk di bangku kelas 1 SMP Muhammadiyah. Lagi-lagi ia berhenti sekolah karena tak punya uang untuk beli seragam.
Pamannya yang bekerja di Departemen P&K akhirnya memboyong Sobary ke Jakarta. Awal 1967, ia bersekolah di SMP Negeri XII Wijaya, Jakarta Selatan. Untuk bertahan hidup di Jakarta, Sobary melakukan apa saja; mulai dari menyapu jalanan di Blok M hingga menjadi tukang antar roti. Ia bahkan mengaku pernah tidur di emperan toko bersama para gelandangan ibu kota. Dari sini ia mengaku bisa merasakan langsung kehidupan orang-orang yang terpinggirkan.
Karier kepenulisan Sobary sudah dimulai saat ia duduk di bangku SMP. Ia rajin mengirim cerpen anak-anak untuk majalah Si Kuncung dan Kawanku. Saat tulisannya dimuat dan menerima honor, kepercayaan dirinya menguat. Sobary yakin ia bisa menulis dan bisa menjadikan tulisan sebagai sandaran kehidupan.
Berhasil menjadi lulusan terbaik di SMP Negeri XII, Sobary melanjutkan pendidikan ke Sekolah Pekerja Sosial Atas Negeri Jakarta dengan beasiswa dari Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Selanjutnya, atas saran guru bernama Amir Mahtum, ia ikut tes di Universitas Indonesia dan diterima di Jurusan Kesejahteraan Sosial FISIP UI.
Orang Kecil dan Sufisme
Saat menjadi mahasiswa, Sobary berusaha memperluas tema-tema tulisannya. Ia giat menulis resensi buku dan mulai berani mengkritik fenomena sosial di zamannya. Tulisan berjudul “Kang Suto” yang terbit 1980-an, misalnya, berisi kritik atas fenomena semangat keberagamaan orang-orang Jakarta yang hanya melahirkan sikap dogmatis nan kaku.
Syahdan, Kang Suto, seorang penarik becak di pinggiran Jakarta, mengalami kebimbangan. Penyebabnya adalah ia ingin belajar salat. Tapi Kang Suto tak mengerti bacaan dan doa salat dalam bahasa Arab. Usahanya belajar mengaji ke seorang ustaz berakhir mengenaskan. Alih-alih mendapat bimbingan, Kang Suto malah disalah-salahkan karena terus gagal melafalkan “ain” dan “alhamdulillah” dengan benar.
Sang ustaz bilang, bahasa Arab tidak sembarangan. Salah bunyi bisa salah arti. Salah arti bisa-bisa malah dosa. “Mau belajar malah dapat dosa,” gerutu Kang Suto. Di Sruweng, kampung halamannya, tidak ada huruf hijaiyah “ain”, yang ada “ngain”. Alhamdulillah dalam surah Alfatihah pun dibaca “Alkamdulillah”.
Tulisannya yang berjudul “Kang Sejo Melihat Tuhan” juga mengangkat kritik dengan napas yang hampir sama. Melalui lakon Kang Sejo, seorang tuna netra yang berprofesi sebagai tukang pijat dan tidak bisa berbahasa Arab, Sobary seolah-olah hendak berpesan bahwa keakraban dengan Tuhan bukanlah monopoli agamawan dan hartawan. Sebab yang terpenting bukanlah mengucap nama Tuhan dalam bahasa Arab atau bahasa Jawa, tapi menghadirkan-Nya dalam ingatan, ucapan, dan laku perbuatan. Esai inilah yang membuat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjuluki Sobary dengan sebutan Kang Sejo.
Selain senang menggunakan lakon orang kecil untuk menyampaikan kritik, Sobary juga kerap memanfaatkan tokoh pewayangan sebagai sarana menyindir keadaan. Bahkan ia juga tak segan mengambil perumpamaan hewan—seperti dalam esai berjudul "Anjing" dan "Bunglon"—untuk menyentil polah manusia yang menyebalkan.
Meski kisah-kisah yang diangkat kadang-kadang bersifat fiksi, sulit untuk mengatakan karya-karya Sobary terlepas dari realitas hidup keseharian. Dalam "Kang Suto" atau "Kang Sejo Melihat Tuhan" atau "Anjing", dapat dirasakan betapa Sobary menjadi bagian inheren dari cerita yang dituturkannya. Pada konteks ini, gagasan dan kritik Sobary agaknya turut dibentuk oleh latar belakangnya yang berwarna-warni sebagai orang Muhammadiyah yang lahir dari keluarga abangan dan pengalamannya bergaul dengan orang-orang kecil.
Di sisi lain, kritik-kritik Sobary terhadap praktik beragama yang sekadar menonjolkan kulit membuat sebagian orang mengidentifikasinya sebagai pembawa pesan sufisme Jawa. Salah satunya adalah W.S. Rendra. Saat memperkenalkan Sobary kepada penyair Sitor Situmorang, Rendra mengatakan Sobary sebagai penulis yang menjadikan sufisme sebagai kritik. "Itu kata Rendra, loh ya, bukan saya yang bilang sendiri," ujar Sobary kepada Tirto ketika ditemui di kediamannya pada awal Ramadan ini.

Lantas, apa itu Islam Jawa bagi Sobary?
Ia mengatakan, Islam Jawa tak beda dengan Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Islam Jawa adalah proses terus menerus seorang manusia mengenal Tuhan menuju maknanya yang paling sejati. Bukan sekadar kemasan tampilan dan ucapan.
“Islam Jawa itu, ya, Islam. Juga proses pencarian manusia kepada Tuhannya,” tutur Sobary.
Kepiawaian Sobary berolah kata tidak hanya mewujud dalam bentuk esai. Disertasinya di Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia yang berjudul “Perlawanan Politik dan Puitik: Ekspresi Politik Petani Temanggung” (2016) dinilai para pengujinya sebagai warna baru dalam gaya penulisan karya ilmiah di dunia akademik.
“Ini disertasi pertama kali yang ditulis dengan head, hand and heart. Saya mengapresiasi pembaruan penulisan disertasi seperti ini,” kata Fentiny Nugroho, salah seorang penguji disertasinya, yang juga diamini Gumilar Rusliwa Somantri, penguji yang lain.
Di usianya yang hampir menginjak 66, Sobary sudah menulis ratusan artikel di berbagai media massa di antaranya Kompas, Tempo, dan Republika. Bahkan hingga kini, ia masih rutin menulis esai di Koran Sindo. Esai-esai itu telah dikumpulkan dalam belasan buku. Selain itu, Sobary juga menulis beberapa novel.
Boleh setuju atau tidak, melalui pelbagai kritik dan sindiran dalam tulisannya, Sobary telah mengajak para pembacanya pulang ke jati diri mereka sebagai manusia.
Sepanjang Ramadan hingga lebaran, redaksi menyuguhkan artikel-artikel yang mengetengahkan pemikiran para cendekiawan dan pembaharu Muslim zaman Orde Baru dari berbagai spektrum ideologi. Kami percaya bahwa gagasan mereka bukan hanya mewarnai wacana keislaman, tapi juga memberi kontribusi penting bagi peradaban Islam Indonesia. Artikel-artikel tersebut ditayangkan dalam rubrik "Al-Ilmu Nuurun" atau "ilmu adalah cahaya".
Editor: Ivan Aulia Ahsan