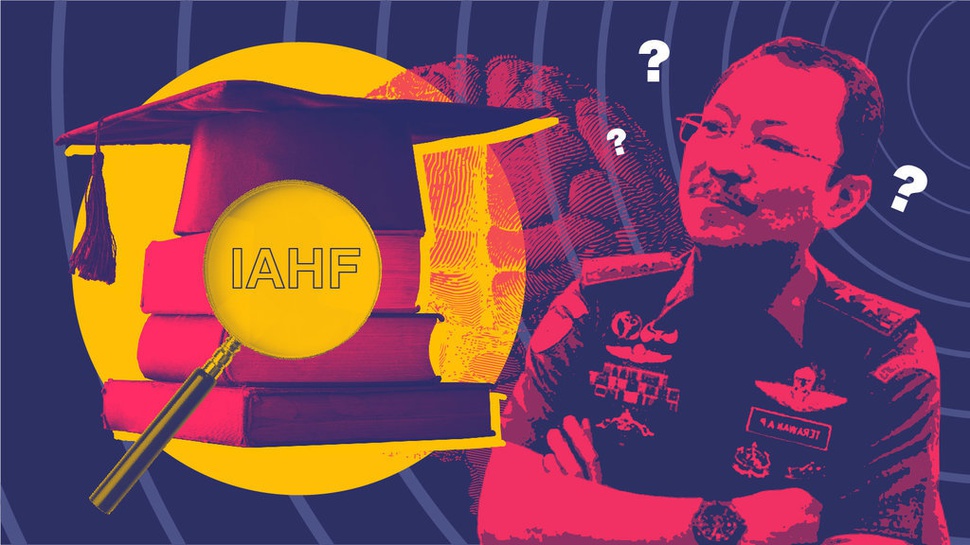tirto.id - Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sudah menjatuhkan sanksi kepada Terawan Agus Putranto sejak Februari 2018. Beragam kebijakan ditempuh untuk mengurai kontroversi. Tapi semuanya menguap begitu saja, sementara Terawan justru melenggang jadi Menteri Kesehatan di Kabinet Indonesia Maju, pada periode kedua masa pemerintahan Joko Widodo.
Ribut-ribut soal terapi Intra Arterial Heparin Flushing (IAHF) alias “cuci otak” yang dilakukan Terawan bermula saat ia mendapat sorotan MKEK IDI pada tahun 2015. Awal Januari tahun itu MKEK sudah memanggil Terawan untuk meminta penjelasan soal terapinya yang diklaim dapat menyembuhkan stroke.
Kala itu Terawan telah mempraktikan terapi cuci otak di RSPAD Gatot Soebroto kira-kira selama sepuluh tahun. Pada tahun yang sama, Terawan juga tengah menggarap disertasi soal IAHF di Universitas Hasanuddin, Makassar. Ia mendaftar program doktoral pada tahun 2013 dan lulus dengan predikat sangat memuaskan.
Disertasi berjudul “Effect of Intra Arterian Heparin Flushing (IAHF) Against Cerebral Blood Flow, Motor Evoked Potentials, and Motor Function in Chronic Ischemic Stroke” dinyatakan memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Disertasi pada 8 Mei 2016.
Jika ditarik ke belakang, Terawan sudah melakukan terapi cuci otak jauh sebelum disertasinya rampung. Dalam disertasinya, Terawan menyebut terapi IAHF sudah dilakukan pada rentang tahun 2011-2014. Masa itu diklaim Terawan sebagai studi pendahuluan. Meski disebut studi pendahuluan, akan tetapi tidak ada karya ilmiah yang menjadi landasannya.
Disertasi tersebut menjadi satu-satunya kajian yang ia jadikan landasan ilmiah IAHF. Artinya, terapi IAHF yang ia lakukan sebelum 2016 tak memiliki landasan keilmuan, jika tak mau dibilang ilegal.
Menyembunyikan Anjing
Tirto dan Tempo berkolaborasi menelaah disertasi Terawan. Kami menemui beberapa narasumber yang terdiri dari pakar-pakar kesehatan, Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) khusus untuk menangani IAHF, promotor, serta penguji disertasi.
Kami mempelajari bersama disertasi setebal lebih kurang 135 halaman itu dan menemukan beberapa kejanggalan. Salah satunya soal pengutipan yang kurang lengkap dan tidak sesuai konteks. Kutipan studi Jessica H. Lewis paling jadi sorotan. Terawan menggunakan penelitian tahun 1964 itu sebagai tinjauan pustaka utama.
Ia juga meletakkan dasar pemikiran Lewis dalam jurnal terbitan Bali Medical Journal dan Indonesian Biomedical Journal – jurnal yang ia buat dari hasil turunan disertasi.
Dalam Tinjauan Pustaka bagian pembahasan Heparin, Terawan menuliskan “Heparin telah digunakan secara luas pada kelainan tromboemboli (sumbatan pembuluh darah) pada manusia”. Lalu di pembahasan selanjutnya ia menyatakan “Berlawanan dengan temuan in vitro, heparin merupakan agen trombolitik yang paling aktif dalam menurunkan ukuran clot”.
Kami mencoba mencari studi asli milik Lewis dan menemukan terbitannya di American Journal of Physiology. Ternyata kutipan pertama di studi asli bukan menjadi sari dari penelitian Lewis. Lewis hanya menjadikan kalimat tersebut sebagai prolog yang menjelaskan bahwa studi soal terapi tromboemboli memiliki tingkat kesukaran tinggi, sehingga banyak pakar tertarik meneliti.
Temuan menarik lainnya, penelitian Lewis ini tidak dilakukan pada manusia melainkan pada anjing jenis mongrel. Fakta ini yang tidak diungkap Terawan dalam disertasinya. Kata "anjing" sebagai hewan uji coba tidak ditemukan dalam disertasi Terawan sehingga seolah-olah penelitian Lewis itu dilakukan pada manusia.
Selain itu, penelitian Lewis juga tidak dilakukan pada kondisi in vivo (dalam tubuh makhluk hidup), melainkan kondisi in vitro (tabung gelas). Lewis mengumpulkan gumpalan darah (clot) anjing mongrel dalam tabung dan memberikan heparin untuk melihat reaksi peluruhan clot. Hasilnya menyatakan heparin tidak menyebabkan perubahan fibrinolitik (enzim yang mencegah penggumpalan darah) anjing.
Kejanggalan lain, beberapa referensi yang digunakan juga tak sejalan dengan kerangka besar disertasi. Dalam disertasinya, Terawan menerapkan metode IAHF pada pasien stroke iskemik kronik dengan waktu onset lebih dari 30 hari. Ia mengutip beberapa sumber untuk dijadikan landasan teori, diantaranya studi Schllinger (2001), Copen (2012), Font (2010), atau Yucheng (1995).
Padahal studi-studi tersebut jelas-jelas diterapkan pada kasus stroke iskemik akut. Heparin hanya bisa melisiskan/meluruhkan clot pada bekuan darah anyar (stroke iskemik tipe akut), yakni dengan waktu pembekuan tidak lebih dari 4,5 jam.
Keliru Itu Wajar
Sebelum diterima di Universitas Hasanuddin Makassar, Terawan pernah mengajukan program doktoral di tempat lain. Pada tahun 2011, ia bahkan sempat menunjukkan proposal IAHF kepada Teguh AS Ranakusuma, guru besar bidang Nurologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Saat itu Teguh meminta Terawan menyusun kajian ilmiah terhadap IAHF.
“Silakan bagus, ilmu itu bergerak, dinamis, tidak ada kebenaran sejati dalam kehidupan manusia,” katanya merunut kembali obrolan saat itu.
Teguh akhirnya diundang sebagai salah satu penguji. Ia ingat sekali sudah memberi komentar positif terhadap metode IAHF, tapi hanya sekadar untuk alat deteksi dini, bukan terapi pengobatan. Tapi, dalam wawancara kolaborasi kali ini, Terawan sangat jelas mengatakan bahwa inovasinya telah melampaui itu semua.
“Lha itu tergantung ilmunya. Kalau ilmunya baru sampai diagnosa ya pandangannya diagnosa. Kalau ilmunya sudah sampai ke terapi, maka dia akan membuka itu semua,” kata Terawan.
Terawan juga membela diri terhadap tuduhan manipulasi dan fabrikasi data pada disertasi. Menurutnya, uji klinis IAHF terhadap hewan bisa langsung dilewati karena sudah menjadi bahan riset terdahulu (Lewis, 1964). Pun penggunaan heparin yang lebih ia tekankan pada aspek keamanan, bukan berdasar pada jenis stroke iskemik akut, ataupun kronik.
“Ndak ada, sudah langsung manusia,” ia menampik tuduhan pembelokan informasi pada studi Lewis.
Ringkasnya, selagi penelitian umum soal Digital Subtraction Angiography (DSA) dan heparin pada dosis dan tingkatan tertentu dinyatakan aman, maka IAHF miliknya pun begitu adanya. Tak puas dengan jawaban tersebut, kami mengulik informasi dari promotor disertasi Terawan.
Dua dari tiga promotornya merupakan guru besar dari Universitas Hasanuddin Makassar. Irawan Yusuf adalah ahli farmakogenomik dan Bachtiar Murtala seorang radiolog. Usaha konfirmasi kepada Irawan tak berbuah hasil karena ia menolak diwawancara. Sedangkan Bachtiar bersedia mengklarifikasi sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai pembimbing.
“Sebetulnya saya berat hati melayani, karena ini soal sensitif. Beliau (Terawan) tahu ini tidak begitu berkenan,” ujarnya membuka obrolan kami.
Satu per satu pertanyaan menyoal kejanggalan disertasi IAHF kami lontarkan. Masalah ketidaksesuaian pengutipan, indikasi manipulasi, dan hasil disertasi. Bachtiar selalu mengulang-ulang pernyataan bahwa apapun yang terjadi, gelar doktoral tak bisa dicabut karena merupakan kewenangan universitas. Apalagi cuma karena kutipan yang kurang lengkap.
“Rektor sudah tanda tangan ijazah, artinya dia sudah melewati syarat kelulusan dari universitas. Jokowi pun tak berhak membatalkan, apalagi Ikatan Dokter Indonesia (IDI),” tegas Bachtiar.
Dalam pandangan Bachtiar, IDI adalah kelompok yang bertanggung jawab atas mencuatnya kasus ini. Ia justru defensif dan mengatakan tidak ada disertasi yang sempurna. Apalagi dibatasi dengan administrasi, biaya, dan waktu. Malah menurutnya untuk bisa nyatakan bagus, sebuah kajian ilmiah harus meninggalkan masalah baru untuk diteliti ilmuwan berikutnya.
“Kalaupun keliru itu wajar, kalau Anda tidak setuju silahkan dibantah dengan penelitian.”
Kekuatan Rangkap Jabatan
Disertasi IAHF milik Terawan mengambil 75 sampel pasien stroke iskemik di RSPAD Gatot Soebroto dalam rentang waktu tujuh bulan, yakni mulai Februari hingga September 2015. Setelah melakukan serangkaian proses, ia membandingkan tiga faktor kesehatan pasien sebelum dan sesudah menerima terapi IAHF.
Ada tiga kesimpulan yang dicantumkan Terawan hasil pengujian IAHF, yakni aktivitas darah ke otak, gerak motorik, dan reflek pasien dalam menerima rangsang. Semuanya menunjukkan perubahan positif menurut hasil uji dalam disertasi. Kami meminta penjelasan Bachtiar soal pengujian ulang hasil klinis ini. Ternyata, baik promotor maupun penguji tidak melakukan uji ulang hasil disertasi.
Mereka menyerahkan pengukuran hasil uji klinis pada tim dokter spesialis – yang juga berasal dari RSPAD Gatot Soebroto. Padahal kala itu Terawan tengah menjabat jadi ketua etik kedokteran rumah sakit, kepala rumah sakit, sekaligus ketua perhimpunan dokter spesialis radiologi. Tiga jabatan krusial yang memegang kendali besar tapi dengan kontrol minim.
“Ini sudah lewat sidang, lalu apa masalahnya?” Bachtiar justru bertanya balik ketika kami sodorkan fakta tersebut.
Dari wawancara dengan Bachtiar kami malah mendapat informasi, bahwa ada disertasi lain yang dikerjakan bersamaan dengan milik Terawan. Dengan data yang sama dihasilkan beberapa disertasi berbeda, termasuk salah satu yang ia ketahui berada di bidang neurologi. Tapi tak ada satupun yang muncul ke permukaan, kecuali IAHF Terawan.
Kejanggalan lain menyoal penarikan sejumlah biaya pada sampel, dan ketiadaan lembar persetujuan yang ditandatangani sampel. Idealnya peneliti tidak menarik biaya kepada sampel, namun lampiran pertama disertasi tersebut menyebut biaya terapi ditanggung mandiri oleh pasien. Mengenai hal ini Bachtiar enggan berkomentar, karena menurutnya masalah tersebut tidak masuk alur keilmuan disertasi.
“Itu masuknya pelayanan RSPAD. Tapi saya yakin lah inform consent pasti sudah ditandatangani pasien sebelum dilakukan tindakan,” katanya.
IAHF: DSA Modifikasi
Tiga hari setelah dirawat di RSPAD Gatot Soebroto dan menjalani IAHF, Doni merasa pegal-pegal di badannya berangsur leyap – meski sebenarnya hasil cek laboratorium pra terapi mengungkap riwayat kesehatannya baik saja. Tapi ia langsung memutuskan menjalani terapi “cuci otak” lantaran sebelumnya mengalami bengkak kaki kiri setelah 7 jam perjalanan udara.
“Ya lumayan, dulu sering pegal di leher,” katanya pada kami seraya menepuk tengkuk bagian atas.
Selain karena pembengkakan di kaki, ia mengatakan mengambil terapi IAHF sebagai upaya preventif agar tubuhnya tak mengalami penggumpalan darah. Riwayat keluarga besar Doni memiliki penyakit stroke dan darah tinggi. Jadi ia berpikir lebih baik mencegah dan mengeluarkan biaya Rp50 juta untuk prosedur operasi kurang dari 10 menit, daripada harus terlambat mengobati.
Rencananya ia juga akan membawa sang istri yang punya riwayat diabetes untuk melakukan terapi serupa. Saat kami tanya soal tidak adanya landasan klinis pada terapi ini, Doni cuma tertawa.
“Ya aku sadar sih jadi kelinci percobaan. Tapi ini lumayan, setahun nggak perlu buang duit atau habis waktu buat pijet.”
Testimoni soal keberhasilan terapi IAHF bukan cuma dilontarkan Doni seorang. Sudah banyak pasien-pasien Terawan, termasuk para pejabat dan politisi lebih dulu mengglorifikasi manfaat terapi 'cuci otak' Terawan. Mereka percaya bahwa IAHF merupakan penemuan anyar – yang justru harus diakomodasi keberlangsungannya oleh pemerintah.
Padahal setelah mengkaji disertasi, kami – dan narasumber ahli – tak menemukan perbedaan antara metode DSA yang digunakan untuk tahapan diagnosis dengan IAHF. Terawan sempat mengutarakan bahwa IAHF merupakan metode DSA umum yang sudah dimodifikasi sehingga mampu melisiskan clot pada stroke.
Namun letak modifikasi yang ia sebutkan tidak dipaparkan secara gamblang dalam disertasinya. Pada bagian Definisi Operasional disertasi, Terawan menyebut IAHF dilakukan dengan cara:
“... memasukkan kateter melalui arteri femoralis hingga mencapai arteri carotis dan arteri subclavia, kemudian dilanjutkan angiografi dengan memasukkan bahan kontras. Dilanjutkan dengan flushing heparin 5000 IU/500cc NS.”
Ketika kami elaborasi, Bachtiar Murtala selaku promotor disertasi Terawan mengatakan perbedaan terapi IAHF dengan DSA biasa berfokus pada penambahan cairan fisiologis khusus – selain heparin, dan pengaturan tekanan saat melakukan penyemprotan.
“Jadi bukan asal semprot karena terlalu kencang juga bisa pecah pembuluh darah. Diatur berapa volumenya supaya bagus.”
Kami lalu meminta pendapat ahli lain, Moh. Hasan Machfoed, profesor neurologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Ia menyatakan tak ada perbedaan antara teknik IAHF dan DSA. Mekanisme keduanya berfungsi untuk mendeteksi pembuluh darah yang tersumbat lewat penyemprotan cairan kontras.
Baik IAHF maupun DSA sama-sama menggunakan tekanan untuk memasukkan cairan kontras. Sementara heparin digunakan sebagai “pembuka jalan” bagi kateter yang masuk ke tubuh.

Jika dijelaskan secara sederhana, darah akan menggumpal ketika mendapat intervensi dari benda asing. Misal saat terluka, tak lama darah yang keluar akan menggumpal karena tubuh memiliki fungsi antifibrinolitik (membekukan darah). Pemberian heparin bertujuan agar kateter DSA bisa masuk ke dalam tubuh tanpa terjadi penggumpalan darah baru.
Di sini heparin menjalankan fungsinya mencegah terjadinya pembekuan darah saat ada benda asing masuk ke dalam tubuh.
“Bedanya dia kasih nama yang lain, padahal tidak ada beda sama sekali,” ujar Machfoed. Ia juga sempat membuat jurnal tandingan yang terbit di BAOJ Neurology (Juni 2019) untuk menguliti studi milik Terawan.
Tata laksana penanganan stroke iskemik yang benar, menurutnya harus dibedakan berdasar jenis stroke. Pada stroke iskemik akut, obat-obatan penghancur clot bisa diberikan kepada pasien dengan catatan tidak lebih dari lima jam. Jika lewat batas waktu mekanisme pembekuan darah normal akan terganggu, sehingga mengakibatkan adanya pendarahan di otak.
Kondisi tersebut tak lagi manjur dibenahi dengan obat-obatan – termasuk heparin, hingga akhirnya membikin kelumpuhan pada fungsi tubuh. Tata laksana penangan stroke pertama memang jarang dilakukan di Indonesia. Sebabnya pasien sering terlambat dibawa ke rumah sakit.
Jika stroke sudah melebihi “golden period” (kurang dari 12 jam) maka dokter tetap akan memberikan obat yang sama, ditambah meminta pasien menurunkan faktor risiko dengan olahraga serta hidup teratur.
“Itu terapi yang paling baik, bukan ‘cuci otak’ langsung sembuh (strokenya),” kata Machfoed.
Jika IAHF dan DSA tak punya perbedaan, maka sebenarnya tak salah merasa aman saat menjajal metode tersebut. Toh, DSA memang sudah digunakan luas di dunia medis, jauh sebelum Terawan mengklaim memodifikasinya menjadi IAHF.
Pertanyaannya kemudian, bagaimana alat diagnostik bisa memberi efek “sembuh” bagi banyak orang? Penjelasan yang paling mungkin adalah efek plasebo.
___________
Laporan ini merupakan hasil kolaborasi Tirto dan Majalah Tempo. Semua hasil wawancara dan data yang didapat reporter Tirto dan Tempo digunakan bersama sebagai bahan tulisan. Reporter Tirto yang terlibat dalam liputan ini: Aulia Adam, Aditya Widya Putri, dan Adi Briantika.
Editor: Mawa Kresna