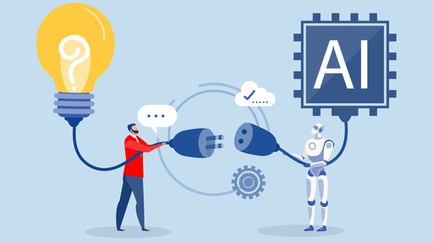tirto.id - Tahun 2019 kemarin wilayah Indonesia melewati kemarau yang lebih panjang dibanding periode sebelumnya. Kemudian kekeringan itu ditutup dengan datangnya musim hujan yang sedikit telat, ditambah, banjir di sejumlah wilayah. Banyak orang baru merasakan dampak nyata perubahan lingkungan.
Sejumlah wilayah yang tak pernah kekeringan tiba-tiba saja sulit menemukan sumber air saat kemarau. Para warga di wilayah tersebut harus membeli air dari depot-depot isi ulang dan menghemat pemakaian air harian. Kondisi tersebut rata-rata berlangsung 2-3 bulan lamanya.
Kemarau panjang dihapus hujan dengan intensitas rendah di awal November. Sampai di sana kekeringan belum tuntas semua, hingga Desember akhir tepat malam pergantian tahun hujan deras mengguyur Indonesia. Paginya sejumlah warga--yang sebagian tak pernah terdampak banjir--melaporkan huniannya sudah tergenang air.
Di tengah narasi soal perubahan lingkungan yang kembali digaungkan, muncul pula opini-opini penangkalnya. Di tingkat global, kelompok-kelompok konservatif menolak mempercayai konsep perubahan iklim. Alih-alih membenahi alam, mereka mencari kambing hitam atas dampak perubahan iklim dan lingkungan yang kini kita rasakan.
Di Indonesia kita bisa mendengar suara mereka lewat pandangan yang mengaitkan banjir dengan azab maksiat di tahun baru. Bahkan sekolompok warga di Bekasi menyegel toko minuman beralkohol karena menyakini toko tersebut sebagai salah satu pemicu banjir awal tahun kemarin.
Tak perlu kaget melihat fakta tersebut, sebab menurut survei tahunan YouGov-Cambridge Globalism Project 2019, Indonesia dinobatkan menjadi negara dengan penduduk paling meragukan perubahan iklim (18 persen). Statistik ini diperoleh melalui survei lebih dari 25 ribu orang dari 23 negara di seluruh Eropa, Amerika, Afrika dan Asia pada bulan Februari dan Maret 2019.
Masyarakat Indonesia banyak yang tak percaya bahwa manusia membawa pola perubahan terhadap lingkungan. Begitu pula dengan masyarakat Arab Saudi (16 persen), dan Amerika Serikat di urutan ketiga (13 persen). Negara terakhir terkenal sebagai sarangnya ilmuwan yang tidak percaya bahwa perubahan iklim benar-benar terjadi.
Bahkan Presiden Donald Trump pernah bilang bahwa perubahan iklim adalah “hoaks” belaka. Ia menampik laporan perubahan lingkungan yang dikeluarkan oleh negaranya sendiri dan menuduh narasi tersebut berbau politis.
Mengapa Mereka Tak Percaya Perubahan Lingkungan?
Orang-orang dengan tingkat pendidikan rendah, memiliki umur lebih tua, dan lebih religius cenderung jadi kelompok yang mengabaikan perubahan lingkungan. Mereka kurang bisa menerima fakta perubahan lingkungan karena tidak memiliki informasi memadai. Tapi The Conversation menyebut bahwa penolakan terhadap isu perubahan iklim di kalangan konservatif didorong oleh faktor politis.
Bagi sejumlah konglomerat, fakta-fakta perubahan iklim dianggap sebagai ancaman bagi bisnis mereka. Jika kampanye perubahan lingkungan berhasil dan dunia bersama-sama menuju ekonomi rendah emisi, maka transisi tersebut akan mengganggu agenda politik dan bisnis orang-orang kaya ini.
Seorang jurnalis Amerika bernama Christopher Leonard berhasil membuka persekutuan jahat Trump dan Charles dan David Koch (Koch bersaudara) dalam isu perubahan lingkungan. Investigasinya dimuat dalam buku bertajuk Kochland: The Secret History of Koch Industries and Corporate Power in America (2019).
Koch bersaudara (dan Koch Industries) adalah salah satu perusahaan swasta terbesar di Amerika. Koch bersaudara selama ini jor-joran membiayai beragam aktivisme yang menyangkal perubahan lingkungan. Bisnis Koch bersaudara memang bergerak di industri bahan bakar fosil yang menjadi salah satu sumber polusi karbon terbesar.
“Koch mendanai konferensi yang dihadiri ilmuwan, kelompok advokasi nirlaba, dan akademis yang mereka sebut ‘echo chamber’,” tulis Leonard.
Konferensi tandingan bertajuk “Global Environmental Crisis: Science or Politics?” digagas Koch pada tahun 1991. Kelompok pendukung industri bahan bakar fosil dalam konferensi tersebut bereaksi setelah Presiden George H. W. Bush mengumumkan dukungan atas perjanjian pembatasan emisi karbon--sebuah kebijakan yang berpotensi mengancam bisnis Koch Industries.
Menurut laporan Leonard, think tank asal Washington Third Way bekerja untuk Koch dalam upaya negosiasi North American Free Trade Agreement. Tujuannya agar bisnis impor minyak dari Kanada milik Koch tidak terganggu. Terakhir Leonard menguak persekutuan jahat antara Koch bersaudara, Trump, dan Wakil Presiden Mike Pence.
Pada tahun 2016 publik sempat mengira Koch tidak mendukung Trump. Tapi nyatanya, setelah dilantik, Presiden Trump selalu mengeluarkan pernyataan dan kebijakan yang menyangkal perubahan iklim. Leonard berkesimpulan Koch bersaudara telah melakukan lobi melalui Wakil Presiden Mike Pence, yang beberapa kali datang di gelaran konferensi Koch, termasuk pada tahun 2010 di Colorado.

Perubahan Lingkungan itu Nyata
Kenaikan permukaan laut membuat dua pulau di provinsi Sumatera Selatan, Pulau Betet dan Pulau Gundul, lenyap tenggelam. Secara global, dari pengamatan rata-rata sejak tahun 2005-2015 disimpulkan bahwa permukaan laut rata-rata naik 3,6 mm per tahun. Sebagian besar perubahan ini terjadi lantaran volume air meningkat akibat pemanasan global.
“Faktor utamanya karena es mencair. Kita telah kehilangan sebagian besar gletser,” tulis BBCdalam laporannya.
Data satelit menunjukkan es di laut Kutub Utara telah berkurang drastis sejak 1979. Kondisi yang sama terjadi di Greenland, Antartika Barat, dan Antartika Timur. Bumi telah berubah menjadi lebih panas akibat efek rumah kaca, kini suhu rata-rata planet kita mencapai 15 derajat celcius.
Mekanisme efek rumah kaca sejatinya menjaga sebagian energi matahari diserap di bawah atmosfer dan dipancarkan ke segala arah untuk menjaga bumi tetap hangat. Tapi kiwari efek rumah kaca diperparah dengan gas yang dilepaskan dari industri dan pertanian. Apalagi karbon dioksida bertahan lebih lama di udara.
Cina adalah negara dengan emisi karbon dioksida paling besar di dunia, disusul oleh Amerika dan negara-negara Uni Eropa. Sementara Indonesia tak kalah banyak menyumbang karbon dioksida (urutan ke-12). Keadaan ini diperparah dengan pembalakan, kebakaran, dan alih fungsi hutan.
Karbon yang berhasil diserap pepohonan akhirnya dilepas lagi dan menambah kontribusi pemanasan global. Sejak revolusi industri sekitar tahun 1750, tingkat karbon dioksida telah meningkat lebih dari 30 persen, dan suhu global naik 1,5 derajat celcius.
“Jika tren pemanasan terus berlanjut, suhu bumi bisa meningkat 3-5 derajat celcius pada akhir abad ini,” demikian rangkum BBC.
Catatan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) menyatakan 20 tahun terakhir menjadi tahun paling panas yang dirasakan dunia. Periode 2015-2018 memiliki suhu tertinggi di antara semua masa. Perlu usaha keras untuk mengembalikan wajah bumi yang koyak.
Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Oktober 2018 memperingatkan dunia untuk mengurangi emisi global hingga 45 persen di tahun 2030 dan meniadakan penggunaan batu bara. Jika tantangan itu gagal maka manusia harus bersiap menghadapi kenaikan permukaan laut dan perubahan signifikan suhu laut dan tingkat keasamannya.
Di sisi pangan, iklim pertanian akan kehilangan kemampuan menanam beras, jagung, dan gandum. Kenaikan suhu udara dan air akan membawa pada kekeringan berkepanjangan, mengurangi lapisan es, dan membikin kualitas air permukaan menurun.
Sementara perubahan iklim menghadirkan risiko tambahan yang memicu stres, penuaan dini, meningkatkan paparan penyakit melalui air dan makanan, dan meningkatnya kematian akibat suhu panas. Meragukan perubahan lingkungan ketika dampaknya mengancam kehidupan di depan mata adalah kebodohan luar biasa.
Editor: Windu Jusuf
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id