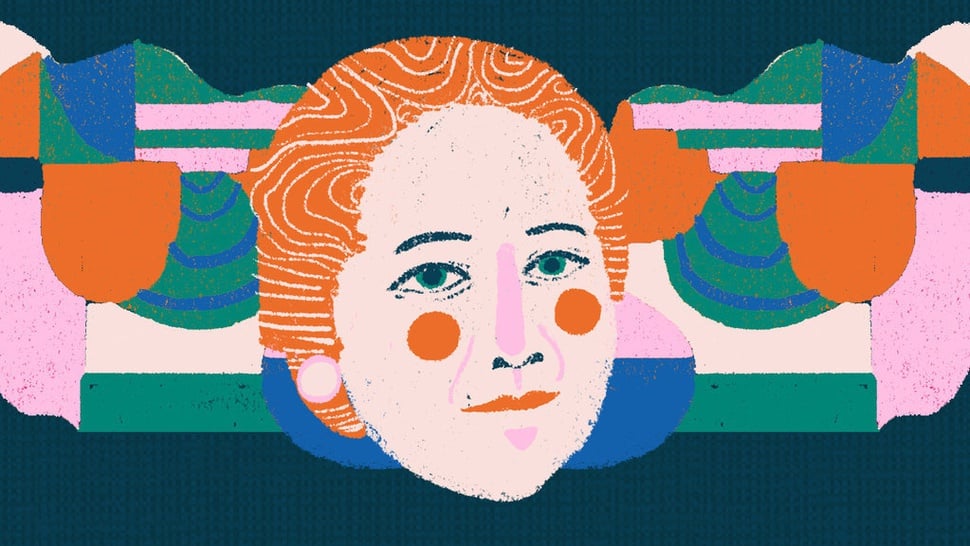tirto.id - Setiap orang, kelompok masyarakat, dan bangsa memiliki cita-cita sendiri tentang masa depan seperti apa akan dijalaninya. Sejak revolusi Perancis sampai lahirnya pemberontakan Komune Paris 1848, proletariat Eropa telah terlibat dalam serangkaian aksi kolektif menuntut perbaikan nasib di tengah sistem kapitalisme yang baru berkembang saat itu.
Kekuatan spiritualnya bertolak dari pelbagai doktrin sekte-sekte keagamaan, yang menempatkan cinta kasih dan persaudaraan manusia sebagai tujuan bersama, yang melahirkan Chartisme, Owenisme, sampai sosialisme modern pasca penerbitan Manifesto Komunis karya Karl Marx dan Friedrich Engels pada 1848.
Perkembangan serupa berlangsung dalam sejarah awal pergerakan antikolonial di Hindia-Belanda pada awal abad 20. Sejumlah tindakan penuh keberanian dari sosok sejarah masa lalu memberi contoh serangkaian tindakan keperwiraan ketika menghadapi kekuatan kolonialisme Belanda. Sebut saja kisah Pangeran Diponegoro di Jawa, Sultan Hasanuddin di Makassar, Pattimura di Maluku, dan perjuangan Tjut Nyak Dhien di rimba belantara Aceh.
Betapapun begitu, kisah-kisah mereka belum melahirkan sebuah kitab yang merangsang pemikiran intelektual kaum terpelajar di Hindia-Belanda tentang arti penting perjuangan kolektif dan bagaimana seharusnya masyarakat masa depan yang akan mereka wujudkan.
Barulah pada awal abad 20 kitab itu lahir. Penerbitan surat-menyurat pribadi Raden Ajeng Kartini dengan sahabat penanya, berjudul Door Duisternis tot Licht atau Habis Gelap Terbitlah Terang, pada 1911 menjadi bacaan yang beredar luas di kalangan terpelajar. Buku ini menuntun mereka dalam melihat arah kemajuan masa depan.
Gagasan yang terkandung di dalam Habis Gelap Terbitlah Terang mewakili pandangan dari sosok pribadi yang menyerap cahaya pengetahuan modern (baca: barat), dan menjadikan pengetahuan itu sebagai teropong kritis atas kekangan sistem feodal (dan kolonial) yang menghambat kemajuan masyarakat jajahan di Hindia-Belanda.
Pengaruh 'Habis Gelap Terbitlah Terang'
Sejauh mana arti penting karya ini bisa dilihat dari sejumlah catatan yang ditulis kaum terpelajar pergerakan kebangsaan Indonesia. Dalam buku kenang-kenangan Budi Utomo, yang terbit pada 1918, Raden Ayu Sriati Mangunkusumo, adik kandung dr. Sutomo yang menikah dengan Goenawan Mangunkusumo, menulis: “Kita perempuan, seringkali dianggap lemah dan perlu dilindungi. Suara kita tidak pernah didengar."
“Namun akhirnya ada sebuah awal, yang kita tahu semua, sejak pemikiran pendahulu kita yang mulia, Kartini, yang memengaruhi pemikiran banyak orang.” (Gedenkboek Boedi Oetomo, 1908-1918).
Apabila kesadaran kebangsaan yang lahir dari gerakan Budi Utomo masih dianggap terlalu bersifat Jawasentris, kita bisa melihatnya lagi dalam catatan kenangan pergerakan Perhimpunan Indonesia di Belanda. Ini sebuah perkumpulan kaum terpelajar dari latar belakang beragam etnis, yang menyebut Kartini sebagai “pemula gerakan emansipasi perempuan Indonesia” (Indonesische Vereeniging. Gedenkboek, 1908-1923).
Di Hindia-Belanda, sejumlah klub sosial dibentuk dengan menggunakan nama Kartini. Sebuah laporan rahasia pemerintah tentang aktivitas kaum pergerakan di bawah pimpinan Douwes Dekker di Bandung menyebutkan kegiatan diskusi di dalam Raden Adjeng Kartini-Club. Klub ini membahas rencana reformasi birokrasi kolonial dan otonomi Hindia-Belanda dari negeri induk. (Nota Betrefende De Geschriften van Douwes Dekker, 1913: 63).
Raden Adjeng Kartini-club memang tidak dibentuk untuk menjalankan propaganda politik kaum pergerakan, tetapi tidak dapat disangkal bahwa gaung Kartini telah menjadi bagian tak terpisah dari aktivitas pergerakan antikolonial Indonesia saat itu.
Pemikiran Kartini
Lahir pada 21 April 1879 dari keluarga bangsawan Jawa, yang menempatkan pendidikan modern sebagai kunci kemajuan, Kartini tumbuh sebagai warga dunia yang percaya bahwa pendidikan bagi kaum perempuan adalah kunci penting emansipasi manusia—atau, paling tidak, bagi masyarakat Jawa tempatnya tinggal.
Semasa lajang sebagai perempuan mandiri, Kartini telah melahirkan sejumlah tulisan, seperti “Upacara Perkawinan pada Suku Koja” yang terbit di Holandsche Lelie saat berusia 14 tahun. Begitupun ide-ide yang tertuang dalam surat-menyurat dengan sahabat penanya.
Setelah pernikahannya dengan bupati Rembang, Raden Adipati Djojodiningrat, Kartini merasakan horison pemikirannya berkembang. “Di rumah orang tua saya dulu, saya sudah tahu banyak. Tetapi di sini, di mana suami saya bersama saya memikirkan segala sesuatu, di mana saya turut menghayati seluruh kehidupannya, turut menghayati pekerjaannya, usahanya, maka saya jauh lebih banyak lagi menjadi tahu tentang hal-hal yang mula-mula tidak saya ketahui. Bahkan tidak saya duga, bahwa hal itu ada”, tulis Kartini kepada Nyonya Abendanon yang menjadi sahabat penanya(Surat kepada Ny. R.M. Abendanon-Mandri, 10 Agustus 1904).
Kartini juga merencanakan menulis sebuah saga berupa kisah sejarah tanah Jawa. Tanda bahwa pemikiran Kartini semakin berkembang dan matang bisa dilihat dalam surat terakhirnya kepada Nyonya Abendanon terkait rencana pemerintah menyelidiki akar kemiskinan masyarakat Jawa.
Kartini menulis bahwa akar sesungguhnya kemiskinan orang Jawa terletak pada masalah pajak dari kebijakan yang dibuat pemerintah kolonial sendiri. Gagasan seperti ini pula yang menjadi landasan kritik kaum pergerakan antikolonial terhadap kebijakan pemerintah Hindia-Belanda saat itu.
Sayang usia Kartini pendek saja. Ia meninggal pada usia 25 tahun, tak lama setelah melahirkan seorang bayi lelaki yang sehat pada 17 September 1904. Segala rencana untuk tulisan mewakili pemikirannya yang matang tidak sempat terwujud.
Meski begitu, cahaya kehidupan Kartini semakin bersinar setelah kematiannya. Setelah terbentuknya negara republik Indonesia yang merdeka, ia hadir sebagai model utama yang memberi inspirasi bagi gerakan perempuan Indonesia. Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) menamakan buletin resmi mereka sebagai Api Kartini, sebagai penghormatan terhadap cita-cita emansipasi perempuan yang diimpikannya. Atas perjuangan organisasi perempuan itu, Kartini secara resmi ditetapkan menjadi pahlawan nasional pada 1964.

Kritik dan 'Jawasentrisme'
Pada masa kontemporer sosok Kartini sebagai pelopor emansipasi perempuan telah melahirkan sejumlah kritik.
Pertanyaan yang muncul adalah mengapa bukan Tjut Njak Dhien yang memimpin perlawanan terhadap kekuatan militer Belanda di rimba belantara Aceh? Mengapa juga bukan Rohana Kudus yang menjadi pionir jurnalis perempuan dari Minangkabau, atau Raden Dewi Sartika yang menjalankan pendidikan perempuan di Jawa Barat?
Dalam arus pemikiran ini, tuduhan keras yang dilontarkan terhadap sosok Kartini dapat dirangkum dalam dua arahan.
Pertama, Kartini dianggap sebagai "produk berhasil" proyek modernitas kolonial awal abad 20. Namun, persoalannya siapakah sosok penting tokoh pergerakan antikolonial yang tidak menjadi bagian dalam proyek modernitas kolonial?
Husen Djajadiningrat, sejarawan produk pendidikan modern Belanda, atau Haji Agus Salim yang menjadi tokoh penting pergerakan Islam di Indonesia, adalah anak didik Snouck Hurgronje. Begitu juga H.O.S. Tjokroaminoto yang dipromosikan D.A. Rinkes, dan bahkan Musso yang menjadi anak didik G.J.A Hazeu—masing-masing menjabat sebagai penasihat gubernur jenderal untuk urusan penduduk bumiputera.
Kedua, tuduhan tentang sifat "Jawasentrisme" dalam sistem politik dan kebudayaan nasional Indonesia setelah kemerdekaan. Kartini sendiri tidak membayangkan dirinya sekadar mewakili orang Jawa dalam menjalankan agenda emansipasi. Surat kepada sahabatnya memberikan gambaran ini.
“Sekiranya undang-undang negeri saya mengizinkan, saya tidak ingin dan berbuat lain dari pada menyerahkan diri untuk pekerjaan dan perjuangan Wanita baru di Eropa,” tulis Kartini kepada Stella (Surat Kartini kepada E.H. Zeehandelaar, 25 Mei 1899).
Dengan segala keterbatasannya, Kartini mampu membayangkan diri menjadi bagian perjuangan internasional melewati bangsa, negara, serta agama.
Diringkus sebagai Komoditas
Membaca ulang karya Kartini menggaungkan kembali sejumlah kritik yang pernah ada terhadap sosoknya. Namun, kita tetap “harus berlaku adil”—meminjam uraian Armijn Pane dalam terjemahannya terhadap surat-menyurat Kartini.
“Sebelum tahun 1904 itu masyarakat Bumiputera belum dapat melakukan cita-cita yang baru yang diangan-angankannya. Masa itu masa bercita-cita, dan Kartini cocok dengan semangat zamannya,” tulis Pane menutup uraiannya dengan mengatakan bahwa “Zaman itu tepat jika digambarkan dengan ucapan Kartini tentang dirinya sendiri dengan senangnya: “Belumlah menjadi apa-apa, tapi sudah boleh menjadi apa-apa.” (Pane, 2008: 22).
Sebagai penutup, sebuah catatan perlu ditekankan terhadap cara orang-orang Indonesia memandang emansipasi perempuan pada masa kini.
Dalam setiap momen perayaan Kartini, media massa Indonesia menampilkan kisah sukses para perempuan dan profesi mereka di dalam dunia modern, yang dianggap "mewakili" semangat Kartini. Cara ini tidak keliru, tetapi belum lengkap.
Dalam suratnya kepada Estella H. Zeehandelaar, seorang perempuan Yahudi dan aktivis sosialis, bagian pengantar dalam perkenalan surat itu memberikan kita gambaran pemikiran Kartini: “Saya ingin berkenalan dengan seorang gadis modern, yang berani, yang dapat berdiri sendiri... yang selalu bekerja tidak hanya untuk kepentingan dan kebahagiaan dirinya sendiri saja, tetapi juga berjuang untuk masyarakat luas, bekerja demi kebahagiaan banyak sesama manusia." (Surat Kartini kepada Estella H. Zeehandelaar, 25 Mei 1899).
Kartini mengharapkan bertemu bukan saja perempuan modern yang mandiri, tetapi juga perempuan yang bekerja untuk kebahagiaan sesama manusia. Maka, dengan cara ini Kartini tetap penting dan relevan dalam kehidupan kita sekarang.
Editor: Fahri Salam