tirto.id - Pemandangan pagi hari dengan duduk-duduk di beranda ditemani secangkir kopi dan koran telah berganti. Kini, orang-bangun pagi membuka smartphone mereka, membuka pesan dan berita. Bukan di situs-situs berita, melainkan pada ragam aplikasi media sosial, lewat timeline Twitter, Facebook, Instagram, bahkan Youtube.
Luthfi merupakan salah satu orang dari golongan tersebut. Ia lebih memilih melihat berita dan informasi terbaru lewat timeline Instagram. Pagi itu, ia memberi tahu berita tentang pengepungan kantor LBH oleh sejumlah massa yang menyebut diri anti-PKI. Sehari sebelumnya, beredar pesan berantai di Whatsapp, Telegram, dan Facebook bahwa LBH akan mengadakan rapat PKI.
“Padahal acara yang digelar acara seni,” kata Luthfi.
Baca juga:Masyarakat Diajak Memerangi Berita Hoax
Jika Anda juga termasuk kelompok yang membaca berita dari media sosial seperti Luthfi, berarti Anda serupa dengan sebagian penduduk di negara-negara di Asia Pasifik. Berdasarkan riset Reuters Institute 2016, kecenderungan orang membaca berita melalui media sosial memang semakin tinggi.
Di Singapura dan Malaysia, lebih dari 25 persen responden menjadikan media sosial sebagai sumber utama dalam mengakses berita. Angka ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan di Inggris sebesar 8 persen dan di Amerika Serikat 15 persen.
“Riset ini menunjukkan hubungan antara perusahaan media dan platform teknologi seperti media sosial saling membutuhkan,” kata Direktur riset Reuters Institute, Rasmus Kleis Nielsen.
Bahkan kita sering temukan platform media berita yang mengambil informasi dari media sosial. Misalnya saja berita tentang kejadian yang dicuitkan korban sebagai narasumber utama di media sosial miliknya. Atau, berita dari beragam status petinggi negara dan selebritas.
Baca juga:Kelahiran Generasi Z Kematian Media Cetak
Menurut survei di tahun berikutnya, 19 persen responden Reuters malah sengaja membuka Facebook untuk mencari berita. Mereka setuju platform besutan Mark Zuckerberg ini berisi beragam informasi berguna. Animo serupa tak ditemukan di platform media sosial lainnya. Hanya satu dari sepuluh responden yang menyatakan Youtube sebagai sumber berita berguna, dan ada 6 persen respons serupa untuk Twitter.
Baca juga:Budaya Berbagi di Media Sosial
Efek Media Sosial
Media sosial telah terbukti menjadi sumber informasi tak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi instansi pemerintah. Bahkan, akun-akun media sosial pemerintah saat ini lebih ramah menyapa masyarakat. Mereka memaksimalkannya sebagai alat untuk berinteraksi.
Contohnya saat akun twitter @DitjenPajakRI terhadap cuitan Raditya Dika saat berkunjung ke rumah Raffi Ahmad. Ketika itu Radit memamerkan mobil Koenigsegg yang diduga milik Raffi. Alih-alih guyon, cuitannya malah ditanggapi serius oleh @DitjenPajakRI. Dalam cuitannya tersebut, akun @DitjenPajakRI seolah mengumumkan kepada masyarakat bahwa pengenaan pajak tak pandang bulu.
“Tolong bilangin ke Kak Raffi, jika ada penambahan harta di tahun berjalan, jangan lupa laporkan di SPT Tahunan ya Kak,” kicau sang admin.
Baca juga:DKI Jakarta Genjot Penerimaan Pajak Mobil Mewah
Di waktu lain, admin @DitjenPajakRI juga menanggapi dengan santai pertanyaan nyeleneh dari seorang netter tentang perlakuan pajak terhadap aktivitas pesugihan. Lalu, akun media sosial milik pemerintah lainnya yang sering berinteraksi dengan masyarakat adalah akun twitter @_TNIAU. Selain sabar menghadapi berbagai macam pertanyaan, akun ini juga seringkali langsung mengklarifikasi hoax yang beredar di masyarakat.
Misalnya saja saat Ratna Sarumpaet mengatakan bahwa Ahok telah membeli tentara, kepolisian, dan KPK. Sang admin langsung berkicau dengan me-mention langsung akun twitter Ratna.
“Bu @RatnaSpaet pegang kwitansinya? Boleh lihat Bu?” balas sang admin.
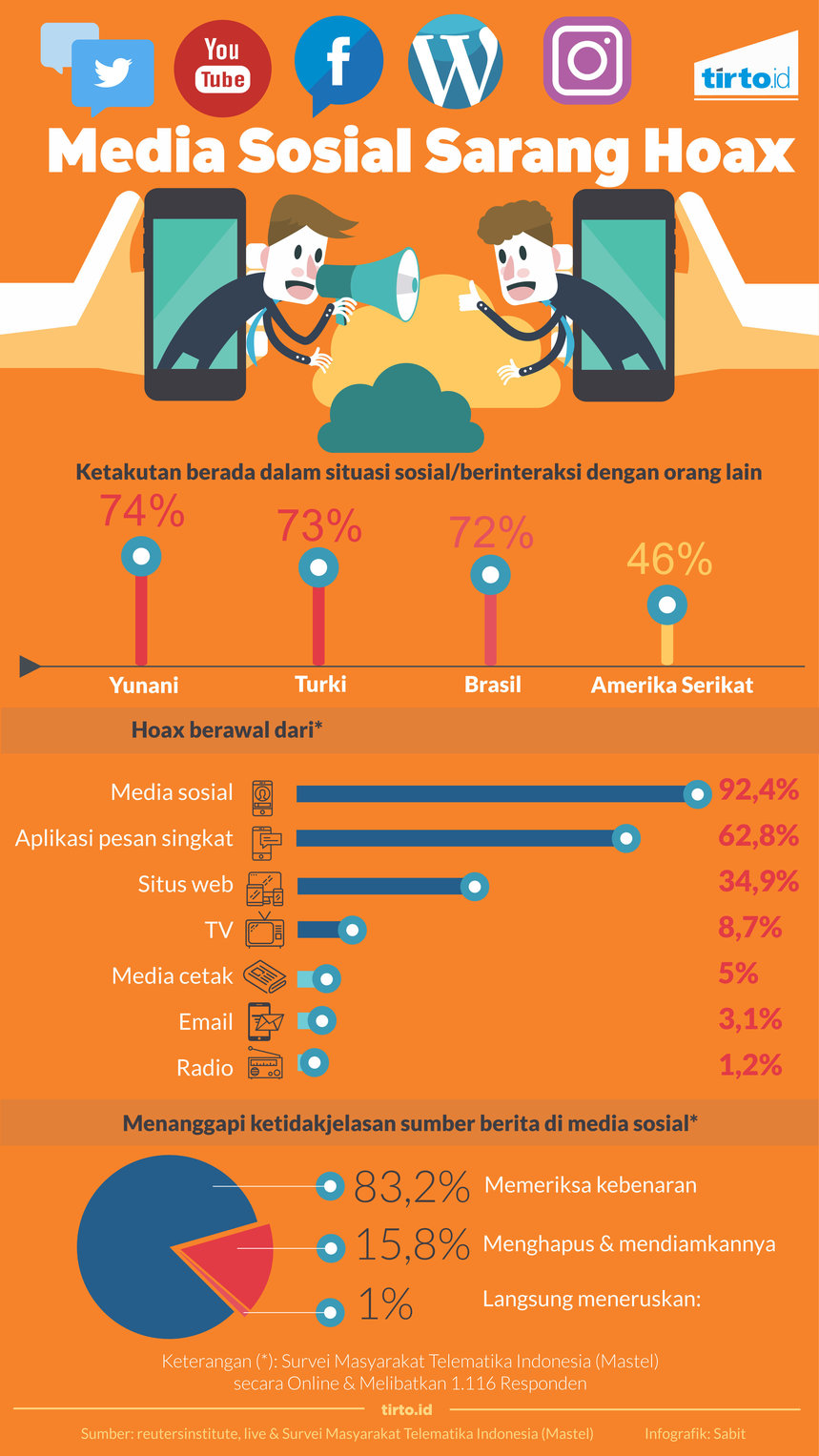
Kekuatan media sosial dalam mempengaruhi publik pun dimanfaatkan oleh para pemimpin negara. Misalnya saja Presiden Barack Obama. Saat kampanye politik dan memerintah, ia terkenal aktif menggunakan Twitter dan Facebook sebagai alat berkomunikasi.
Obama sering mengunggah beragam kebijakan pemerintah mulai dari masalah perubahan iklim, kenaikan upah, kesehatan, pendidikan dll. Contoh lain adalah Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak.
Media sosial bahkan pernah menunjukkan kekuatannya dalam menggulingkan kekuasaan di Tunisia, Mesir, Libya dan Yaman. Pergerakan ini bermula dari kisah Mohamed Bouazizi seorang pedagang buah yang tidak mampu membayar uang sogok ke tiga orang petugas pemda. Barang dagangan Bouazizi digaruk dan si ia habis dipukuli petugas. Lantas Bouazizi frustasi, dan membakar dirinya dengan bensin.
Kabar kematian si penjual buah tersiar di beragam media sosial. Dan membakar semangat perubahan, membuat rezim yang berkuasa 23 tahun di Tunisia tumbang. Mesir, mengikuti setelahnya, seorang aktivis perempuan, Asmaa Mahfouz mengunggah video menyuarakan perubahan di Mesir. Orasinya membakar semangat para pemuda Mesir untuk ikut turun ke Lapangan Tahrir menuntut mundur Presiden Mubarak.
Demokrasi di Tunisia dan Mesir berjalan lebih cepat akibat kekuatan media sosial.
Kebebasan untuk Membenci
Namun, hati-hati, selain jadi saluran kebebasan berekspresi, media sosial juga jadi saluran kebebasan untuk membenci. Demikian hasil penelitian Merlyna Lim, ahli media digital dan masyarakat jejaring global pada Carleton University, yang diringkas pada situs The Conversation.
Ia menyimpulkan pada Pilkada DKI kedua belah pihak menggunakan pesan-pesan negatif lewat media sosial, salah satu caranya adalah menggunakan selebritas media sosial sebagai corongnya. Kedua kubu membingkai informasi dan cerita untuk menarik emosi, tanpa atau dengan sedikit fakta obyektif.
Bagaimana media sosial menjadi saluran kebebasan untuk membenci? Lim menunjukkan bagaimana percakapan dan interaksi antar-pengguna media sosial saat pilkada lalu pada umumnya ditandai label yang menghina. Label yang menghina ini berperan dalam membangun musuh bersama.
Kelompok anti-Ahok, lanjut Lim, melabeli pendukung Ahok dengan istilah-istilah seperti kafir, maksiat, haram, pembohong, penipu, bodoh, babi, dan kecebong. Satu istilah luput direkam oleh Lim: "munafik."
Pendukung Ahok juga melabel lawannya. Biasanya lawan Ahok dibingkai sebagai anti-nasionalis dan pengkhianat. Sebutan-sebutan yang terlontar adalah Muslim radikal, preman berjubah, teroris, pendukung ISIS, dan anti-sains, unta, kaum bumi datar, orang sumbu pendek.
Saking buruknya polarisasi itu, lanjut Lim, kelompok lain jadi tidak nampak. Padahal, ada warga Jakarta yang memilih Ahok berdasarkan prestasinya, tapi tidak setuju dengan beberapa kebijakannya. Pemilih Anies ada yang menentukan pilihannya karena tak setuju kebijakan Ahok yang pro-elit. Namun, suara-suara ini tenggelam di tengah ekstremnya hiruk-pikuk kedua pendukung.
Penulis: Aditya Widya Putri
Editor: Maulida Sri Handayani












