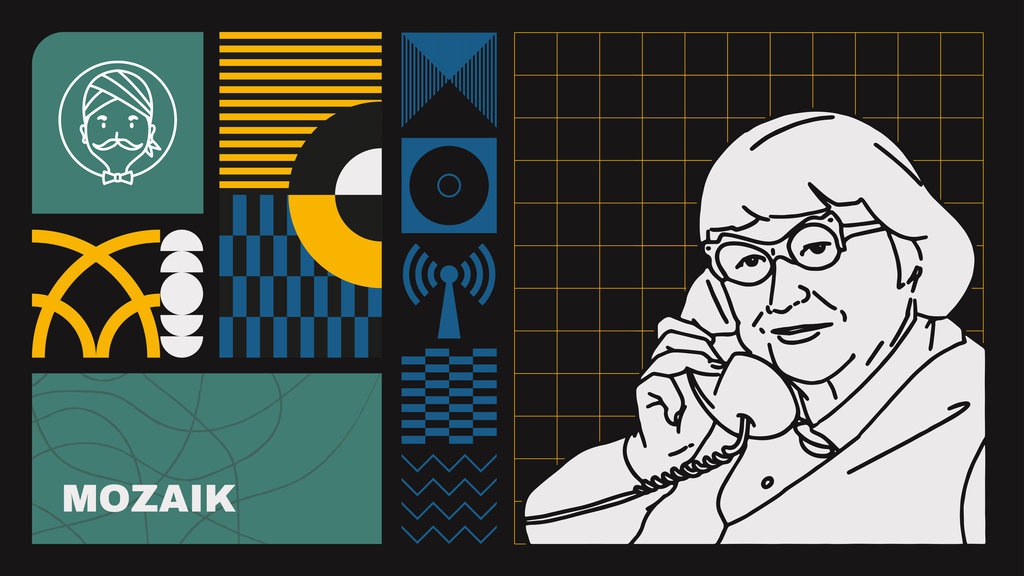tirto.id - Enam kapal Belanda tertahan di Brisbane pada 25 September 1945 setelah pengumuman Komite Perselisihan Dewan Perdagangan dan Perburuhan Australia memasukkan mereka ke dalam daftar hitam kapal yang dilarang berlayar ke Indonesia.
Aksi boikot ini dilatari protes terhadap tindakan Belanda yang mengklaim kendali atas Indonesia yang baru saja merdeka. Pemboikotan berlangsung dari tahun 1945 hingga 1949 yang terjadi di banyak pelabuhan di Australia.
Serikat pekerja maritim Australia menolak menangani barang-barang yang diangkut kapal-kapal Belanda, terutama kebutuhan militer. Aksi boikot kemudian melebar pada transportasi udara, perdagangan, layanan jasa, dan pengiriman.
Joris Ivens, sutradara sekaligus Komisaris Film Hindia Belanda, dalam film dokumentar Indonesia Calling (1946) menggambarkan boikot di Australia secara aktif didukung oleh para pekerja Asia, terutama pekerja India dan China.
Aksi ini melibatkan setidaknya 31 serikat pekerja di berbagai wilayah pelabuhan serta berhasil mengembargo sekitar 1500 kapal dagang dan militer milik Belanda, termasuk dua kapal pasukan Inggris.
Pada 1946, seorang perempuan asing yang lama menetap di Bali melakukan perjalanan ke Australia guna mengabarkan situasi terkini di Republik yang baru diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.
Ia melakukan diplomasi dan berhasil mendapatkan dukungan dari serikat pekerja Australia untuk tetap melakukan boikot terhadap Belanda yang dikenal dengan gerakan “Black Armada”.
Aksi boikot tersebut merupakan salah satu boikot maritim terbesar di dunia.
Karena sering berkonfrontasi dengan pihak imigrasi, perempuan ini biasa melakukan perjalanan secara ilegal dengan berbagai nama samaran: Tanchery, Vannine, Oestermann, Daventry, Manxy, Djokja Josy, Vannen, Vanessa, Solo Sally, Molly McTavish, Modjokerto Molly, dan Merdeka Moll.
Sementara The New York Times edisi 9 Oktober 1960 memanggilnya Surabaya Sue, Manx, Yankee Mata Hari, dan semua mengenalnya sebagai K’tut Tantri, sebuah nama pemberian Raja Bali.
Tahun-tahun berikutnya, ia mengabarkan kondisi Republik melalui corong-corong siaran radio berbahasa Inggris. Kontribusinya semakin memperkuat aksi pemogokan di pelabuhan-pelabuhan Australia terhadap kapal-kapal Belanda.
Perannya saat itu kemudian menjadi awal hubungan persahabatan Indonesia-Australia.
Lahir dari Jiwa Petualang Viking
Manx, salah satu nama samaran K’Tut Tantri merujuk pada suku bangsa di Pulau Man, pulau di lautan Irlandia, tanah leluhurnya. Meski lahir dengan nama Muriel Stuart Walker pada tanggal 19 Februari 1898 dan tercatat di Glasgow, Skotlandia, Tantri enggan mengakui dirinya sebagai orang Skotlandia.
Dalam memoar romannya Revolusi di Nusa Damai (1960) ia bangga akan darah leluhurnya sebagai bagian dari bangsa perompak Viking ketika menyerbu Pulau Man sekitar abad ketiga belas. Sebab itulah ia dan keluarganya kadang percaya akan takhayul dan hal-hal gaib.
Jiwa petualang Viking juga yang membulatkan tekadnya untuk memilih Bali sebagai tempat impiannya: menyalurkan kegemaran melukis ditemani pemandangan alam Bali nan eksotis.
Ayahnya, seorang arkeolog, dikabarkan pergi ke daratan Afrika saat ia masih dalam kandungan. Ayahnya meninggal ketika malaria melanda wilayah itu, membuat ibunya, menikah kembali dengan orang Skotlandia.
Setelah Perang Dunia Pertama, ia dan ibunya pindah ke Hollywood, Amerika Serikat. Sementara ayah tirinya dikabarkan tewas saat perang terjadi.
Di AS, Tantri menempuh pendidikan, lantas bekerja sebagai jurnalis untuk majalah Inggris. Ia banyak menulis artikel mengenai kritik film dan kesenian. Adaptasi dengan budaya setempat membuat ia dan ibunya merasa nyaman dibanding harus tinggal di Skotlandia.
Suatu hari di tahun 1932, ia mengunjungi bioskop Hollywood Boulevard dan menonton film dokumenter Bali: The Last Paradise yang disutradarai James A. FitzPatrick. Dari situ ia mulai tertarik untuk mengunjungi Bali.
“Saat itu kukenali tempat yang selalu kuidamkan,” tulisnya dalam memoar.
Ibunya sempat menolak dan menyamakan tabiat dengan ayahnya sebagai orang yang gemar bertualang untuk menemukan bangsa-bangsa yang aneh.
Namun ia akhirnya pindah ke Bali dan menetap di sana selama bertahun-tahun.
Singgah di Batavia, Diterima Raja Bali
Tantri tiba di Batavia usai berlayar berbulan-bulan melalui beberapa persinggahan, mulai dari Afrika, India, Hongkong China, Semenanjung Malaya, dan Sumatra. Keberaniannya meninggalkan segala gemerlap Hollywood membuat heran para pejabat Belanda yang ditemuinya di tempat ia harus mengurus dokumen dan penginapan.
Ia tiba di Pelabuhan Tanjung Priok dan berkeliling Batavia. Tantri takjub dengan pembangunan gedung dan hotel di sepanjang kanal Molenvliet, seperti Hotel Des Indes, Des Galleries, Der Nederlander, Koningsplein (Lapangan Gambir), hingga Istana Gubernur Jenderal yang saat itu berada dalam kekuasaan Bonifacius Cornelis de Jonge.
Untuk menuju Bali, ia membeli kendaraan kecil yang akan menemani pertualangannya melintasi jalur pantai utara menuju Banyuwangi, lalu menyeberang dengan kapal laut yang akan berlabuh di Bali.
Ia sempat berdebat dengan pegawai hotel asal Belanda ketika tiba di Denpasar saat mengungkapkan niatnya untuk berbaur dengan masyarakat lokal. Pegawai menganggap derajat orang kulit putih akan turun ketika hal itu dilakukan Tantri.
Empatinya muncul terhadap rakyat Bali dan perjuangan rakyat Indonesia secara umum pada momen tersebut. Ia mulai membenci sikap dan kebijakan supremasi kulit putih orang-orang Belanda.
Nasib baik kemudian membawanya ke Istana Raja Bali setelah mengitari hutan dan pergunungan. Dalam bukunya disebut nama raja yang menyambutnya adalah Anak Agung Gede dan nama putranya ialah Anak Agung Nura.
Hans Hägerdal, sejarawan dari School of Cultural Sciences, Linnaeus University di Växjö, Swedia, menyebutkan bahwa Anak Agung Gede adalah tokoh yang sama untuk Raja Bangli I Dewa Gede Taman. Sedangkan Anak Agung Nura merupakan keponakan raja yang memiliki nama Anak Agung Gede Oka, bukan anak raja sebagaimana disebut dalam buku Tantri.
Hans menyebut ada satu peristiwa saat Oka dibunuh pasukan Republik sekitar tahun 1945/1946 karena dianggap memihak NICA-Belanda, hal yang juga disebutkan Tantri dalam bukunya yang terbit tahun 1960, bahwa Nuri dibunuh tentara Republik pada periode yang sama.
“Sungguh berbahaya menggunakan buku perempuan itu sebagai referensi sejarah. Karena buku ini tak pelak lagi mencampurkan fakta dan fiksi,” ujarnya kepada National Geographic.
Namun begitu, Tantri memang sudah mewanti-wanti pembacanya di halaman pembuka memoarnya bahwa beberapa nama dan lokasi di Bali sengaja disamarkan dan diganti, kecuali nama-nama tokoh besar karena berkaitan erat dengan sejarah yang terjadi. Ia mengatakan bahwa semua rangkaian peristiwa dalam bukunya adalah benar dan sesuai fakta.
Ia mendapatkan nama K’tut--yang berarti anak keempat-- Tantri dari raja yang ia temui dan diangkat sebagai anak keempatnya, sekaligus diizinkan menetap di istana. Tantri mulai belajar berbagai budaya setempat, mulai dari upacara-upacara, aneka kesenian, hingga memperdalam bahasa Bali dan Melayu.
Era Peperangan
Dukungannya terhadap perjuangan rakyat memang sudah hadir ketika berdebat dengan petugas hotel di Denpasar. Lebih-lebih ketika Jepang mulai mendatangi Bali yang porak poranda dibumi hanguskan pasukan Belanda yang kian terpojok. Tantri tak bisa berbuat banyak selain harus mengungsi ke Surabaya yang dianggapnya lebih aman.
Pada era pendudukan Jepang, Tantri bergabung dengan gerakan bawah tanah dan kelompok mata-mata di Surabaya untuk mengetahui siasat serta rencana Jepang. Ia berkeliling kota, bergaul dengan berbagai kalangan, juga belajar bahasa Jepang. Semua dilakukannya untuk mengumpulkan informasi mengenai Dai Nippon.
Ia ditangkap Kempetai saat tengah tidur di pagi hari dan diseret ke penjara di Kediri sebagai tawanan Jepang. Di sel ia diintimidasi dan diperlakukan secara tidak manusiawi.
Tantri sempat dibebaskan setelah tiga minggu dipenjara tanpa alasan dan dikembalikan pulang ke Surabaya. Namun ia ditangkap kembali setelah diduga menjadi mata-mata Sekutu karena dokumennya yang berkebangsaan Amerika Serikat ditemukan.
Tentara Jepang terus menginterogasinya, tetapi ia bergeming hingga siksaan demi siksaan kembali didapatkan, menurunkan berat badannya yang nyaris mendekati 30 kg. Ia mendekap di sel tersebut selama dua tahun sampai akhirnya dipindahkan ke Rumah Sakit Ambarawa di Semarang karena kondisinya terus menurun.
Itu terjadi menjelang kekalahan Jepang tahun 1945. Mereka enggan melihat warga AS menderita karena akan memperburuk keadaan ketika pasukan Sekutu tiba di Surabaya.
Memasuki September 1945, ketika kesehatannya mulai membaik, pilihan disodorkan tentara Republik kepadanya: kembali ke AS dengan pengawalan hingga selamat atau memilih bergabung bersama pejuang Indonesia mengusir penjajah.
Para pejuang di Surabaya saat itu tengah mengusir Inggris yang mulai menguasai kota.
Tantri memilih bergabung dengan para pejuang. Ia menulis kolom di berbagai koran dan menyiarkan berita di Radio Pemberontak Surabaya dalam bahasa Inggris.
Dari sini ia mendapatkan julukan sebagai Surabaya Sue (penggugat dari Surabaya) oleh pendengar dan wartawan asing.

Miss Daventry, nama samarannya yang lain tertera pada surat kabar Rajat edisi November 1945. Ia melampiaskan kekesalannnya pada militer Inggris dan NICA yang memanfaatkan pasukan Sekutu sebagai jaminan keamanan di Surabaya.
"Kemaren kamoe merajakan Thankgiving Day. Akoe tak bisa ikoet gembira karena akoe ada di tengah mereka jang dengan darah dan air mata sedang berdjoang mati2-an menontoet rahmat jang soedah kamoe perdapat itoe," tulisnya.
Pertengahan 1946, saat ibu kota berpindah ke Yogyakarta, Tantri ditempatkan di kantor Kementerian Pertahanan dan sempat menjadi agen untuk menjaring kelompok-kelompok yang berkhianat kepada Indonesia.
Tantri mulai dekat dengan tokoh-tokoh besar seperti Sukarno, Hatta, Syahrir, dan Amir Sjarifuddin. Bahkan pada kesempatan lain, ia tak sadar pernah satu mobil dengan Tan Malaka.
Ia juga sering ditugaskan secara ilegal ke Singapura dan Australia untuk menggalang dana dan dukungan solidaritas internasional. Salah satu misinya adalah mendukung serikat pekerja di Australia agar terus melakukan boikot terhadap kapal-kapal Belanda.
Pada satu kesempatan, ia pernah menuliskan pidato Bung Karno dalam bahasa Inggris yang akan disampaikan dalam siaran radio Voice of Free Indonesia di Yogyakarta.
Tahun 1950, ia menjadi pegawai di Departemen Penerangan sebagai wartawan. Atas pengabdiannya itu ia diganjar Bintang Mahaputra Nararya pada tahun 1998.
K’tut Tantri wafat pada 27 Juli 1997 di sebuah panti jompo di Sydney. Abunya disebar di Pantai Kuta setelah upacara pemakaman dengan peti berbalut merah putih berhiaskan ornamen Bali, sebagaimana wasiatnya.
Namanya tak banyak dikenang dalam buku-buku sejarah sebagaimana ia tuturkan dalam memoarnya.
“Mungkin saja orang Indonesia akan melupakan diriku apabila negara itu sudah benar-benar merdeka. Kenapa tidak? Aku kan hanya ombak kecil di tengah alun banjir semangat kemerdekaan.”
Penulis: Ali Zaenal
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id