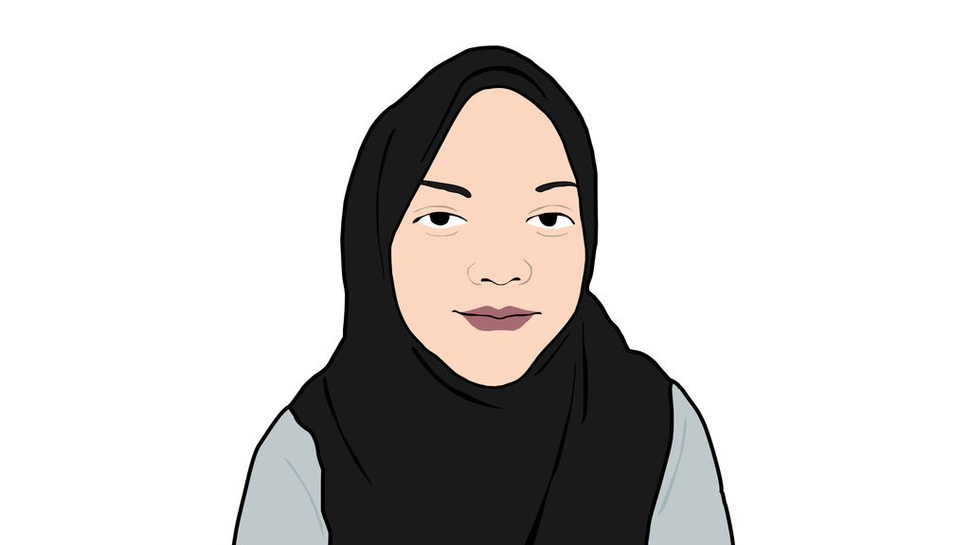tirto.id - Terhitung sejak 22 Februari 2018, Serikat Dosen dan Pekerja Universitas di Inggris (UCU/University and College Union) melakukan aksi mogok untuk menolak pengurangan dana pensiun mereka yang diatur dalam Universities Superannuation Scheme (USS). Mereka menentang pengurangan besaran jumlah pensiun hingga sekitar 10.000 pound sterling atau setara Rp190an juta per tahun.
USS sendiri merupakan skema pensiun swasta terbesar untuk institusi pendidikan tinggi dan universitas di Inggris.
Wacana pengurangan dana pensiun bermula dari proposal yang diajukan oleh UUK (Universities UK) yang mewakili hingga sekitar 350 universitas di Inggris. UUK mengajukan "penyesuaian" ini dengan alasan bahwa anggaran pensiun mengalami defisit hingga 6,1 miliar poundsterling.
Proposal ini kemudian dibicarakan dengan UCU. Namun setelah 35 kali rapat bersama tidak terjadi kesepakatan antara keduanya. UUK bersikeras mengurangi dana pensiun, sementara UCU tetap menolaknya. Ini yang kemudian membuat UCU menggelar aksi mogok.
Aksi mogok ini terjadi pada lebih dari 60 institusi pendidikan tinggi di seluruh Inggris dan akan berlangsung selama 14 hari hingga 16 Maret mendatang.
Hampir tidak ada kegiatan belajar mengajar selama mogok berlangsung. Para anggota UCU membentuk garis jaga atau picket line di setiap kampus untuk menunjukkan besarnya kekuatan aksi mogok. Para sivitas akademika dianjurkan tidak melewati picket line ini atau memasuki gedung kampus karena akan melemahkan kekuatan mogok.
Para sivitas akademika, termasuk mahasiswa, menyikapi aksi mogok dengan berbeda-beda. Ada yang menunjukkan solidaritasnya dengan turut serta dalam aksi dan mencari tempat alternatif lain untuk belajar atau mengerjakan tugas. Namun ada pula yang memilih untuk tidak bersolidaritas.
Marketisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia
Aksi mogok serentak di bebagai universitas seperti yang terjadi di Inggris ini merupakan peristiwa penting yang menunjukkan respon terhadap kecenderungan umum marketisasi pendidikan tinggi yang terjadi di seluruh dunia.
Di Indonesia, marketisasi pendidikan tinggi terjadi hanya beberapa tahun setelah Soeharto turun tahta, tepatnya ketika Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum disahkan. Universitas Indonesia (UI) adalah salah satu perguruan tinggi negeri pertama yang menerapkan skema ini.
Salah satu gagasan utama dari aturan ini adalah otonomi perguruan tinggi. Pada masa Orde Baru, lembaga pendidikan tinggi dikontrol sedemikian rupa oleh negara sehingga kampus tak punya kebebasan akademik. Kontrol inilah yang berusaha dikoreksi lewat aturan baru.
Persoalannya, ide mengenai otonomi—yang bisa dimaknai secara luwes sebagai kebebasan dari intervensi negara—juga mencakup otonomi dalam hal pembiayaan. Lewat skema badan hukum, negara perlahan lepas tanggung jawab dari masalah pembiayaan. Kampus diminta untuk mencari uang sendiri. Konsekuensinya, biaya pendidikan perlahan naik karena peserta didiklah yang paling mudah jadi sumber pendanaan meski aturan serupa memungkinkan perguruan tinggi mencari pembiayaan dari tempat lain seperti perusahaan atau bahkan mendirikan usaha sendiri (ventura).
Skema marketisasi kemudian semakin baku setelah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) disahkan pada 17 Desember 2008. UU BHP sendiri adalah bagian dari proyek Bank Dunia dengan nama IMHERE (Indonesia-Managing Higher Education for Relevance and Efficiency Project) yang bertujuan "mereformasi sistem pendidikan Indonesia" (baca: menjadikan pendidikan tak lagi dimaknai sebagai "barang publik" melainkan "barang privat").
Berkat perlawanan dari mahasiswa dan masyarakat umum, UU BHP akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konsitusi (MK) pada 31 Maret 2010. Ketika itu MK mengatakan apabila perguruan tinggi punya wewenang mencari uang sendiri untuk membiayai operasionalnya, hal tersebut dapat mengganggu fungsi utama dari pendidikan tinggi itu sendiri. Lewat putusan ini dapat ditafsirkan bahwa pembiayaan perguruan tinggi seharusnya menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya.
Namun tak lama setelahnya, muncul Undang-Undang baru yang tidak lain adalah "wajah baru" dari UU BHP: Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Substansi UU yang disahkan pada 13 Juli 2012 sama belaka dengan UU BHP: bahwa selain otonomi akademik (yang bahkan tidak sepenuhnya berlaku karena banyaknya kasus pelarangan diskusi-diskusi yang dinilai subversif), perguruan tinggi juga punya otonomi non-akademik seperti mencari uang sendiri.
Persoalannya, meski biaya kuliah semakin mahal, hal ini tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan dan kepastian kerja para dosen. Banyak dari dosen perguruan tinggi, misalnya, tidak punya ikatan kerja yang jelas dengan kampus. Mereka layaknya buruh kontrak di pabrik yang bahkan telah berada pada ikatan semacam itu selama bertahun-tahun.
Banyak di antara dosen yang diupah berdasarkan berapa banyak mata kuliah yang diampu dan dibayar berdasarkan SKS. Jika kuliah memasuki masa libur semester, praktis tak ada penghasilan.
Akibatnya mereka harus mengajar di lebih dari satu kampus karena uang dari satu kampus saja tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan pada gilirannya tidak membuat mereka mampu mentransfer pengetahuan yang dimiliki secara maksimal.
Meski kondisi kerja semakin rentan, namun respon/solusi para pengajar perguruan tinggi di Indonesia cenderung individualistik seperti contoh mengajar di banyak tempat di atas. Tidak banyak perlawanan konkret dengan berbasis kerja-kerja kolektif.
Memang ada satu-dua perlawanan yang mengambil bentuk demikian. Misalnya yang terjadi di UI pada 2013 lalu. Ketika itu, ratusan dosen dan pekerja UI yang tergabung dalam Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia (PPUI) melakukan aksi demonstrasi menuntut kepastian status kerja. Namun ini pun tidak bertahan lama. Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Yarsi dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta bahkan mogok kerja tahun lalu. Namun ini tetap saja tidak mewakili narasi umum perlawanan para pengajar terhadap status kerja mereka.
Dalam sebuah percakapan, Tim Pringle, pengajar senior di Development Studies SOAS dan anggota UCU, mengatakan kepada saya bahwa kondisi kerja dalam pendidikan tinggi membuat banyak dosen di kampus-kampus Inggris bergabung dengan serikat.
"Yang kami saksikan adalah proses proletarisasi yang semakin menguat di sektor pendidikan. Hal ini mempengaruhi kondisi kerja yang membuat orang menyadari bahwa serikat buruh itu relevan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka dalam bekerja," demikian Tim.
Hingga saat ini, UCU mampu menjaring sekitar 120 ribu anggota dari seluruh Inggris. Fokus mereka adalah melawan penurunan upah dan fleksibilitas kerja.
Enggan Disebut Buruh
Meski begitu tetap saja ada tantangan. Salah satunya faktor teknologi yang memungkinkan akademisi untuk bekerja di manapun. Faktor ini membuat pengumpulan orang untuk rapat, demo, atau mogok jadi lebih rumit dari yang sudah-sudah. Namun karena teknologi pula penyebaran gagasan jadi lebih lancar. Faktor lainnya adalah bahwa masih banyak dari mereka yang khawatir akan reaksi dari petinggi universitas, terutama para pekerja yang tidak punya kontrak kerja yang tetap. Kontrak mereka mungkin tidak diperpanjang jika bergabung ke serikat.
Bagi saya di sini letak masalahnya: sejarah Inggris kaya dengan gerakan buruh. Sedangkan di Indonesia, ingatan historis tentang sejarah gerakan buruh secara sistematis dihapus sejak 1965. Selain itu, politik "massa mengambang" selama 32 di bawah Orde Baru membuat kita tidak tidak familiar dengan pengorganisiran perlawanan secara kolektif. Imajinasi itu tercerabut dari pikiran kita.
Pemisahan kategori pekerja (bahwa karyawan berbeda dengan buruh) sejak masa Orde baru pun telah menciptakan segregasi di antara para pekerja hingga saat ini. Sebagai contoh, dosen dan pekerja kantoran atau pekerja lainnya seringkali dianggap berbeda. Padahal, mereka sama-sama bekerja di bawah sistem kerja upahan.
Meski demikian, selain faktor-faktor historis tersebut, ketiadaan serikat dosen yang kuat di Indonesia juga terkait erat dengan konteks lainnya, yakni konteks ekonomi politik.
Di bawah negara kesejahteraan (welfare state) di Barat sana (termasuk Inggris) yang kemudian ditiru banyak negara berkembang, biaya pendidikan dibebankan pada negara. Setelah era negara kesejahteraan berakhir, orientasi pelayanan publik termasuk sistem kerja di dalamnya memang mengalami perubahan haluan. Sama halnya dengan jaminan kesehatan, pendidikan yang awalnya dianggap sebagai barang publik, berubah wujud jadi komoditas.
Kurikulum pendidikan tinggi pun akhirnya cenderung hanya dibuat untuk memenuhi kebutuhan praktis dari industri dan pasar. Ironisnya, kapitalisme sendiri membutuhkan intelektual-intelektual yang nantinya dapat menyokong sistem ekonomi-politik yang penuh dengan kontradiksi tersebut.
Mereka yang bekerja di sektor publik, termasuk pendidikan tinggi, cenderung mendapatkan jaminan kesejahteraan yang minim dari negara. Tidak bisa dipungkiri, konteks ini pula yang melatari ketiadaan agensi atau pelopor untuk membentuk serikat dosen yang besar dan kuat di Indonesia.
Ketiadaan jaminan kesejahteraan dari negara membuat kondisi kerja para dosen—khususnya dosen honorer—sangat rentan. Akibatnya, para dosen seringkali kesulitan untuk menyiasati bagaimana cara mengorganisir sejawatnya karena disibukkan dengan kegiatan mencari nafkah.
Orientasi pendidikan tinggi pun semakin lama hanya ditujukan untuk mencetak manusia siap kerja. Hasilnya, para pekerja di dalamnya, termasuk para dosen, berada dalam skema kerja yang berorientasi pada produk semata.
Apa produknya? Mahasiswa.
Tak heran jika performa dan pencapaian mahasiswa kemudian hanya diukur berdasarkan nilai ujian dan bukan pada proses pendidikan yang dipimpin oleh pengalaman dalam belajar. Daya kritis mahasiswa pun semakin dibatasi oleh kurikulum yang menjauhi ilmu-ilmu kritis.
Pada titik ini tak ada alasan untuk tidak melakukan "pengorganisiran lintas serikat". Sudah saatnya para dosen, pekerja universitas dan mahasiswa bekerja bersama mengorganisir diri untuk melampaui segala tantangan yang ada untuk mengubah wajah pendidikan Indonesia.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.