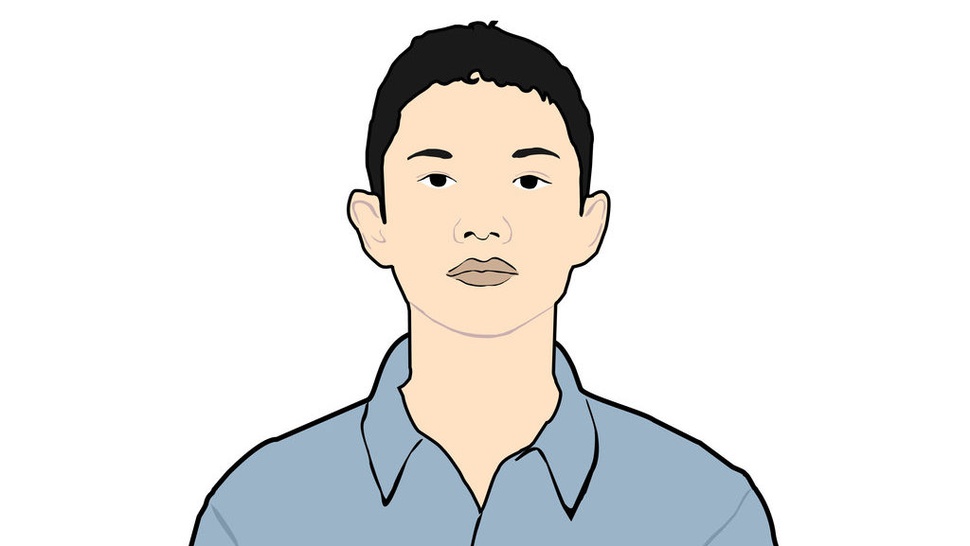tirto.id - Akhir tahun 2017 pemerintah Indonesia memutuskan jatah ilmu sosial-humaniora akan dipangkas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Alasannya, penerima beasiswa LPDP dari latar belakang ilmu sosial-humaniora sudah banyak. Plus, prioritas LPDP kini adalah sains dan teknologi.
Jika membaca data LPDP yang dikutip Tirto, ditinjau dari bidang ilmu yang diminati oleh peserta LPDP, bidang teknik telah diambil oleh 1.999 orang, sains 1.711 orang, pendidikan 1.354 orang, kedokteran dan kesehatan 1.070 orang, sosial 935 orang, ekonomi 675 orang, hukum 481 orang, serta budaya, seni, dan bahasa 480 orang. Jadi, sebenarnya secara kuantitas masih berimbang.
Langkah pemerintah seolah mewajarkan bahwa dengan lebih memprioritaskan sains dan teknologi dalam pembiayaan LPDP, bidang ilmu tersebut lebih terlihat hasil nyata secara fisik. Tetapi, melihat lebih mendalam, kerja-kerja untuk memahami masyarakat dengan lebih baik, menata lembaga-lembaga pemerintahan, dan mengatur ekonomi jelas punya kontribusi besar—dan itu semua bisa terlaksana dengan baik lewat penguasaan ilmu sosial.
John Maynard Keynes tidak langsung turun ke lapangan membantu jutaan pengangguran saat Depresi Besar melanda Amerika Serikat dan sebagian besar dunia pada 1930-an. Tetapi gagasan-gagasannya membantu dunia keluar dari situasi krisis tersebut. Max Weber mungkin tak pernah memberikan pelayanan publik kepada banyak orang, tetapi gagasannya tentang birokrasi kini membuat pelayanan publik dapat berjalan teratur. Paulo Freire tak pernah menyusun kurikulum pendidikan di negara mana pun, tapi berkat gagasannya kita jadi tahu bahwa ada yang salah terhadap sistem pendidikan selama ini.
Langkah LPDP mengurangi kuota beasiswa bagi peminat ilmu-ilmu sosial-humaniora sangat mungkin menggambarkan paradigma orang Indonesia yang semakin terjebak dengan penyakit lama mereka, yakni tidak benar-benar paham dengan masyarakatnya dan tidak paham sama sekali dengan masyarakat dunia luar.
“Meski semakin banyak orang Indonesia belajar di luar negeri,” tulis Anthony Reid, guru besar emeritus studi Asia di Australia National University dalam Majalah Tempo edisi 20 November 2011, “mereka yang ada di bidang ilmu sosial menulis hampir secara eksklusif tentang negaranya sendiri, Indonesia. Segelintir ilmuwan di universitas di Indonesia yang meneliti dan mengajar tentang negara selain Indonesia.”
Reid menambahkan hampir 90 persen karya tulis tentang Indonesia di jurnal-jurnal internasional tidak ditulis oleh orang yang tinggal di Indonesia. “Sesuatu yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang paling tidak efektif di dunia dalam menjelaskan dirinya kepada dunia,” demikian Reid.
Mari ambil contoh. Gubernur-Jenderal Inggris untuk Hindia Thomas Stanford Raffles. Bukunya, The History of Java (1817), pernah menjadi rujukan utama tentang Jawa. Sementara kita sendiri sedikit sekali mengerti tentang Inggris, apalagi dunia. Karya antropolog Amerika Serikat Clifford Geertz, The Religion of Java (1960), memperkenalkan kepada kita pembagian tipologi keagamaan masyarakat Jawa. Kita? Jangankan tipologi keagamaan di AS; tahu tentang santri, abangan, dan priyayi saja dari Geertz.
Christian Snouck Hurgronje melakukan penelitian mendalam di Aceh yang hasilnya membuat Belanda memenangkan Perang Aceh. Sementara kita, jangankan tahu tentang masyarakat Belanda, basis pengetahuan kita tentang Aceh keburu dibangun oleh Hurgronje.
Benedict Anderson dengan The Imagined Communities (1983) menyadarkan kita tentang bagaimana nasionalisme muncul dari kerja-kerja jurnalistik. Sementara kebanyakan dari kita tahu tentang nasionalisme sekadar dari slogan “NKRI harga mati”. Gerry van Klinken mengulik dinamika kelas menengah di Indonesia, sementara kita tidak tahu apa-apa tentang kelas menengah di negara lain. Alih-alih, kita hanya bisa menyebut “kelas menengah ngehek”.
Lewat Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 (1990), Takashi Shiraishi memperkenalkan kepada dunia dinamika gerakan nasionalis era 1920-an ketika Islam dan komunis bahu-membahu melawan kolonialis. Sekarang, kita tidak benar-benar paham tentang komunisme di Indonesia apalagi komunisme di belahan dunia lain.
Herbert Feith dalam The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (1962) menyuguhkan pengetahuan kepada pembaca mengenai dua tipe kepemimpinan politik di Indonesia—solidarity maker seperti Sukarno dan administrator seperti Hatta; sementara kita mungkin tidak tahu apa-apa tentang mereka kecuali wajah mereka tampil pada selembar uang Rp100 ribu.
Martin van Bruinessen, Mitsuo Nakamura, Robert Hefner, Mark Woodward, Harry J. Benda, William Liddle, dan Kikue Hamayotsu berusaha memahami pergumulan Islam dan politik di Indonesia. Sementara kita masih gagap memahami fenomena sosial-politik Islam di negeri sendiri, terlebih di tempat lain.
Sukarno tanpa ilmu sosial dan humaniora mungkin tidak akan pernah menjadi pemimpin besar bangsa kita; beliau mungkin hanya akan jadi insinyur suruhan Belanda. Tanpa ilmu sosial dan humaniora, Romo Mangun sangat mungkin hanya arsitek, alih-alih menjadi pastor humanis dan membangun permukiman penduduk Kali Code. Dan tanpa ilmu sosial, Tan Malaka tak akan pernah menjadi tokoh revolusioner dan memperkenalkan konsep republik untuk Indonesia; kariernya akan mentok sebagai guru di Kweekschool.
Ilmu Sosial-Humaniora dan Kebijakan Publik
Alih-alih memangkas jatah ilmu sosial-humaniora dari LPDP, ada baiknya pemerintah menilik terlebih dahulu situasi pendidikan humaniora dan penelitian sosial di Indonesia.
Sebagaimana diuraikan oleh Samuel (2010), Dhakidae (2003), Hadiz (2016), Hadiz dan Dhakidae (2006), serta Fansuri (2015), sudah sejak lama ilmu sosial-humaniora di Indonesia berhubungan dengan kekuasaan dalam bentuk kebijakan publik.
Efeknya, ilmu sosial-humaniora tidak punya otonomi keilmuan dan hanya dijadikan alat legitimasi agar kebijakan publik terlihat ilmiah. Kondisi ini semakin parah pasca-Orde Baru, karena meskipun cengkeraman negara terhadap ilmu sosial-humaniora sudah jauh berkurang tetapi pasar bebas mulai mendikte perkembangan ilmu sosial-humaniora sebatas menjadi "alat ukur" yang bisa menghasilkan profit.
Riset kolaboratif di bawah Pusat Kajian Komunikasi, Universitas Indonesia, The Centre for Innovation Policy and Governance, dan the Asia Research Centre, Murdoch University Australia, juga menunjukkan pada bidang ilmu sosial, otonomi universitas negeri untuk mencari pemasukan selain dari anggaran negara telah menyebabkan komersialisasi layanan pendidikan dan penelitian, yang tak ada korelasi langsung dengan kualitas akademis. Selain itu, birokrasi universitas negeri belum efektif mendukung riset unggulan.
Sistem rekrutmen dosen yang cenderung tertutup, dosen yang lebih suka ngendon di lembaganya untuk melanjutkan pendidikan tinggi, mekanisme penilaian kinerja dan struktur gaji yang menjauhi orientasi pada prestasi akademis, serta tingginya jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun secara keseluruhan berkontribusi terhadap kondisi pendidikan yang mandek, sempit, dan tertutup (insular).
Dosen-dosen ilmu sosial cenderung tertutup, dan melakukan riset sebatas disiplinnya, dan belepotan mengomunikasikan hasil risetnya pada publik. Kondisi demikian disebabkan oleh birokrasi pendidikan tinggi yang mempersulit kolaborasi akademis akibat rumitnya peraturan.
Di sisi lain, jika yang bermasalah adalah birokrasi kampus, insentif riset, dan kualitas akademik fakultas-fakultas ilmu sosial—yang juga tidak asing bagi jurusan-jurusan sains dan teknologi—maka menambah jumlah kuota LPDP untuk sarjana sosial pun tak akan mengubah keadaan.
Pemerintah bisa menilik program INTERCO-SSH punya Uni Eropa. Di Eropa, ilmuwan-ilmuwan Eropa diberi dana dan tetap punya otonomi keilmuan untuk meneliti perkembangan, manfaat, serta kegunaan ilmu sosial-humaniora untuk kebijakan publik. Dalam konteks Indonesia, LPDP bisa diarahkan agar mengadopsi skema INTERCO-SSH guna memberi ruang analisis sosial dalam kebijakan. Dengan skema tersebut, LPDP bahkan lebih unggul selangkah karena menggelontorkan beasiswa juga.
Tentu isu-isu terkini seperti bonus demografi, ketimpangan sosial-ekonomi, "poros maritim", permasalahan politik identitas, komunitas ASEAN, serta perkembangan ICT (termasuk big data dan start-up) harus bisa dijawab oleh para akademisi sosial-humaniora di Indonesia. Dengan pemangkasan LPDP untuk sektor humaniora dan pembiaran tradisi akademik yang buruk di kampus-kampus humaniora, isu-isu tersebut akan melenggang tak terjawab.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.