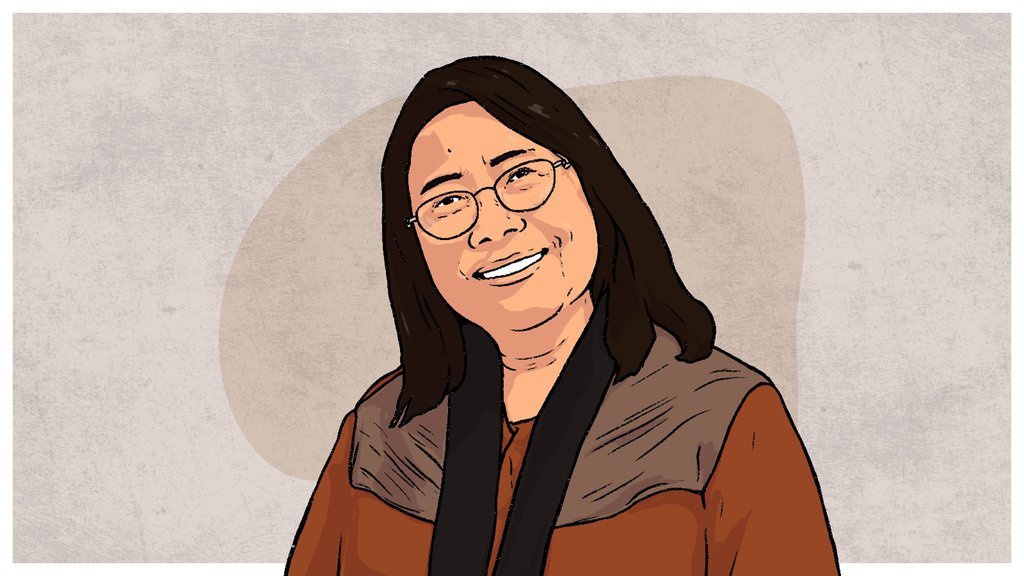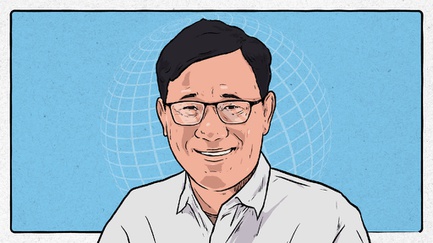tirto.id - Mantan Deputi Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani, buka-bukaan alasan keluar dari lingkaran istana. Salah satunya berbeda sikap politik dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2024.
Jokowi sendiri diduga ikut cawe-cawe mendukung secara langsung presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sementara Jaleswari berada disebrangnya yakni mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
“Jadi ketika saya mundur, saya merasa bahwa harapan-harapan itu karena Pak Jokowi punya pilihan politik yang berbeda dengan saya, saya tidak melihat bahwa harapan baru itu ada di sana gitu,” ujar dia dalam Podcasts For Your Politic, di Kantor Tirto.
Selain bicara perbedaan sikap politik dengan Jokowi, dia melihat ada ideologi-ideologi yang sudah tidak sejalan dengan Jokowi sejak di periode pertama. Dia menilai pemerintah saat sudah melampaui batas hingga menabrak konstitusi.
“Nah ketika aturan-aturan itu, ketika hal-hal yang menjadi pedoman kita bersama itu kemudian satu per satu mulai ditabrak, saya rasa kita juga sudah harus mulai mempertanyakan,” kata Jaleswari.
Di luar itu, Kepala Lab 45 itu, juga bicara pembatalan pengesahan RUU Pilkada oleh DPR RI lalu. Ini tak lepas dari gelombang aksi rakyat Indonesia, yang didominasi oleh mahasiswa. Bahkan usai DPR RI resmi membatalkan RUU Pilkada, ribuan mahasiswa tetap menggelar aksi untuk mengawal putusan MK di 54 titik nasional.
Jaleswari menilai bahwa mahasiswa yang masuk dalam kategori Generasi Z ini, telah membawa harapan baru bagi demokrasi Indonesia yang saat ini sedang terpuruk.
Simak pandangan eks Deputi KSP, Jaleswari Pramodhawardani, terkait hal lainnya soal gelaran pilkada 2024? Akankah kontestasi pemilihan kepala daerah ini bisa berlangsung tanpa adanya kecurangan? Berikut petikan wawancara kami:
Kenapa keluar dari KSP?
Jadi banyak sekali yang menanyakan kenapa saya mundur, atau kenapa saya keluar dari kantor staf presiden. Alasan cepatnya adalah karena waktu itu saya bergabung dengan TPN (Tim Pemenangan Nasional) [Ganjar-Mahfud], yang sebetulnya dilihat dari aturan tidak apa-apa. Karena ada aturan-aturan yang sudah saya penuhi. Misalnya saya keluar dari komisaris, saya keluar sejak Oktober malah.
Terus kemudian, kenapa saya baru keluar belakangan? Karena sebetulnya ketika keluar dari komisaris itu, saya sebetulnya juga pengen langsung keluar. Tapi waktu itu dilarang Pak Mahfud waktu itu karena alasannya memang lebih kepada kerja teknokratis. Ada beberapa pekerjaan rumah penting yang harus kita selesaikan, yaitu penyelesaian yudisial pelanggaran ham berat masa lalu. Dan kita masih punya beberapa hal yang perlu dituntaskan.
Tetapi waktu itu ternyata tidak mudah ketika pilihan politik kita berbeda. Alasan saya waktu itu adalah saya tidak mau jadi beban politiknya Pak Jokowi maupun kawan-kawan yang merasa, “kenapa Deputi V pilihan politiknya berbeda tapi kok masih di dalam”.
Sebetulnya bisa saja saya berargumen bahwa saya akan profesional tapi itu kan agak susah untuk dijelaskan semacam itu karena pada umumnya orang akan percaya bahwa akan sulit orang yang berbeda pilihan politiknya tetap kerja di tempat yang berbeda.
Kemudian terus terang saya memilih pilihan politik yang berbeda itu karena ada ukuran-ukuran yang waktu itu juga berbeda. Saya ingin menyampirkan harapan baru kepada Pilpres ke depan gitu. Sama sebetulnya seperti saya punya harapan baru dulu kepada Pak Jokowi.
Jadi ketika saya mundur, saya merasa bahwa harapan-harapan itu karena Pak Jokowi punya pilihan politik yang berbeda dengan saya, saya tidak melihat bahwa harapan baru itu ada di sana gitu. Jadi makanya saya mencoba untuk menyampaikan itu, tetapi saya paham kalau tetap ada pro kontra seputar saya mundur. Jadi ada situasi-situasi yang memang lebih karena perbedaan politik dan harapan-harapan itu.

Di periode kedua mbak melihat apa yang akhirnya memutuskan untuk ada ideologi-ideologi yang tidak sejalan lagi dengan Bapak (Jokowi) seperti di di periode satu?
Buat saya, ini kan sebuah negara besar ya. Dan kita ini penting untuk disiplin dan tertib terhadap konstitusi. Bahwa kita harus disiplin untuk menjalankan konstitusi. Itu sebuah pedoman lah. Ibaratnya supaya kita tidak tersesat, kita memilih konstitusi itu untuk menjadi pedoman kita bernegara.
Nah ketika aturan-aturan itu, ketika hal-hal yang menjadi pedoman kita bersama itu kemudian satu per satu mulai ditabrak, saya rasa kita juga sudah harus mulai mempertanyakan.
Dulu pas di awal-awal di periode pertama [Jokowi] dia bertugas Majalah Time juga sempat bilang Pak Jokowi itu sebagai harapan baru. Tapi kalau misalkan dilihat di situasi sekarang, sepertinya itu menggeser harapan baru itu? Dan ada lagi tidak yang mengganjal sampai hari ini?
Ya mungkin kesalahan kita adalah kita melihat harapan itu statis ya. Padahal harapan itu dinamis. Orang itu dinamis. Jadi kalau melihat hari ini, mungkin kalau misalkan ditanya apa sih pelajaran kita untuk melihat hari ini? Jangan percaya orang, Tapi percaya lah nilai. Karena orang bisa berubah, harapan orang itu bisa berkembang. Berkembang itu apakah itu tetap lurus saja, menyesatkan, atau belok-belok, kita nggak ngerti.
Tapi kekuasaan itu harus diawasi. Dan itu bukan tugas satu dua lembaga pemerintah. Tapi kita masyarakat sipil. Kita masyarakat sipil yang harus ikut mengawasi. Karena kita sudah menyerahkan mandat itu ke yang namanya presiden kita.
Jadi kitalah yang mengawasi itu. Dan mengawasi itu bukan kemudian dikotomis yang di dalam atau di luar. Ada kan sinisme-sinisme yang mengatakan ‘ah ya kalau sudah di dalam, pasti sudah berubah, dekat dengan kekuasaan’. Itu menyederhanakan persoalan gitu.
Terus terang saya yang waktu itu di dalam agak jengkel. Karena juga banyak teman-teman yang kerja keras. Karena kalau sudah arahan presiden itu kan semua harus tegak lurus. Harus tegak lurus birokrasi dan lain-lain. Tapi ibaratnya kalau birokrasi itu kan memang dia harus patuh karena satu komando ya. Kita nggak bisa ngebayangin kalau birokrasi atau TNI-Polri itu arahan satu apa namanya komando gitu. Kemudian harus belok-belok malah kita nggak bisa melihat itu.
Tapi kami yang di Kantor Staf Presiden itu, saya merasa ya, kita tuh punya kemewahan untuk, karena kami bukan birokrat-birokrat. Tapi kami adalah sebetulnya dibentuk karena politiknya presiden gitu. Jadi kita bergerak di situ dan kita melakukan hal-hal yang itu tadi, kayak semacam check and balances lah.
Kita oke, kita tegak lurus, tapi kita tetap ada nilai yang kita genggam. Entah itu nilai kemanusiaan, demokrasi, hukum yang tidak tumpul ke bawah, tajam ke bawah, dan seperti itulah.
Tapi sebenarnya Pak Jokowi itu menerima semua masukan-masukan enggak sih? Mungkin badannya juga kan punya catatan-catatan.
Paling tidak ada tiga. Paling tidak kalau yang saya langsung RUU TPKS menjadi TPKS dan kemudian PPRT. PPRT tuh lebih parah lagi. Itu 20 tahun mangkrak. Tetapi kami, tim kami di KSP sudah menyelesaikan sampai ke DPR. Jadi itu bola panas tuh sudah bukan di pemerintah lagi.
Terus yang ketiga Papua. Waktu di awal tuh presiden itu kan menampakkan keseriusan dan kepeduliannya terhadap Papua. Salah satu yang mungkin sangat teknis itu adalah bagaimana pasar mama-mama Papua yang 13-an tahun mangkrak itu pun akhirnya bisa.
Akhirnya memang kita di birokrasi pemerintahan itu butuh orang-orang, harus memperbanyak orang-orang yang bisa mengorkestrasi kerja-kerja itu. Tidak sekedar kerja yang mengada rutin-rutin gitu aja. Tapi bukan sekedar output aja.Tapi outcome-nya apa gitu. Misalkan dengan pasar di sana itu bukan hanya dulu gak ada pasar, sekarang dibangun pasar. Tapi itu gunanya pasar itu apa. Apakah juga menyejahterakan secara langsung tidak langsung kepada ibu-ibu atau mama-mama Papua.
Saya hanya ingin mengatakan gini loh. Hari ini kita bisa sampai pada pendidikan terhadap presiden dengan segala macam kontroversialnya. Tapi karena saya peneliti saya akan menyampaikan bahwa manusia itu kompleks.
Jadi kekuasaan itu kita semua sepakat itu candu. Nah itu betul-betul seperti kita memegang bola panas lah ya. Kekuasaan itu akan menyejahterakan kalau kita waras dan sadar betul bagaimana itu dilakukan. Tapi kalau itu sekedar kepentingan sesaat, kepentingan jangka pendek, kepentingan sekelompok tertentu, golongan tertentu, nah itu akan berubah.
Sebaik-baik orang ya kalau tak ada pengawasan yang melekat, tidak ada sistem pengawasan kita itu juga termasuk lemah. Kadang-kadang kita ini kan melihat, katakanlah pemimpin atau tokoh-tokoh yang seharusnya menyejahterakan dan berikan rasa aman kepada semua warga dengan tanpa pilih kasih, itu kan kadang-kadang kita marah. Tapi kita lupa harus kita ciptakan mekanismenya.
Jadi saya tuh melihat ya ke depan itu, kita harus menciptakan mekanisme kita sendiri untuk bagaimana pengawasan itu lebih efektif. Dan kemudian kita gak ada yang namanya pendidikan politik publik itu.
Saya gak tahu ya, tapi masa Pak Jokowi 10 tahun itu semua orang-orang baik, akademisi, semua itu banyak sekali yang masuk. Dan saya sering bilang ke kawan-kawan juga ya kita juga gak bisa mengelak. Kita juga bagian dari berkontribusi mungkin walaupun kita tidak melakukan hal yang menyimpang misalnya. Tetapi kita tidak cukup keras atau mungkin kita tuh tidak cukup berjuang lebih dan kemudian gak bisa sendiri.

Ada momen enggak sih Mbak Dhani tuh merasa kecewa dengan pilihan kebijakannya Pak Jokowi gitu?
Ada, KPK yang pertama. Perubahan KPK yang kemudian jadi satu rumpun dengan pemerintahan itu, itu sebetulnya rentetan. Pertama Mas Gibran, kemudian Mas Bobi, terus KPK. Pak Jokowi pasti akan tetap disalahkan karena dia sebagai pemimpin tertinggi gitu.
Tetapi kita juga ikut berkontribusi mungkin yang di dalam itu mungkin kurang keras. Tapi yang jelas waktu itu kami sudah sangat berupaya. Bahkan kajian ataupun analisis kita untuk tidak melakukan itu menurut kami, kami sudah sangat keras. Jadi kita gak bisa seakan-akan, saya tuh dan kawan-kawan di KSP tuh hanya satu unsur, satu elemen. Pak Jokowi tuh punya banyak pintu, punya banyak orang.
Dan kalau sering dikatakan Pak Jokowi tuh pembisiknya siapa? Jangan, jangan bilang gitu. Pak Jokowi itu sangat otoritatif, sangat otonom. Dia memang banyak pembisiknya, tetapi pada akhirnya dialah yang menentukan. Ini juga untuk menghindari kita untuk menyalahkan orang lain. Walau gimana pemimpin tertinggi itu yang paling harus bertanggungjawab.
Tapi sebagai akademisi gitu Mbak Dhani kan udah dari 2015, kemudian melihat akademisi-akademisi yang juga masuk ke Istana itu seperti apa sih melihatnya?
Iya karena waktu itu kita ingin ini membuktikan saja bahwa kami para akademisi, peneliti memang harus diakui punya harapan tadi itu. Jadi ketika kita euforia tentang presiden terpilih yang presiden Jokowi, itu kan waktu itu kan sampai ada headline Jokowi Adalah Kita. Itu kan menunjukkan bahwa ini loh tidak punya darah biru politik tapi bisa di sana.
Jadi ini punya harapan bagi si Badu, si Husin, Hasan di pelosok kampung sana bahwa ‘oh iya ya, saya suatu saat nanti bisa loh jadi presiden kalau saya berintegritas’. Saya bilang selalu tubuh rakyatnya dan kemudian kita langsung bilang, kan kita selalu mendikotomi elit itu buruk, rakyat itu baik.
Jadi Pak Jokowi itu gak usah ngomong dulu. Tubuh rakyatnya itu sudah langsung kita memitoskan dia orang baik. Dia orang yang tidak mungkin berbuat jahat, menyimpang. Dia dari keluarga biasa-biasa saja pasti dia akan memperlakukan kekuasaan itu tidak seperti yang lain-lainnya. Kurang lebih seperti itu.
Nah mitos yang tidak sengaja kita bangun itu akhirnya juga membuat mungkin ya, mungkin lensa kritis kita itu juga agak memudar. Jadi kita perlu untuk kritik, dengan otokritik kita bisa maju. Kita perlu berdamai dengan diri sendiri. Kita tidak apa-apa terluka, jautuh kita bangkit lagi. Tapi dengan cara tadi kritik terhadap diri sendiri.
Kita juga perlu lho otokritik, karena dengan otokritik itu kita bisa maju. Maksudnya kita perlu berdamai dengan diri sendiri. Kita nggak apa-apa.

Sebenarnya kalau misalkan dilihat peran akademis ini di masa depan itu akan berdampak seperti apa sih?
Sangat luar biasa. Justru sekarang ini, kawan-kawan yang pernah sekolah, kawan-kawan yang pernah kuliah, itu kan sebetulnya kita itu sebagai mahasiswa, atau pernah mahasiswa, itu kan diajarkan untuk berpikir secara metodologis. Check and recheck. Kemudiannya hal-hal yang sifatnya objektivitas, rasional, kita harus melakukan triangulasi data. Itu kan artinya kita jangan percaya gitu saja. Realita atau fakta sosial berlapis-lapis. Kita juga tidak mudah untuk mengabstraksikan sosial yang ada di ini, harus dengan ilmu.
Nah dengan begitu kan kita melihat bahwa golongan akademisi, kemudian kawan-kawan NGO dan lain-lain itu, itu sesuatu unsur yang sangat penting gitu dalam memikroskopin jalannya pemerintahan. Karena dengan, misalkan kawan-kawan NGO, dengan pengalaman dan keterampilannya di akar rumput, itu dia bisa melihat, ‘eh enggak gitu,enggak gitu, rakyat nggak seperti itu’.
Tapi juga jangan juga menjengkelkan misalnya dengan yang sudah mungkin yang pernah memberikan usulan ‘pak, demokrasi itu bukan isu rakyat, ini isu elit’. Ini juga menjerumuskan loh. Demokrasi yang dia katakan barusan tadi, itu kan sebetulnya demokrasi dengan bahasa elit. Tapi demokrasi dengan bahasa rakyat kan ada.
Bahasa demokrasi itu apa sih? Demokrasi itu kan kedaulatan rakyat. Disana juga ada gotong royong. Di mana di sana juga bagaimana modal sosial mereka yang mungkin nggak pakai kata demokrasi, tapi sebetulnya itu mencerminkan demokrasi. Kearifan lokal itu kan banyak hal yang seperti demokratis, gotong royong, musyawarah, atau apapun namanya gitu.
Nah jadi kalau misalkan kita bicara demokrasi kita ini lagi terburuk, iya. Tapi di seluruh dunia juga gitu, iya. Tapi apakah kita juga akan membiarkan itu terjadi? Karena di antara semua sistem pemerintahan atau politik yang ada yang selama ini, demokrasi itu yang terbaik dari yang terburuk. Kecuali ada sistem lagi apa? Otoriter kan nggak mungkin.
Jadi demokrasi itu saat ini adalah kita anggap yang terbaik gitu loh. Nah kemudian, apa namanya, sekarang demokrasi kita di mana? Kita sudah menurun. Kita masuk demokrasi yang cacat. Kita, ada unsur-unsurnya yang membuat kita turun. Itu seperti apa? Soal kebebasan berekspresi, segala macam. Indikator objektif itu kan, indikator-indikator menunjukan dan itu bukan kata saya tetapi itu ada indikator objektif yang baik nasional maupun internasional juga diakui bahwa itu adalah barometer kita untuk melihat demokrasi kita ada di mana.
Dan kita jangan tolak itu, ‘ah itu kita baik-baik saja’ gimana? Kemudian kan nggak ada ditangkap. Masa ukurannya seperti itu kan nggak juga. Rasa takut orang, rasa nggak bebas itu aja menunjukkan bahwa demokrasi kita tuh tidak menjamin hak-hak seperti itu. Jadi situasi sekarang itu memang demokrasi kita sedang baik-baik saja.
Berarti lebih baik membiarkan para akademisi ini di dalam istana atau lebih baik di luar saja deh enggak usah ikut campur dalam istana gitu melihat kondisi sekarang? Atau memang sudah seharusnya mereka masuk ke situ gitu?
Kalau saya melihatnya gini, akademisi yang tadi saya bilang dilatih untuk berpikir kritis, metodologis, itu sebetulnya dengan modal yang luar biasa ini, dia menjadi wakil dan jembatan kita untuk selalu dekat dengan kekuasaan dan mengingatkan itu. Dan sebagai akademisi, itu juga seharusnya kita bukan akademisi saja, kita tuh harus fleksibel melihat kekuasaan. Jadi kita mudah masuk ke kekuasaan, tapi kita juga ringan keluar dari kekuasaan.
Karena ketika kita sudah masuk, kita tuh kadang-kadang lupa bahwa ini saatnya keluar. Kata cukup ini sering susah untuk disampaikan ke kita.
Itu juga yang menjadi kritik sebenarnya kan? Maksudnya ketika dilihat akademisi orang-orang yang sudah masuk itu pasti akan berubah gitu di dalam. Walaupun mereka juga bergumul ya dengan diri sendiri.
Jadi maksud saya itu melihatnya jangan hitam putih. Karena enggak semua orang akan seperti itu. Karena sayang juga kalau orang-orang baik yang berjuang, tidak seperti seperti mainstream yang ada, itu kemudian tidak dihargai juga gitu. Padahal dia juga sebetulnya kerja keras, tapi mungkin sendiri gitu.
Menurut saya ini harus ada kolaborasi. Kawan-kawan yang akademisi, praktisi, NGO, media yang masuk ke dalam. Itu nggak bisa sendiri dia harus menggandeng temannya untuk jadi, tersambung terus gitu.
Jadi misalkan di dalam ada regulasi yang bahaya. Kasih ‘eh sebentar lagi nih hati-hati gini-gini’. Itu kerja sama yang baik gitu. Jadi untuk menyelamatkan Indonesia itu terlalu kecil kalau hanya disampirkan kepada sekelompok kecil orang gitu.
Ini kan rumah besar kita gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab di situ. Dan ketimbang kita mencaci atau mengutuki situasi semacam ini, ya kita sekarang tawarannya adalah apa yang harus dilakukan dan terus terang Mbak, saya itu kaget, takjub, dan juga gembira bahwa masih ada harapan.
Ketika tanggal 22 Agustus kemarin, kawan-kawan mahasiswa yang kita bicara itu adalah Gen Z. Gen Z itu sering kita stigma generasi yang rapuh. Generasi yang melek teknologi, iya. Tetapi yang alergi politik tiba-tiba mengkonsolidasi dirinya.
Tiba-tiba dia mengkoordinasikan dirinya sendiri. Ini kan generasi yang unyu-unyu, tapi tiba-tiba dia nggak mau di perintah ini nih. Dia mengkoordinasi dan 54 titik secara nasional. Semua kaget, semua kaget dan RUU Pilkada nggak jadi, harus diakui.
Jadi maksud saya ini juga bagian dari cara kita jangan melihat sesuatu itu hitam putih. Gen Z luar biasa. Dan itu mereka kayak menyampaikan: oke, kita mungkin alergi politik mungkin pilihan kita sering dituduh oleh lembaga survei yang berkontribusi untuk memenangkan seseorang.Tapi pada satu titik kami juga tahu bahwa untuk urusan konstitusi kami nggak main-main. Itu pesan itu tuh luar biasa.
Jadi saya terus terang melihat 22 Agustus kemarin tuh kita masih punya harapan. Dan harapan itu membesar atau mengecil tergantung kita.

Sebenarnya enggak hanya di 22 Agustus itu ya, mungkin sebelum-sebelumnya suara-suara guru besar, akademisi itu untuk Pilpres juga kan?
Itu iya. Tapi maksud saya kita ini kan sering lihat gerakan mahasiswa 98 itu selalu kita panggul kemana-mana bahwa itu adalah yang paling ideal. Iya, itu pada waktu itu. Iya betul. Tapi kita juga punya mahasiswa zaman sekarang yang punya tantangannya sendiri, yang punya caranya sendiri untuk merespon situasi Tanah Air hari ini.
Nah ini mereka pakai cara sendiri. Dan itu keren banget menurut saya. Keren banget dalam artian kalau misalkan ditarik 79 tahun Indonesia, itu selalu ada orang muda di sana. Ada selalu orang muda yang di depan. Dengan tantangan yang berbeda, dengan keterampilan yang berbeda. Ini kan anak-anak muda yang terampil melek teknologi gitu, yang alergi terhadap politik bahkan.
Tapi mungkin pada satu titik mereka udah nggak bisa lagi gitu. Melihat, oh iya ya ketika konstitusi urusannya, ketika tidak semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum pemerintahan dan politik misalnya. Mereka ini bereaksi karena mereka bagian dari warga negara. Dan mereka juga pastilah diskusi-diskusi di forum terbuka, tertutup, itu kan pasti juga membuat masukan-masukan dan kesadaran, simbol-simbol kesadaran mereka.
Tapi suara-suara kayak, tadi guru besar akademisi itu, waktu juga pas Pilpres juga yang baru-baru ini, RU Pilkada, itu sempat dituding karena enggak menerima kekalahan gitu sebagai protes?
Itu pikiran sempit. Setahu saya ya, ini kita kan nggak melihat satu, dua, tiga kampus. Ini kan hampir merata. Ada forum rektor, guru besar, profesor, dokter, semua ada di sana. Nah kita harus cemas gitu. Mereka bergerak, itu kan tidak seperti politisi-politisi argumennya. Mereka kan di situ ada argumen kemanusiaan, argumen demokrasi, argumen soal hukum, argumen soal politik, soal keadaban politik, soal. Nah ukuran-ukuran itu menurut, para cerdik-cendika itu, intelektual, apa namanya, ilmuwan ini, itu sudah tidak lagi. Sudah jauh dari ukuran-ukuran yang seharusnya ada.
Politik ini kan ya harus ada etika dan keadaban gitu loh. Hukum itu ya harus tidak, apa membeda-bedakan. Kemudian, apa namanya, soal bagaimana konstitusi itu seakan-akan diacak-acak, itu kan juga bagaimana mereka mempertanggungjawabkan kemahasiswaan kalau seperti itu.
Jadi kegelisahan, para dosen, para ilmuwan, penelitis, semuanya di kampus-kampus itu, itu harusnya itu direspons positif. Dan itu menjadikan masukan yang luar biasa. Bukan ketimbang malah kita bilang dibayar lagi, itu sungguh menghina sekali.
Tapi kalau melihat Mbak Dhani sebagai kepala Lab 45 ya, berarti mendirikan ini?
Sebenarnya ini kan kumpulan teman-teman ya layak Andi Widjajanto, ada Mamur Kelia, saya ini orang-orang yang sejak 2013 bersama pak Jokowi terus ya. Yang kita selalu dikenal tim 11. Waktu itu memang kita butuh kajian cepat untuk presiden. Kita akhirnya butuh unit reaksi cepatnya. Jadi ini tim muda semua. Itu di bawah 30.
Jadi anak-anak muda ini latar belakangnya ada yang HI, ada yang komunikasi, ada yang gender, ada yang politik, ada macam-macam. Jadi kumpul di sana, mengerjakan itu. Jadi kajian-kajian kami itu macem-macem. Ada kajian tentang defisional dan TNI, tentang cyber, tentang ekonomi ya, politik-ekonomi, terus kemudian industri pertahanan, macam-macam
Dan melihat situasi Pilkada sekarang gimana nih?
Saya rasa kalau misalkan jawaban cepat saya, ini mengkopipis praktek-praktek Pilpres. Jadi maksudnya kita pernah mengalami itu, dan sekarang kita akan mengalami, mengantisipasi, dan sekarang apakah kita, cara kita sama, kita lebih pintar maka kita menciptakan mekanisme untuk penangkalan, ataukah kita biasa-biasa aja karena sudah menyerah. Yang ini sih saya sama sekali tidak menyarankan dan jangan masuk dalam list.
Jadi maksudnya opsi-opsi itu tergantung kita gitu. Dan saya rasa gerakan 22 Agustus itu sudah harusnya menyadarkan simpul-simpul kesadaran kita untuk kita bergerak gitu. Bagaimana dalam derajat yang paling rendah misalkan melakukan pengawasan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota. Karena motifnya dan prakteknya sama gitu.
Jadi RRU Pilkada kita ke depan itu kita harus melihat ya, melihat sekarang aja fenomena kotak kosong, terus kemudian satu partai dikroyok banyak partai, logistik sudah mulai berhamburan. Halo ini sebenarnya negara siapa ya? Maksudnya ini kan negara rumah kita bareng-bareng gitu ya.
Jadi maksud saya karena kita punya pengalaman yang baru kemarin Februari, seharusnya Pilkada ke depan itu yang akan berlangsung ini kita lebih mengantisipasi, lebih waspada. Dan yang paling menurut saya itu ya ciptakan mekanisme bagaimana penanggulangannya. Dan itu nggak bisa sendiri, lagi-lagi nggak bisa sendiri. Mungkin ya justru ini momentum di mana kita semua berkolaborasi.
Kita ngobrol sama kawan-kawan media, kita ngobrol sama kawan-kawan NGO yang punya tema-tema sendiri, kan ada yang HAM, ada yang anti-korupsi, ada yang lingkungan, ada yang macam-macam. Kenapa? Karena ini nanti ber-impact kepada kebijakan daerah loh. Soal lingkungan hidup segala macam itu akan punya implikasi ke sana. Jadi kalau melihat Pilkada, menurut saya sih seyogyanya kawan-kawan masyarakat sipil, akademisi, media, itu berkolaborasi untuk menciptakan apa mekanisme.
Kemudian apakah melihat ada potensi-potensi masalah keamanan gitu dan konflik nanti ketika Pilkada mendatang gitu?
Iya pastilah ya. Kita pasti, kita mungkin sudah bisa menduga gitu. Dari sekarang media juga sering memuat tentang fenomena kotak kosong. Itu kan tidak bagus buat demokrasi kita. Bagaimana pilihan-pilihan rakyat, bagaimana harapan-harapan rakyat untuk tokoh atau pemimpin yang berbeda itu kemudian tidak diberikan ruang gitu.
Jadi misalkan dikeroyok dengan partai-partai yang banyak. Jadi ini apa namanya Pilkada itu disederhanakan hanya soal elektabilitas, hanya dilihat sebagai kalah atau menang kelompok lain terhadap kelompok lainnya lagi. Tapi dalam prosesnya, Pilkada itu kan harus kita menganggap sebagai sebuah proses yang tidak hanya kampanye aja. Tetapi kalau prosesnya ini tidak mencerminkan demokratis, itu kan juga sebetulnya hasilnya sama aja gitu.
Misalkan gini, kenapa tidak diberikan apa namanya opsi-opsi pemerintah daerah yang bermacam-macam. Karena apa? Saya paham karena uang yang beredar itu sudah terlalu banyak mahar. Mahar politik kita itu sudah sangat-sangat mahal dan nggak masuk akal. Jadi memang pada akhirnya kita dipaksa jadi pesimis karena melihat situasi seperti ini.
Jadi itu tadi, kalau karena kita sudah tahu polanya di Pilpres kemarin, maka kita juga penting untuk menciptakan bagaimana sih keluar dari ini. Bagaimana penguatan yang bisa kita lakukan satu bulan ke depan. Ini jangka waktunya pendek dan kalau bisa kita juga perlulah memikirkan solusi jangka menengah dari panjangnya karena ini ada institusi sosial, baik di daerah maupun di pelosok-pelosok sana yang sudah rusak karena politik.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id