tirto.id - Suatu siang di awal 1960-an, Ketua Central Committee Partai Komunis Indonesia (CC-PKI) D.N. Aidit bersuara lantang menolak bantuan asing yang masuk ke Indonesia. Ia menyerukan kepada pemerintahan Sukarno agar berdiri di atas kaki sendiri, tidak tergantung bantuan pihak asing, terutama negara-negara kapitalis Barat, juga International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia.
Seperti diungkap Bradley R. Simpson dalam Economists with Guns: Authoritarian Development and US-Indonesian Relations 1960-1968 (2008), Aidit mengecam proposal pemerintah RI yang menyetujui tawaran bantuan dari IMF di bawah pengaruh Amerika Serikat. Menurutnya, meminta pinjaman dari luar negeri bukanlah jalan keluar bagi kesulitan ekonomi negara, justru membuat rakyat Indonesia menjadi pelayan asing.
Polemik mengenai hal ini terus bergulir selama beberapa tahun berikutnya. Hingga akhirnya, pada 17 Agustus 1965, tepat pada hari peringatan kemerdekaan RI ke-20, Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan IMF.
Namun, beberapa bulan setelah itu, kekuasaan Sukarno mulai melemah dan terguncang setelah terjadinya Gerakan 30 September (G30S) 1965. Akhirnya secara perlahan tapi pasti, sang presiden ditumbangkan.
Orde Lama tergerus dan tamat, lalu digantikan Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Bersama Presiden RI ke-2 itu, Indonesia kembali merajut kemesraan dengan IMF dan bertahan sangat lama.
Berutang Selepas Berdaulat
IMF atau organisasi dana moneter internasional resmi dibentuk pada 27 Desember 1945. Indonesia yang empat bulan sebelumnya menyatakan proklamasi kemerdekaan tertarik untuk bergabung dengan organisasi ini. Kala itu, dikutip dari buku Di Bawah Cengkeraman IMF (2002) karya Indra Ismawan, IMF masih beranggotakan 29 negara (hlm. 16).
Belum sempat Indonesia masuk, pasukan Belanda yang membonceng Sekutu datang kembali. Selama lebih dari empat tahun berikutnya, Indonesia harus berkutat dengan rangkaian peperangan dan upaya diplomasi untuk mewujudkan terbentuknya negara yang benar-benar berdaulat.
Menjelang pungkasan tahun 1949, setelah melalui proses yang rumit, Belanda akhirnya mengakui secara penuh kedaulatan Indonesia. Republik pun harus segera bangkit setelah habis-habisan menghadapi berbagai cobaan dan kehancuran ekonomi selama masa Revolusi.
Tak cuma itu. Pemerintah RI, sebut Boediono dalam Ekonomi Indonesia (2017), harus menanggung utang pemerintah Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar dolar AS, sesuai hasil Konferensi Meja Bundar atau KMB (hlm. 87). Indonesia juga wajib membiayai 17 ribu karyawan eks Belanda selama 2 tahun, serta menampung 26 ribu tentara bekas KNIL.
Situasi ini membuat perekonomian nasional langsung goyah hanya beberapa pekan setelah pengakuan kedaulatan. Redi Rachmat dalam Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan dan Kesatuan Bangsa (1992) mencatat, Indonesia mengalami defisit hingga 5,1 miliar rupiah (hlm. 19).
Oleh karena itu, negara ini jelas membutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Maka, pemerintah Indonesia di bawah rezim Sukarno mengajukan permohonan menjadi anggota IMF dan Bank Dunia. Proses untuk ini bergegas dilakukan.
Akhirnya, tulis Beng To Oey dalam buku Sejarah Kebijaksanaan Moneter Indonesia Volume 1 (1991), dengan penandatanganan Articles of Agreement dari IMF dan Bank Dunia tanggal 15 April 1954, Indonesia resmi menjadi anggota dari dua lembaga keuangan internasional tersebut (hlm. 315).
Indonesia juga diajak untuk ikut merintis International Finance Corporation (IFC), lembaga finansial global yang bernaung di bawah Bank Dunia. Tanggal 28 Desember 1956, Indonesia resmi bergabung dengan IFC. Pada tahun yang sama, IMF mengguyur Indonesia dengan pinjaman sebesar 55 juta dolar AS.
Antara IMF, Sukarno, dan PKI
Pinjaman besar dari IMF ternyata belum cukup untuk mengatasi krisis perekonomian yang melanda negara. Terlebih lagi, menurut laporan IMF, dikutip Baskara T. Wardaya dalam Indonesia Melawan Amerika Konflik PD 1953-1963 (2008), jumlah seluruh utang RI kepada Belanda hingga 1961 masih sebesar 51,6 juta dolar AS (hlm. 286).
Presiden Sukarno dalam posisi sulit. Di satu sisi, dana segar dibutuhkan agar krisis moneter tidak kian parah, juga untuk membayar angsuran utang Belanda. Di sisi lain, PKI menentang jika pemerintah terus bergantung kepada IMF. PKI kala itu cukup berpengaruh karena menjadi salah satu pilar Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) andalan Bung Karno.
Aidit selaku wakil PKI mengusulkan jalan radikal sebagai salah satu solusi. Menurutnya, catat Daniel Dhakidae melalui buku Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru (2003), Indonesia harus kembali kepada kekuatan bangsa sendiri (hlm. 183).
Saran Aidit, pemerintah wajib melakukan pembersihan ke dalam, mengubah sistem masyarakat dengan mengorbankan sebagian kaum penindas kota dan desa, yaitu kaum kapitalis-birokrat, kaum komprador, juga tuan tanah. Namun, usul radikal ini berisiko besar dan berpotensi memantik konflik masyarakat, dari kalangan atas, menengah, sampai bawah.
Sukarno akhirnya mengambil jalan tengah karena saran Aidit tidak disepakati sebagian besar elemen lain di pemerintahan. Pada 28 Maret 1963, presiden mengumumkan Deklarasi Ekonomi (Dekon) yang pada intinya memadukan usulan PKI tentang penguatan ekonomi rakyat, namun juga tidak menutup diri kepada bantuan asing.
Dipaparkan Rex Mortimer dalam Indonesian Communism under Sukarno: Ideology and Politics 1959-1965 (1974), presiden tampaknya tidak ingin kehilangan bantuan dari IMF sehingga dikeluarkanlah Deklarasi Ekonomi itu. Dalam beberapa pekan, IMF siap menggelontorkan tahap pertama dana pinjaman untuk Indonesia sebesar 30 juta dolar AS.
Deklarasi Ekonomi kemudian ditindaklanjuti dengan merilis Regulasi Ekonomi pada 26 Mei 1963. Hal ini disikapi dengan keras oleh PKI karena menganggap regulasi itu terlalu patuh kepada arahan IMF dan negara-negara kapitalis barat.
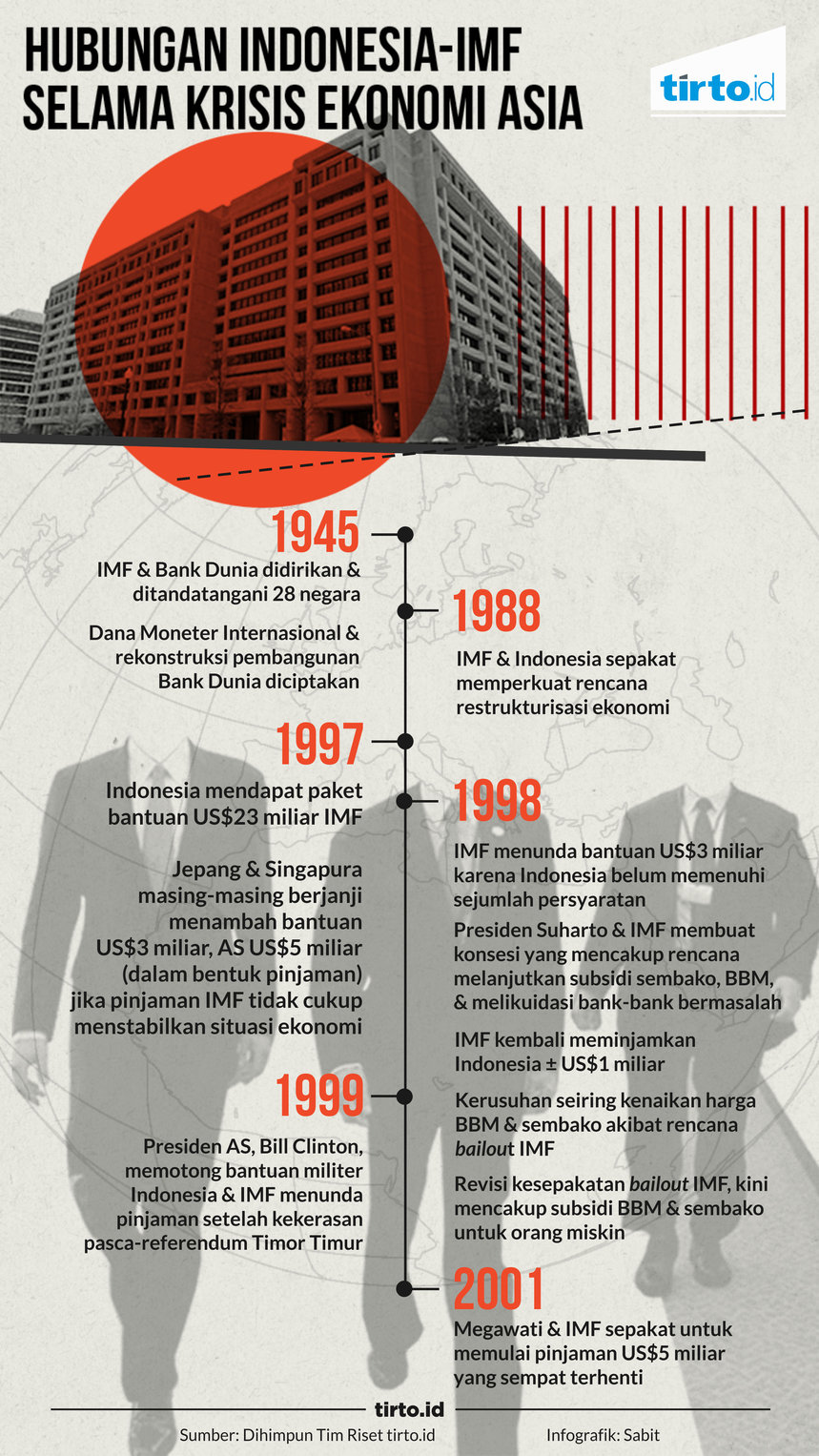
Bercerai, lalu Rujuk Lagi
Suasana semakin memanas. Situasi kala itu sangat semrawut lantaran Sukarno juga sedang gencar-gencarnya menggalakkan kampanye ganyang Malaysia. Di saat-saat rumit itulah PKI berhasil mendesak presiden untuk mencabut Regulasi 26 Mei 1963. Alhasil, IMF pun membatalkan bantuannya kepada Indonesia.
Bahkan, pada 17 Agustus 1965, Presiden Sukarno memutuskan bahwa Indonesia resmi keluar dari keanggotaan IMF. Padahal, menurut laporan jurnal Warta Perdagangan (Volume 18, 1965) terbitan Departemen Luar Negeri, RI masih memiliki utang sebesar kurang lebih 63 juta dolar AS (hlm. 30).
Relasi Indonesia dengan IMF juga Bank Dunia serta perangkat-perangkat ekonomi internasional lainnya kembali membaik setelah PKI dan Orde Lama tergulung sebagai dampak terjadinya peristiwa berdarah G30S 1965.
Pada 21 Februari 1967, Indonesia resmi bergabung lagi dengan IMF berkat peran Soeharto yang kala itu sedang mengintip takhta kepresidenan RI seiring pengaruh Sukarno yang semakin meluruh.
IMF menyambut baik kembalinya Indonesia. Tak perlu waktu lama, IMF segera mengirim pinjaman sebesar 51,75 juta dolar AS pada 1968. Lalu disusul gelombang dana berikutnya, menurut laporan jurnal The Bank (1971), senilai 35,75 juta dolar AS sebagai rangkaian dari perjanjian tahun 1968 tersebut (hlm. 57).
Sejak saat itu, terlebih sepanjang berkuasanya rezim Orde Baru pimpinan Soeharto, Indonesia menjadi salah satu mitra setia IMF dan Bank Dunia, bersama banyak negara lainnya. Relasi harmonis Indonesia dengan IMF terus terjalin dari waktu ke waktu, dari rezim ke rezim, hingga detik ini.
Editor: Ivan Aulia Ahsan












