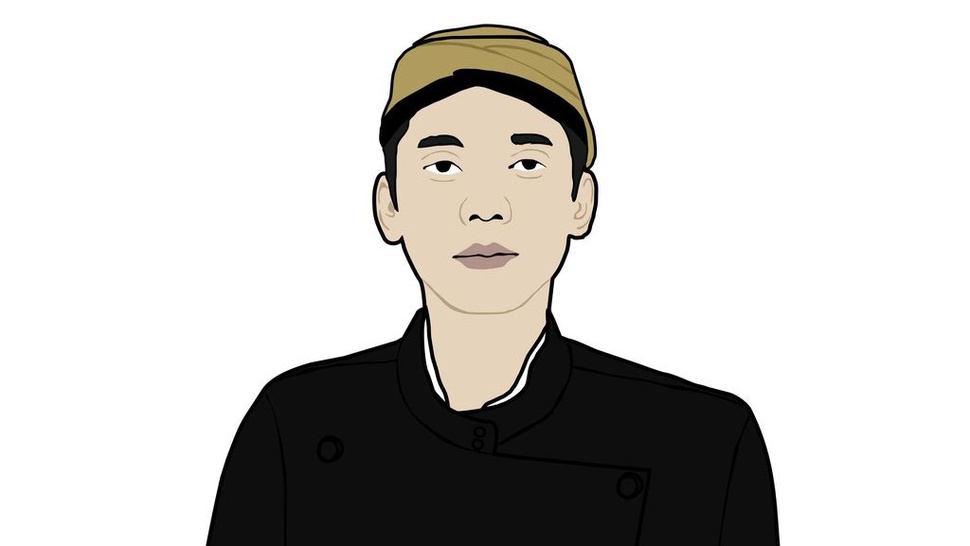tirto.id - Di Kota Solo, kampung halaman Presiden Joko Widodo, tengah terjadi ontran-ontran. Pangkal masalahnya ialah Pemkot Solo hendak membangun masjid raya di taman Sriwedari yang melegenda itu. Selain dikenal sebagai kawasan seni-budaya, ruang publik tersebut kental nilai sejarah. Tak kurang jurnalis Marco Kartodikromo kesengsem dan menceritakan keramaian di taman yang dibangun oleh Paku Buwana X itu dalam novel Student Hidjo.
Siapa bilang Paku Buwana X tak sadar ruang dan tak punya pandangan visioner? Meski menyandang gelar mentereng Sayidin Panatagama Khalifatullah dan memegang tongkat kekuasaan, elemen masjid tak ia sertakan tatkala membangun Taman Sriwedari alias Kebon Raja. Berbekal duit segepok, bisa saja Susuhunan memerintahkan abdi dalem kalang (tukang kayu) mendirikan tempat ibadah kala itu.
Namun, masjid yang merupakan pendukung kelancaran program islamisasi sekaligus mengokohkan kedudukan PB X sebagai pemimpin agama cukup diwujudkan dengan merawat dan memakmurkan Masjid Gedhe. Mejid megah ini menyatu dengan alun-alun utara dan kampung Kauman sebagai syarat pokok tata ruang kota Jawa.
Rupanya Pakubuwana X paham Taman Sriwedari yang dibuka pada 1899 Masehi dengan sengkalan ”Luwih Katon Esthining Wong” itu sengaja dibuat untuk ruang budaya dan kesenian. Raja yang di kemudian hari digelari Pahlawan Nasional ini tak mau intervensi dengan kegiatan keagamaan karena rawan menimbulkan ketegangan sosial. Terlebih lagi, keduanya memang memiliki atmosfer dan misi yang berbeda. Sembahyang membutuhkan keheningan untuk mendekatkan diri dengan Gusti Allah, sedangkan pertunjukan seni-budaya sarat kebebasan, hingar bingar, serta gayeng.
Unsur Langgar (masjid kecil) pun tak ditemukan zaman PB X yang menahkodai Keraton Kasunanan periode 1893-1939 itu. Cukuplah menggelar acara Malam Selikuran yang dilaksanakan di malam ke-21 Ramadan demi menambah kemeriahan ruang publik yang berada di tengah kota tersebut. Lantas, masyarakat di Kota Bengawan merespon kemeriahan tradisi itu dengan menyalakan lentera di depan rumah, tidak memberontak atau merengek meminta dibuatkan tempat ibadah.
Dalam ingatan kolektif wong Solo terekam sepotong pupuh yang mencitrakan Sriwedari yang asri: Kebon Raja winangun Sriwedari, tanam tetuwuhan agung hanggung ngrembuyung rumbaka nglimputi taman myang Segaran (Kebun Raja yang disebut Sriwedari dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang rindang memayungi taman Segaran yang asri).
Masyarakat se-Solo Raya berbagai bangsa (ras) dan anak-anak makin betah berlama-lama di situ berkat tontonan gerombolan fauna. Tidak sia-sia PB X menggelontorkan dana membangun kebun binatang pertama di Jawa itu, dan menghadirkan seekor gajah sebagai magnet. Ruang gerak politik raja yang menyempit akibat intervensi Belanda ternyata bukanlah suatu ganjalan untuk memanjakan hati para kawula. Tali hubungan kawula-gusti kudu dirawat, karena sejatinya “istana” itu ada di hati rakyat.
Kemeriahan demi kemeriahan tanpa henti dapat dijumpai di ruang sosial-budaya ini. Dalam arsip Jubileumfeesten Soerakarta menginformasikan, Malam Sriwedari yang berlangsung pada 31 Augustus hingga 6 September 1923 diisi pesta kembang api, banyak stand dan pertunjukan seperti tenda minuman dan champagne, tenda kue-kue, tenda toerki, stand aneka bunga, caroussel (draainmolen), restaurant, serta pertunjukan bioskop terbuka dan wayang wong. Lampu sokle atau penerangan besar yang memancar hingga menjangkau daerah sekitar kota laksana surat undangan bagi pengunjung untuk segera datang di Sriwedari. Pelancong dan pengunjung lainnya menyaksikan keramaian ini dipungut biaya sebesar 1 gulden, kecuali untuk kanak-kanak, yang hanya membayar setengah harga.
Ketenaran kawasan Sriwedari sebagai ruang hiburan dan budaya sulit dibendung dan gaungnya mendunia. Tak kurang baginda Raja Chulalongkorn dari kerajaan Thailand (Gajah Putih) mengunjungi Kebonraja guna menjawab rasa penasaran. Tamu agung yang menginap di Hotel Rusche ini memang beberapa kali menginjakkan kaki ke telatah Solo, yaitu pada 1871, 1896, 1901, dan 1934. Ia merasa kunjungannya Kota Bengawan tak lengkap apabila belum bertandang ke taman kota ini.
Dari keterangan Imtip Pattajoti Suharto dalam Journeys To Java by a Siamese King (2001), terendus empat alasan raja tersebut memilih mengunjungi Surakarta dan Yogyakarta. Pertama, karena kesan baik terhadap keramahan pemerintah Hindia Belanda manakala ia kali pertama melakukan perjalanan tahun 1871.
Ia menyurat dalam bukunya: “Saya memperoleh keramahan terbaik dan masih menghargainya hingga sekarang”.
Kedua, hendak meneropong Jawa lebih komplit. Ketiga, alasan kesehatan. Dia disarankan oleh dokter Barat kala mengunjungi Bangkok, untuk mendatangi daerah pegunungan di Jawa yang sangat baik untuk memulihkan kesehatan. Keempat, tiadanya konflik politik antara negara Gajah Putih dan Belanda serta perhatiannya terhadap sistem pemerintahan di Jawa yang menurutnya unik.
Wajah baginda bersama permaisurinya dari negeri Gajah Putih itu dimuat harian milik Boedi Oetomo, Darmo Kondo, supaya masyarakat Solo dan sekitarnya bisa menyaksikan. Termasuk memahami sedikit pengetahuan mengenai negeri Thailand yang disertakan dalam surat kabar.
Sang penguasa Thailand sangat gembira dan puas menyaksikan keelokan Bonraja. Kunjungan istimewa oleh raja mancanegara itu diliput oleh jurnalis Darmo Kondo (28 Juni 1934). Tak ayal, Sriwedari yang menjadi kebanggaan orang Solo pun jadi kembang lambe (“buah bibir”) dan namanya harum. Solo yang dijuluki sebagai “surga Hindia Belanda” kian sulit terbantahkan.
Demikian pula Solo yang menjadi jujugan orang keplet ilat (menikmati makan enak), salah satunya menginjakkan kaki ke Sriwedari. Selain posisinya strategis dan terbuka, di lahan Sriwedari juga berdiri beberapa restoran kondang. Orang yang lapar usai keliling melihat pertunjukan wayang wong, kebun binatang, dan museum Radya Pustaka tak perlu beranjak dari area Sriwedari.
Banyak warung makan dan hobi wong Solo memuja lidah membuat redaktur Koemandang Jawi (24 Desember 1917) urun rembuk mengusung judul “Perasaan Lidah”. Terurai bahwa faedah perasa lidah, yakni menambah kesenangan kita atas makanan yang merasuk ke badan. Perlu sekali makanan dikunyah sedemikian mantap dan supaya mengenai ujung saraf lain yang tidak kelihatan. Perasa lidah juga bakal menimbang apakah makanan itu berguna atau tidak. Jangan dikira makanan lezat selamanya baik bagi badan. Karena makanan sehari-hari jadi tak lezat lagi. Informasi yang diketengahkan sang jurnalis itu mencerminkan citarasa tinggi dalam diri masyarakat kala itu.
Demikianlah kilas balik sejarah Kebonraja. Melintasi waktu dan menarik kembali busur kehidupan yang pernah terbentang jauh di belakang, diketahui bahwa Taman Sriwedari jadi tempat berkumpul masyarakat internasional dan kosmopolit. Ruang publik ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hiburan dan mewadahi pelaku seni berekspresi, bukan semata untuk kepentingan religi. Aspek seni dan budaya menjadi sarana pengikat ampuh masyarakat luas berinteraksi sosial dan menjaga harmoni kota. Secara sosial, Sriwedari dari waktu ke waktu sudah menyatu di relung hati warga.
Haruskah ciptaan visioner PB X ini hilang dengan pembangunan masjid raya?
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.