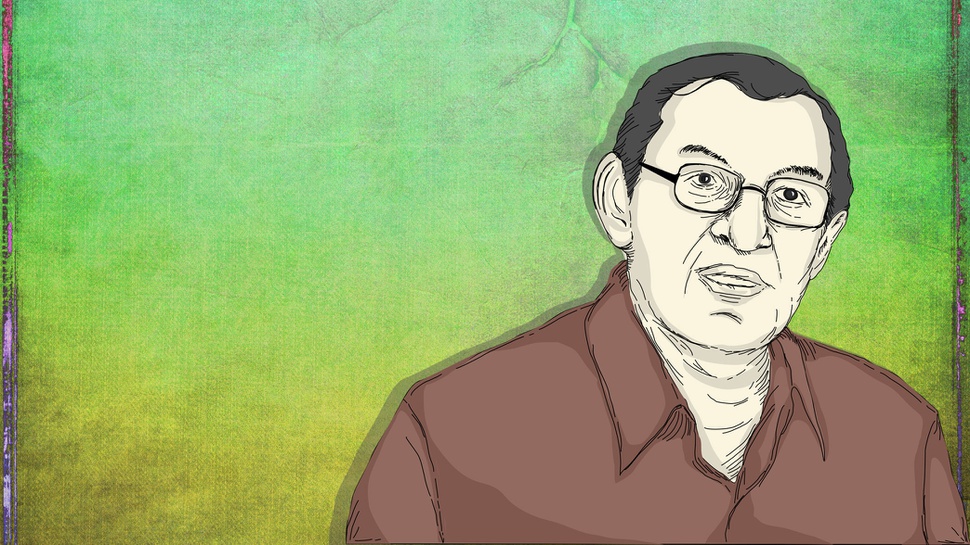tirto.id - Bagian pertama wawancara dengan Prof. DR. Muhammad Quraish Shihab, MA., banyak berkisar tentang pengalaman personal mengalami pendidikan keluarga, pesantren dan di al-Azhar. Juga banyak membahas mengenai kehabiban, dan apa arti serta tugas keturunan Rasul di zaman sekarang (baca wawancara bagian pertama: "Banyak Habib yang Tidak Mencerminkan Akhlak yang Baik").
Di bagian kedua ini, penulis 15 jilid kitab Tafsir al-Misbah ini banyak bercerita tentang etika kaum terpelajar dalam mencari ilmu pengetahuan. Ia menyayangkan kurangnya sikap hormat menghormati dan kerendahan hati.
"Seorang yang berkata 'saya tidak tahu' itu lebih cerdas daripada orang yang berkata 'saya tahu' padahal dia tidak tahu," katanya.
Kerendahan hati itulah yang membuatnya sangat menyadari kemungkinan Tafsir al-Misbah yang ditulisnya sudah tidak lagi relevan atau bahkan memuat banyak kesalahan. Quraish Shihab menganggap setiap tafsir itu terikat dengan zamannya karena setiap tafsir atau studi tentang Alqur'an memang harus bisa menjawab problematika zaman sekarang.
Ia juga menjelaskan latar belakang munculnya tuduhan Syiah yang diarahkan kepadanya. Seingat Quraish Shihab, tuduhan itu baru muncul dengan begitu gamblang saat mulai beredar kabar ia akan diangkat sebagai Menteri Agama oleh Presiden Soeharto.
"Karena jauh sebelum Revolusi Iran, jauh sebelum terjadinya perang antara Irak dan Iran, itu Saudi Arabia bersahabat dengan Iran. Tidak ada itu tuduhan bahwa Iran kafir dan sebagainya," ujarnya saat ditanya dampak Revolusi Iran pada 1979 terhadap konstelasi politik global.
Lalu bagaimana pendapatnya tentang fatwa ulama dan perlukah fatwa dijaga dan dikawal? Berikut wawancara Quraish Shihab dengan Zen RS dan Ahmad Khadafi dari Tirto pada 20 Januari 2017 di kediamannya di Cilandak, Jakarta Selatan.
Gus Mus (Mustofa Bisri), Anda juga, mengalami dikecam dengan kasar oleh orang-orang yang bahkan menulis satu artikel tentang Islam pun tidak pernah. Ini fenomena apa?
Saya kira berkaitan dengan moral. Seorang yang bermoral itu, ada yang bertanya pada dia dan dia tahu jawabannya, tetapi hadir bersama dia seseorang yang lebih tua [usianya], atau yang lebih senior [pengetahuannya], dia tidak boleh menjawab. Itu yang diajarkan [pada] kita.
Kaum terpelajar seharusnya seperti itu?
Kita di Al-Azhar begitu. Pernah saya datang pada salah seorang yang sudah tua, terus saya bertanya, katakanlah soal hukum. Apa jawabannya? "Jangan tanya saya, tanya dia. [Walau] dia lebih muda, tapi dia lebih tahu dari saya." Atau paling tidak, kalau dia mau jawab, terlebih dulu minta izin pada yang lebih senior. Sama halnya dengan salat, tidak ada yang mau terus ingin tampil jadi imam, yang ada dipersilakan. Itu hormat. Hal ini yang kita kehilangan.
Terus yang kedua, hal yang kita kehilangan itu, bahwa banyak di antara kita yang sok tahu dan malu berkata "saya tidak tahu". Iya, kan?
Dan itu bisa sampai ke [contoh] di jalan. Anda bertanya pada orang: "Di mana jalan ini?" Dia kasih Anda jawaban yang dia [sebenarnya] tidak tahu. Dia tetap menjawab karena dia malu berkata "saya tidak tahu". [Akhirnya] Nyasar.
Nah, dalam tradisi keilmuan kita, berkata "saya tidak tahu" itu sudah jawaban.
Kenapa?
Anda, kan, bertanya pada saya. Anda ingin memperoleh informasi dari saya, saya berikan Anda informasi itu. Apa itu informasinya? "Saya tidak tahu'".
Sikap seperti ini sikap apa?
Oh, itu sikap seorang gentleman. Sikap ksatria sebenarnya.
Dan itu sikap ilmiah?
Iya, itu sikap ilmiah. Nah, karena itu dalam pandangan ilmu, seorang yang berkata "‘saya tidak tahu" itu lebih cerdas daripada orang yang berkata "saya tahu" padahal dia tidak tahu.
Nah, bukankah studi tentang tentang agama, studi tentang Alquran, studi tafsir hadis, itu ada banyak di kampus-kampus. Ini sebenarnya problem apa?
Itu barangkali juga salah satu kekurangan [pendidikan formal] kita. Saya sudah tulis, beberapa kali saya menulis. Saya katakan, apa yang saya peroleh di pesantren itu lebih mantap. Di pesantren saya dua tahun. Ini lebih bernilai bagi saya dari apa yang saya peroleh di Mesir selama sepuluh tahun. Yang saya peroleh dari kiai saya: ketulusan.
Ini waktu mondok di Malang itu?
Iya. Dia tulus mengajar, tulus menasehati. Ini yang hilang dari kita. Yang saya peroleh dari sana adalah hubungan jiwa dengan jiwa. Yang kita peroleh di sekolah, takut sama guru. Guru mengajar [tapi] tidak mendidik, guru memberitahu, ini begini, tidak peduli muridnya mengerti atau tidak. Sebagian begitu. Jadi tidak ada hubungan ruh. Dulu itu ada. Hubungan sangat menghormati guru.
Terkait tentang relasi batin dengan guru, mungkin ini tradisi tarekat, nasab kepada ilmu pengetahuan?
Betul, betul, betul. Walaupun kita harus akui, bahwa memang tidak semua, apa yang bisa dipraktikkan dulu masih bisa dipraktikkan sekarang.
Secara umum, saya berkata, dulu guru itu pasti lebih pandai dari murid. Kalau sekarang tidak pasti, kan? Karena informasi segala macam, tapi walaupun demikian, tidak boleh Anda angkuh. Bahkan kalau di tasawuf walaupun dia salah.
Kalau dalam tradisi tasawuf, kan, apa perintah guru harus diikuti...
Harus diikuti.
Nah, sisa dari moralitas pembelajaran di zaman dulu yang masih relevan dalam pendidikan modern itu apa?
Saya kira hubungan batin. Harus ada hubungan batin. Antara guru dengan murid. Hubungan itu paling tidak tercermin dalam kasih sayang pendidik dengan anak didik.
Dalam sejarah, ulama-ulama kita dulu sangat kosmopolit, dengan jalur intelektual yang membentang dari Kairo, Hadrami, Istanbul, sampai langsung ke Saudi, beberapa menjadi mahaguru dan imam di Saudi.
Kita hormat kepada semua yang telah memberi sumbangan untuk perkembangan ilmu dan persebaran untuk masyarakat. Tetapi, apa yang mereka lakukan itu untuk masanya dan masyarakatnya. Kita kalau masih meniru mereka tidak ada gunanya, dong. Masyarakat kita berubah. Jadi kita hormat sama Al-Bantani, Nawawi, kita hormat sama semuanya. Kita hormat sama Buya Hamka. Beliau-beliau itu menghadapi masanya, menafsirkan Alquran sesuai dengan perkembangan masyarakatnya.
Kita sekarang problematikanya lain. Bisakah kita memberikan solusi melalui studi kita terhadap Alquran untuk masyarakat kita, bukan untuk masyarakat yang lain pada masa yang lain. Problem di Saudi beda dengan problema kita, kan?
Artinya boleh jadi Tafsir Al-Misbah pun mungkin sudah tidak relevan lagi?
Betul. Bisa jadi. Bukan hanya tidak relevan, bisa jadi ada yang salah. Nah itu tugas anak-anak muda, dong. Saya tidak mengingkari, bisa jadi [Tafsir al-Misbah] ada yang tidak relevan lagi.
Saya teringat dulu Pak Harun Nasution, pernah berkata begini, “Saya dinilai orang pembaharu, sekarang orang menilai Nurcholis [Madjid] pembaharu, tapi saya bilang pada Nurcholis: 'Suatu waktu engkau akan dikira kolot, karena kamu hanya memberi solusi untuk masyarakat yang kamu hadapi'.”
Jadi saya bisa jadi mengalami hal yang sama. Saya berusaha merevisi, tapi sudah tidak mampu menulis lagi. Saya masih menulis, tapi sudah tidak mampu lagi menulis untuk Tafsir Al-Misbah, untuk melakukan koreksi. Paling kalau saya melakukan koreksi, melalui acara-acara di Metro TV.
Sejak kapan punya niat membuat sebuah tafsir yang mungkin awalnya juga tidak berniat langsung membuat tafsir yang utuh?
Betul itu. Jadi, setelah saya selesai di jurusan tafsir di Mesir dan kembali ke Indonesia. Sekian banyak orang berkata bahwa 'tulislah kitab tafsir'. Saya bilang kalau saya tidak dipenjara, saya tidak bisa. Buya Hamka itu berhasil karena dia dipenjara. Karena ketika kita di penjara kita tidak ada [kegiatan], boleh jadi menulis menjadi hiburan. Banyak yang menulis di penjara, Sayid Qutb juga di penjara. Saya beruntung bahwa saya dalam dua tanda petik “dipaksa” oleh Pak Habibie jadi Duta Besar.
Di Kairo?
Di Kairo. Dan hubungan kita dengan Kairo baik. Hubungan saya pribadi dengan dosen-dosen yang sebagian teman saya, atau mengenal saya, sangat baik. Perpustakaan kaya. Tugas menjadi duta besar dengan gaya kepemimpinan saya menjadi ringan. Karena apa? Kumpulkan para staf, [saya tanyakan] apa yang akan kalian lakukan, setiap minggu rapat laporkan, kalau ada yang perlu dibenahi, dibenahi, saya memberi kepercayaan kepada mereka.
Saya sadar, bahwa saya bukan diplomat. Yang mengelilingi saya diplomatnya. Saya sadar, bahwa ada di antara mereka yang jauh lebih pandai daripada saya dalam bidangnya. Sehingga saya tenang dan mereka pun tenang. Mereka kalau mau melangkah, [baru bertanya] bagaimana ini, Pak? [Saya tanya balik] Bagaimana pendapat kau? Oh, iya bagus. Bagaimana ini, Pak? Saya kira ini perlu diskusikan. Jadi saya punya waktu sangat luang.
Di situlah dimulai?
Di situlah saya mulai. Saya tadinya berencana tafsir itu paling tiga jilid.
Ah, tapi ada satu hal yang berkaitan dengan Alquran. Anda [akan merasa] asyik. Saya bilang begini, untuk menulis komentar tentang suatu ucapan atau tulisan, Anda harus mengenal siapa yang berucap? Kalau Anda tidak kenal, Anda [akan] salah alamat.
Anda harus tahu, bahwa [Alquran] yang berbicara itu Tuhan. Kalau Anda percaya bahwa Dia itu Tuhan, Anda pasti yakin bahwa apa yang disampaikannya benar. Nah, kalau Anda sudah mengenal kalimat-kalimat-Nya, kata-kata-Nya, kandungan-Nya, maka Anda akan cinta pada-Nya. Kalau Anda cinta pada-Nya, maka Dia akan menyampaikan pada Anda rahasia-rahasia-Nya, dan Anda tidak akan bosan untuk “duduk” bersama-Nya.
Ada rahasia atau kejutan yang pernah dialami selama menulis Tafsir Al-Misbah?
Oh, jelas. Salah satunya: saya tidak pernah terbayang bahwa Tafsir Al-Misbah itu 15 jilid. Rata-rata satu jilid 700 halaman, kan? Dan itu dalam waktu yang sangat singkat. Saya bertugas [sebagai duta besar], saya menulis, saya bersama keluarga. Saya duduk tidak kurang dari 8 jam sehari untuk menulis dan membaca. Sampai sekarang saya masih sering menulis. Tiap pagi saya menulis.
Saat itu, kan, menjadi bagian dari pemerintah sebagai Duta Besar. Pernah juga menjadi Menteri Agama. Apa yang bisa ditarik dari pengalaman-pengalaman itu dalam soal pelik hubungan ulama dengan umaro, kaum cendekiawan dengan kekuasaan?
Saya melihat mutlak adanya hubungan baik antara ulama dengan pemerintah. Karena pemerintah berkewajiban menyejahterakan masyarakatnya dan ulama bisa memberi bimbingan keagamaan. Saya berkata begini bukan hanya untuk ahli agama, tapi untuk semua yang berilmu. Kaum terpelajar. Dia bisa memberi tuntunan, bisa memberi koreksi.
Jadi saya tidak sependapat, dan itu pernah saya tulis, dengan Imam Ghazali, yang berkata ulama jangan mendekati pemerintah [dengan alasan] karena dia [ulama] bisa tergiur. Saya katakan tidak. Itu tergantung dari pribadi masing-masing, kan? Kita berkewajiban menyampaikan saran, kritik, dan sebagainya. Tapi dengan cara-cara yang diajarkan agama. Nah, salah satu cara adalah bersikap lemah lembut.
Menjadi menterinya Pak Harto kalau dilihat dari perspektif sekarang enggak menyesal ya?
Saya bersyukur berhenti. Saya khawatir kalau lanjut saya korupsi. Siapa yang bisa menjamin Anda berada di lingkungan seperti itu, siapa yang bisa menjamin? Saya khawatir saya salah. Saya bersyukur karena dengan berhenti, Pak Habibie angkat saya jadi Dubes [di Kairo].
Dan melahirkan Tafsir Al-Misbah.
Iya, melahirkan Tafsir Al-Misbah.
Apa yang membuat Anda tidak menolak tawaran dari Pak Harto menjadi Menteri Agama?
Barangkali kalau saya cerita, Anda anggap saya membuat-buat. Sebenarnya saya menolak. Saya sudah bilang, "Jangan saya, Pak. Ada yang lebih baik dari saya." Tapi, kan, kekuasaan Pak Harto begitu besar. Anda mau bilang apa?
Siapa, sih, yang bisikin sampai akhirnya nama Anda yang muncul sebagai Menteri Agama?
Saya jauh sebelum jadi menteri sudah akrab dengan dengan Mas Bambang [Triatmodjo], dengan Mbak Tutut, karena sebelum itu saya di MPR. Mereka sudah tahu saya. Dia (Pak Harto) tahu saya.
Termasuk klarifikasi soal Syiah atau tidak? Itu yang nanya waktu itu Mbak Tutut atau Pak Bambang?
Bukan, Pak Bambang. Jadi, di depan Pak Harto, saya bilang: "Tanya kepada Pimpinan RCTI. Tanya dia, bagaimana sikap saya terhadap seorang yang dikenal Syiah yang mau mengajar, memberi kuliah-kuliah, memberi tabligh [di RCTI]."
Jadi saat itu ada seorang yang dikenal Syiah, saya dengar dia mau masuk ke RCTI, saya berpesan pada pimpinan RCTI: "Jangan terima dia!" Karena saya khawatir dia sebarkan ajaran Syiah.
Itu konteksnya semacam screening sebelum jadi menteri begitu ya? Atau sudah dilakukan jauh sebelumnya?
Saya kira jauh sebelumnya Pak Harto sudah…
Bukan, pertanyaan tentang Syiah tadi?
Oh, iya. Eh, pertanyaan tentang Syiah, isu tentang Syiah itu muncul setelah tercium bahwa saya dicalonkan jadi menteri.
Oh, konteks politiknya kira-kira itu?
Iya, konteks politiknya itu.
Jadi sebetulnya tuduhan baru itu ya?
Oh baru itu. Baru.
Hampir bisa dikatakan sekonyong-konyong?
Ya. Atau mungkin juga memang sebelumnya [sudah ada]. Tidak pernah ada tuduhan yang begitu gamblang sebelumnya. Kan memang saya ini tidak memedulikan siapa yang berbicara/menulis. Sehingga bisa jadi dalam buku saya ada pandangan-pandangan ulama-ulama Syiah yang saya kutip.
Sampai sekarang masih ditanya soal Syiah ini?
Kemarin ini saya masih ditanya. Saya bilang, “Bolehkah saya mengutip pendapat orang kafir dalam tafsir?”
“Boleh.”
“Bolehkah saya mengutip ucapan orang gila yang mengandung hikmah?”
“Boleh.”
“Kenapa kamu melarang saya mengutip pendapat ulama Syiah? Selama itu benar.”
“Pernahkah kamu membaca dalam tafsir saya ada pendapat ulama Syiah yang pernah saya bantah?”
“Tidak.”
“Baca. Ayat ini, coba kamu lihat bagaimana pendapat saya.”
Jadi, ilmuwan tidak boleh takut menyampaikan pendapat yang dianggapnya benar.
Dengan teori apapun tidak usah takut ya?
Tidak boleh (takut). Kita harus berusaha untuk mencari kebenaran. Dan kita menyampaikan apa yang kita anggap benar walaupun dalam saat yang sama kita berkata, oh boleh jadi itu salah. Jangan mentang-mentang, ini pasti benar, Anda pasti salah. Tidak begitu.
Kalau saya telusuri sejarah pergerakan mahasiswa, saya buka-buka arsip HMI, misalnya, amat biasa masih pakai rok selutut. Titik baliknya persis setelah revolusi Iran 1979.
Betul, waktu Iran. Setelah revolusi Iran. Karena menurut yang saya lihat, sebelum tahun 1980-an itu, ketakutan akan Syiah tidak seperti sekarang.
Memang ada perbedaan antara sebagian pemikir-pemikir muslim di kalangan Sunni apalagi di kalangan Wahabi dengan pemikir-pemikir muslim yang ada di Iran. Perbedaan yang paling besar di tanah Saudi itu haram belajar filsafat. Kalau di Iran, itu sangat mendalam. Sehingga logika yang mereka gunakan itu mengagumkan bagi kaum terpelajar. Ditambah lagi penerjemahan buku-buku mereka. Sehingga Mizan pun dituduh Syiah, kan? Menjadi menggaung lagi tuduhan bahwa saya Syiah setelah saya menulis buku Sunni-Syiah Bergandengan Tangan, Mungkinkah?
Itu konteksnya apa ya menulis itu?
Sebenarnya begini. Itu waktu saya masih di Makasar. Revolusi Iran menggaung. Ada teman-teman di Universitas Hasanuddin minta saya menjelaskan apa, sih, bedanya Sunnah dan Syiah? Saya jelaskan. Dengan merujuk pada kitab-kitab Sunnah dan kitab-kitab Syiah. Saya katakan ada perbedaan, tapi tidak prinsipil. Mereka juga muslim.
Jadi pendekatan menulis buku Sunni-Syiah waktu itu pendekatan ilmiah?
Iya, pendekatan ilmiah. Mereka berkata begini. “Di mana letak perbedaannya?”
Perbedaan satu-satunya yang sangat menonjol adalah bahwa mereka mengakui Imamah. Bahwa setelah Nabi itu, Imam, kepala negara, Sayyidina Ali.
[Perbedaannya] dalam masalah politik begitu ya?
Jadi masalah politik, masalah suksesi. Dan sekarang itu sudah ditelan sejarah. Karena jauh sebelum Revolusi Iran, jauh sebelum terjadinya perang antara Irak dan Iran, Saudi Arabia bersahabat dengan Iran. Tidak ada itu tuduhan bahwa Iran kafir dan sebagainya. Nah, setelah ini, sudah persoalan politik. Sekarang lebih persoalan politik lagi. Kita tidak ingin dipecah belah.
Selain pertanyaan tentang Syiah, tentang keluarga yang enggak pakai jilbab itu masih sering ditanyakan?
Lho, kenapa? Persoalannya sekarang, memeluk agama dan melaksanakan agama jangan karena terpaksa. Tuhan mau ketulusan Anda melaksanakan agama. Nah, sekarang jilbab, apakah semua ulama berkata wajib? Atau ada yang berkata tidak? Apakah ulama sepakat bulat bahwa tangan seluruhnya harus ditutup? Ada penafsiran. Kalau Anda tanya pada saya, "yang baik" itu berbeda dengan apa "yang harus".
Saya merasa pendekatan Anda lebih ke sosiologis?
Iya memang. Saya tidak berpikir orang-orang semacam kiai-kiai zaman dulu itu ndak ngerti agama. Tapi boleh jadi pendekatan mereka itu pendekatan sosiologis yang dikaitkan dengan agama. Dilihat [dulu], selama pakaiannya cukup terhormat, jadi dia bolehkan. Kalau tidak, kenapa kyai-kyai itu [dulu] bolehkan? Kenapa? Itu kyai-kyai besar, loh. Buya Hamka, Kiai Haji Hasyim Asy’ari. Iya, kan?
Saya sambil bergurau berkata, salah satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, mereka ndak ngerti agama. Kira-kira mereka ndak ngerti agama? Kiai Haji Hasyim Asy’ari ndak ngerti agama? Jadi itu tidak mungkin. Yang kedua, takut sama istrinya. Saya menjawab, kiai itu orang yang paling tidak takut sama istrinya. Di mana-mana ia kawin. Jadi bukan itu.
Kalau begitu pasti mereka melihat bahwa ada celah untuk membenarkan seseorang mengenakan pakaian yang sesuai dengan pakaian yang dianggap terhormat oleh masyarakat.
Kalau tentang fatwa ulama?
Pada prinsipnya fatwa itu tidak mengikat. Sekarang begini, saya mau cerita lagi. Kiai Haji Ibrahim Husain. Salah seorang ketua Majelis Ulama yang semasa sama saya, semasa dengan Pak Kiai Hasan Basri. Datang seseorang bertanya pada dia.
"Pak Kiai, saya menceraikan istri saya. Saya berkata, talak tiga. Apakah jatuh talak saya tiga?”
Pak Ibrahim Husain bertanya, “Kamu masih cinta tidak?”
“Saya masih cinta Pak Kiai.”
“Tidak jatuh. Boleh kembali.”
Lalu Pak Ibrahim cerita pada saya. Cerita pada kami. Lho kenapa kasih fatwa begitu? Pendapat ulama Ahlusunnah, kan, bahwa yang berkata jatuh talak tiga, ya jatuhnya tiga. Dia bilang begini:
“Kalau dia tidak senang dengan fatwa saya, dia akan pergi cari ulama lain sampai dia dapat yang membolehkan [kembali rujuk]. Karena fatwa itu tidak mengikat. Tidak mengikat yang bertanya kecuali kalau dia puas. Dia akan cari orang lain sampai dia dapat pendapat yang membolehkan itu."
Jadi, fatwa itu tak mengikat, semua ulama yang belajar tahu itu.
Jadi karena tidak mengikat, tidak perlu ada gerakan jaga fatwa?
Seharusnya tidak ada. Kenapa harus dijaga? Kalau ada fatwa lain, mau dijaga juga? Tambah kerjaan aja.
Dalam konteks sekarang bagaimana Majelis Ulama menyampaikan fatwa-fatwa yang tidak mengakibatkan perpecahan umat, atau kehancuran bangsa ini.
Itu urgen untuk situasi sekarang?
Situasi sekarang.
Patut diprioritaskan?
Harus. Harus diprioritaskan. Karena semua pendapat, walaupun benar, tetapi apabila mengakibatkan mudharat yang lebih besar, harus ditunda.
Tidak dibatalkan, tapi ditunda?
Iya, ditunda. Dulu masa saya, masa Pak Hasan Basri menjadi Ketua Umum [MUI], itu fatwa dibahas di majelis. Lalu diangkat di rapat Majelis Ulama. Itu dilihat apakah fatwa ini atau itu wajar untuk diumumkan oleh Majelis Ulama atau kita tunda. Itu yang berlaku. Karena kita melihat kemashlahatan. Jadi saya kira, apalagi apa yang dinamakan Fatwa Majelis Ulama, itu bukan fatwa. Itu, kan, pernyataan pimpinan Majelis Ulama.
Jadi fatwa-fatwa yang merawat persatuan itu prioritas?
Prioritas. Saya teringat ada hadis. Pernah suatu waktu Nabi duduk bersama beberapa orang sahabatnya, antara lain Abu Hurairah. Beliau berkata: Siapa yang akhir ucapannya adalah lailahailallah masuk surga.
Abu Hurairah bergegas pergi menyampaikan berita gembira ini di pasar. Di tengah jalan ia bertemu dengan Sayyidina Umar. “Heh, kenapa kamu bergegas-gegas?”
“Saya ingin menyampaikan ini.”
Terus Sayyidina Umar pegang tangannya, “Mari kita kembali kepada Nabi.”
“Wahai Nabi, ini orang [Abu Hurairah] mau menyampaikan ini. Ini bisa merusak. Nanti mereka mengandalkan itu. Jangan dulu disampaikan.”
Kata Nabi: "Betul, jangan disampaikan dulu."
Jadi, ucapan saja—apalagi fatwa—jangan sampai mengakibatkan madharat yang lebih besar daripada apa yang ingin dihindari. Itu prinsipnya.
Kita bicara fatwa, ya. Kita tidak bicara kasus. Sederhana. Karena itu tidak perlu dikawal, dong.
Apa yang akhirnya menjadi seperti sekarang (sampai ada gerakan pengawal atau penjaga fatwa)?
Saya kira politik. Saya tidak memihak salah satu dari tiga calon. Tetapi saya berpihak kepada tuntunan moral agama. Salah satu di antaranya, kalau ada orang salah minta maaf, maafkanlah dia. Itu, kan, tuntunan agama, toh? Dan itu tergantung masing-masing orang, kan? Ada orang yang bersedia memaafkan, ada yang tidak. Jadi saya tidak salahkan orang yang tidak bersedia memaafkan.
Karena siapa tahu dia memang marah ya?
Saya tidak tahu. Dia mungkin menganggap tidak wajar untuk dimaafkan. Jadi dalam kasus ini, kalau ada anggota masyarakat kita yang berkata, maafkan saja, ya itu wajar-wajar saja. Tapi kalau ada yang berkata, harus dihukum, wajar-wajar juga. Kalau saya, saya maafkan. Jalan penyelesaian hukum ini yang paling bagus. Semua harus bisa menerima. Jadi tidak perlu ada lagi nanti ucapan-ucapan bahwa ini sebenarnya ada permainan dan sebagainya. Kita terima, hendaknya menerima.
Penulis: Zen RS