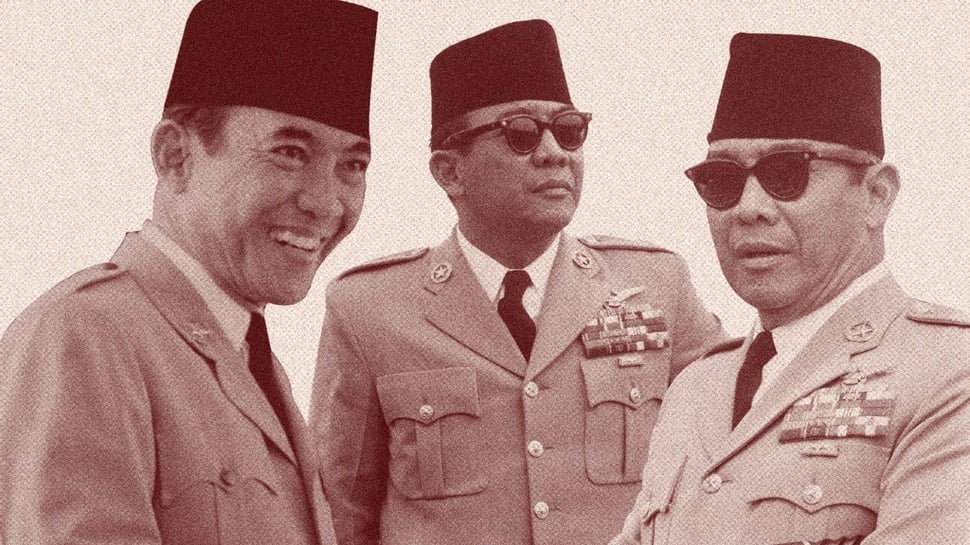tirto.id - Presiden Joko Widodo mewacanakan kebijakan darurat sipil sebagai respons pemerintah atas krisis pandemi covid-19 di Indonesia. Status itu rencananya akan diterapkan bersamaan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sedang digarap peraturan pelaksanaannya.
"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," kata Jokowi dalam rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, lewat video conference dari Istana Bogor, Senin (30/3/2020).
Wacana itu segera disambut secara negatif. Tagar #TolakDaruratSipil sempat trending di Twitter pada Selasa (31/3/2020). Beberapa pihak pun menyuarakan pandangannya agar Presiden Joko Widodo tidak buru-buru menetapkan darurat sipil. Salah satunya Komisioner Komnas HAM Choirul Anam.
Choirul tak sepakat jika pemerintah menerapkan PSBB plus "didampingi kebijakan darurat sipil”. Definisi PSBB dan dampaknya bagi pemerintah berbeda dengan karantina wilayah. Selama karantina wilayah, sebagaimana diamanatkan UU Kekarantinaan Kesehatan Pasal 55, kebutuhan dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Sementara PSBB--dengan atau tanpa tambahan status darurat sipil--tidak mewajibkan pemerintah memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Penerapan PSBB paling sedikit meliputi: peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Semua ini sebenarnya sudah berjalan sejak tiga pekan terakhir.
"Jika merujuk Pasal 59 UU Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah pusat lepas tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan hidup masyarakat," ujar Choirul Anam melalui pesan tertulis yang diterima reporter Tirto.
Selain itu, ia juga menilai status tersebut justru "melahirkan berbagai pelanggaran HAM dan juga potensial menimbulkan tindakan koersif yang masif dan meluas."
Sebagaimana disebut dalam Perppu no. 23/1959, status darurat sipil memang memberikan kewenangan besar bagi aparat yang disebut Penguasa Darurat Sipil untuk bertindak koersif. Sebagai misal, dalam Pasal 17 beleid itu disebutkan bahwa Penguasa Darurat Sipil berhak "mengetahui semua percakapan", "melarang pengiriman berita-berita", "melarang pemakaian alat telekomunikasi", bahkan "menyita atau menghancurkan perlengkapan tersebut."
Pada Pasal 19 dan Pasal 20 bahkan disebutkan bahwa Penguasa Darurat Sipil berhak "membatasi orang berada di luar rumah" dan "memeriksa badan dan pakaian tiap-tiap orang yang dicurigai." Bagi Choirul, semua ini akan menakutkan masyarakat dan "potensial merusak yang sudah terbangun."
Sehari setelah polemik bergulir, Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan lebih lanjut atas pernyataannya. Ia menekankan bahwa penetapan darurat sipil adalah opsi terakhir yang akan diambil pemerintah jika kondisi akibat covid-19 dianggap tidak biasa.
"Semua skenario kita siapkan dari yang ringan, moderat, sedang, sampai kemungkinan yang terburuk. Darurat sipil itu kita siapkan apabila terjadi kondisi abnormal. Perangkatnya kita siapkan. Sekarang ini tentu saja tidak," ujar Presiden Jokowi sebagaimana dikutip laman Kompas, Selasa (31/3/2020).
Meski masih sekadar wacana, kekhawatiran Chairul Anam dan publik atas darurat sipil itu wajar belaka. Status darurat sipil atau keadaan bahaya tanpa pengawasan memang membuka celah yang rawan disalahgunakan. Terlebih jika menilik konteks sejarah lahirnya peraturan tersebut.
Kekecewaan Daerah & Kekacauan Pusat
Di masa Revolusi, pemerintah beberapa kali menetapkan negara dalam status bahaya berdasarkan UU no. 6/1946. Di antaranya ketika Perdana Menteri Sjahrir diculik, pemberontakan PKI 1948, dan ketika Belanda menginvasi untuk kedua kalinya. Di masa RIS dan Demokrasi Perlementer, status keadaan bahaya juga diterapkan di beberapa daerah yang mengalami pemberontakan.
Bedanya, pada dekade 1950-an pemerintah menggunakan lagi peraturan keadaan bahaya era kolonial yang disebut Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg yang disingkat SOB.
Hariyono dalam disertasinya yang berjudul "Keadaan Bahaya di Indonesia 1957-1963" (2004) menyebut bahwa sejak awal 1950-an Maluku berstatus darurat perang gara-gara pecahnya pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Begitu juga daerah Sulawesi kala pecah pemberontakan Andi Aziz. Status yang sama juga diterapkan di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang diguncang pemberontakan DI/TII serta PKI di daerah Merapi-Merbabu Compleks (MMC).
“Menghadapi pelbagai penyelundupan di wilayah Indonesia yang sebagian di antaranya dilakukan oleh pemberontak, menjadikan pemerintah pada tahun 1952 memberlakukan status keadaan perang untuk seluruh wilayah perairan Indonesia,” tulis Hariyono (hlm. 7).
Meski demikian, hingga tahun 1957 pemerintah pusat tak pernah menerapkan status keadaan bahaya berskala nasional.
Pada paruh akhir 1956, timbul pembangkangan terhadap pemerintah pusat di beberapa daerah di Sumatra. Pangkal soalnya adalah kecilnya alokasi dana pembangunan untuk daerah. Gerakan oposisi ini dipelopori oleh para panglima militer dengan dukungan kaum sipil setempat. Mereka secara sepihak memberlakukan keadaan darurat di wilayahnya dan membentuk suatu dewan daerah.
Sejarawan M.C. Ricklefs menyebut dewan daerah yang pertama kali dideklarasikan adalah Dewan Banteng di Sumatra Tengah pimpinan Letkol Ahmad Husein pada 20 Desember 1956. Selang dua hari kemudian, Kolenel Maludin Simbolon mengumumkan berdirinya Dewan Gajah di Medan. Seiring bergantinya tahun, dewan-dewan daerah bermunculan pula di Kalimantan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan juga Maluku.
“Dalam banyak hal, mereka mempunyai pertalian dengan pemimpin-pemimpin Masyumi setempat, satu-satunya partai di antara partai-partai ‘empat besar’ yang bersimpati pada kekecewaan daerah,” tulis Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern (2008, hlm. 504).
Sementara itu, iklim politik di Jakarta juga tak kalah kacau. Kabinet Ali Sastroamidjojo hasil Pemilu 1955 di ujung tanduk, gara-gara pertikaian tak berkesudahan di antara partai koalisinya. Masalah itu jadi tambah pelik karena sejak awal sudah mendapat tekanan dari Presiden Sukarno yang tak sabar dan PKI yang tak dapat jatah menteri.
“Ketidakpuasan semakin meluas setelah kabinet dirasa tidak melakukan perbaikan terhadap struktur pemerintahan, korupsi dan inefisiensi yang semakin meluas,” tulis Hariyono dalam disertasinya (hlm. 125).
Keadaan Bahaya 1957
Untuk mengatasi keadaan yang demikian runyam, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kolonel Abdul Haris Nasution mengusulkan kepada Presiden Sukarno untuk menetapkan keadaan darurat perang. Meski beberapa perwira tak sepakat dengan ide Nasution, namun mereka tak punya banyak opsi. Pemikiran Nasution praktis saja: status darurat perang akan membuat Presiden dan militer punya kekuasaan dan alat untuk mengurus perpecahan yang terjadi.
Presiden Sukarno setuju dengan prakarsa Nasution. Ketika Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya kepada Presiden Sukarno pada 14 Maret 1957, selang 30 menit kemudian Presiden Sukarno mengumumkan keadaan darurat perang berdasar SOB 1939. Peristiwa itu sekaligus jadi tengara tumbangnya sistem Demokrasi Parlementer di Indonesia.
“Tak seorang pun tahu bagaimana bentuk baru dari pemerintahan yang akan datang, kecuali bahwa pemerintahan tersebut tidak akan semacam demokrasi banyak-partai yang dirasakan telah gagal di negara ini,” tulis Ricklefs (hlm. 506).
Hariyono dalam disertasinya menyebut bahwa SOB 1939 mengenal dua tingkatan keadaan bahaya, yaitu “keadaan darurat perang” dan “keadaan perang”. Pada akhir tahun 1957, pemerintah menerbitkan UU no. 74 tentang Keadaan Bahaya sebagai pengganti SOB.
Setelah Dekrit Presiden 1959, untuk menyesuaikan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945, UU Keadaan Bahaya lantas direvisi lagi dengan terbitnya Perppu no. 23 tentang Keadaan Bahaya yang kemudian dijadikan undang-undang dan berlaku hingga kini.
“Uniknya masih banyak tulisan yang menyebut diberlakukannya keadaan bahaya sampai 1963 sebagai keadaan SOB, sebuah istilah populer yang mudah diingat namun secara yuridis dan akademis sebenarnya hal tersebut merupakan istilah yang keliru,” tulis Hariyono (hlm. 5).
UU no. 23/1959 tentang Keadaan Bahaya mengenal tiga tingkatan status bahaya, yaitu darurat sipil, darurat militer, dan keadaan perang. Hanya Presiden yang boleh mengumumkan tingkatan keadaan bahaya untuk seluruh atau sebagian wilayah negara. Pun demikian dengan pencabutan status keadaan bahaya itu.
Penentuan status keadaan bahaya itu berdasarkan pada tiga kriteria. Pertama, terancamnya keamanan atau ketertiban hukum oleh pemberontakan, kerusuhan, atau bencana alam. Kedua, timbul perang, dan ketiga adanya keadaan-keadaan khusus yang mengancam negara.
Segala kebijakan darurat sipil hanya bisa dilaksanakan oleh presiden sebagai Penguasa Perang Tinggi (Peperti). Tugas Peperti dibantu oleh badan khusus yang dibentuk oleh Presiden. Badan tersebut terdiri dari Menteri pertama, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Kepala Staf Angkata Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Negara.
UU no. 23/1959 juga mengatur bahwa presiden hanya akan mempertanggungjawabkan kekuasaan yang dijalankan selama keadaan bahaya pada MPR. Jelaslah bahwa selama keadaan bahaya presiden punya kuasa lebih besar daripada saat keadaan normal. Terlebih dalam badan khusus pembantu presiden itu duduk pula orang-orang militer.
Akibat Penetapan Keadaan Bahaya
Masa Keadaan Bahaya berlangsung hingga 1963 dan selama itu pula Presiden Sukarno bertindak laiknya penguasa tunggal. Begitupun militer, terutama Angkatan Darat, yang bisa menduduki jabatan sipil dan memengaruhi kebijakan. Peranan partai politik dan DPR sebagai pengawas eksekutif pun menurun drastis.
Selain itu, tekanan dan sensor terhadap pers dengan alasan menjaga ketertiban umum pun semakin kencang. Mulanya penguasa militer mengawasi pemberitaan yang menyangkut soal kemanan, tapi kemudian melebar pada soal politik. Dalam tahun 1957 saja Hariyono mencatat sebanyak 125 kasus penindakan terhadap pers gara-gara SOB.
“Kebebasan pers sejak diterapkan keadaan darurat perang segera mengalami keterbatasan, karena pihak militer ikut terlibat dalam memberikan proses perijinan serta pelarangan pers. Pers yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum dapat dibredel,” tulis Hariyono (hlm. 163).

Dikutip dari Ulf Sundhaussen dalam Politik Militer Indonesia 1945-1967 (1981, hlm. 223), SOB memungkinkan militer mengeluarkan perintah/peraturan yang menyangkut ketertiban umum dan keamanan ketika kondisi darurat perang. Selain itu, dalam keadaan lebih gawat, militer dapat mengubah ketentuan peraturan umum serta berwenang mengambil tindakan apa pun yang dianggap perlu.
Peran militer yang menonjol di era darurat itu tampak ketika terjadi nasionalisasi perusahaan Belanda pada akhir 1957. Nasution mengumumkan perintah penertiban pengambilalihan perusahaan Belanda pada 13 Desember 1957. Pengumuman itu langsung menghentikan semua gerakan pendudukan perusahaan yang sebelumnya dilakukan oleh organisasi buruh dan kelompok masyarakat.
“Dilarang kepada siapapun untuk mengoper perusahaan2 Belanda. Pengoperan hanja dilakukan oleh Penguasa Militer. [...] Tiap tuntutan dan persoalan jang diadjukan oleh pihak Belanda tidak diselesaikan setempat tetapi harus diteruskan kepada Penguasa Militer/KSAD untuk kemudian diteruskan kepada pemerintah,” demikian instruksi Nasution sebagaimana dikutip harian Pedoman (14/12/1957).
Tahun 1958, Nasution bertindak lebih jauh dengan mengatakan kepada Presiden Sukarno bahwa Angkatan Darat ingin melanjutkan peran nonmiliter itu setelah status keadaan bahaya dicabut. Nasution menawarkan konsep “Jalan Tengah” yang akan memberikan peluang bagi militer, khususnya Angkatan Darat, untuk berperan dalam pemerintahan sipil.
Konsep “Jalan Tengah”—yang nantinya jadi fondasi doktrin Dwifungsi ABRI, sebut Nasution seperti dikutip Harold Crouch dalam The Army and Politics in Indonesia (2007): “… memberikan cukup saluran pada tentara kita bukan sebagai organisasi, tetapi sebagai perorangan-perorangan yang menjadi eksponen daripada organisasi kita, [untuk] turut serta menentukan kebijaksanaan negara kita pada tingkat-tingkat yang tinggi.”
Konteks penerapan keadaan bahaya zaman itu jelas berbeda dibanding keadaan saat ini. Namun, menilik pemakaian wewenang yang kebablasan saat UU Keadaan Bahaya diterapkan pada 1957-1963, maka kekhawatiran Komisioner Komnas HAM Choirul Anam bukan isapan jempol belaka. Terlebih jika sistem pengawasan terhadap pemerintah tidak kuat.
Maka itu, terkait darurat sipil Covid-19, peneliti senior Imparsial, Anton Aliabbas mengatakan, pemerintah RI perlu berhati-hati dalam membuat kebijakan darurat sipil sebagai penyerta kebijakan pembatasan sosial.
"Tetap mengacu pada UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah belum semestinya menerapkan status darurat sipil ketika UU Kekarantinaan dan UU Penanggulangan Bencana masih dapat dioptimalkan guna mengatasi pandemik Covid-19.
Editor: Irfan Teguh Pribadi