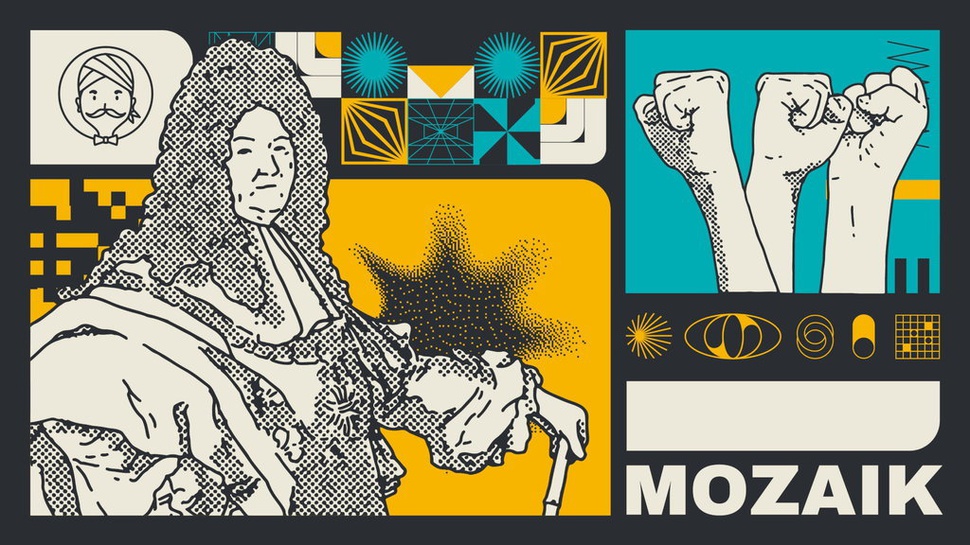tirto.id - Di Abad Pertengahan, Montpellier merupakan salah satu kota terpenting Perancis. Kota ini, berpenduduk sekitar 20.000 jiwa yang mayoritas bekerja sebagai petani. Banyak pula institusi negara berdiri beserta pejabat-pejabatnya tinggal di kota ini.
Awalnya, kehidupan di Montpellier berjalan biasa-biasa saja. Namun, perang melawan Spanyol yang berlangsung selama 24 tahun sejak 1635 kemudian memporak-porandakan kehidupan di kota ini, terutama bagi kaum petani atau kelas menengah-bawah.
Situasi kian memburuk manakala dua orang utusan Raja Louis XIV bernama Baltazar dan Romanet datang tepat pada awal Juni 1645. Mereka membawa titah bahwa, berdasarkan aturan baru bertajuk Joyeux Avènement à la Couronne, tarif pajak lama bakal dinaikkan dan akan menyusul penetapan jenis-jenis pajak baru.
Pajak-pajak baru itu, merujuk penuturan William Beik dalam “The Culture of Protest in Seventeenth-century French Tows” (terbit di jurnal Social History, Vol. 15, 1990), “Sangat banyak jenisnya dan, sialnya, tak jelas peruntukannya dan terlalu rumit strukturnya.”
Aturan baru itu lantas memicu desas-desus buruk tentang pajak di tengah masyarakat Kota Montpellier.
“Dipengaruhi banyaknya penduduk kota yang tak memahami penjelasan Baltazar dan Romanet,” tulis Beik, “muncul pula rumor yang menyatakan bahwa wanita akan dikenai pajak untuk setiap anak yang mereka miliki.”
Rumor itu bukan saja memanaskan emosi masyarakat Montpellier, melainkan juga membuat Prancis secara keseluruhan bergejolak. Terlebih, rumor itu kemudian terbukti benar. Maka besatulah penduduk wanita Montpellier untuk menyatakan ketidaksetujuannya.
Mereka pertama-tama melempari rumah keluarga pejabat bernama Maduron dengan batu. Maduron jadi sasaran lantaran dia merupakan penjamin emisi atas aturan pajak baru tersebut. Aksi penduduk wanita Montpellier pun kian menjadi-jadi di akhir Juni 1645.
“Kelompok wanita yang dipimpin oleh seorang istri pembuat ubin berjuluk Monteille melancarkan aksi-aksinya dengan membawa kapak, pisau, tombak, serta pedang sembari berseru ‘semua orang-orang partai harus dihabisi dan rumah-rumah mereka harus kita hancurkan’,” tulis Beik.
Per tanggal 30 Juni 1645, huru-hara akhirnya menggelora di seantero Montpellier. Kelompok-kelompok lain pun menyusul turun protes usai tersiar kabar tentang eksekusi mati dua orang terpidana di penjara kota yang dianggap tak adil.
Masih menurut Beik, kaum wanita yang dikepalai Monteille lantas bersatu-padu menghancurkan penjara kota setelah tersulut rumor yang menyatakan bahwa, “Wanita-wanita yang melakukan protes itu lebih layak dihukum dibandingkan dua terpidana tersebut.”
Sebagai tanggapan atas protes warga Montpellier, Raja Louis XIV mengeluarkan attroupement alias titah penurunan pasukan. Sayangnya, titah itu justru jadi bencana.
Maka makin padulah penduduk Montpellier melawan titah rajanya sendiri. Mereka menganggap penguasa telah bertindak seenaknya. Sembari menyerukan jargon “Vive la liberte” penduduk Montpellier serentak menyerang pejabat-pejabat negara yang tinggal di kota tersebut untuk “dimusnahkan”, entah nyawa maupun harta bendanya. Perlawanan itu lantas menyebar ke titik-titik lain di Perancis.
Karena aksi protes yang makin tak terkendalai, Raja Louis XIV menyerah dan menyanggupi seluruh tuntutan penduduk Montpellier.
Protes warga Montpellier itu, juga aksi-aksi protes lain kemudian, terang menegaskan karakter masyarakat Perancis. Dalam buku berjudul Urban Protest in Seventeenth-century France (1941), Beik menulis, “Protes merupakan fitur original dalam kehidupan masyarakat Prancis.”
Charivari
Aksi protes menjadi sinyal utama untuk mengingatkan penguasa Perancis bahwa mereka bekerja untuk rakyat, bukan sebaliknya. Namun, tak semua protes digerakkan murni oleh masyarakat semisal dilakukan penduduk Montpellier itu. Protes dapat pula muncul atas manipulasi penguasa atau elite demi memenuhi kepentingan mereka.
Meski begitu, mayoritas aksi protes dalam sejarah Perancis lahir dari semangat charivari yang hidup di masyarakat bawah.
Henry Kahane dalam “Charivari” (terbit dalam jurnal The Jewish Quarterly Review, Vol 52, 1962), menjelaskan bahwa charivari dapat dimaknai sebagai “mempermalukan pembuat kebisingan”. Uniknya, charivarisebenarnya berakar dari ketaksukaan masyarakat Perancis—penganut Paganisme dan kemudian Kristen—di masa lalu terhadap kebisingan kaum Yahudi.
Kata charivari mulanya berasal dari bahasa Portugis “caraba” atau “carava” yang merupakan turunan dari bahasa Ibrani “hebra” atau “habura”. Arti kata ini yang sesungguhnya adalah perkumpulan.
Dalam sosio-budaya Yahudi, kata “hebra” atau “habura” dipakai untuk mendeskripsikan kebiasaan orang-orang Yahudi, terutama kaum aristokrat, melakukan upacara pemakaman spesifik.
Merujuk catatan Infante Alfonso, adik termuda Raja Juan Carlos dari Spanyol, yang bertarikh 1323, upacara pemakaman spesifik yang dimaksud adalah, “Pada hari tertentu dalam setahun, orang-orang Yahudi berpuasa [...] Kemudian, seseorang dari mereka mengunjungi pemakaman [...] Setelah itu, diadakan jamuan makan. Yang terakhir ini berubah menjadi perayaan yang rumit dengan pementasan parodi dan menyanyikan lagu.”
Perayaan kematian dengan parodi dan nyanyian tentulah menimbulkan kebisingan dan masyarakat Perancis amat membenci hal itu.
Mengapa demikian? Beik dalam studi lain yang berjudul “The Violence of the French Crowd from Charivari to Revolution” (terbit dalam jurnal Past & Present, Vol. 197, 2007), kebencian masyarakat Perancis terhadap kebisingan itu terjadi seiring dengan perubahan lanskap masyarakat Perancis. Masyarakat Perancis yang semula hidup di desa-desa yang berjauhan lambat laun terkonsentrasi menjadi masyarakat kota yang ruang hidupnya kecil.
Masyarakat kota yang ruang hidupnya sempit itu pun harus mau berbagi fasilitas umum, seperti sumur, jamban, atau kios pasar. Menurut Beik, masyarakat Perancis menganggap hal itu sebagai kemunduran sehingga mereka menginginkan adanya ruang privat yang harus dihormati siapapun.
Karena itulah mereka membenci segala sesuatu yang bikin bising lantaran dianggap melanggar privasi. Lalu, charivari menjadi cara masyarakat Perancis untuk meminta pertanggungjawaban terhadap siapapun yang melanggar privasi. Awalnya, charivari ditujukan pada kaum Yahudi dengan cara diolok-olok.

Transformasi Charivari
Perlahan-lahan, charivari bertransformasi. Ia bukan hanya ditujukan untuk kaum Yahudi, tapi semua kelas atau kelompok masyarakat yang dianggap melanggar privasi atau melanggar norma sosio-budaya masyarakat Perancis.
Namun, sekadar olok-olok kemudian makin tak cukup untuk menggugat. Frank R. Baumgartner dalam “The Politics of Protest and Mass Mobilization in France” (terbit dalam jurnal French Politics and Society, Vol. 12, 1994) menjelaskan bahwa masyarakat Perancis kemudian paham bahwa pelanggar privasi atau norma terburuk adalah kaum penguasa, seperti halnya pemicu aksi protes warga Montpellier pada 1645.
Maka olok-olok pun bertransformasi menjadi aksi protes untuk menghadapi kesewenang-wenangan penguasa. Entah itu dilakukan secara baik-baik maupun dengan cara keras, bahkan sangat keras, kala suara masyarakat tak jua didengar.
Aksi protes paling keras terjadi pada Juli 1789, kala kepala Raja Louis XVI dipenggal untuk menggiring penghapusan feodalisme serta pendeklarasian hak-hak asasi manusia–diikuti oleh terbentuknya konstitusi pertama Perancis yang demokratis.
Meski begitu, konstitusi yang dibuat untuk membatasi kekuasaan penguasa pernah pula mengalami menyelewengan. Seperti saat Charles de Gaulle menetapkan Konstitusi Republik Kelima pada 1958 yang malah membuat kekuasaan makin sentralistik.
Protes akhirnya jadi alternatif populer yang dimiliki masyarakat Perancis untuk membendung penguasanya yang keblinger. Selama penguasa masih saja mengeluarkan kebijakan nyeleneh, selama itu pula masyarakat Perancis akan melakukan protes. Dalam catatan sejarah Perancis, mayoritas protes yang dilakukan warganya berakhir dengan keberhasilan.
Sampai-sampai seorang pujangga anonim pernah berkata: Personne ne proteste comme les Français. Des salaires stagnants? Démolir une banque. Des politiques éducatives élitistes? Brûlez des voitures. Famille royale complaisante? Révolution!--Tidak ada yang memprotes seperti orang Perancis. Gaji stagnan? Hancurkan bank. Kebijakan pendidikan elitis? Bakar beberapa mobil. Keluarga kerajaan semena-mena? Revolusi!”
Editor: Fadrik Aziz Firdausi