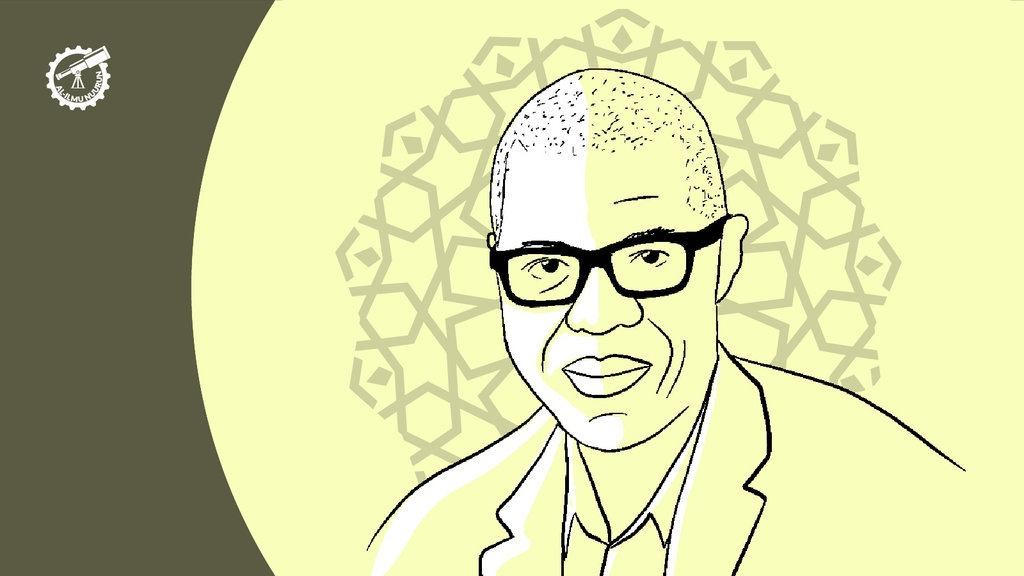tirto.id - Pada akhir 2018 saya bersilaturahmi dengan tiga orang Indonesia di New York untuk mendengar langsung cerita dan kecendekiaan mereka dari Manhattan, pulau yang ditukar Belanda dengan Pulau Banda. Ketiga orang itu adalah Bung Max Surjadinata, Bung Coen Husain Pontoh, dan Bung Nindyo Sasongko. Meski Surjadinata sudah berumur di atas 80, semangat dan gerak-geriknya masih trengginas. Silaturahmi ini sengaja saya lakukan karena saya juga ingin mendengar ikon Afrika di Columbia yang karyanya sempat saya baca di perpustakaan Berlin: Souleymane Bachir Diagne.
Bagi saya, ada titik temu ketika menatap mata ketiga bung Indonesia itu dan Bung Diagne. Mereka sama-sama menyuarakan pembebasan dalam ruang kerja masing-masing. Jika ketiga bung menceritakan soal Indonesia pascamerdeka, maka si bung dari Senegal berbicara tentang pembebasan intelektual Afrika. Saat berbicara, Diagne bisa betah berlama-lama menjelaskan soal filsafat, Islam, dan pengamatan lainnya. Namun ia penyimak yang tekun ketika kita lawan bicaranya sedang menjelaskan sesuatu, tak terburu-buru menyanggah atau menyela.
Lahir dan besar di Senegal, Diagne dididik langsung ayahnya, Sheikh Diagne Ahmadou. Ayahnya memperkenalkan Diagne pada pemikiran Muhammad Iqbal. Dalam penuturan Diagne, ayahnya mengajar Islam yang bertenaga dan berdaya intelektual kritis sesuai dengan apa yang Iqbal sebut ‘spirit khalifah Umar’. Ini membekas dalam dirinya hingga menjadikan Iqbal sebagai filsuf favorit untuk dibaca ulang. Diagne menulis komentar tentang Iqbal bersama filsuf Afrika terpenting abad ke-20 sekaligus presiden pertama Senegal, Léopold Sédar Senghor (m. 2001). Mengikuti jejak Senghor, Diagne berhasil lolos ujian masuk Lycée Louis-le-Grand, SMA bergengsi di Paris yang melahirkan banyak filsuf, ilmuwan, seniman, dan negarawan.
Lalu ia berhasil menempuh ujian kompetitif memasuki École normale supérieure (ENS), salah satu perguruan tinggi paling prestisius di Paris dengan kurikulum yang bebas dipilih. Selama kuliah di sini, ia belajar dengan Louis Althusser dan Jacques Derrida. Gelarnya ia peroleh dari Universitas Paris 1 Panthéon-Sorbonne hingga doktor dalam matematika pada 1982, lalu doktor kedua bernama doctorat d’Etat pada 1988 dengan disertasi tentang logika dan matematika George Boole, filsuf Inggris abad ke-19.
Kariernya secara umum terbagi dua. Pertama, di Senegal era 1980-an hingga 1999 ia dipercaya banyak jabatan strategis termasuk menteri pendidikan dan kebudayaan, selain meramaikan iklim intelektual di negerinya dan mengajar filsafat di Universitas Cheikh Anta Diop, Dakar. Kedua, sejak 2002 hingga kini ia berkarier di Amerika sebagai guru besar bidang filsafat dan kajian Perancis.
Filsafat: Kebutuhan dan Kewajiban
Ia kini lebih banyak dikenal dalam bidang pemikiran Islam dan kajian pascakolonial, ketimbang pakar logika dan matematika. Setidaknya dari riwayat masa kecilnya, ia memasuki dunia filsafat Islam dan kajian pascakolonial melalui Iqbal dan Senghor. Dua tokoh besar ini sering dibaca sendiri, sering pula dibaca bersamaan, guna membangkitkan semangat intelektual pada abad ini, terutama untuk menghadirkan dua identitas besar dalam dirinya: keislaman dan keafrikaan. Ia baru belakangan dikenal menekuni dunia filsafat Islam, lantaran ia menuliskan karyanya dalam bahasa Perancis, lalu baru diterjemahkan ke Inggris.
Diagne menghadirkan Iqbal sebagai ikhtiar untuk menghadirkan suara lain yang tidak dilandasi kecurigaan dan kemarahan. Filsuf Charles Taylor memuji Diagne berhasil menghadirkan Iqbal yang menghancurkan segala berhala suku dan kasta melalui kemanusiaan dan kesetiaan (fidelity). Bagi Diagne, Iqbal membuka ruang ijtihad dalam wujud spirit gerakan untuk mencapai kesadaran diri. Ini kemudian dijadikan basis untuk menghadirkan Islam demi pembentukan ‘masyarakat yang terbuka’— masyarakat yang adil dan menjunjung tinggi kesetaraan, bukan primordialisme.
Spirit filsafat Iqbal dijadikan Diagne sebagai momen kebangkitan dan kebebasan yang terlepas dari citra buruk fatalisme di tubuh umat maupun dalam gambaran Barat. Filsuf Jerman abad ke-17, Gottfried Leibniz, pernah menyebutnya 'fatum mahometanum' atau fatalisme sebagai takdir bangsa muslim. Konteksnya waktu itu adalah masyarakat Turki Usmani—terlepas dari salah pemahaman dan bias orientalisme. Karena itu imperatif Iqbal tentang filsafat aksi dan konsep etis dari tanggung jawab manusia menjadi penting untuk dibuka kembali.
Dorongan intelektual Diagne salah satunya bisa ditemukan dalam kalimat tanya yang ia ajukan: Comment philosopher en Islam? (Bagaimana cara berfilsafat dalam Islam?) Dia bukan seorang peneliti filsafat Islam yang menggali filsafat tertentu melalui penelusuran konsep dan konteksnya. Ia menggunakan filsafat Islam masa lalu untuk menghadirkan gairah berfilsafat masa kini. Diagne memandang pemikiran memiliki sayap yang tak bisa dihentikan oleh siapapun ketika terbang. Dengan langgam menulis esai ala Perancis, ia menggali suatu hal secara metaforis dengan kalimat-kalimat yang baik, tapi kadang kala sulit dimengerti karena kita mesti berbekal bacaan sebelumnya.
Dalam esai-esainya, ia berargumen filsafat ialah kebutuhan dan kewajiban. Diagne juga menekankan bagaimana Islam berdialog dengan tradisi intelektual lain seperti dicontohkan filsuf muslim masa lalu yang berdialog dengan Plato, Aristoteles, atau Plotinus dan filsuf muslim masa kini yang berdialektika dengan Nietzsche, Bergson, dan seterusnya. Dialog intelektual ini, baginya, menghasilkan gerak kebudayaan yang dinamis. Ini bagian yang dalam tradisi kenabian disebut "kebijaksanaan sebagai barang yang hilang" dan dalam bahasa Quranik disebut "yang memperoleh kebijaksanaan, ia telah mendapat anugerah yang tak tepermanai" (Al-Baqarah ayat 269).
Upaya berdialog ini yang Diagne gunakan untuk menggali Iqbal bersama Senghor melalui pengaruh filsafat Bergson. Hubungannya agak pelik karena Diagne membawa Bergson, Iqbal, dan Senghor untuk menggali pemikiran pascakolonial. Sehingga ia menyebutnya sebagai “Bergson pascakolonial”.
Elan vital Asia-Afrika
Apa pengaruh penting Bergson bagi Diagne?
Pengaruh paling menonjol adalah konsep élan vital—dalam dunia intelektual Indonesia kerap disinggung tanpa menyebutkan siapa penemunya—dari Bergson terkait evolusi kesadaran, kehendak bebas, durasi, waktu, dan intuisi.
Bagi Iqbal, konsep itu memengaruhinya untuk menelaah gerakan kreatif dalam rangka menyegarkan kembali kesadaran-diri (khudi) dalam tubuh umat Islam. Bagi Senghor, élan vital berpengaruh pada caranya meneroka estetika dan ke-diri-an bangsa-bangsa Afrika. Senghor menyebutnya ‘Negritude’, yakni gerakan politik dan intelektual sebagai perlawanan terhadap kolonialisme dan emansipasi dari beban perbudakan.
Bergson dalam diri Iqbal dan Senghor menjadi semangat pembebasan secara intelektual, politik, dan kebudayaan. Senghor menggunakan Bergson untuk mencari konsep pengetahuan dan seni dalam konteks Afrika. Sementara Iqbal menggunakan Bergson untuk menggali penyempurnaan kreasi manusia melalui élan vital menuju penciptaan ‘masyarakat terbuka’.
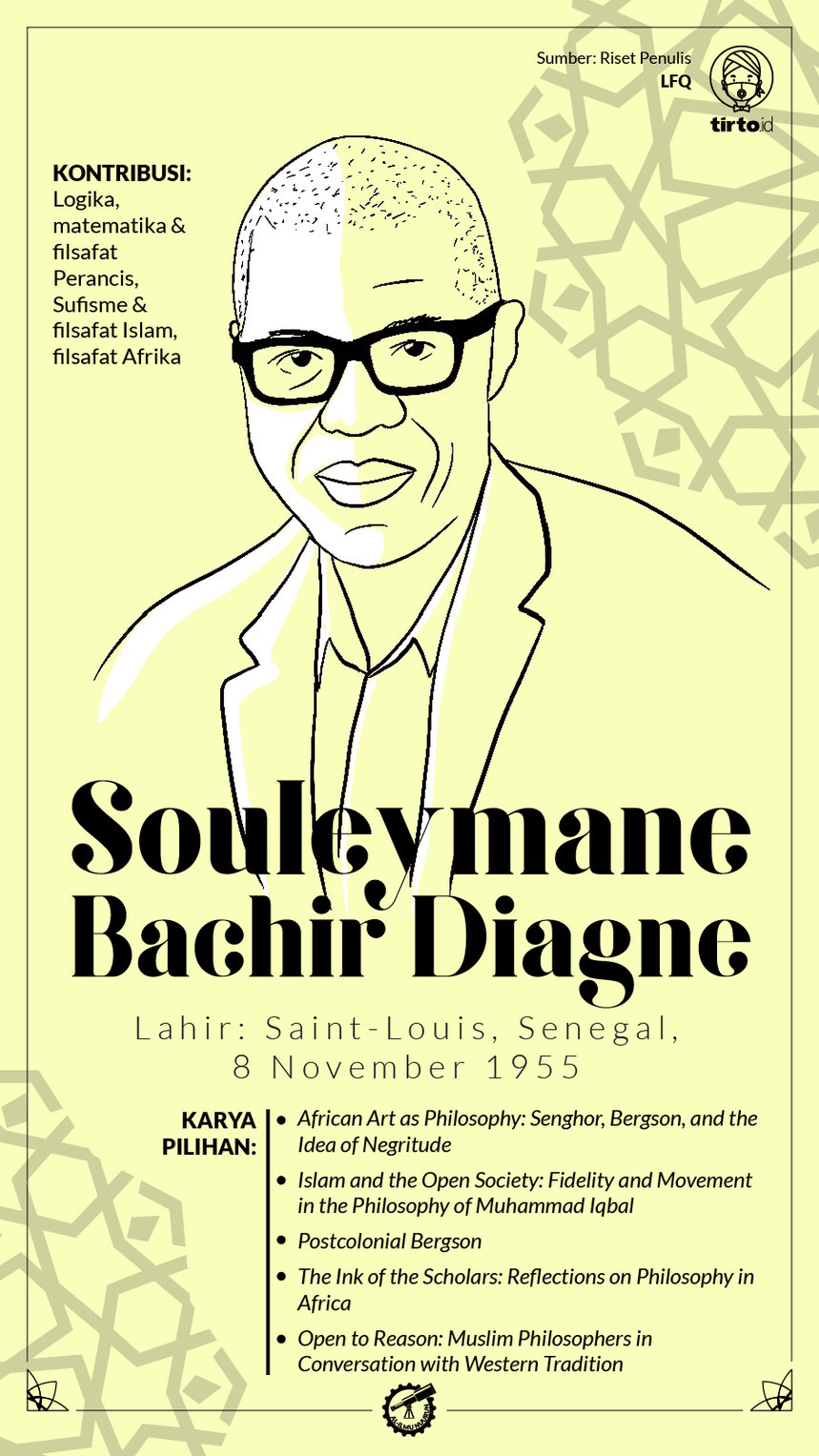
Saya melihat inovasi Diagne itu adalah sintesis kreatif guna memadukan semangat Islam-Asia (Iqbal) dan Katolik-Afrika (Senghor) sebagai solidaritas Asia-Afrika dalam konteks kemungkinan filsafat non-Barat. Diagne menyebutnya ‘the post-Bandung world’.
Diagne juga menggali kemungkinan narasi lain melalui konsep Emmanuel Levinas tentang philosophie de l’autre atau filsafat sang liyan. Keterkaitan Levinas dan dunia pascakolonial memang sangat erat. Filsuf Perancis ini mengaitkan filsafat, universalitas, dan kolonisasi, lalu menyebut dekolonisasi sebagai sejarah letusan massa Asia-Afrika dalam mengidentifikasi diri dari peradaban Barat yang berlandaskan Bibel dan tradisi Yunani.
Dalam kerangka pascakolonial itu, Diagne membuka kemungkinan tentang pluralisasi bahasa dan filsafat. Salah satu akibatnya ialah melihat pluralisasi sejarah masa lalu sehingga reduksi Barat atas transmisi pengetahuan harus diubah. Semula, kecenderungan umumnya ialah lintasan filsafat Yerusalem-Atena-Roma-Kristen-Barat, lalu ia harus dilihat melalui rute yang beragam. Misalnya, Yunani ke Damaskus, dan juga ke Baghdad-Nishapur-Cordoba atau Toledo, atau dari Maroko ke Timbuktu di Afrika Barat.
Terkait dengan hal itu, ia ikut mengkritik persepsi Afrika yang terbangun dari budaya lisan atau oral. Tentu saja, budaya lisan bukan sesuatu yang salah. Namun Diagne berargumen bahwa tradisi tulisan dan berfilsafat sangat kuat ketika Islam hadir di Timbuktu hingga setidaknya pada masa sarjana besar abad ke-16: Ahmad Babab al-Timbukti.
Tradisi intelektual masa lalu bagi Diagne penting diangkat. Khazanah manuskrip Timbuktu belakangan menjadi perhatian yang mencengangkan. Bersama rekannya, sejarawan Afrika Selatan Shamil Jeppie, Diagne berusaha merevitalisasi warisan masa lalu ini melalui élan vital filosofisnya. Ia membaca filsafat Perancis kontemporer untuk menghidupkan kembali apa yang tenggelam melalui semangat baru; bukan hanya untuk berfilsafat cara Islam dengan baik, tapi juga membangun solidaritas lintas budaya dan lintas agama. Abad ini mungkin kita akan menyaksikan kebangkitan Asia-Afrika dan Diagne menyumbang banyak di dalamnya.
==========
Redaksi Tirto kembali menampilkan rubrik khusus Ramadan "Al-Ilmu Nuurun". Tema tahun ini adalah para cendekiawan muslim global abad ke-20 dan ke-21. Kami memilih 33 tokoh untuk diulas pemikiran dan kontribusi mereka terhadap peradaban Islam kontemporer. Rubrik ini diampu kontributor Zacky Khairul Umam selama satu bulan penuh.
Zacky Khairul Umam adalah alumnus Program Studi Arab FIB UI dan kandidat doktor sejarah Islam di Freie Universität Berlin. Saat ini sedang menyelesaikan disertasi tentang pemikiran Islam di Madinah abad ke-17. Ia pernah bekerja sebagai peneliti tamu pada École française d'Extrême-Orient (EFEO) Jakarta 2019-2020.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id