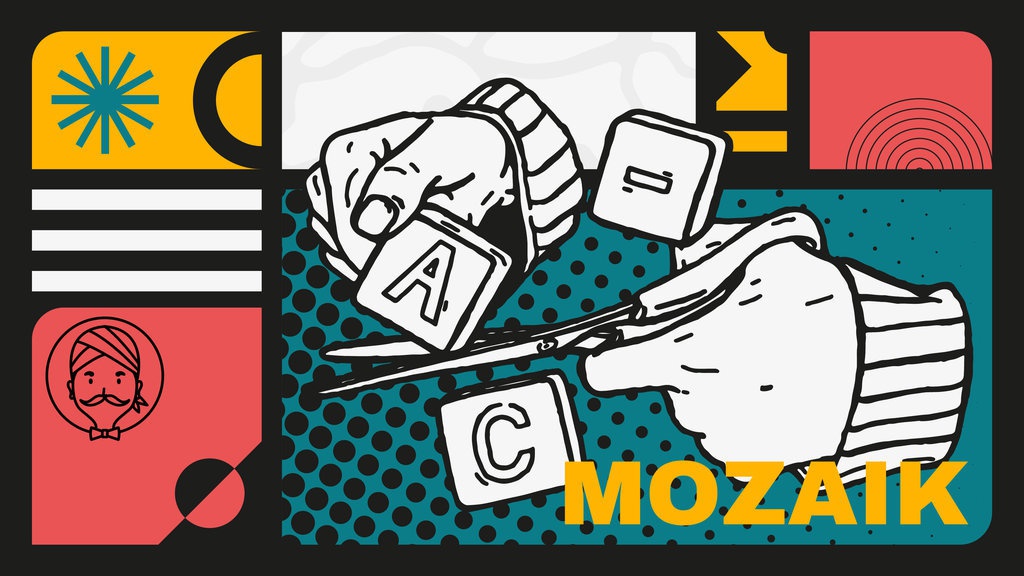tirto.id - Setiap akhir tahun akan ada satu kata yang frekuensi kemunculannya meningkat di media massa. Kata itu bukan "Natal" atau "Tahun Baru" yang memang dirayakan di penutup tahun, melainkan "Nataru", gabungan keduanya.
Tidak diketahui kapan persisnya "Nataru" mulai muncul dan dipopulerkan media. Tetapi setidaknya tujuh tahun lalu, tepatnya pada 11 Januari 2015, media daring metrobali.com sudah mengunggah berita dengan judul “Resmi Ditutup Posko NATARU 2015/2016 Di Bandara Ngurah Rai”.
Singkatan yang terdengar seperti kosakata bahasa Jepang itu seiring tahun makin populer. Kendati demikian, hingga dekade berganti, kata "Nataru" masih membuat dahi mengernyit setiap akhir tahun.
Penggunaan singkatan meningkat pesat selama Perang Dunia II (1939-1945) karena kebutuhan yang sangat tinggi dan mendesak untuk komunikasi dan penyandian dalam penyampaian pesan militer.
Menurut Tatum Derin dkk. dalam “Indonesians’ Tendency to Refer Abbreviation as Acronym: Types of Abbreviation as Word Formation Process” (PDF), kebutuhan menyingkat kata di masa perang pula yang melahirkan kata “akronim” pada 1943 dari sebuah pusat riset teknologi komunikasi ternama, Bell Labs.
Merujuk KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), akronim merupakan "singkatan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar".
Akronim-akronim terkenal yang lahir di pertengahan abad ke-20 dan tidak lagi diingat sebagai akronim, antara lain radar (radio detection and ranging), sonar (sound navigation ranging), laser (light amplification by stimulated emission of radiation), scuba (self-contained underwater breathing apparatus), dan rudal (peluru kendali).
Pada pertengahan abad ke-20 inilah Presiden Sukarno membanjiri bahasa Indonesia dengan akronim sebagai alat politiknya. Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat), berdikari (berdiri di atas kaki sendiri), atau Tavip (Tahun Vivere Pericoloso--tahun-tahun yang menyerempet bahaya) adalah sebagian kecil dari warisan bahasa Sukarno.
Akrobat bahasa Sukarno melalui penciptaan akronim tecermin dalam, misalnya, USDEK. Akronim ini merupakan kependekan dari Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.
Betapa kompleks gagasan yang termaktub dalam satu kata USDEK, mengingat masing-masing elemen pembentuknya pun ideologis. Dengan menciptakan satu kata USDEK, penutur tidak perlu bersusah-payah mengingat dan menerangkan kelima gagasan pembentuknya.

Menurut ahli linguistik George Kingsley Zipf, Law of Abbreviation merupakan sifat struktural bahasa, yang menyatakan bahwa semakin sering suatu kata digunakan, maka akan semakin pendek kata tersebut.
Law of Abbreviation merupakan upaya terbaik untuk memetakan bentuk-makna di bawah tekanan untuk berkomunikasi secara akurat namun tetap efisien. Zipf menyebutnya sebagai Principle of Least Effort--berkomunikasi dengan usaha minimal--yang berfungsi menyampaikan akurasi dan efisiensi sekaligus.
Orang Indonesia tampaknya paham betul hukum dan prinsip Zipf tersebut, baik untuk membuat komunikasi lebih efisien maupun untuk kelakar dan propaganda politik, yang berpotensi memunculkan makna kedua.
UUD (Undang-undang Dasar 1945) dan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) merupakan dasar konstitusi dan dasar hukum bagi para penegak hukum, acuan yang sakral dalam kehidupan hukum dan berkonstitusi bangsa Indonesia.
Namun, dalam ketidakpastian atas hukum yang murah dibeli, orang Indonesia menemukan kepanjangan yang tepat untuk menyatakan kefrustrasian itu secara jenaka tanpa harus berhadapan dengan pasal-pasal penghinaan, yakni UUD (Ujung-ujungnya Duit) dan KUHAP (Kasih Uang Habis Perkara).
Pemerintah tak jarang memanfaatkan akronim untuk melakukan praktik yang mengerikan dengan penciptaan kata baru yang terdengar biasa, namun berpotensi menafikan makna sesungguhnya. "Waskat" (pengawasan melekat) dan "petrus" (penembakan misterius) adalah dua kata yang populer di masa Orde Baru.
Siapa sangka bahwa “waskat” yang sama sekali tak terdengar seram merupakan tindakan preventif dan represif Orde Baru untuk mengawasi tokoh-tokoh yang mereka curigai. Demikian juga dengan "petrus" yang serupa nama salah satu murid Yesus, mengandung makna kejahatan kemanusiaan di masa rezim Soeharto.
Dalam hal ini, rupanya militer berperan sebagai markas besar akronim yang sangat produktif. Sejak tahun 1960-an, akronim merupakan bagian dari kurikulum yang diajarkan kepada para kadet di akademi-akademi militer.
Seturut catatan Soenjono Dardjowidjojo dalam “Acronymic Patterns in Indonesian” (Southeast Asian Linguistic Studies, 1979), pasca Peristiwa G30S 1965, akronim semakin banyak ditemukan di media massa seiring meningkatnya peran militer dalam kehidupan sipil dan pemerintahan.
John de Vries dalam “Indonesian abbreviations and acronyms” menyebutkan, kendati mulanya diproduksi oleh militer, popularitas akronim militer di kalangan sipil adalah hasil kerja jurnalisme. Artinya, para jurnalislah yang memaksakan penggunaan akronim-akronim tersebut kepada pembaca dan pemirsa.
Akronimisasi dalam bahasa Indonesia mencapai jumlah yang sangat mencengangkan dan membingungkan, terutama bagi penutur asing yang mempelajari bahasa Indonesia.
Menurut Russell Jones dalam “Acronyms in Bahasa Indonesia”, pada 1974 saja, Morzer Bruyns mencatat bahwa singkatan dan akronim dalam bahasa Indonesia sudah mencapai 27.000 lema, jumlah yang setara dengan seluruh lema pada suatu bahasa. Mochtar Lubis menyebutnya sebagai “penyakit” dalam jurnalistik.

Pembentukan akronim pun tidak selalu beraturan, bahkan bisa mencapai tingkat yang dapat diberi imbuhan pen-, di-, me-, dan kan- sehingga menjadi kata kerja atau kata benda baru.
Misalnya, memahmilubkan (menyidang melalui Mahkamah Militer Luar Biasa), dipetruskan (dibunuh pemerintah melalui penembakan misterius), atau pencekalan/mencekal (terkena operasi cegah dan tangkal oleh pemerintah sehingga tidak dapat melakukan kegiatan di Indonesia).
Kegilaan pada akronim menunjukkan bagaimana sikap orang Indonesia terhadap bahasanya. Selain sebagai pemersatu bangsa dalam arti sesungguhnya, bahasa Indonesia tidak dipandang sebagai alat tutur yang ajek, melainkan selalu berubah. Dinamika pembentukan akronim, baik yang gagal maupun berhasil, juga layak diingat.
Mahbub Djunaidi, tokoh pers yang aktif di era 1960-1980an dan dikenal sebagai kolumnis yang nakal dan jenaka bahkan tak luput dari kenakalan akronimisasi bahasa Indonesia.
Majalah Tempo edisi 12 Oktober 1974 mencatat bahwa dalam upaya pengindonesiaan istilah-istilah asing, Mahbub Djunaidi mengusulkan akronim “sarman” sebagai padanan kata untuk condom, yang merupakan kepanjangan dari “sarung mani”.
Tak lama berselang pada 2 November 1974, seorang pembaca mengirimkan protes atas usulan Mahbub dan mengusulkan kata lain sebagai padanan “kondom”.
“Mengapa tidak diganti saja dengan MAHBUB yang kalau dipanjangkan jadi Mani Adam Hanyut Bersama Usainya Ber…. saja?”
Demikian bunyi usulan pembaca tersebut, yang ternyata namanya Sarman.
Penulis: Uswatul Chabibah
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id