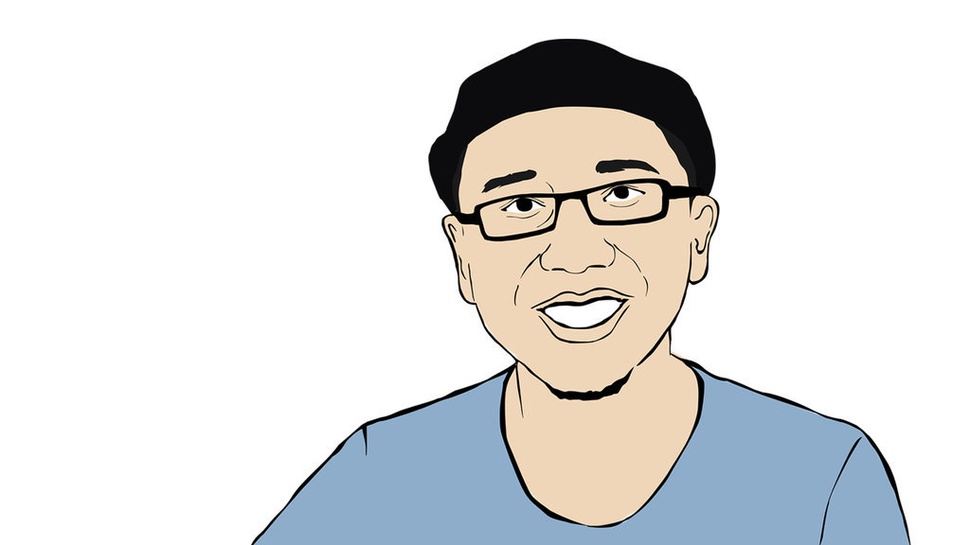tirto.id - Rabu siang, 6 Desember 2017, tak lama setiba di Sukajadi, kawasan utara Bandung, sebuah pesan WhatsApp diterima Wulan, bukan nama sebenarnya.
Isinya: terjadi perkelahian seorang warga di RW 11 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan. Wulan segera bergegas menuju tempat itu.
Lokasinya tiga meter dari Taman Film Bandung dan persis di belakang Balubur Town Square. Rencananya, Pemerintah Kota Bandung, melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Prasarana Sarana Utilitas, Pertanahan dan Pertamanan, akan membangun rumah deret di wilayah ini. Dan itu adalah implementasi dari program nasional Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang dicanangkan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Untuk itu, permukiman warga di sana bakal digusur. Warga ditawarkan tinggal di rumah susun di Rancacili. Nanti, setelah rumah deret selesai, warga diperbolehkan kembali dan tinggal secara gratis untuk lima tahun pertama. Untuk tahun keenam dan setelahnya, warga diwajibkan membayar sewa.
Sebagian besar warga menolak rencana tersebut. Mereka protes. Salah satunya mendatangi Balai Kota Bandung pada 26 Oktober 2017. Sejak itu Wulan dan beberapa koleganya turut bersama warga menghadapi sengketa.
Tapi, hingga kini, belum ada kesepakatan bulat antara Pemkot Bandung dan warga. Sementara mesin pengebor tanah telah beroperasi. Dan persis ketika Wulan tiba di RW 11 pada Rabu sore, 6 Desember, sebuah ekskavator bersiap mengeruk.
Wulan dan 100-an orang lain berusaha menghalangi ekskavator yang akan menggusur permukiman Tamansari.
Sabas, seorang warga di sana, mengatakan bahwa dari 90-an rumah di RW 11, dengan total 197 kepala keluarga, hanya ada 25 rumah yang setuju digusur. Itu pun uang ganti rugi yang dijanjikan Pemkot Bandung belum diterima. Selain itu, Dadan Ramdan Hardja dari Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat menyatakan setidaknya ada dua kejanggalan dalam proyek ini.
“Pertama, rencana ini bukan rencana bareng tetapi rencana sepihak. Tidak memenuhi asas partisipasi, asas keterbukaan informasi, dan administrasi publik. Kedua, di sini sudah ada praktik alat berat, pengeboran, tetapi Amdal-nya (analisis mengenai dampak lingkungan) belum ada, izin lingkungannya belum ada. Itu melanggar hukum lingkungan. Tidak sesuai dengan prinsip membangunnya Ridwan Kamil yang (mengklaim) kolaboratif,” ujar Dadan.
Guna membedah program Kotaku dan perkembangan kota Bandung termutakhir, Husein Abdulsalam dari Tirto mewawancarai Frans Ari Prasetyo, peneliti kelahiran Bandung yang meriset tentang perkembangan kota Bandung. Berikut petikan wawancaranya.
Sekarang muncul program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Apakah ini efektif?
Pemerintah menetapkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target nasional. Itu dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Disebutkan, salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) hektare. Penanganan pemukiman kumuh ini menyasar kota-kota besar di indonesia, termasuk Bandung.
Akibatnya, semua kota berlomba mendapatkan pengakuan untuk menjalankan program ini, karena secara politik nasional akan menunjukkan bahwa kotanya berhasil membangun, ditandai ada peningkatan di pelbagai macam indeks pembangunan.
Sebenarnya, program ini akan berjalan efektif jika semua perangkat menuju program ini sudah jelas dan tanpa polemik, terutama terkait lahan dan kriteria kumuh itu sendiri. Dan, tentu saja, dengan cara melakukan pelibatan langsung dan partisipasi aktif dari warga setempat, bukan relokasi tanpa syarat alias penggusuran.
Permasalahan utama adalah pencaplokan lahan oleh pemerintah atau investor terhadap kampung-kampung kota yang notabene permukiman padat dan banyak dihuni warga kelas ekonomi rendah dan banyak bekerja dalam sektor informal.
Siapa yang dikorbankan? Ya warga miskin kota. Karena warga miskin kota dianggap residu demografi dalam pembangunan.
Program Kotaku seolah berpihak pada warga dengan memberi jalan keluar dari kemiskinan perkotaan, dengan memberikan rumah melalui relokasi dan rusunisasi. Namun, ini hanyalah pelanggengan nilai budaya lama: kepemilikan rumah selalu dipromosikan, dilegitimasi, dan disubsidi oleh kebijakan negara. Ujungnya hanya untuk penguasaan lahan perkotaan, untuk dipertukarkan dengan kepemilikan lain yang lebih komersial. Tentu saja memperkuat argumen ekonomi seputar pentingnya kapitalisme atas lahan, sewa, dan spekulasi.
Ke arah mana pembangunan Kota Bandung?
Kota Bandung hendak berubah dengan bersolek, hanya saja terlalu menor. Kota ini ingin disulap menjadi episentrum bisnis, jasa, dan leisure di bawah bendera MP3EI & RPJMN sekaligus taklid menjalankan amanat city without slums, yang terimplementasi pada program Kota Tanpa Kumuh.
Bandung dan pemimpin kotanya jelas sekali memiliki kepentingan untuk menyukseskan dengan jargon yang tak kalah hebat: Kota Juara, Kota Smart dan Kreatif, hingga Kota Ramah HAM.
Namun, semua hanya kilau permukaan, yang ujung sebenarnya akumulasi kapital, gentrifikasi, dan segregasi masyarakat kota yang semakin tajam. Dana yang digelontorkan bukan hanya untuk membangun, tapi dana untuk menggusur. Penggusuran di Kota Bandung pun dikemas dengan nama: penggusuran partisipatoris, penggusuran humanis, hingga penggusuran yang ramah HAM.
Tentu, ada yang ajaib dengan frasa itu—tapi begitulah kejadiannya. Di kota ini penggusuran dianggap sesuatu yang wajar dan semua warga dianggap mafhum.
Pembangunan infrastruktur begitu masif siang-malam, tetapi indeks kesejahteraan warga tak juga dapat terungkit. Di lain pihak, profit dan modal yang deras menopangi agenda kultural dan ekonomi Kota Bandung
Di Bandung, ruang interaksi yang tersisa di kampung-kampung kota dipaksa lenyap. Diganti objek dan lanskap yang fotogenik, instagramable, swafoto layak unggah, sebagai barometer kebahagiaan warga Kota Bandung yang anomali terhadap realitas.
Masak iya rumah digusur bahagia? Masak iya kebanjiran bahagia? Masa iya nongkrong di taman kota lalu digebuk militer bahagia? Masak iya maraknya geng motor itu tanda kota aman dan masyarakat yang bahagia?
Maka, sebagian warga yang tidak rela ruang hidupnya diobrak-abrik oleh kekuasaan dan modal, saling bersolidaritas membentuk forum-forum akar rumput yang otonom, egaliter, demokratis, non-hierarkis, musyawarah mufakat, yang tentu saja sangat partisipatoris, bukan sekadar pseudo-partisipatoris seperti yang selama ini diagungkan Pemkot Bandung.
Ada frasa ‘Membangun tanpa Menggusur’, apakah mungkin?
Mungkin dilakukan jika konsepnya revitalisasi, bukan relokasi, apalagi dengan cara menggusur paksa. Skemanya: peran aktif warga secara partisipatoris untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya, keluarga, dan warga tempatan sebagai bagian dari memori kolektif bersama tentang ruang hidup, akses hidup, dan jaringan sosial. Pemerintah menjadi fasilitator untuk revitalisasi ini, sesuai amanat undang-undang yang harus menyediakan pemukiman layak.
Tetapi, seperti yang saya utarakan sebelumnya, apa ada pemerintah yang mau melakukan ini terutama dalam konteks Bandung? Ada lahan bernilai tinggi yang diperebutkan di sini. Maka, penggusuran, pencaplokan lahan, dan skema relokasi terutama terhadap warga miskin kota menjadi hal lebih mudah dan cepat untuk mengapitalisasi lahan tersebut daripada revitalisasi yang memakan waktu dan tidak memberikan distribusi dan agregasi penaikan nilai lahan bagi kepentingan modal dan pemerintah.
Meski revitalisasi sebagai upaya untuk menciptakan kembali ruang yang lebih demokratis di kota yang telah dibangun kembali secara partisipatif tidak pernah benar-benar terjadi, tetapi ini adalah montase yang tetap menarik sebagai bagian dari politik ruang, lahan, dan pemukiman perkotaan.
Jika merujuk Bandung karena sudah kadung akan dan sudah terjadi penggusuran, maka dibumbuilah dengan istilah “penggusuran humanis”—yang ditandai seremonial “tumpengan” dan doa bersama, termasuk memberikan uang “kerohiman” yang tak ada dalam skema anggaran apa pun.
Itu terjadi di Kampung Kolase. Kampung itu sekarang tinggal nama, digantikan oleh taman cantik bernama Teras Cikapundung. Warganya dipindahkan ke rusun.
Beberapa warga kota yang digusur dipindah ke rusun (Kasus Bukit Duri Jakarta, Kampung Kolase Bandung), apakah tepat?
Saya rasa itu tidak tepat. Ini seperti skenario land grabbing dalam konteks perkotaan, didorong oleh pemerintah untuk kepentingan investor, secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya ya itu: Kampung Kolase.
Tahun 2015, Pemkot Bandung bersama Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citarum melakukan program penataan wilayah Sungai Cikapundung, kemudian diejawantahkan dalam program pembangunan fasilitas umum berupa taman kota bernama Teras Cikapundung. Secara politik, ruang taman ini menunjukkan estetika kota modern yang diusung oleh pemimpin kota.
Sebelum penggusuran, warga diberi stigma sebagai warga ilegal, hunian kumuh, dan berada di wilayah sepadan sungai. Padahal, warga telah menempati lahan ini sejak awal 1970-an. Mereka merasa punya hak karena membayar pajak tanah kepada pemerintah hingga saat itu. Jadi, tidak bisa dikatakan tidak memiliki properti lahan sama sekali. Warga juga memiliki identitas resmi dan memiliki hak politik dalam pemilu yang teregistrasi.
Akhirnya, terdapat 39 KK yang digusur secara paksa untuk dipindahkan ke rusunawa Sadang Serang yang berjarak ± 4 km dari tempat semula. Warga mesti menyewa hunian di rusunawa. Mereka tidak dapat ganti rugi hak properti yang mereka miliki sebelumnya.
Ada 5 KK yang menolak karena mereka menilai hak properti lebih besar dari sekadar menerima rusunawa. Mereka tidak mendapatkan apa pun, dan hingga sekarang mengontrak di areal yang tidak jauh dari Kampung Kolase.
Tidak dipungkiri, terdapat hunian warga lain yang dinilai kurang layak. Sebenarnya, itu dapat direvitalisasi tanpa harus dipindahkan.
Kehidupan warga yang menerima rusunawa ini tak jauh lebih baik dari sebelumnya. Mau sejahtera gimana? Sekarang mereka harus sewa, padahal sebelumnya tidak. Sekarang akses tempat usaha atau kerja menjadi jauh. Intinya, ada ongkos yang menjadi beban hidup yang bertambah dari tempat semula.
Nah, di sisi lain, ada lahan lain yang lokasinya bertetangga dan sehamparan dengan Kampung Kolase yang bersertifikat. Pertanyaannya, kenapa bisa bersertifikat sedangkan Kampung Kolase tidak?
Selain itu, masih ada satu hamparan lahan lain yang sudah dibeli swasta untuk dibangun apartemen/hotel. Namun, karena tidak memiliki akses jalan, dan untuk harga akses jalan ini sangat mahal, melalui penghilangan Kampung Kolase, Pemkot Bandung seakan membentuk lanskap baru yang memberikan akses jalan gratis kepada swasta dengan kemasan infrastruktur publik. Namanya Teras Cikapundung itu.
Terlihat bagaimana warga kampung kota tidak memiliki hak atas lahan. Juga bagaimana pemerintah lebih menguntungkan pihak pemodal/swasta. Akhirnya, kampung ini hanya tinggal nama.
Kita bisa ambil contoh lagi: warga Kiaracondong yang digusur pada 2016. Janjinya, Ridwan Kamil akan membuat rusunami dan rusunawa, tetapi warga menolak relokasi dan penggusuran paksa pun terjadi. Lalu apa yang terjadi setelah lahan seluas 13 ha tersebut dibiarkan kosong dan warga lupa?
Tiba-tiba, November 2017, di lahan itu ada peresmian pembuatan Taman Asia-Afrika seluas 2,6 ha yang luasan sisanya akan dibangun zona ekonomi komersial berupa hunian alias apartemen. Jadi taman ini untuk siapa ? Taman ini milik publik atau privat ? Lalu, apa kabar warga yang digusur dan rencana rusunami atau rusunawa untuk mereka ? Apakah ini yang dimaksud membangun tanpa menggusur?
Setidaknya ada tiga tempat di Bandung (Kebon Jeruk, Dago Elos, dan Tamansari) tengah menghadapi ancaman penggusuran. Dan Bandung—demikian orang sering berkata—dikenalsalah satu destinasi wisata dan "kota kreatif." Dari segi ekonomi-politik, apakah ada kaitan antara keduanya?
Sederhananya, secara historis, Bandung dibentuk untuk kepentingan kolonial dan aktivitas jasa, serta leisure yang amat terkait dengan turisme. Salah satu bonus yang dipunyai Bandung dari zaman kolonial adalah bentuk arsitektur bangunan.
Dalam perkembangannya, Bandung mengalami perubahan sangat besar dari segi infrastruktur kota dan pengaturan skema sosial kewargaan. Salah satu faktor terbesarnya: sejak terkoneksinya Bandung dengan Jakarta, pusat ibu kota Indonesia, pada 2004. Urbanisasi yang pesat, migrasi, serta mobilitas orang dan modal membuat daya dukung kota berkurang cepat secara signifikan, terutama terkait kepadatan penduduk dan permukiman.
Dalam konteks Bandung, akhirnya, relasi ekonomi-politik perkotaan terajut sempurna, apalagi dengan kemasan baru bernama "Kota Kreatif" pada awal 2000-an. Konsep ini menjadi booming di Indonesia. Sejumlah kota besar di Indonesia mencoba menerapkan konsep tersebut. Bandung adalah salah satunya, dan konsep ini terangkat semakin masif ketika Ridwan kamil menjabat Wali Kota Bandung dalam empat tahun terakhir.
Dalam formasi 'kota kreatif', hubungan timbal balik antara faktor ekonomi dan politik dilakukan dengan mengonstruksi susunan ruang-ruang kerja politik perkotaan dan aktivitas ekonomi kreatif.
Namun, menurut saya, apa yang terjadi di Bandung melebihi itu semua. Di kota ini, seperti yang terjadi, adalah politik spasial (spatial politic), kontestasi perkotaan, serta imajinasi politik dan ruang perkotaan. Maka, akan sangat naif jika apa yang terjadi di Kebon Jeruk, Dago Elos, dan Tamansari bila tak dikaitkan dengan identitas 'kota kreatif' Bandung. Kita bisa periksa, secara geografis, lokasi ketiganya sangat strategis untuk nilai kapitalisasi lahan atau hunian.
Apa yang paling kentara dari proses perubahan ruang hidup Kota Bandung?
Tentu saja, dalam relasi ekonomi-politik ini, adalah penguasaan dan distribusi lahan perkotaan. Upaya perubahan status lahan dan hunian akan dengan cepat terjadi atas permintaan pasar kelas tertentu. Dan, warga miskin kota akan sangat mudah tersingkir karena lemah daya tawar politik, ekonomi, dan geografis.
Skema penggantian ini salah satunya melalui penggusuran. Gentrifikasi, ghetonisasi, dan segregasi tidak bisa dihindarkan, bahkan semakin besar dan tajam memengaruhi semua sendi kehidupan warga kota.
Kita harus melihat kota sebagai lokasi produksi urbanisasi. Alih-alih melihat setiap pabrik, sekolah atau kantor berbeda, kita harus melihat keseluruhan kota sebagai mesin pabrik yang menghasilkan kehidupan sehari-hari di kota dan kontestasinya. Karena itu kita harus mengatur perlawanan pada skala kota jika memang hak atas kota terancam terampas.
Apakah ini berlaku pada kota-kota lain, misalnya Jakarta atau Surabaya?
Tentu saja, tapi dalam formasi berbeda karena secara historis dan kultur pun berbeda. Tapi proses gentrifikasi melalui skema penggusuran warga miskin kota berlaku sama di keduanya. Kita ingat apa yang terjadi di Bukit Duri (Jakarta) dan di Strenkali (Surabaya). Semua punya motif yang sama terkait pengaturan ruang perkotaan kontemporer dan gagasan regresif tentang ruang estetika yang terkandung dalam neo-ekspresionisme, terkandung dalam skema 'kota kreatif.'
Sempat muncul kritik kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil bahwa pembangunan di masanya penuh ‘gimmick’. Dalam konteks pembangunan kota, apa sih yang disebut gimmick?
Kata “gimmick” ini muncul karena ada sejumlah hal yang ditutupi oleh hal-hal yang bersifat permukaan atau artifisial. Sangat wajar jika itu disematkan dalam kepemimpinan Ridwan Kamil. Bisa dilihat, pembangunan kota hanya di arena permukaan; semua serba artifisial, bukan substansial, dan alpa terhadap skala prioritas warga.
Misalnya, banyak pembangunan yang tidak merujuk kepada RPJMD atau tertib RTRW/RDTR, termasuk tertib birokrasi, transparan terkait anggaran, dan data pembangunan. Padahal kota ini mendapatkan banyak penghargaan atas itu semua.
Memang, ada informasi yang dibagikan kepada publik tetapi tidak semua juga diberikan kepada publik. Padahal, sesuai undang-undang, itu sudah seharusnya menjadi kewajiban pemerintah agar tidak ada sengketa informasi. Pembangunan seharusnya tidak lagi menciptakan lanskap akumulasi modal dan pembersihan kelas yang masif dan modernis, tetapi yang berjalan melalui narasi kewargaan, berskala kecil, dan tidak mencolok.
Apa konsekuensi bagi masyarakat jika pembangunan mengarah kepada ‘gimmick’?
Akan sangat terkait dengan good governance: akuntabilitas, transparansi, ketertiban birokrasi, dan pelayanan publik, termasuk kepercayaan publik, akan dipertaruhkan dari hasil-hasil pembangunan yang dicapai kota ini.
Saya pikir publik kota ini sudah smart dalam menilai kotanya dan pemimpinnya. Dengan membangun kota, infrastruktur, dan perumahan, kelebihan modal akan diserap, tetapi siapa yang menyerapnya?
Di pelbagai tempatmuncul resistensi terhadap kebijakan pemkot, bagaimana peran warga dalam perkembangan suatu kota?
Resistensi, saya pikir, sangat wajar karena menyangkut aset dan akses hidup serta ruang hidup komunal yang dirampas kekuasaan kota.
Kita perlu fokus pada produksi kota, bukan hanya konsumsi di dalam diri mereka, untuk memahami dinamika kapitalisme kontemporer dan melihat perlawanan oleh proses ini. Misalnya, kita perlu membangun jembatan antara kelas pekerja tradisional dan gerakan perkotaan; keduanya saling terkait dan selalu terjalin untuk menunjukkan potensi revolusioner gerakan perkotaan yang memiliki tuntutan reformis (seperti hak atas perumahan dan layanan publik).
Kota-kota dapat direorganisasi dengan cara lebih adil secara sosial dan ekologis. Mereka dapat menjadi berfokus pada perlawanan terhadap kerja kapitalis dan memperjuangkan hak atas kota. Gerakan konservasi kota, salah satunya melalui resistensi, dapat digambarkan sebagai pembantu mengatasi gentrifikasi akhir-akhir ini.
Melalui itu, peran warga coba diaktivasi kembali secara partisipatoris. Itu untuk menyiasati pembangunan yang menihilkan peran warga, terutama terkait isu lahan dan hunian.
Dalam pembangunan kota, pelibatan masyarakat, terutama masyarakat rentan perkotaan, menjadi sangat penting karena perubahan di kota sangat berdampak bagi kehidupan mereka secara langsung. Pasalnya, mereka banyak di sektor informal, baik secara hunian maupun pekerjaan dan pendapatan.
Ketika ada resistensi, kerap ditemui represi aparat. Apa pantas Bandung disebut 'Kota Ramah HAM'?
Saya pikir tidak. Bagaimana bisa kota yang mengklaim sebagai 'kota ramah HAM' di depan publik dunia, dalam Konferensi Asia-Afrika 2015, nyatanya memperlakukan warga jauh dari ramah HAM?
Nyatanya, perwujudan Bandung sebagai 'kota ramah HAM' tidak ditopang skema regulasi yang mendorong upaya ke arah sana. Tidak ada peraturan daerah yang menaungi payung hukum dari klaim 'kota ramah HAM' tersebut. Itu menjadi salah satu indikator awal bahwa ada imajinasi gelar kota HAM untuk Bandung hanya utopia.
Kegagalan pemerintah Kota Bandung dalam merespons hal yang telah diklaim dalam perayaan KAA ke-60 itu sebagai 'kota ramah HAM' pun terlihat. Dari aktivitas penggusuran atau relokasi terhadap pedagang kaki lima, yang tengah berusaha bertahan hidup mandiri dalam mendapatkan hak atas akses ekonomi di kota Bandung.
Hal sama terhadap kampung kota: hilangnya Kampung Kolase sebagai hak warga kota menjadi tanda Kota Bandung tidak bisa ramah terhadap penduduk kotanya, terutama penduduk marjinal yang dikategorikan sebagai warga miskin kota.
Alih-alih memberdayakan warga miskin kota berdasarkan haknya sebagai warga kota dengan predikat HAM, malah penguasa kota mengalienasi dengan dalih dan upaya pembangunan kota. Tidak salah, memang, tetapi memanusiakan manusia merupakan hal paling substantif dalam penegakan HAM di kota.
Maka, Bandung perlu pembenahan birokrasi dan penyusunan regulasi kota melalui Perda, yang akan mendorong upaya menuju 'kota ramah HAM', yang diimpikannya itu. Regulasi ini akan menjamin bahwa penduduk kota berhak atas kotanya dan dilindungi hak asasi manusianya sesuai ketentuan hukum, termasuk hukuman terhadap yang melanggarnya.
HAM harus bekerja sebagai pembangunan dasar atas hak kota, bukan sebagai pembangunan dasar atas HAM (Hotel, Apartemen, dan Mal) yang merenggut HAM (Hak Asasi Manusia) yang sebenarnya.
Di Kebon Jeruk, warga berhadapan dengan PT KAI. Di Dago Elos, warga berhadapan dengan sekelompok individu lain. Bisa dibilang keduanya berhadapan dengan pihak swasta/privat. Bagaimana peran yang seharusnya Pemkot Bandung ambil terkait kedua kasus ini?
Merujuk Undang-Udang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dalam pasal 2 menyebutkan, "Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ... merupakan kekayaan nasional." Ini diturunkan dari UUD 1945 pasal 33 yang menyebut: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Lebih fokus lagi dalam UUPA pasal 9 menyatakan, Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya."
Jika merunut kepada objek yang dipersengketakan, yaitu lahan dan ruang hidup warga, hendaknya Pemkot Bandung mendukung dan melindungi warga, terutama warga miskin kota karena itu diamanatkan dalam undang-undang.
Pemkot Bandung harus menjadi perpanjangan tangan warga miskin kota untuk mendapatkan haknya atas kota, termasuk hak atas aset dan akses lahan yang telah lama ditempatinya sepanjang itu tidak melanggar hukum.
Dari sini, kita bisa mengambil kesimpulan, pemerintah harus memberikan kesempatan kepada warga untuk mendapatkan akses lahan/tanah. Misalnya, dalam bentuk kepemilikan sah yang dilindungi hukum dengan mempertimbangkan faktor secara sosial. Mensyaratkan tujuan bahwa rumah ini terutama untuk warga miskin kota, bukan malah melakukan pencaplokan lahan dengan mengusir warga miskin kota untuk memberikan kesempatan kuasa lain seperti investor.
==========
Wawancara ini direspons oleh Pemkot Bandung dengan hak jawab, dianggap “tidak berimbang” karena tidak ada porsi pernyataan dari Pemkot Bandung. Hak jawab secara lengkap bisa baca DI SINI.
Penulis: Husein Abdulsalam
Editor: Fahri Salam