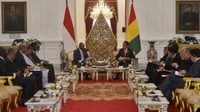tirto.id - Musim semi rakyat akhirnya datang ke Sudan. Sejak Desember 2018 ribuan warga memenuhi jalanan Ibukota Khartoum untuk menuntut turunnya rezim pemerintahan Umar al-Bashir yang telah berkuasa sejak 1989.
Al-Bashir keliru mengelola ekonomi negara. Sudan jatuh ke jurang inflasi yang parah, berlanjut pada kelangkaan pangan, terutama roti, yang harganya naik hingga dua kali lipat.
Massa juga turun ke jalanan Kota Arbara (Negara Bagian River Nile), Dinder (Negara Bagian Sennar) & Port Sudan (Negara Bagian Laut Merah). Dalam salah satu aksi terpenting, ratusan orang bergerak menuju istana presiden di ibukota, namun dihadang oleh gas air mata dan represi aparat.
Tapi demonstrasi bukan urusan perut semata. Bashir mengendalikan Sudan lewat rezim otoritarian yang korup. Oleh sebab itu massa aksi meneriakkan slogan-slogan menuntut transparansi pemerintahan, kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, protes atas wabah kemiskinan, juga pengangguran yang luas.
Bashir berkelit. Mengutip CNN World, mula-mula ia mengatakan tidak akan mengundurkan diri sebab tahun depan akan ada pemilihan presiden. Ia kemudian mengklaim bahwa demonstrasi dipicu infiltrasi pihak-pihak yang ingin mengganggu kestabilan dalam negeri Sudan.
Pria berusia 75 tahun itu kemudian menanggapi gelombang protes dengan gebukan yang lebih keras. Aparat keamanan memburu massa aksi untuk ditangkap, dipukuli, atau kombinasi keduanya. Per Jumat (25/01/2019) kemarin korban yang meninggal menurut pemerintah adalah 26 orang, sementara versi oposisi mencapai 40 orang.
Bashir seakan sedang menutupi fakta bahwa problem berasal dari model kepemimpinannya sendiri. Para pengamat juga menilai latar belakang militeris Al-Bashir dan kongsinya dengan golongan Islamis adalah dua hal pokok yang membuat Sudan porak-poranda.
Bashir masuk ke barisan ketentaraan Sudan pada 1960. Ia juga belajar di Akademi Militer Mesir dan merampungkan studinya di Akademi Militer Sudan pada 1966. Kariernya melesat, hingga ia menduduki jabatan sebagai kolonel pada akhir dekade 1980-an.
Di masa itu pula, tepatnya pada 30 Juni 1989, Bashir memimpin kudeta militer terhadap pemerintahan koalisi Perdana Menteri Sadiq al-Mahdi yang sedang goyah. Al-Mahdi adalah politisi dari kalangan sipil yang sebelumnya terpilih secara demokratis.
Kudeta tidak hanya melibatkan militer, tapi juga kaum Islamis yang dipimpin Hassan Al-Turabi. Kongsi keduanya memancing konflik berkepanjangan di tengah masyarakat Sudan yang multi-etnis, agama, dan budaya.
Milton Viorst pernah menyinggung problem keragaman multi-dimensi Sudan dalam analisis di kanal Foreign Affairs. Sudan adalah negara yang dihuni oleh hampir 40 juta orang dan 100 bahasa. Mereka terbagi dalam faksi-faksi berbasis kesukuan. Tapi yang paling panas adalah perseteruan wilayah Utara dan Selatan.
Orang-orang di Utara mayoritas Arab-Muslim, sementara di Selatan didominasi warga keturunan orang kulit hitam Afrika yang beragama Kristen. Alih-alih membentuk negara sekuler untuk meredam ketegangan politik identitas, duo Bashir dan Turabi justru menyulap Sudan sebagai negara Islam.
Turabi kerap didaulat sebagai salah satu figur paling berpengaruh dalam politik modern Sudan. Ia berperan penting dalam melembagakan aturan-aturan syariah di Sudan pasca-kudeta 1989.
Ia memimpin National Islamic Front (NIF), gerakan politik yang tidak menjangkau suara banyak tapi punya daya tawar kuat di tataran elite.
Eksperimen negara Islam dianggap Turabi sebagai jalan agar Sudan punya identitas serta arah yang jelas. Tapi buahnya adalah rangkaian kontroversi, seperti pembentukan polisi negara NIF yang punya kaitan dengan milisi NIF.
Keduanya ditujukan untuk mencegah pemberontakan rakyat. Namun mereka, terutama milisi NIF, dilaporkan melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia. Ada eksekusi sewenang-wenang, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, hingga pembatasan kebebasan berbicara, berkumpul, dan menjalankan keyakinan.
Dalam analisis bertajuk Sudan and the Unbearable Lightness of Islamism: From Revolution to Rentier Authoritarianism (2017), Giorgio Musso menyebutkan bahwa aliansi militer-Islamis dan deklarasi Sudan sebagai negara Islam memang jalan pintas yang sengaja ditempuh Bashir untuk berkuasa.
Milton Viorst mencatat pertentangan Utara dan Selatan tidak hanya soal agama, tapi juga kebudayaan. Warga di Sudan Selatan, yang kenyang diskriminasi elite di Utara, pada akhirnya merasa sedang mempertahankan budaya aslinya dari Islamisasi dan Arabisasi yang digenjot pemerintahan Bashir dan Turabi.
Saat rencana mendirikan sistem federal gagal, warga di Selatan mencari alternatif lain. Sejak 1983 Tentara Pembebasan Rakyat Sudan selatan (SPLA) mendesak agar Sudan menerapkan demokrasi yang sepenuhnya sekuler. Mereka juga menuntut penentuan nasib sendiri (self-determination).
Perang sipil kedua di Sudan pecah dan menjadi salah satu yang terlama sepanjang sejarah. Dua juta orang mati akibat perang, kelaparan masal, juga wabah penyakit. Sudan memang sudah rusak oleh perang sebelum era Bashir. Bashir tidak meredakannya, tapi memanaskannya secara sistematis.
Laporan Muhammed Osman dan Max Bearak untuk Washington Post menyebut rezim Bashir mengeksploitasi pemisahan rasial di Sudan. Saat generasi muda lelah dengan strategi tersebut, mereka balik melawan rezim. Solidaritas lintas-etnis terbangun karena satu suara: jatuhnya Bashir.
“Itu (pemisahan rasial) tidak lagi bekerja. Mereka boleh memisahkan kami di masa lampau. Itu bekerja dengan baik untuk orang tua kami dan kakek nenek kami. Tapi tidak untuk kami, generasi baru. Kami sedang melawan mereka,” kata salah seorang demonstran kepada Osman.

“Kami ingin negara bebas dari rasisme. Kami sudah tidak bisa lagi mentolerir pembunuhan di mana-mana lalu tetap diam,” kata seorang demonstran lain, Khalid Siddiq, yang dengan semangat meneriakkan slogan “kebebasan, perdamaian, keadilan”.
Perlawanan terhadap Bashir tidaklah mudah. Bagi sebagian orang Bashir memenuhi definisi sebagai diktator era modern—jenis diktator yang masih mengadakan pemilu tapi mencuranginya melulu agar bisa berkuasa selama mungkin. Bashir melakukan ini, sehingga pemilu di eranya selalu berakhir dengan keributan.
Pemilu 2010 dan 2015, misalnya, dimenangkan Bashir dengan jumlah pemilih yang rendah. Middle East Eye melaporkan keduanya diwarnai dengan aksi boikot dari partai oposisi dan kecaman dari para pemantau pemilu internasional.
Selain represi terhadap demonstran, Bashir menanggapi musim semi rakyat Sudan dengan mengetatkan sensor media massa, menangkapi jurnalis, dan memberangus surat kabar yang memberitakan demonstrasi. Akses ke media sosial baik Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp diblok, yang oleh orang-orang disiasati dengan mengunduh VPN.
Bashir sebenarnya telah kalah pada 2011, ketika hasil referendum menyatakan Sudan Selatan lepas menjadi republik mandiri. BBC World mencatat dari situlah ekonomi Sudan mulai menderita karena Sudan kehilangan tiga perempat minyaknya yang terletak di Sudan Selatan.
Minyak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar Sudan. Kehilangan minyaklah yang membuat inflasi makin parah serta kelangkaan pangan makin sering terjadi. Seiring tumbuhnya aktivisme para pemuda Sudan, kondisi tidak disia-siakan kelompok oposisi untuk menggoyang rezim Bashir.
Kalah di Selatan, Bashir mengamuk di Barat. Lebih tepatnya di wilayah Darfur. Lagi-lagi, pangkal persoalannya adalah isu rasisme dan agama.
Pada Februari 2003 muncul dua kelompok pemberontak Tentara Pembebasan Sudan (SLA) dan Gerakan Keadilan dan Kesetaraan (JEM).
Mayoritas anggotanya berasal dari kalangan petani yang memprotes ketidakadilan di bawah pemerintah Sudan yang didominasi orang-orang Arab. Bashir, dengan mental militerismenya, merespon dengan lebih buas.
Jika para pemberontak dibiarkan, Sudan akan kehilangan teritorinya (lagi), demikian argumen Bashir. Ia kemudian menyokong milisi Arab bernama Janjaweed dengan senjata dan peralatan komunikasi intelijen militer Sudan, lalu menugaskan mereka untuk menciptakan neraka di Darfur.
Vox melaporkan Tentara Sudan memberikan dukungan lewat serangan udara. Helikopter tempur dan pesawat pembom menarget pemukiman sipil. Beberapa jam setelah operasi militer selesai, giliran Janjaweed menyisir desa-desa miskin. Mereka memperkosa, membunuh, memutilasi, dan mengusir penduduk lokal.
Hasil panen penduduk dijarah atau dihancurkan. Pasokan air sengaja dicemari mayat. Rantai pasokan air dan makanan diputus. Etnis seperti Fur, Marsalit, dan Zaghawa dibabat habis akibat dianggap mendukung para pemberontak.
Dalam kurun waktu lima tahun, diperkirakan lebih dari 200.000 orang meninggal karena penyakit, kelaparan dan kekerasan konflik di Darfur. Sekitar 2,5 juta orang terpaksa mengungsi dari kampung halamannya.
Bashir secara konsisten menyangkal hubungannya dengan Janjaweed. Namun ia tetap ditetapkan sebagai penjahat perang oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dengan tuduhan sebagai dalang genosida di Darfur.
Musa Hilal, pemimpin Janjaweed yang paling dihormati, sudah ditangkap pada November 2017. Ia tengah menjalani pengadilan militer. Tapi tidak demikian dengan Bashir, yang masih duduk manis di kursi kepresidenan, sembari menutup kuping terhadap aspirasi rakyatnya.
Massa anti-Bashir masih bertahan di Khartoum dan di kota-kota lain. Mereka tidak lupa dengan kegilaan Bashir di Darfur. Mereka meneriakkan banyak slogan. Salah satunya bernada sinis sekaligus pedas:
“Hei, dasar kau rasis yang sombong, kita semua adalah Darfur!”
Editor: Windu Jusuf