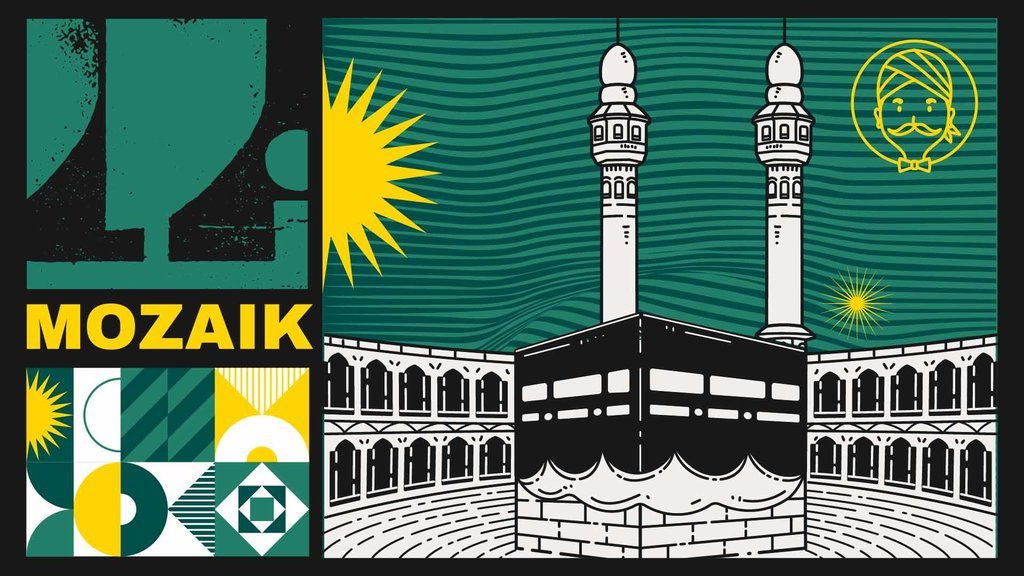tirto.id - Pada 20 November 1979 yang juga bertepatan dengan 1 Muharam 1400 alias hari pertama tahun baru Islam dan juga sekaligus abad baru, ratusan pria dan wanita berkumpul di Masjidil Haram, salah satu tempat tersuci dalam dunia Islam sekaligus tempat di mana Kabah, patokan arah beribadah kaum Muslim, berada.
Ratusan muslim tersebut bukan datang untuk beribadah, tetapi mereka memiliki maksud lain. "Sekelompok Muslim yang diduga berasal dari Iran tersebut berkumpul untuk merebut Masjidil Haram," ungkap Philip Taubman dalam reportasenya untuk The New York Times.
Layaknya orang-orang Prancis yang merebut penjara (Bastille) di tahun 1790 atau orang-orang Rusia yang mengepung gedung parlemen (Duma) pada 1917, gerombolan muslim tersebut juga berniat memulai revolusi. Tujuan utama aksi mereka adalah demi menggulingkan penguasa yang berkuasa atas Masjidil Haram.
Tutur M. E. McMillan dalam From the First World War to the Arab Spring (2016) disebutkan bahwa kelompok Muslim yang diketuai oleh ulama kharismatik bernama Juhayman ibn Muhammad al-Utaybi dan iparnya, Muhammad ibn Abdullah al-Qahtani, tersebut melakukan revolusi untuk menggulingkan Kerajaan Arab Saudi.
Arab Saudi dianggap menodai kesucian nilai-nilai keislaman serta tak sungguh-sungguh menengakkan syariat di wilayah kekuasaannya, yang kebetulan merupakan tempat kelahiran Islam.
Suatu alasan yang dipikir McMillan aneh. Hal ini karena Arab Saudi seakan lupa tentang bagaimana kerajaan yang dinamai sesuai dengan nama keluarga yang mendirikannya, al-Saud (ibn Saud), mampu berkuasa di atas tanah tersuci dunia Islam.
Cikal Bakal Dinasti Arab Saudi
Berdiri pada 1932, cikal-bakal Kerajaan Arab Saudi bermuara pada sebuah sub-suku Arab yang bernama Dirriya. Suku tersebut mendiami oasis kecil di tengah-tengah Jazirah Arab yang eksis sejak 1744.
Dipimpin Muhammad ibn Saud, "The House of Saud," Dirriya hanyalah sub-suku kecil, yang tak memiliki pengaruh apapun--kala itu, bahkan acap-kali menerima hardikan dari sub-suku Arab lain yang lebih besar dan lebih berkuasa di Timur Tengah.
Pada periode kepemimpinan tersbut muncul ulama eksentrik, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, yang berupaya mengembalikan kemurnian Islam.
Dirinya menganggap ajaran Islam kala itu, pasca ditinggalkan Nabi Muhammad, dinodai oleh "inovasi-inovasi" tak jelas, tak sesuai dengan syariat alias "bid'ah". Oleh karena itu, ia berhasyarat untuk menghancurkan segala praktek tersebut untuk mengembalikan Islam pada fitrahnya, Quran dan Hadist. Ajaran atau keyakinan tersebut, pada kemudian hari dikenal sebagai Wahhabism
Muhammad ibn Saud terpesona. Bukan cuma terpesona dengan Wahhabism sebagai ajaran, juga sebagai caranya memperoleh kekuasaan yang lebih besar dari sekedar Dirriya.
Muhammad ibn Saud kemudian mendatangi Muhammad ibn Abd al-Wahhab, mengajaknya bekerjasama untuk bersatu-padu memurnikan ajaran Islam.
Dalam benak Muhammad ibn Saud, ajakan tersebut juga sekaligus sebagai upaya mengganggam kekuasaan lebih besar di Jazirah Arab. Keduanya memulai kerjasama dengan menikahkan silang sudara-saudara mereka hingga akhirnya terbentuk "The House of Saud & Wahhab."
Paham Wahabism sejatinya ditentang mayoritas para pemimpin sub-suku Arab kala itu karena, misalnya, menonjolkan sikap anti-toleransi pada non-Muslin dan bahkan pada Muslim sendiri yang tak sependapat. Namun, via ajaran Wahhabism, Muhammad ibn Saud seketika memperoleh legitimasi religius.
Melalui legitimasi yang dimilikinya, Muhammad ibn Saud melancarkan banyak "perang suci" berselubung pemurnian ajaran Islam. Suatu peperangan yang menjadikan musuh yang dilawan Muhammad ibn Saud seakan-akan adalah "musuh agama."
Karenanya, masyarakat Jazirah Arab kemudian bersimpatik pada Muhammad ibn Saud dan, per awal abad ke-19, aliansi ini sukses menaklukan seluruh penjuru Jazirah Arab, termasuk, tentu saja, titik-titik tersuci dunia Islam serta wilayah-wilayah di Jazirah Arab yang dikuasai Turki Usmani, semisal Basra (wilayah Irak saat ini).
Naas, kekuasaan super besar ini berakhir pada 11 September 1818, gara-gara serangan balik yang dilancarkan Mesir. Serangan ini memaksa pewaris tahta Muhammad ibn Saud kala itu, Abdullah, ditangkap dan dibawa ke Istanbul untuk diadili.
Untunglah, memasuki abad ke-20, pewaris selanjutnya dinasti al-Saud, Abd al-Aziz (Ibn Saud) berhasil membangun kembali kekuasaan dengan keberhasilannya merengkuh wilayah seluas Arab Saudi modern saat ini. Di tangan Abd al-Aziz-lah, Kerajaan Arab Saudi berdiri.

Ironis, ketika Arab Saudi berdiri, perkawinan antara al-Saud dan al-Wahhab seakan-akan berhenti, tak bersinergi sebagai satu kesatuan utuh. Dimana, sebagai negara, Arab Saudi kemudian dijalankan dengan dua pemerintahan yang berbeda.
Untuk urusan politik, keamanan, dan ekonomi, klan al-Saud bekerja. Di sisi lain, untuk urusan keagamaan dan sosial, klan al-Wahhab mengatur. Dan, dari status quo inilah, diinisiasi penemuan ladang minyak. Klan al-Saud lalu memadu asmara dengan pihak lain, yakni Amerika Serikat.
Campur Tangan Barat
Perlahan-lahan, mengutip paparan McMillan, "Arab Saudi lalu menjadi negara yang dipenuhi kontradiksi, muncul jurang sosial tinggi, pembatas keluarga al-Saud dengan masyarakat umum, andil dari embargo minyak yang sukses melejitkan harga minyak mentah di pasaran [...] Dibanjiri pekerja-pekerja minyak dari Barat, kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Arab Saudi lalu kembali dihinggapi bid'ah yang tak bisa dikendalikan klan Wahhab."
Suatu keadaan yang membuat banyak kelompok masyarakat tak suka dengan klan al-Saud berkuasa, termasuk "Ikhwan," salah satu tulang punggung terpenting militer Arab Saudi. Tempat kakek Juhayman mengabdi.
Pikir Juhayman, adu-kasih Arab Saudi dengan Amerika Serikat yang terlihat mencampakan Wahhabism keterlaluan. Bukan gara-gara kerjasama dengan Amerika Serikat (AS) membuat bid'ah kembali muncul, melainkan karena AS, dalam benak Juhayman, merupakan musuh utama Islam.
Merujuk reportase Bernard Lewis dalam The Revolt of Islam, didaulatnya Amerika Serikat sebagai musuh utama Islam bermuara pada adanya perbedaan konsep bangsa/negara antara Barat dan dunia Islam.
Bagi Barat, unit dasar organisasi manusia adalah negara, yang kemudian dibagi lagi dalam berbagai cara, salah satunya adalah agama. Di sisi lain, dunia Islam melihat unit dasar organisasi manusia adalah agama, yang lantas dibagi-bagi menjadi bangsa/negara.
Salah satu alasan mendasar beda cara pandang Islam melihat konsep bangsa/negara terjadi karena, khususnya di Timur Tengah, semua negara yang eksis hari ini merupakan entitas baru.
Berdasarkan etimologi nama-nama negara di Jazirah Arab, misalnya, nama negara seperti Suriah, Palestina, dan Libya tak pernah digunakan berabad-abad lalu di wilayah-wilayah mereka.
Contoh lainnya, Algeria, Tunisia, bahkan Arab Saudi tidak memiliki padanan dalam bahasa Arab. “Tidak ada kata dalam bahasa Arab untuk Arab (Arab Saudi),” ungkap Lewis.
"Bukan karena bahasa Arab tak berkembang, tetapi karena masyarakat (Jazirah) Arab tak pernah berpikir bahwa mereka akan terkota-kota dalam bangsa/negara berbeda," lanjut Lewis.
Via konsep ini, seluruh masyarakat Jazirah Arab akhirnya percaya bahwa musuh utama mereka adalah kaum non-Muslim. Misalnya, yang pertama-tama diwakili oleh Kekaisaran Bizantium di Konstantinopel, lalu Kekaisaran Rowawi Suci di Vienna (dan akhirnya melekat pada AS)
Singkat cerita, Islam seyogyanya merupakan medium utama pemersatu masyarakat Jazirah Arab atau Timur Tengah.
Mereka tidak pernah mengaku sebagai "orang Arab" atau "orang Turki," misalnya, tetapi mengaku sebagai kaum Muslim. Karenanya, konsep bangsa/negara pemersatu dunia Islam alias Kekhalifahan tak pernah sirna dalam benak setiap kaum Muslim.
Di titik inilah sebab-musabab AS didaulat menjadi musuh utama dunia Islam berasal, yang dimulai pada 1918, tahun di mana Kesultanan Turki Usmani, yang banyak diyakini sebagai pewaris Kekhalifahan Islam, berakhir untuk digantikan negara Turki sekuler.
Uniknya, berakhirnya Turki Usmani tidak digawangi oleh AS, melainkan oleh orang-orang Turki sendiri (yang beraliran sekuler) sebagai buah dari serangan yang dilancarkan Barat, yang diwakili oleh Kerajaan Inggris dan Kekaisaran Perancis.
Tentu, seteru dunia Islam dan Barat tak terjadi untuk pertama kalinya pada 1918 itu. Pada 1683, misalnya, pasukan Turki Usmani sempat hancur lebur di Vienna.
Juga, pada 1798, pasukan yang dipimpin Napoleon Bonaparte berhasil menguasai Mesir, untuk digantikan Inggris melalui pasukan yang dikepalai Horatio Nelson beberapa tahun kemudian.
Namun, yang berbeda, atas keyakinan masyarakat Jazirah Arab bahwa mereka merupakan satu kesatuan di bawah panji Islam dan Turki Usmani merupakan simbol pemersatunya dalam bentuk Kekhalifahan. Berakhirnya Turki Usmani gara-gara Barat bertransformasi menjadi luka terbesar dunia Islam (Jazirah Arab).
Apalagi, keruntuhan Turki Usmani dilanjutkan dengan kian merajalelanya penjajahan Barat di Timur Tengah, termasuk di negara-negara Islam (atau mayoritas berpenduduk Muslim) lain di seluruh dunia, misalnya Indonesia. Alhasil, Barat menjadi musuh utama bersama dunia Islam.
Penentang Barat, kemudian, menjadi "sahabat" dunia Islam, seperti yang pernah melekat pada Jerman (negara Barat yang menjadi musuh Barat di Perang Dunia Kedua) dan Uni Soviet.
Sebaliknya, pemimpin dunia Barat lalu menjadi "super villain" atau "The Great Satan" dunia Islam. Tak lain, pemimpin dunia Barat itu adalah Amerika Serikat. Negara yang lantas melakukan "penjajahan baru" di Timur Tengah, yakni dengan memeras minyak bumi Jazirah Arab.
Juhayman dan para pengikutnya yang berasal dari pelbagai negara dengan berusaha menggulingkan Arab Saudi yang sudah terlena dengan kesejahteraan yang dibawa AS. Mereka merebut dan menyandera Masjidil Haram demi menggelorakan revolusi di benak setiap Muslim.
Pikir Juhayman, penyanderaan Masjidil Haram merupakan cara jitu melakukan revolusi. Musababnya, Masjidil Haram merupakan pusat kaum Muslim dan, merujuk Quran, haram hukumnya peperangan/aksi bersenjata dilakukan di sana, Haram al-Sharif, alias menihilkan kemungkinan pasukan Arab Saudi melakukan perlawanan.
Naas, strategi brilian ini hancur gara-gara Juhayman dan pengikutnya sendiri karena gagal memahami adanya dua faksi berbeda dalam dunia Islam, yakni Suni dan Syiah.
Juhayman, dalam peyanderaan Masjidil Haram tersebut, mengikrarkan iparnya, Muhammad ibn Abdullah al-Qahtani, sebagai Imam Mahdi, figur mesiah akhir zaman dunia Islam yang lebih menggaung di kalangan Syiah, bukan Suni.
Padahal, tentu, faksi terbesar dunia Islam adalah Suni. Dari sini, simpatik terhadap Juhayman berkurang. Sementara itu, tak mau melanggar Quran, pasukan Arab Saudi bersiasat mengakhiri penyanderaan Masjidil Haram dengan cara membanjiri lorong bawah tanah Masjidil Haram dengan air yang dialiri muatan listrik.
Dua minggu sejak penyanderaan Masjidil Haram dilakukan, Juhayman dan pengikutnya berhasil diatasi dengan memakan korban jiwa sang Imam Mahdi gadungan sendiri, ratusan pengikutnya, serta puluhan jamaah Masjidil Haram yang tak tahu menahu tentang revolusi tersebut.
Juhayman sendiri dieksekusi Arab Saudi pada 1980. Dan, tak berselang lama sejak penyanderaan Masjidil Haram dilakukan, atas dasar serupa (pertemuan antara Perdana Menteri Iran Mehdi Bazargan dan Penasihat Keamanan Amerika Serikat Zbigniew Brzezinski untuk meningkatkan hubungan Iran-Amerika Serikat), revolusi lain di dunia Islam terjadi, yakni Revolusi Iran.
Editor: Dwi Ayuningtyas
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id