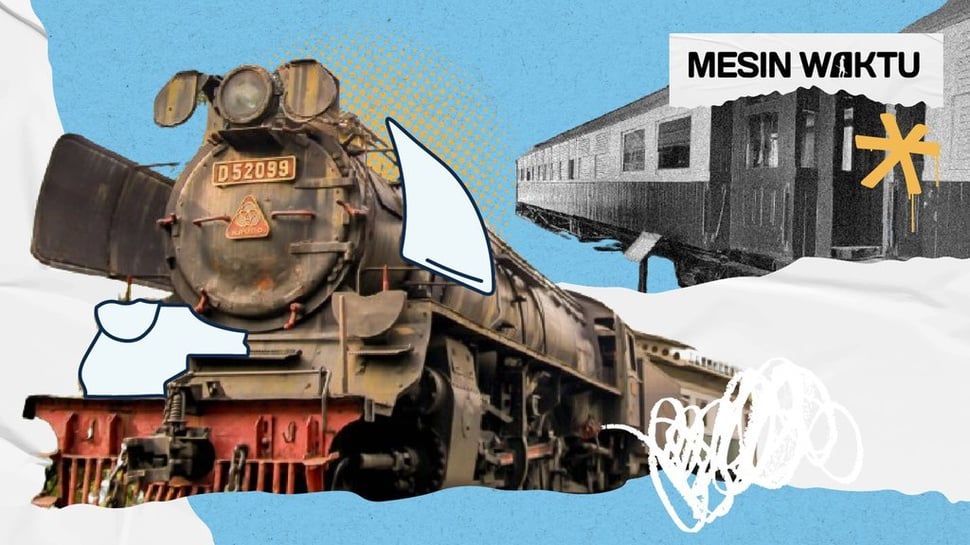tirto.id - Bertandang ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII), selain menilik anjungan daerah dari Sabang sampai Merauke, kita juga bisa sekaligus menikmati banyak museum. Di antaranya ada Museum Penerangan, Museum Keprajuritan, Museum Pusaka, Museum Listrik dan Energi Baru, Museum Prangko, dan Museum Transportasi.
Beberapa waktu lalu, saya meluangkan waktu berkunjung ke museum yang disebut terakhir.
Kala memasuki halaman museum, saya disambut dengan ramainya anak-anak sekolah dasar yang kebetulan melakukan kunjungan ke museum tersebut. Mereka tampak antusias wara-wiri mengamati beberapa koleksi museum. Beberapa anak tampak sedang bermain di sekitar koleksi besar yang terletak di bagian depan museum.
Saya bilang besar karena secara harfiah, ia memang bukan koleksi yang biasa dari segi ukuran. Itu adalah dua gerbong yang kini lazim disebut sebagai Kereta Api Luar Biasa (KLB).
Kata besar itu juga bisa disematkan untuk menyifati sejarah yang pernah dilaluinya. Pasalnya, dua Gerbong KLB itu (diregistrasi dengan nomor IL.7 dan IL.8) merupakan saksi bisu perjuangan pemimpin-pemimpin Indonesia di masa awal Kemerdekaan.
Ia pernah berjasa mengantar Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta hijrah dari Jakarta ke Yogyakarta pada 3-4 Januari 1946. Epiknya, perjalanan hijrah itu dilakukan secara rahasia di tengah gerakan serdadu Belanda untung menguasi Jakarta.
Perjalanan itu juga menjadi awal dari momen penting berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Yogyakarta kemudian menjadi ibu kota Indonesia sejak 1946 hingga 1949.
Jakarta Tak Aman, Yogyakarta Jadi Tujuan
Usai Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, tentara Sekutu si pemenang Perang Dunia II datang ke Indonesia. Mereka punya tugas utama melucuti senjata dan memulangkan tentara Jepang ke negara asalnya.
Namun, situasi jadi runyam karena Netherlands Indies Civil Administration (NICA) ikut pula dalam rombongan pasukan Sekutu.
NICA yang semula dibentuk dan beroperasi di Australia datang ke Indonesia untuk mengklaim kembali wilayah Hindia Belanda. Kehadiran NICA lantas menjadi ancaman bagi Republik Indonesia yang baru lahir itu.
Di Jakarta, polah NICA tentu saja amat mengganggu jalannya roda pemerintahan Indonesia. Dengan persenjataan yang lebih superior, tinggal menunggu waktu saja hingga Jakarta benar-benar jatuh ke tangan NICA. Oleh karena itu, pemimpin RI membuka opsi untuk memindahkan pusat pemerintahan ke kota lain yang lebih aman.
“Berhubung dengan Jakarta sudah mulai tidak aman, pada tanggal 4 Januari 1946 presiden dan wakil presiden dengan keluarga dan staf mereka pindah ke Yogyakarta, yang juga dijadikan ibu kota Republik Indonesia,” tulis Mohammad Hatta dalam autobiografi Untuk Negeriku III, Menuju Gerbang Kemerdekaan (2010).
Perjalanan di Bawah Tangan
Dalam kondisi genting itulah, KLB berperan. Karena kondisi keamanan yang tak kondusif, perpindahan para pemimpin RI pun dipersiapkan secara rahasia. Dengan opsi yang terbatas, rombongan pemimpin negara diputuskan akan menuju Yogyakarta secara diam-diam dengan kereta api.
Budi Kurnia dalam studinya Peranan Pemuda Kereta Api dalam Pengambilalihan Kekuasaan Kereta Api dan Pengawalan Perjalanan Presiden RI ke Yogyakarta (1945-1947) (1996) menulis bahwa pemindahan pemimpin RI saat itu dibantu persiapannya oleh para pekerja perkeretaapian Jakarta.
Mereka menyiapkan satu rangkaian kereta api spesial yang dulu pernah digunakan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sebelum digunakan, gerbong-gerbong yang digunakan diperbaiki terlebih dahulu.
Saat itu, ada delapan gerbong yang disiapkan untuk melaksanakan operasi hijrah rahasia itu. Rangkaian kereta api spesial itu mulai melaksanakan tugasnya pada sore hari tanggal 3 Januari 1946.
Budi Gundawan dalam studinya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kehidupan Sosialnya Pada Masa Perang Kemerdekaan 1945-1949 (1990) menulis bahwa rangkaian kereta api spesial itu ditarik secara perlahan menuju ke Pegangsaan Timur, tempat kediaman Presiden Sukarno.
Sore itu, Hatta dan beberapa pemimpin RI yang lain juga telah berkumpul di rumah Sukarno. Posisi rumah Sukarno memang strategis karena hanya berjarak beberapa meter dari rel kereta api.
Kala waktu bergerak ke petang, rombongan pemimpin RI mulai naik ke KLB. Sekira jam 18.00, rangkaian KLB pun mulai bergerak.
Rangkaian KLB berjalan dengan kecepatan rendah dari Pegangsaan hingga Stasiun Jatinegara. Untuk menghindari kecurigaan tentara Belanda yang berpatroli, seluruh lampu di gerbong dimatikan selama perjalanan itu.
KLB mulai dipacu dengan kecepatan tinggi setelah menjauh dari Jatinegara. Beberapa pekerja perkeretaapian juag diikutkan untuk mengawal perjalanan secara bergantian. Lepasa dari Jakarta, KLB tersebut berhenti di beberapa stasiun, di antaranya Stasiun Cikampek, Cirebon, Purwokerto, dan Maos.
Buku Takhta untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX (2011) menyebut bahwa selama singgah di beberapa stasiun itu, rombongan pemimpin RI mendapat sambutan hangat dari rakyat. Rombongan pun akhirnya tiba di Stasiun Tugu menjelang subuh hari tanggal 4 Januari 1946.
Kedatangan rombongan pemimpin negara di Yogyakarta disambut langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII.
“Pada tanggal 6 Januari 1946, masyarakat Yogyakarta mengadakan upacara penyambutan kedatangan pemimpin-pemimpin republik, bertempat di bekas Gedung KNI daerah,” tambah Budi Gundawan (1990).
Upacara ini diselenggarakan sebagai bentuk dukungan rakyat Yogyakarta untuk melanjutkan perjuangan.

Gerbong Kenangan Masa Revolusi
Momen hijrah secara rahasia itu rupanya amat membekas di memori Dwitunggal Sukarno-Hatta. Kisah itu lalu diabadikan Hatta dalam autobiografinya. Dan begitu pula Sukarno, seperti diungkapkan kembali oleh Cindy Adams dalam buku Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia(1965).
Menurut Sukarno, itu adalah momen krusial dalam sejarah RI yang baru saja berdiri. Perpindahan itu disebutnya telah menyelamatkan perjuangan Indonesia.
Pada 28 September 1965—di hari peringatan dwidasawarsa Perusahaan Nasional Kereta Api (PNKA), Presiden Sukarno menceritakan ulang peristiwa hijrah itu.
“Saya merasa terharu jika mengingat kejadian magrib 4 Januari 1946 [tepatnya 3 Januari]. Saudara tahu Pegangsaan Timur No. 56 itu adalah di tepi jalan kereta api. Saudara Anwar ini magrib-magrib membawa kereta api di belakang rumah saya itu. Pada waktu sudah mulai gelap, saya dimasukkan dalam kereta api itu dan terus diangkut ke Yogyakarta. Dan dari Yogyakartalah revolusi dipimpin terus, revolusi mendapat pimpinan terus. Sampai saudara-suadara mengetahui sejarah Yogyakarta. Kemudian kembali ke Jakarta, sampai sekarang alhamdulillah revolusi selamat... Siapa bilang saya dari Tegal, saya dari Majalengka. Siapa bilang revolusi kita gagal? sebab kita punya PNKA,” (Pidato Presiden No. 811, 28 September 1965. Arsip Nasional Republik Indonesia).
Menilik kisah epiknya itu, maka amatlah layak dua Gerbong KLB itu dimuseumkan. Kita boleh bersyukur bahwa Gerbong KLB dirawat dengan baik di Museum Transportasi. Kedua gerbong kereta bersejarah itu kini ditempatkan di bawah bangunan kanopi yang melindunginya dari paparan cuaca.
Dari papan informasi yang diletakkan di depan Gerbong KLB, kita beroleh informasi bahwa ia merupakan buatan Staatsspoorwegen (SS). Gerbong dengan berat kosong 38.100 kg dan panjang antara 18.640–18.500 mm itu diproduksi oleh SS di bengkel besar Bandung dan mulai aktif bertugas sejak 20 Mei 1919.
Pada awalnya, kereta tersebut merupakan kereta inspeksi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Maka tak heran interior gerbong KLB terbilang mewah, tak serupa gerbong kereta api pada umumnya. Fasilitas gerbong ini amatlah lengkap, mulai dari meja dan kursi yang dapat dipindah, tempat tidur, dan kamar mandi dengan instalasi bathtub dan toilet.
Fitur lain yang juga spesial dari KLB adalah pendingin ruangan. Udara sejuk yang terasa pada gerbong berasal dari es balok. Buku Sejarah Perkeretaapian Indonesia Jilid I (1997) menjelaskan bahwa balok-balok es ditempatkan di instalasi khusus di bawah gerbong. Apabila balok-balok es itu sudah mencair sepenuhnya, balok-balok es yang baru akan dimasukkan kala kereta api singgah di stasiun-stasiun tertentu.
Penulis: Omar Mohtar
Editor: Fadrik Aziz Firdausi