tirto.id - Dewan Perwakilan Rakyat sudah mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pengesahan ini masih menuai polemik karena dalam UU tersebut terdapat sejumlah potensi masalah yang bisa mewarnai proses pemberantasan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa itu.
Potensi masalah pertama terdapat pada definisi. Dalam Pasal 1 UU tersebut, terorisme didefinisikan “Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”
Potensi masalah kedua muncul dari Pasal 25 UU Pemberantasan Terorisme baru. Aturan itu mengatur waktu yang bisa digunakan untuk menahan tersangka dan terdakwa kasus terorisme. Total waktu penahanan yang diatur beleid itu, mulai dari tahap penyidikan sampai perpanjangan penahanan maksimal 290 hari. Lama waktu itu melebihi total masa penahanan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selama 170 hari.
Potensi selanjutnya terdapat pada pasal 43C ayat (1). Ayat ini menyebut pengertian kontra radikalisasi sebagai “suatu proses terencana, terpadu, sistimatis dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme [...] untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme.”
Terakhir, ketidakjelasan definisi “paham radikal terorisme.” Frase ini tercantum mulai BAB VIIA tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
Bisa Menyasar Lawan Politik Hingga Melanggar KUHAP
Soal definisi, Direktur Imparsial Al Araf menganggapnya sebagai hal yang multiinterpretatif. Ia khawatir definisi ini bisa berpotensi disalahgunakan untuk menindak kelompok-kelompok yang selama ini kritis terhadap pemerintah.
“Seharusnya kemarin Pemerintah dan DPR tak memasukkan unsur tentang 'motif politik, atau ideologi, dan gangguan keamanan',” kata Al Araf di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/5/2018).
Al Araf berkaca pada UU sebelum revisi yang tak memasukkan motif dalam definisi. Meski begitu, Al Araf bersyukur motif ini tidak dimasukkan dalam pasal 5,6, dan 7 yang mengatur unsur-unsur pidana aksi teror.
Ia berharap UU ini tidak dijadikan senjata memberangus kelompok yang kritis terhadap kekuasaan. “Tetapi benar-benar menyasar organisasi teroris,” ujar Al Araf.
Sementara terkait rentang waktu penahanan, pengamat terorisme dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya menilai lamanya waktu ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, terlebih ada kekhawatiran muncul penyiksaan dan pengabaian hak tahanan.
“[Masa penahanan panjang] sangat merugikan tersangka atas haknya untuk disidang dalam suatu peradilan yang cepat dan sederhana,” ujar Harits dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto.
Ia pun menyoroti soal ketidakjelasan frase “orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme”. Ia khawatir penentuan kelompok rentan justru bisa menimbulkan konflik.
Sama dengan frase orang atau kelompok yang rentan, frase paham radikal terorisme bersifat tidak jelas sehingga berpotensi membuat penyidik menyalahgunakan wewenang. “Penyidik dapat seenak sendiri menentukan orang-orang yang wajib mengikuti program kontra radikalisasi dan deradikalisasi,” ujarnya.
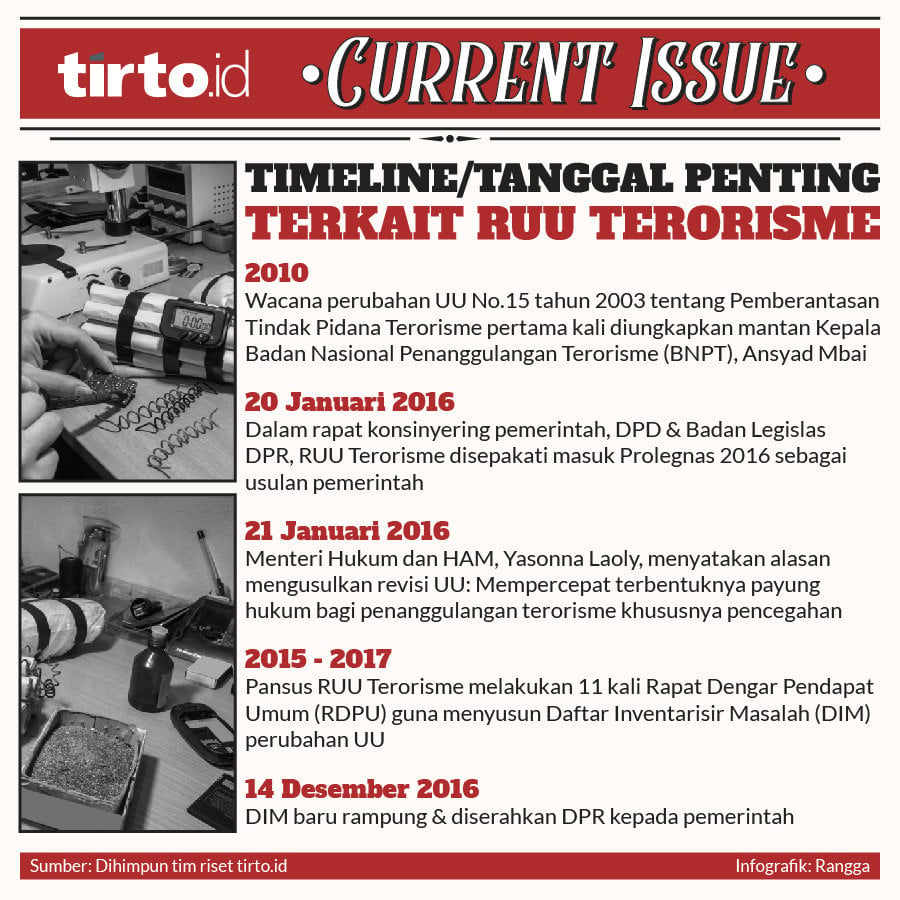
Tanggapan Pansus UU Terorisme
Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemberantasan Terorisme dari Fraksi PKS Nasir Djamil menjelaskan berbagai catatan yang diberikan pengamat dan LSM itu.
Pertama, ia menjelaskan ihwal definisi yang multitafsir. Menurutnya, penjelasan motif dalam definisi terorisme justru memperjelas arti dari tindakan itu.
Nasir berkata, usul dimasukkannya motif dalam definisi terorisme berasal dari tiga partai yakni Gerindra, PAN, dan PKS. Keinginan ketiga parpol itu diterima dengan kompromi oleh parpol dalam faksi pemerintah.
“Jadi yang namanya kelompok teroris itu selalu punya motif politik dan ideologi. Kalau dilihat berbagai definisi terorisme, maka salah satu unsur kelompok teroris adalah memiliki motif politik,” ujar Nasir kepada Tirto.
Politikus PKS itu bercerita, awalnya fraksi partai selain Gerindra, PAN, dan PKS tak mau menerima usul pencantuman motif dalam definisi terorisme. Motif ini baru bisa dimasukkan setelah masing-masing fraksi sepakat menghapus kata 'negara' di definisi terorisme.
Nasir menyebut parpol-parpol pendukung pemerintah awalnya enggan menerima usul tiga partai itu jika definisi masih berbunyi “[...] dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan negara.”
Penolakan itu terjadi dinilai Nasir terjadi karena parpol pendukung pemerintah dianggap memiliki pemahaman parsial ihwal arti dan cakupan definisi terorisme. “Jadi kalau kejahatan yang tidak dilandasi motif politik dan bukan kelompok teroris ya enggak bisa diancam pidana terorisme,” ujar Nasir.
Menanggapi lama masa penahanan tersangka dan terdakwa kasus terorisme, Nasir mengakui aturan itu menyimpang dari KUHAP. Akan tetapi, ia beralasan keputusan itu diambil karena mempertimbangkan terorisme sebagai tindak pidana luar biasa.
Menurut Nasir, aparat penegak hukum tak harus memanfaatkan semua waktu yang diberikan untuk menahan tersangka dan terdakwa kasus terorisme sesuai Pasal 25 UU Pemberantasan Terorisme. Ia berharap penegak hukum lebih profesional agar dapat meminimalisir waktu penahanan.
Dalam persoalan objek kontra radikalisasi, Nasir menjelaskan hampir semua golongan dianggap rentan oleh pemerintah dan DPR. ia menyebut contoh kelompok rentan disusupi paham radikal terorisme adalah pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang tingkat pendidikan, ekonomi, dan sosialnya rendah.
"Sebenarnya kemarin dalam penjelasan [Pasal 43C ayat (1)] mau disebutkan 'Mahasiswa, pelajar, dan kelompok lainnya' [sebagai kelompok rentan]. Kami minta itu dihapus karena akan membuat stigma,” ujar Nasir.
Hati-Hati Menggunakan UU Pemberantasan Terorisme
Keberadaan potensi masalah ini ditanggapi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Koordinator KontraS Yati Andriyani mengatakan penegak hukum harus hati-hati menggunakan aturan baru ihwal tindak pidana terorisme. Sikap waspada harus dimiliki karena UU Pemberantasan Terorisme banyak memberi ruang bagi penegak hukum mengeluarkan diskresi.
“Seperti penyadapan, penangkapan selama 14 hari dan dapat diperpanjang 7 hari, penggunaan pasal hate speech atau pemidanaan terhadap orang-orang yang memiliki hubungan dengan jaringan teroris dan melakukan penghasutan. Prinsip kehati-hatian harus dilakukan dengan mengedepankan: proporsionalitas, legalitas, akuntabilitas,” ujar Yati dalam keterangan tertulis kepada Tirto.
Ia juga mengingatkan aparat tidak selalu menggunakan pendekatan eksesif atau kekerasan dalam memberantas terorisme. Yati juga berharap pelibatan TNI dalam memberantas terorisme harus dilakukan tetap dalam koridor operasi militer selain perang (OMSP).
Terakhir, KontraS menganggap pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) tak diperlukan untuk memberantas terorisme. Menurut mereka, pelibatan TNI dalam OMSP tak harus diatur khusus melalui pembentukan Koopssusgab.
“Jika UU ini diberlakukan, penting untuk memastikan adanya safeguard, pengawasan, dan mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam menggunakan kewenangan yang ada di dalam UU,” ujar Yati.
Secara terpisah, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyarankan masyarakat untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika merasa ada aturan yang kurang atau bermasalah di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme baru.
“Ikuti saja proses hukum yang sudah berjalan. Kalau kemudian masyarakat bilang ada yang kurang, boleh mengajukan judicial review ke MK untuk ditambahkan atau menambahkan lagi [usul] ke DPR,” ujar Hidayat.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Mufti Sholih
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id


































