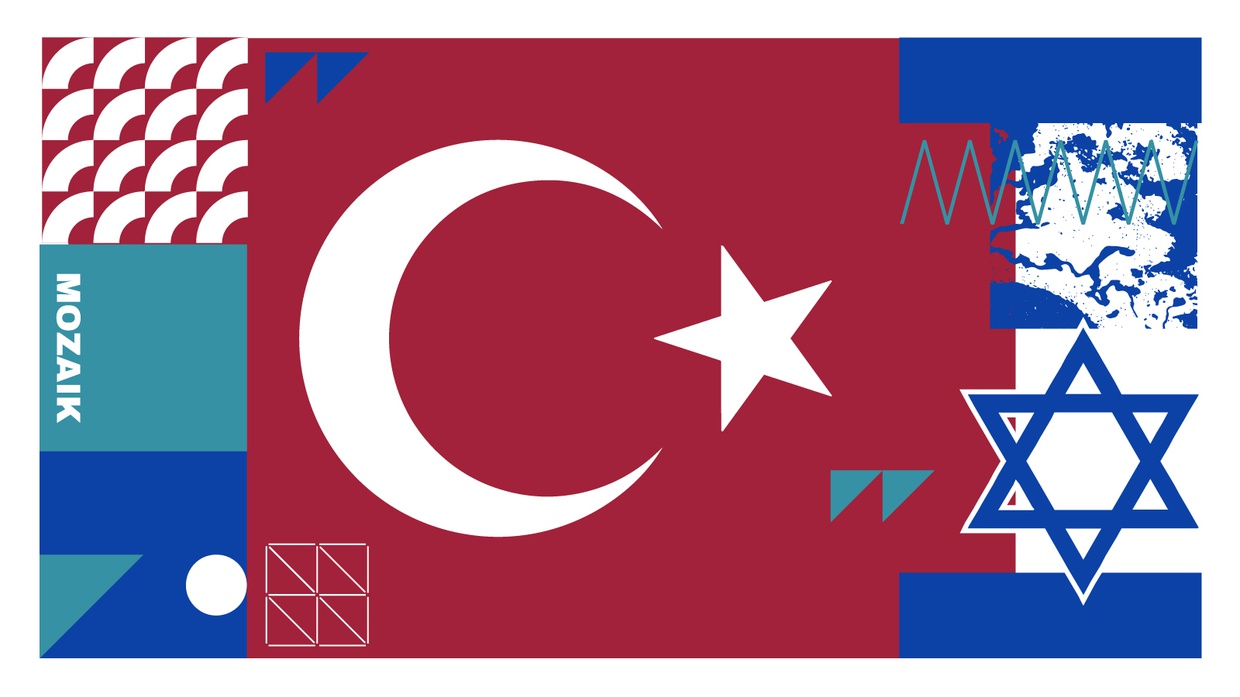tirto.id - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi untuk mengakhiri pendudukan Inggris atas Palestina dan membagi wilayah tersebut menjadi dua, yakni untuk Yahudi dan Arab, pada 29 November 1947. Saat itu negara-negara Arab menolaknya dengan alasan karena resolusi—secara resmi bernama United Nations Resolution 181—tidak sesuai dengan piagam PBB tentang pemberian hak kepada rakyat untuk menentukan nasib sendiri.
Para penolak khawatir karena resolusi tersebut suatu saat akan berdiri negara Yahudi yang mengancam keberadaan orang Palestina. Ketakutan tersebut menjadi nyata setahun kemudian. Aktivis zionisme, David Ben-Gurion, mendeklarasikan pendirian negara Israel pada 14 Mei 1948.
Banyak negara mengakui kedaulatan Israel—yang semakin menambah keabsahan pendiriannya. Di sisi berseberangan, sejalan dengan sikap terhadap resolusi, negara-negara Arab mengutuknya. Ketegangan di Timur Tengah lekas meningkat hingga berujung pecahnya perang antara mayoritas negara Arab (termasuk Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, dan Irak) melawan Israel. Peristiwa ini dikenal sebagai Perang Arab-Israel 1948.
Salah satu pihak yang memilih netral dalam perang adalah Turki meski mereka tidak setuju terhadap resolusi. Saat itu Turki masih menaruh sikap curiga terhadap Israel.
Namun antagonisme Turki-Israel tidak berlangsung lama. Pada 28 Maret 1949, tepat 73 tahun lalu, Turki justru mengakui Israel sebagai negara merdeka dan berdaulat. Keputusan ini membuat Turki menjadi negara mayoritas muslim pertama di dunia yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
Tekanan Perang Dingin
Sebuah pertanyaan mendasar pun menyeruak: Mengapa Turki malah membina hubungan dengan Israel di tengah kalutnya situasi?
Jawabannya dapat ditelusuri dari apa yang terjadi dengan negara itu setelah berakhirnya Perang Dunia II (1939-1945). Turki, dengan luas sekitar 783.562 km persegi, cukup diperebutkan oleh dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet, meski tidak secara langsung seperti Vietnam dan Korea. Hal ini terjadi karena Turki adalah salah satu negara dengan lokasi terbaik di Timur Tengah: di antara Eropa-Asia dan menjadi penghubung antara Laut Hitam-Laut Marmara-Laut Mediterania.
Pada mulanya Turki lebih dekat ke Soviet. Hubungan mereka telah terjalin sejak 1925, tepatnya ketika menyepakati Treaty of Friendship.
Menurut Ferenc Albert Váli dalam Bridge Across the Bosporus: The Foreign Policy of Turkey (2019), relasi Turki-Soviet mulai goyah pada 1936. Penyebabnya adalah karena Turki diberi kontrol untuk mengendalikan Selat Bosporus dan Dardanella yang menghubungan Laut Hitam dan Laut Marmara berdasarkan Konvensi Montreux. Banyak kapal dagang dan kapal perang Soviet yang mengarung di dua selat itu sebelum akhirnya berlayar bebas di Atlantik atau Suez. Soviet jelas punya kepentingan besar untuk mempertahankan kedua selat yang sangat strategis secara ekonomi dan politik itu.
Bagi Soviet, Konvensi Montreux membuat Turki dapat sewaktu-waktu menggunakan kewenangannya untuk kepentingan politik. Soviet khawatir suatu saat manuver Turki akan merugikan mereka. Maka mereka ngotot meminta Turki membagi kewenangan mengurus Selat Bosporus dan Dardanella. Negara komunis ini juga meminta izin untuk membangun pangkalan di dua perairan tersebut.
Keretakan Turki-Soviet mencapai puncaknya satu dekade kemudian. Joseph Stalin memandang bahwa Turki benar-benar tidak lagi netral karena mengizinkan kapal perang Nazi dan AS melewati dua selat itu untuk mencapai Laut Hitam—yang keberadaan mengancam kedaulatan Soviet.
Ini jelas tidak bisa dibiarkan begitu saja. Soviet menekan Turki dan membuat mereka cukup ketakutan, apalagi jarak antar kedua negara cukup dekat. Tidak menutup kemungkinan sewaktu-waktu Soviet menyerang Turki.
Sebagai upaya defensif, Turki memilih menjalin hubungan lebih dekat dengan AS. AS tentu saja menyambut baik. Pasalnya, sebagaimana dipaparkan Bülent Gökay dalam Soviet Eastern Policy And Turkey, 1920-1991 (2006), para elite AS menganggap jika satu negara jatuh ke pelukan komunisme, maka tinggal tunggu waktu saja negara-negara lain yang dekat akan mengalami hal yang sama—dikenal sebagai “teori domino”. Dalam konteks Turki, jika ia jatuh ke tangan Soviet, maka komunisme dapat dipastikan akan menyebar ke selatan Iran hingga India.
Salah satu upaya konkret mendukung Turki adalah mengeluarkan bantuan ekonomi bermotif politik bernama Doktrin Truman, yang konon menjadi penyulut Perang Dingin, sebesar 400 juta dolar AS kepada Turki (dan Yunani) pada 1947. Akan tetapi bantuan itu tidak membuat ancaman komunis serta-merta hilang. Justru Soviet semakin agresif, yang membuat Turki harus memikirkan cara lain agar selamat.
Alhasil, Turki pun mulai memandang perlu dukungan Israel. Elite politik Turki paham betul Israel adalah anak kesayangan AS di Timur Tengah. Dengan mengakui kedaulatan dan menjalin hubungan dengan Israel, Turki juga bakal mengamankan dukungan AS dan negara Barat lain. Turki bakal berhadapan dengan situasi sulit jika ancaman komunis menguat ketika pada saat yang sama tensi politik dengan Israel memanas. Jika persoalan ini dibiarkan berlarut, tentu Turki juga yang bakal rugi.
Atas dasar inilah Turki mengakui secara de facto kedaulatan Israel pada 28 Maret 1949, yang kemudian diikuti pengakuan secara de jure pada 1952.
Israel pun diuntungkan dengan pengakuan Turki. Menurut pakar politik asal Israel Amikam Nachmani dalam Israel, Turkey, and Greece (1987), selain memperoleh banyak keuntungan ekonomi, Turki juga dapat berfungsi sebagai mediator dengan negara-negara Arab yang ditargetkan untuk menjalin kerja sama.
Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim dan cukup modern, Turki saat itu memiliki posisi penting dalam percaturan politik regional dan akan jauh lebih penting di masa depan. Dan ini terbukti ketika pada 1950-an negara tersebut menjalin berbagai kesepakatan politik dan militer dengan negara-negara Arab dan Barat, dan yang paling prestisius: bergabung dengan NATO.

Dikucilkan Arab
Dengan mengakui Israel, menurut Saban Halis Calis dalam Turkey’s Cold War: Foreign Policy and Western Alignment in the Modern Republic (2017: 115), Turki sebenarnya ingin dianggap sebagai jembatan antara Barat dan Timur Tengah untuk membentuk blok anti-Soviet dan anti-komunis. Sementara Shamir Hassan dalam “Turkey’s Israel Policy Since 1945” (2008) mengatakan Turki ingin berguna sebagai perisai komunisme dan fasilitator perundingan di Timur Tengah.
Namun cita-cita membentuk blok anti-komunis dipandang salah langkah. Orang Arab tidak menganggap komunisme sebagai ancaman utama. Justru Israel-lah yang dianggap bahaya tingkat tinggi. Terlebih masih banyak orang Arab, khususnya kaum nasionalis pergerakan kemerdekaan, yang sinis terhadap negara Barat.
Kebijakan pro-Barat, khususnya dukungan terhadap Israel, pada akhirnya membuat Turki terasing di Timur Tengah. Negara yang didirikan Mustafa Kemal Ataturk ini dipandang tidak setia kawan dan dicap pengkhianat.
“Sikap kebarat-baratan Turki itu tidak akan dapat diterima. Bahkan beberapa kelompok Islam menyebut Turki sebagai ‘Israel kedua’ yang juga harus dihancurkan,” tulis Saban Halis Calis.
Penulis: Muhammad Fakhriansyah
Editor: Rio Apinino
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id