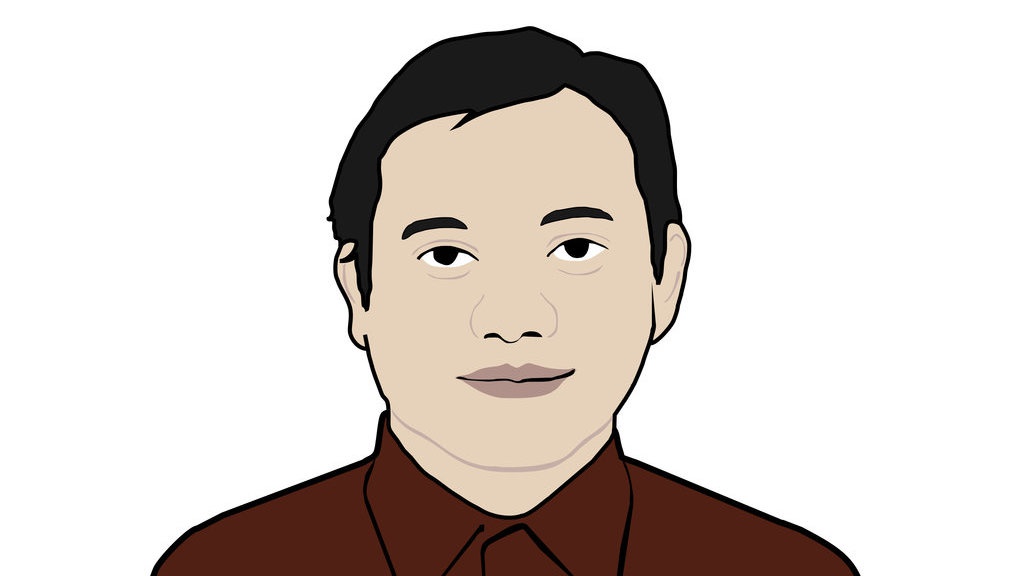tirto.id - Dalam kamus politik Indonesia kontemporer, ‘radikalisme’ adalah satu dari sekian istilah yang paling sering disalahpahami dan disalahgunakan. Terminologi yang sebetulnya telah lama digunakan di Indonesia ini kembali marak setelah kasus terorisme di Surabaya, Sidoarjo, dan Riau pada Mei 2018 ini. Media-media, pejabat negara, dan berbagai kalangan mengalamatkan kekerasan yang dilakukan para pelaku teror kepada satu sebab: radikalisme. Bagaimana cara mengatasinya? Deradikalisasi.
Belakangan, perang melawan ‘radikalisme’ melebar luas ke sejumlah wilayah lain, seperti perguruan tinggi, sekolah, dan masjid yang dianggap telah terpapar ‘radikalisme’. Beberapa profesor, dosen, dan mahasiswa yang dianggap radikal kemudian diproses oleh perguruan tinggi masing-masing. BNPT juga mengeluarkan daftar berisi tujuh universitas negeri ternama di Indonesia yang dianggap terpapar ‘radikalisme’, yang kemudian diklarifikasi oleh Menristekdikti sebagai dugaan belaka.
Tapi tepatkah kampus-kampus negeri dicap terpapar ‘radikalisme’? Kalau iya, radikalisme yang seperti apa?
Negara Juga Bisa Radikal
Kamus Merriam Webster mengartikan “radikal” sebagai opini atau perilaku orang yang menyukai perubahan ekstrem, khususnya dalam pemerintahan/politik. Kamus Inggris lainnya, Oxford Dictionary, memahami ‘radikal’ sebagai orang yang mendukung suatu perubahan politik atau perubahan sosial yang menyeluruh, seorang anggota dari suatu partai politik atau bagian dari partai politik yang melakukan upaya tersebut.
Awalnya berkembang di Inggris Raya, istilah radikalisme mengacu pada aktivitas-aktivitas yang menuntut perluasan hak pilih bagi seluruh warga negara. Di Perancis pada abad ke-19, kata radikal merujuk pada aktivis tiga partai—Partai Republikan, Partai Sosialis Radikal, dan Partai Radikal—yang anti-monarki. Sebelum digunakan untuk mengidentifikasi kaum komunis dan anarkis, istilah kiri-jauh (far-left) dilekatkan pada politik dan ideologi ketiga partai ini.
Ketiga partai ini berlawanan dengan kubu sayap kanan pro-monarki seperti Orléanist, Legitimist, dan Bonapartist—yang masing-masing mewakili tiga dinasti politik yang berbeda.
Sepanjang abad ke-19, para aktivis anti-perbudakan (abolisionists) di Amerika Serikat pun kerap dijuluki radikal oleh lawan-lawan mereka. Bahkan, John Brown, seorang kulit putih yang mengangkat senjata untuk membebaskan budak-budak kulit hitam diyakini sebagai “teroris domestik pertama Amerika”.
Singkatnya, radikalisme tak melulu berhubungan dengan agama. Center for Prevention of Radicalization Leading to Violence (2018) menyebutkan beberapa ekstremisme, antara lain: right-wing extremism, politico-religious extremism, left-wing extremism, dan single-issue extremism. Ekstremisme dan radikalisme dibedakan berdasarkan komitmen atas penggunaan kekerasan. Sebagai catatan, tak semua orang dan kelompok radikal akan jadi ekstremis. Namun benih-benih ekstremisme tertanam melalui fase radikalisasi bertahap.
Right-wing extremism alias ekstremisme sayap kanan umumnya berasosiasi dengan ideologi fasisme, rasisme, supremasisme, dan ultra-nasionalisme. Bartol & Bartol (2017) menyebutkan bahwa teroris sayap kanan di AS biasanya terdiri dari kelompok atau individu ekstremis yang umumnya memiliki pandangan rasis terhadap orang non-kulit putih dan kerap terlibat dalam berbagai bentuk kejahatan berlatar kebencian (hate crime). Warisan Perang Sipil Amerika (1861-1865) membuat ekstremis sayap kanan hingga kini membenci pemerintahan federal—yang menekan pemerintah-pemerintah negara bagian untuk menghapus perbudakan. Beberapa varian ideologi sayap kanan mendambakan pemerintahan yang otoriter.
Studi Elisabeth Carter (2018) menjelaskan bahwa radikalisasi sayap kanan umumnya mengambil bentuk kampanye kebencian terhadap kelompok minoritas (agama, ras, seksualitas), imigran, serta kelompok kiri. Neo-Nazi di Jerman, Golden Dawn di Yunani, serta Front National di Perancis adalah contohnya. Di Norwegia pada 2011, Anders Behring Breivik membantai sekitar 76 orang warga Norwegia. Tindakan tersebut didorong oleh kebenciannya terhadap para imigran (Muslim) serta kelompok-kelompok kiri dan liberal yang pro-hak-hak imigran.
Di Amerika Serikat pasca-Perang Sipil, Ku Klux Klan berkembang sebagai reaksi terhadap penghapusan perbudakan. Kelompok ini mengagung-agungkan supremasi kulit putih rasis, bersikap anti-imigran, anti-semit, dan anti-Katolik. Mereka percaya bahwa Amerika Serikat sejatinya adalah bangsa Protestan kulit putih.
Praktik dan ideologi Ku Klux Klan bisa dimasukkan sebagai politico-religious extremism, sebuah kategori yang melingkupi orang, kelompok, dan pemikiran sayap kanan yang menjustifikasi kampanye-kampanye kebenciannya dengan dasar ajaran agama. Orang dan kelompok dalam kategori ini juga percaya bahwa identitas agama mereka tengah diserang dan dirusak oleh musuh-musuh yang mereka bayangkan: ras minoritas, agama atau aliran tertentu, ataupun bangsa dan negara lain.
Jika kampanye kebencian adalah ciri yang melekat pada radikalisme sayap kanan, ekstremisme sayap kiri (left-wing extremism) umumnya lahir dari gerakan dan pemikiran anti-kapitalisme, anti-kolonialisme, dan militansi untuk mengubah sistem politik yang telah melahirkan ketidakadilan sosial.
Pada dekade 1960-70an di Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang, kelompok-kelompok sayap kiri radikal tumbuh dari perpecahan gerakan hak-hak sipil dan anti-perang yang berbasis kampus. Beberapa di antaranya menempuh jalan kekerasan, misalnya membom markas kepolisian, instansi militer, atau kedubes negara-negara yang mensponsori perang, atau membajak pesawat. Japanese Red Army di Jepang, Weather Underground Organization di Amerika Serikat, Red Army Faction di Jerman, adalah contohnya.
Ada pula single-issue extremism yang berangkat dari isu tunggal, misalnya kelompok pecinta binatang, pendukung anti-aborsi, gerakan anti-LGBT, anti-feminis dan lain sebagainya yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Pada 2009, sejumlah mobil milik ilmuwan neurosains di Universitas California at Los Angeles dibakar oleh para aktivis yang menolak uji coba terhadap kera dan tikus. Beberapa negara bagian AS yang baru melegalkan aborsi pada 1990an dan 2000an awal sempat diguncang oleh serangan bom dan penembakan terhadap klinik-klinik aborsi. Federal Bureau of Investigation (FBI) mengklasifikasikan kelompok ini sebagai special interests extremists, yang aktivitas-nya berputar pada isu-isu tunggal yang mereka geluti (Bartol & Bartol, 2017).
Di Perancis, sekularisme radikal tumbuh sebagai respons atas ancaman terhadap nilai-nilai sekularisme dan liberalisme yang memisahkan negara dan agama. Jika dulu, pada era Revolusi Perancis, yang dihajar oleh kaum sekular radikal adalah Katolikisme, kini serangan terarah kepada simbol dan pakaian yang terasosiasikan dengan Islam, seiring kemunculan aksi-aksi teror yang mengatasnamakan Islam. Contohnya adalah larangan total atas mpenggunaan burqa/ cadar yang menutupi seluruh wajah, burkini (pakaian renang khusus muslimah) di beberapa lokasi, atribut agama di sekolah-sekolah publik sejak 2004.
Di Eropa, yang biasanya identik dengan muslim adalah imigran asal Afrika dan Timur Tengah, khususnya setelah Perang Sipil Suriah. Tak heran jika di Perancis dan Belanda hari ini, sejumlah kalangan sekular radikal beraliansi dengan gerakan-gerakan sayap kanan anti-imigran.
Apakah negara bisa radikal dan melakukan aksi terorisme? Katherine Williams (2012) menyebutkan bahwa kekerasan negara bisa mengambil bentuk kekuasaan tirani. Bahkan dari kasus-kasus yang ada, kekerasan negara menyumbangkan korban lebih banyak daripada bentuk kekerasan dan radikalisme yang lain. Rummel (1994 dalam Williams, 2012) menghitung antara tahun 1900 sampai dengan 1987, sekitar 168 juta orang di dunia melayang nyawanya akibat dibunuh pemerintahnya sendiri.
Terorisme negara, menurut Jack Kitaeff (2017), bisa juga berupa tindakan-tindakan kelompok teroris yang dipekerjakan oleh pemerintahan (atau faksi pemerintah) dan bertindak melawan warga negara, faksi-faksi lawan di dalam pemerintahan, maupun menghantam pemerintahan/kelompok asing.
Uni Soviet dan sekutu-sekutunya, misalnya, diduga terlibat mendukung kelompok-kelompok bersenjata di berbagai belahan dunia yang kerap menggunakan metode terorisme selama era Perang Dingin. Rezim Pol Pot di Kamboja (1976-1979) membunuh sekitar tiga juta rakyat Cambodia. Di kubu lain selama Perang Dingin, Diktator Chili Augusto Pinochet (1973-1990) dan diktator Argentina Jorge Rafael Videla (1976-1981)—keduanya disokong Amerika Serikat—juga membantai orang-orang kiri di masing-masing negara melalui tangan serdadu dan paramiliter.
Jangan lupakan pula rezim junta militer Myanmar (1962-2012) yang amat kejam terhadap minoritas di Myanmar, termasuk etnis minoritas Rohingya di negara bagian Arakan yang hingga kini terusir dan tak diakui sebagai warga negara.
Radikalisme dan Kekerasan
Center for the Prevention of Radicalization Leading to Violence (2018) menyebutkan bahwa dalam proses radikalisasi, orang mengadopsi sistem kepercayaan yang ekstrem—termasuk keinginan untuk menggunakan, mendukung dan memfasilitasi kejahatan—dengan tujuan untuk mempromosikan ideologi, proyek politik, atau perubahan sosial.
Sementara bagi Bartol & Bartol (2017), radikalisasi adalah proses indoktrinasi terhadap individu sehingga ia menerima ideologi dan misi kelompok radikal tertentu. Orang yang terindokrinasi secara bertahap akan memaklumi aksi-aksi kekerasan yang dilakukan kelompok yang mengindoktrinasinya.
Tak mudah jadi teroris. Prosesnya sangat bertingkat, melibatkan banyak aktivitas dan komitmen-komitmen tertentu (Bartol & Bartol, 2017). Tak sedikit individu yang terlibat proses, namun kemudian gamang dan akhirnya batal menjadi teroris.
Studi Moskalenko & Cauley (2009) menjelaskan bahwa mayoritas orang-orang yang menjustifikasi suatu kekerasan politik justru tidak akan pernah terlibat dalam kekerasan politik tersebut. Ada banyak orang yang berpikiran radikal, namun malah tidak melakukan kekerasan.
Tak semua radikalisme beserta prosesnya melahirkan kekerasan, karena dinamika kehidupan personal memang berbeda-beda. Relasi individu dan lingkungan di sekitarnya, proses pengadopsian ideologi, dan tingkat kepercayaan terhadap penggunaan kekerasan demi tujuan yang ingin dicapai adalah beberapa dari sekian banyak faktor yang mendorong radikalisasi maupun deradikalisasi. Tak ada proses yang seratus persen sama untuk setiap individu. Dengan kata lain, sulit mencari garis penghubung yang pasti antara ideologi radikal dan aksi kekerasan.
Editor: Windu Jusuf
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id