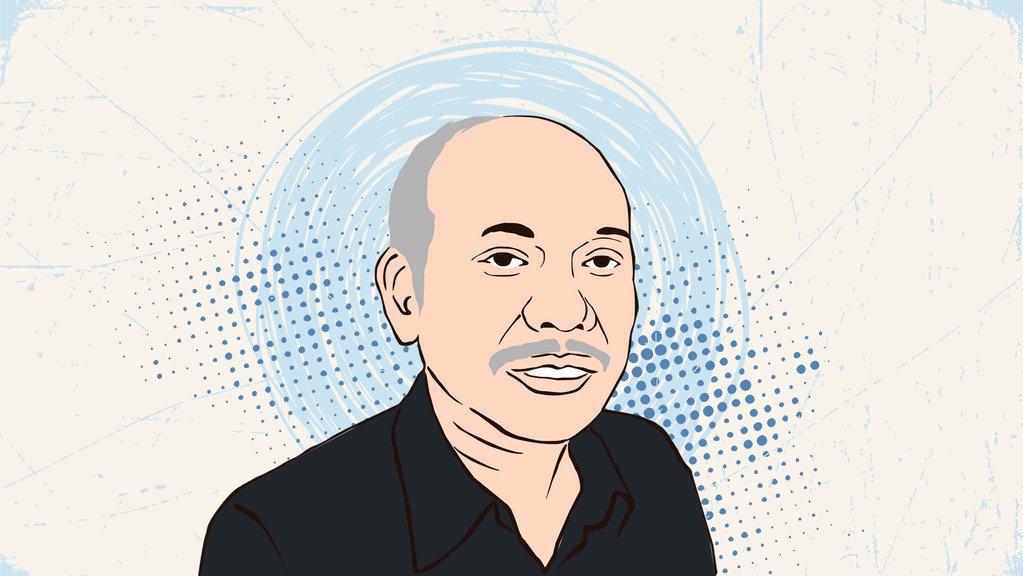tirto.id - Prasangka dan klaim perguruan tinggi sebagai pusat dan benih radikalisme menyeruak setelah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merilis hasil risetnya. Meski perlu diuji secara metodologi, riset yang dikemukakan BNPT membuat "politik ketakutan" setelah secara eksplisit menyebut tujuh perguruan tinggi negeri ternama terpapar ideologi radikal.
Ungkapan itu muncul dari Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Polisi Hamli pada Mei 2018. Saat didesak untuk menjelaskan dasar pernyataannya, Hamli menyebut publik bisa mengecek data penelitian dari lembaga lain, termasuk dari Badan Intelijen Negara.
Ucapan seorang pejabat dari lembaga yang lebih berwenang mengurusi "terorisme" ini bersamaan dengan gelombang penonaktifan sejumlah dosen yang dituding anti-Pancasila karena dituduh mendukung Hizbut Tahrir Indonesia, organisasi perkumpulan yang dilarang pemerintah pada 2017. Penghakiman ini disambut dengan wacana Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi akan mengawasi akun media sosial para dosen dan mahasiswa.
Guna mendapatkan sorotan dan pendapat yang lebih terbuka soal isu ini, Tirto mewawancarai Azyumardi Azra, cendekiawan muslim dan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Ia berkata benih radikalisme di kampus tumbuh karena makin berkembang organisasi mahasiswa berpandangan kanan. Tak cuma HTI, katanya, organ mahasiswa seperti Lembaga Dakwah Kampus dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia pun jadi pintu masuk penyemaian bibit radikalisme.
Di sela kesibukan menghadiri beragam undangan acara, termasuk peluncuran buku di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Azyumardi meluangkan waktu untuk berbagi pandangannya kepada Arbi Sumandoyo dari Tirto, mengenai tuduhan, indikasi, dan problem radikalisme di perguruan tinggi.
Menurut Anda, apa pemicu kalangan akademisi terpapar paham radikal sebagaimana temuan riset BNPT?
Pertama saya kira mungkin, sebelum menjadi dosen, mereka sudah aktif di organisasi-organisasi yang memang cenderung ke kanan. Organisasi ke kanan itu seperti LDK (Lembaga Dakwah Kampus), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan yang lebih keras, paling radikal: HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).
Kedua, kalau mereka tidak aktif dalam organisasi radikal, mungkin karena keilmuannya. Keilmuan eksakta, misalnya. Ilmu alam itu cenderung melihat dunia sebagai hitam-putih. Jadi, orang-Islam yang cenderung hitam putih lebih mudah biasanya terpapar atau menerima ide-ide radikalisme.
Ketiga, mungkin dosen itu tidak memiliki pemahaman Islam yang komprehensif, mengenai macam-macamlah, mengenai politik, ekonomi atau mungkin mengenai fikih atau soal teologi.
Keempat, mereka tidak paham isu-isu politik Indonesia; misalnya, menyangkut katakanlah demokrasi. Ada yang bilang demokrasi tidak sesuai dengan politik Islam; dia dengan cepat menerima itu. Atau, misalnya ekonomi Indonesia sudah neoliberal: "Kita sedang dijajah." Karena dia tidak paham soal politik dan ekonomi Indonesia, dia terima saja argumen itu, sehingga kemudian mudah menerima paham politik dan ekonomi yang radikal.
Definisi radikal dari temuan BNPT dikritik oleh kalangan akademisi karena ukurannya hanya anti-Pancasila?
Saya kira mungkin tingkat kategorisasi yang diadopsi oleh P3M (lembaga perhimpunan pengembangan pesantren dan masyarakat) bisa dipakai. Misalnya, orang itu radikal karena menganggap orang Islam menerima demokrasi sebagai orang yang sudah menyimpang. Kemudian, radikal-moderat ketika menolak orang Islam mengucapkan selamat Hari Natal atau menerima ide khilafah. Lalu, kriteria radikal paling tinggi: ketika ingin berjihad, perang untuk menegakkan khilafah.
Kalau LDK dan KAMMI tadi Anda katakan radikal, bukankah gerakan mahasiswa ini terkait dengan partai?
Sebetulnya tidak ada hubungan langsung dengan partai-partai. Karena partai kita pada umumnya moderat. Baik yang Islam seperti PKS dan PPP, walaupun orientasi keislamannya lebih ketat. Tapi, saya kira, kelompok-kelompok radikal dengan berbagai tiga tingkatan itu membuat berkembang di kalangan dosen dan mahasiswa karena tidak ada gerakan tandingan yang menyainginya.
Mereka, sejak NKK/ BKK, itu organisasi ekstra: kelompok Cipayung, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan seterusnya itu tidak boleh masuk kampus. Akibatnya apa? Seluruh wacana dan gerakan mahasiswa di kampus cenderung dikuasai oleh LDK dan KAMMI, terutama di perguruan tinggi umum. Karena itu Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) universitas dan fakultas itu kebanyakan dari mereka; selalu anak-anak dari LDK dan KAMMI; seperti di Institut Pertanian Bogor, di Universitas Indonesia. Tapi, di IAIN masih mendapat persaingan ketat dari HMI dan PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Sehingga HMI dan PMII yang selalu bergantian menjadi presiden BEM dan sebagainya.
Bagaimana soal pandangan bahwa organisasi keagamaan luput bergerak mengatasi radikalisme di kampus?
Kita tidak bisa mengaitkan NU dan Muhammadiyah karena memang sejak dari dulu tidak pernah berorientasi di kampus. Tidak ada NU dan Muhammadiyah masuk kampus, kecuali sayap-sayapnya. Muhammadiyah melalui UMM dan NU melalui PMII. Jadi itu tidak terlalu terkait dengan organisasi masyarakat.
Jadi, menurut saya, kita tidak bisa mengharapkan ormas-ormas itu bisa langsung masuk kampus. Karena itulah yang lebih efektif adalah organisasi ekstra, kelompok Cipayung itu. Kalau mereka bisa bergerak di kampus, diizinkan kembali, maka LDK dan KAMMI itu tidak leluasa.
Apa langkah kampus mengatasi radikalisme di lingkungannya?
Pertama, pimpinan universitas harus mengontrol fasilitas kampus, masjid, musala, dan ruang-ruang pertemuan. Jadi jangan dibebaskan, diberikan sebebas-bebasnya kepada mahasiswa karena masjid, musala, dan bahkan student center bisa digunakan kegiatan-kegiatan radikal.
Kedua, saya kira, perlu penguatan kembali mata kuliah yang punya kaitan dengan penguatan kebangsaan. Misalnya, Pancasila, kewarganegaraan, sejarah, ilmu sosial harus diperkuat dengan konteks kebangsaan.
Bukankah mata kuliah itu sering dipandang membosankan?
Ya itu harus menjadi kebijakan universitas: mahasiswa ikut semua. Jadi harus ada ketegasan dari rektor dan senat universitas, senat akademik, senat guru besar. Terakhir, pihak kampus harus kembali mengatur kebebasan kampus.
Kebebasan kampus adalah bidang akademik: ilmiah. Tapi tidak dalam bentuk misalnya menyebarkan anti-NKRI dan anti-Pancasila. Karena sekarang ini kebebasan kampus, otonomi kampus, untuk penyebaran paham seperti itu.
Kenapa kita misalnya tidak boleh punya ide mendukung khilafah? Karena itu perlu batasan yang jelas. Pokoknya, otonomi kebebasan akademik itu menyangkut keilmuan, tidak menyangkut, misalnya, kebebasan dalam ide-ide politik. Misalnya, mau mendirikan gerakan negara Islam, Daulah Islamiyah, maupun Khilafah.
Perlu rumusan-rumusan yang jelas, apa itu yang dimaksud otonomi kampus: kebebasan akademik. Tapi kebebasan ini tidak dalam konteks mengganti ideologi negara.
Apa istilah tepatnya menurut Anda, gerakan radikalisme atau Islamisme?
Lebih dari itu. Kalau misalnya dia menolak pemahaman Islam yang berbeda dari mereka, mungkin bisa disebut soft radicalism. Tapi bila sudah sampai pada tingkat mau berjihad, mau mendirikan khilafah, itu sudah sangat radikal sekali. Itu sudah revolusioner.
Anda tadi menjelaskan soal ilmu eksakta, bisa dijelaskan kenapa program studi ini paling mudah terpapar radikalisme?
Karena belajarnya pasti-pasti saja, ada rumus-rumus, teori yang sudah pasti semua, hitam-putih. Tapi kalau bidang ilmu sosial dan humaniora ada bidang yang abu-abu. Karena agama itu berinteraksi dengan masyarakat, dengan lingkungan, dengan sosial dan budaya, sehingga keadaan seperti itu tidak bisa hitam-putih.
Disiplin ilmu itu membentuk cara berpikir. Cara berpikir hitam-putih itu dipengaruhi oleh paradigma ilmu-ilmu eksakta.
Penulis: Arbi Sumandoyo
Editor: Fahri Salam
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id