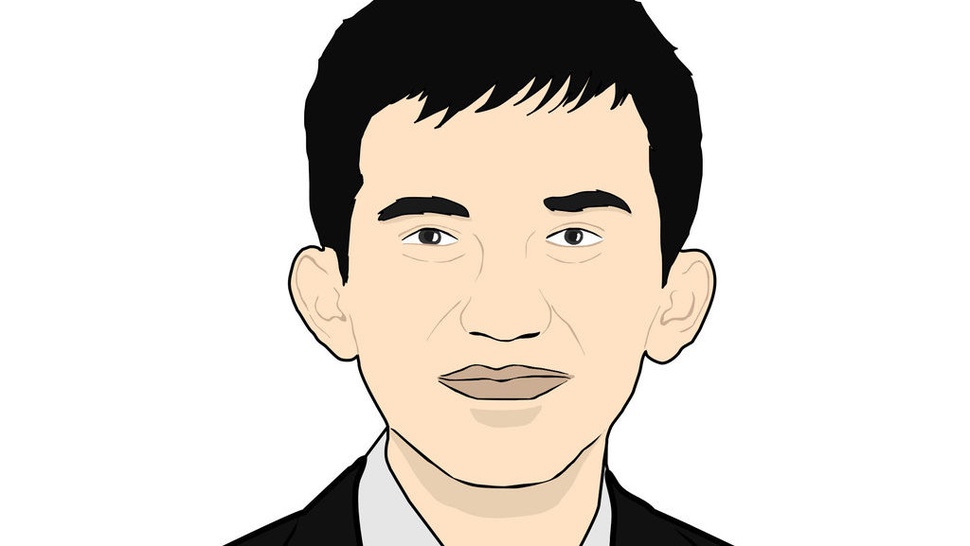tirto.id - Kehadiran Presiden Joko Widodo ke KTT One Belt One Road (OBOR) di Beijing, pekan lalu, menandakan pemerintahan saat ini, bersama 29 negara lain, enggan ketinggalan peluang ekonomi yang dibawa “kereta cepat” Jalur Sutra. Sulit, memang, untuk tidak tergiur pada inisiatif Presiden Tiongkok Xi Jinping yang sudah mengumumkan siap menyuntikkan dana sekitar 1.100 miliar dolar AS itu.
Dinukil dari laman Kementerian Luar Negeri, Jokowi yakin OBOR “akan lebih memperkokoh hubungan ekonomi antara kedua negara, terutama karena Indonesia memiliki fokus pada pembangunan infrastruktur, konektivitas dan poros maritim.” Walakin, ada beberapa risiko ekonomi yang akan dihadapi Indonesia seiring dengan semakin dalamnya langkah negara ini masuk ke pusaran politik infrastruktur Tiongkok tersebut.
(Baca: Jokowi Tawarkan Tiga Megaproyek saat Bertemu Presiden Cina)
Pertama, menggelembungnya defisit perdagangan. Langkah Tiongkok memangkas laju ekonomi ke “kondisi normal” (xin changtai) sekitar 6,5 persen mengakibatkan berkurangnya permintaan Negeri Tirai Bambu terhadap bahan baku dari Indonesia. Bahan baku itu termasuk batu bara, bijih nikel, dan bahan tambang lain. Tiongkok adalah eksportir utama Indonesia.
Di sisi lain, saat basis industri domestik masih rapuh seperti sekarang, langkah Jokowi menggenjot proyek infrastruktur sebagai penyangga vital mewujudkan cita-cita menjadi “Poros Maritim Dunia” akan berakibat pada pelonjakan impor mesin, peralatan listrik, besi/baja, dan barang modal (capital goods) lain dari Tiongkok. Harga barang-barang dari Negeri Panda ini memang lebih terjangkau ketimbang produk dalam negeri lantaran kelebihan kapasitas produksi (excess capacity) berjibun dari “perusahaan zombie” Tiongkok.
(Baca: Pertemuan 'Jalur Sutra' dan 'Poros Maritim')
Buktinya, data Kementerian Perdagangan Tiongkok menunjukkan proporsi ekspor mesin-mesin dan peralatan listrik Tiongkok ke Indonesia naik dari 24,2 persen pada 2005 menjadi 46 persen pada 2015, menjadikannya importir terbesar ke Indonesia. Nilai ekspor besi/baja dan benda-benda turunannya juga meningkat dari 426,4 juta dolar AS (2004) ke 3,089 miliar dolar AS (2015). Sebaliknya, ekspor barang-barang tambang Indonesia ke Tiongkok justru turun dari 11,93 miliar dolar AS (2013) ke 4,98 miliar dolar AS (2015).
Alhasil, dalam perniagaan dengan Tiongkok, Indonesia selalu tekor sampai belasan miliar dolar AS saban tahun. Ke depan, senyampang Indonesia tidak melakukan diversifikasi ekspor, kerugian akibat ketimpangan ekspor-impor ini sangat mungkin akan membengkak. Apa yang disebut diversifikasi ekspor ini mensyaratkan Indonesia mesti menganekaragamkan jenis produk ekspor (horizontal) maupun memperbanyak ekspor produk hilir (vertikal). Kondisi ini ditunjang pemerintah Indonesia belum berhasil melobi Tiongkok melonggarkan pengetatan masuknya sektor hortikultura beserta 30 komoditas ekspor lain yang diganjal hambatan nontarif.
Kedua, membeludaknya tenaga kerja dari Tiongkok. Pembiayaan investasi pembangunan megaproyek infrastruktur oleh Tiongkok banyak menggunakan preferential buyer’s credit (PBC). Talangan lunak ini memang terkesan murah hati. Namun, tujuan utamanya mendorong ekspor sektor yang bersifat strategis untuk membuka pasar ekspor baru sebagai solusi menyempitnya pasar ekspor Tiongkok lantaran kondisi ekonomi global yang masih megap-megap. Dengan instrumen pinjaman tersebut, tidak hanya mensyaratkan sedikitnya 70 persen barang-barang kebutuhan proyek mesti dibeli dari Tiongkok, tetapi juga mengizinkan buruh mereka bekerja pada proyek-proyek yang digarap.
Karena itu menjadi jelas kenapa dalam masa 11 bulan saja terjadi penaikan sekitar 21 persen jumlah tenaga kerja Tiongkok dari 17.515 orang sepanjang 2015 ke 21.271 orang pada 2016. Pelonjakan pekerja ini berbanding lurus dengan jumlah proyek Tiongkok sebanyak 1.052 pada 2015, lantas menanjak 1.734 proyek pada 2016, sebagaimana perincian Badan Koordinasi Penanaman Modal. Artinya, semakin banyak proyek investor Tiongkok di Indonesia, semakin besar pula kemungkinan membanjirnya tenaga kerja mereka ke negara kita, legal atau pula sebaliknya.
(Baca: Heboh Serbuan Tenaga Kerja Cina)
Perlu diingat, ketika tingkat pengangguran terbuka Indonesia masih tergolong tinggi (5,33 persen pada Februari 2017), Indonesia menawarkan sembilan proyek senilai 2,5 miliar dolar AS khusus kepada Tiongkok menggunakan skema pendanaan PBC, 9 Mei 2016 lalu. Proyek ini mencakup jalan tol, terowongan, dam, pengadaan material jembatan dan rel kereta.
Tentu, walau demikian, tidak elok apabila melihat investasi Tiongkok ke Indonesia, atau langkah Jokowi mendekat ke Cina, dari sisi negatif belaka.
Murahnya barang modal dari Tiongkok dan penetrasi tenaga-tenaga ahli mereka, bisa pula kita jadikan peluang untuk menekan biaya sekaligus mempertinggi efisiensi target-target pembangunan melalui transfer ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir. Dengan syarat: pemerintah mampu membuat aturan main menjaga kesetimbangan kepentingan nasional di tengah fakta investasi Tiongkok yang, mengutip Kepala BKPM Thomas Lembong kepada Reuters, sedang menjadi “faktor penggerak penting ekonomi Asia”.
Kita patut mengakui, Tiongkok bisa semaju sekarang berawal dari penggalakan pembangunan infrastruktur sejak digulirkan kebijakan Reformasi dan Keterbukaan (Gaige Kaifang) pada 1978. Semboyan mereka kala itu “yao zhi fu, xian xiu lu”. Maknanya, “Jika ingin sejahtera, bangunlah jalan raya”.
Meskipun Presiden Xi Jinping dalam pidato pembukaan KTT Jalur Sutra menegaskan “tidak akan menyebarkan, apalagi memaksakan, model ekonomi Tiongkok kepada negara lain”, tetapi—memakai judul buku Dahlan Iskan—“Pelajaran dari Tiongkok” ini layak kita teladani.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.