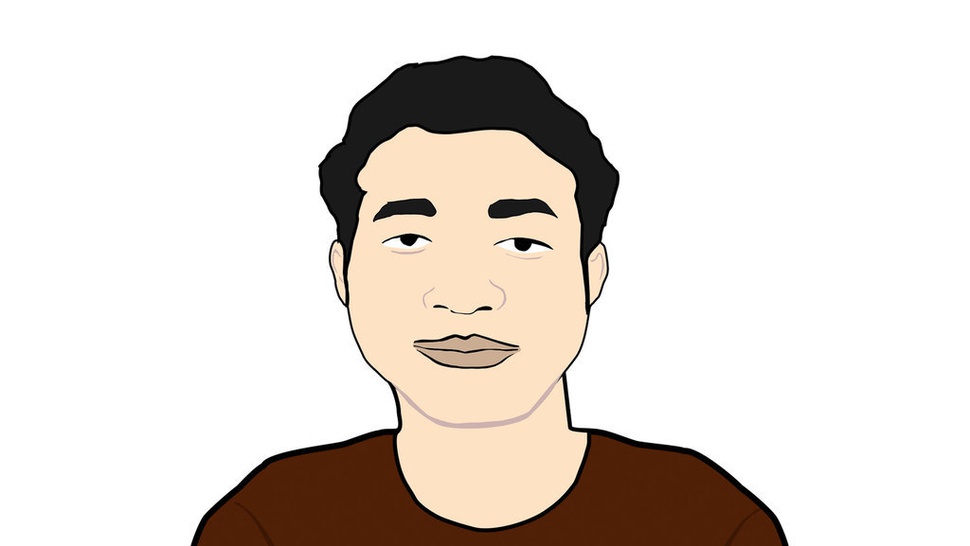tirto.id - Setidaknya ada dua nama yang terus dibahas terkait bursa Pilpres 2019: Joko Widodo dan Prabowo. Kepopuleran keduanya dalam berbagai survei membuktikan ketokohan mereka masih melekat kuat di mata publik.
Di samping itu, Pilpres 2014 memang terkesan seperti pertarungan yang belum tuntas. Tentu bukan cuma soal selisih perolehan suara kedua kandidat yang tidak jauh (6,3 persen). Belum tuntasnya pertarungan politik cenderung disebabkan karena mesin politik eks-capres sampai hari ini belum juga kunjung “dingin”.
Pilpres 2014 adalah polarisasi keras antara gaya politik dua kelompok besar. Hasil Pilpres berlanjut hingga ke tahap “rivalitas intra-pemerintahan”. Konflik politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah-Putih (KMP) adalah contoh betapa kerasnya pertarungan yang berlanjut ke hulu proses demokrasi: DPR RI. Kubu yang satu boleh memenangkan kursi presiden (eksekutif), tetapi kubu lainnya mengunci fungsi perundangan dan anggaran (via legislatif).
Kondisi semacam ini menunjukkan bagaimana masing-masing kelompok politik punya gaya politik yang khas. Ada banyak unsur dalam gaya politik, antara lain mesin ekonomi (kepemilikan sumber daya bisnis), mesin politik (jaringan dan konstituen), sampai brand yang ditanamkan pada publik (visi, janji, label figur, dan komunikasi politiknya).
Kemenangan Pilpres adalah keberhasilan menarik simpati publik secara langsung yang diperoleh dari pencitraan bersifat personal. Gaya muda, penampilan kasual, kemajuan karier politik, dan harapan kebaruan adalah gimmick politik yang pengaruhnya dengan cepat bisa membesar lewat media masssa (televisi, cetak, dan media sosial). Pilihan politik per individu yang tertarik terhadap hal-hal semacam itu terkonversi langsung jadi pilihan atas sosok presiden.
Di sisi lain, kemenangan Pileg adalah keberhasilan mengumpulkan suara lewat jaringan lapangan via gerilya para caleg. Sifat kampanye legislatif relatif berbeda dibandingkan kampanye presiden. Caleg dan parpol punya kedekatan politik ke bawah (basis massa) lebih tinggi dan tersebar. Mereka dikenal secara personal di akar rumput karena lebih tidak berjarak daripada presiden. Kedekatan inilah yang bisa dikonversi menjadi suara untuk anggota dewan.
Kini koalisi politik legislatif telah berubah. Di DPR, sisa-sisa KMP tinggal Gerindra dan PKS. Sembilan partai pendukung Jokowi sebagai capres pada Pilpres 2019 adalah jumlah mayoritas dari daftar parpol peserta Pemilu 2019 (Nasdem, PSI, Golkar, PPP, Hanura, Perindo, PKP, PDIP, dan PKB).
Apakah masifnya dukungan bisa memproyeksi kemenangan di tangan Jokowi tahun depan? Ada dua ukuran buat menerka arah pertarungan politik tahun depan.
Kekuatan Media
Ukuran pertama, bagaimana elektabilitas capres dinaikkan melalui pencitraan. Popularitas capres adalah satu faktor di antara faktor lain, yaitu kekuatan parpol dan jaringannya sebagai kunci kekuatan politik. Lima parpol pendukung kampanye Jokowi pada 2014 mendapat suara sekitar 37 persen DPR, sedangkan suara Pilpres sekitar 53 persen (organic voters). Asumsinya, elektabilitas personal Jokowi (direct voters) adalah 16 persen.
Media massa tetap faktor determinan yang mempengaruhi simpati publik. Menurut survei Nielsen Consumer Media View (NCMW) pada 2017, penetrasi televisi masih berkisar di angka 96 persen. Pada 2014, elektabilitas personal Jokowi digenjot media Surya Paloh (grup Metro TV). Sedangkan Prabowo didukung dua konglomerat media, Harry Tanoesoedibjo (grup MNC) dan Aburizal Bakrie (TV One dan ANTV).
Hari ini, Jokowi didukung sembilan parpol. Mayoritas jaringan televisi swasta juga milik para bos media yang pro-Jokowi. Dalam jajaran itu, paling tidak sudah ada Harry Tanoesoedibjo (RCTI, GTV, MNC TV, dan iNews), Aburizal Bakrie (TVOne dan ANTV), dan Surya Paloh (Metro TV). Ini belum termasuk jaringan bisnis televisi yang dipegang tokoh dan organisasi terkait bisnis (saham perusahaan) dan politik yang jumlahnya puluhan. Faktanya, konglomerat media tidak hanya menjalankan bisnis di satu jenis media (televisi), namun menguasai pula koran cetak, online, dan radio jaringan nasional dan lokal.
Dengan ukuran peningkatan elektabilitas lewat peta jaringan media semacam itu, Jokowi layak dianggap kokoh.
Kekuatan Komunitas
Ukuran kedua terkait cara parpol memaksimalkan jaringan politik lokal (basis massa) dan pengelolaan isu. Jika ditambah jumlah anggota dewan dan kepala daerah, gabungan parpol non-Jokowi relatif masih sama kuatnya dalam jaringan politik lokal. Asumsikan jika kekuatan ke bawah relatif sama, maka pertarungannya adalah soal mengelola isu sehingga bisa mempengaruhi cara pandang publik dalam menentukan presiden yang pantas.
Calon petahana terbuka untuk diserang dari berbagai aspek. Sederet prestasi yang megah bisa cacat oleh segelintir kesalahan yang digaungkan lawan. Inilah yang sedang dilakukan kelompok non-Jokowi. Rivalitas tidak dilakukan dengan mengimbangi platform politik (visi kebijakan, keberpihakan, atau model pembangunan alternatif). Oposisi menjatuhkan citra pemerintah dengan rangkaian kritik yang destruktif, karena memang tidak melulu harus rasional. Jika ini yang terjadi, kemungkinan besar peta yang terbangun nantinya mengarah pada rivalitas Jokowi versus “asal bukan Jokowi”.
Pilkada DKI Jakarta adalah memeri pengalaman baru yang harus diperhitungkan. “In politics, if you can’t convince them, confuse them,” ujar mantan Presiden AS Harry Truman. Bisa dipahami mengapa bermunculan praktik pengelolaan isu tandingan via media digital. Grup-grup di Facebook dan aplikasi perpesanan menjadi konsolidasi efektif mengubah pandangan dan tindakan publik melalui isu SARA. Kementerian Kominfo melansir ada 800 ribu situs hoaks, yang umumnya menebar kebencian (hate speech) lewat isu SARA dan kampanye negatif/hitam terhadap kinerja pemerintah.
Komunitas muda pendukung Jokowi sekarang terdiri dari sisa pendukung pasca Pilpres 2014. Solid atau tidaknya relatif. Yang jelas, gaya politik pemerintah saat ini lebih fokus mempertahankan citra capaian Presiden alih-alih mengelola isu yang dinamis. Sebaliknya, gaya politik kontra-Jokowi mampu beradaptasi dan menciptakan wacana tandingan yang praktis. Walaupun sekarang sulit diukur keberhasilannya, tren media sosial seperti tagar #gantipresiden2019, perdebatan “partai tuhan-partai setan”, atau sejenisnya adalah wujud keleluasaan melancarkan strategi politik apapun.
Gerakan berbasis komunitas, apalagi jika dipersenjatai media sosial, selalu lebih kuat pengaruhnya dibandingkan dengan simpati yang muncul akibat media konvensional. Jangan lupa, pengguna Facebook di Indonesia peringkat empat dunia (130 juta pengguna). Belum lagi sekitar 90 juta pengguna aktif Line, 53 juta pengguna aktif Instagram, dan 50 juta pengguna aktif Whatsapp.
Dengan ukuran jaringan politik dan basis massa, agaknya kelompok non-Jokowi lebih leluasa merancang arena pertandingan. Penyebaran informasi media alternatif pun bisa diarahkan pada tindakan kolektif.
Antitesis Gaya Kepemimpinan
Apakah hal semacam ini patut diperhitungkan? Media sosial punya kekuatan mobilisasi massa lebih cepat karena bebas dari etika jurnalistik dan pertanggungjawaban. Kelompok usia muda dan tengah adalah segmen berkarakter konsumen sekaligus produsen informasi. Jika informasi bersifat provokatif, tindakan komunal jadi kelanjutannya. Aksi 411 dan 212 adalah bukti kekuatan komunitas yang terkonsolidasi dalam isu alternatif. Dalam gerakan tersebut, masyarakat usia muda dan rentang usia tengah (30-40 tahun) menjadi kelompok mayoritas.
Isu alternatif jadi faktor penting dalam siklus politik. Dalam konteks ini, Jokowi pada Pilpres 2014 dianggap semacam “antitesis” (kebalikan) dari kepemimpinan figur militer SBY. Saat itu, unsur “kebaruan” sebagai gimmick politik Jokowi cukup efektif meningkatkan elektabilitas personalnya.
Hari ini, kemunculan nama selain Prabowo seperti Gatot Nurmantyo dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai capres potensial sangat mendukung kecenderungan siklus politik tersebut. Fokus perhatian pemerintah adalah pembangunan infrastruktur, namun lemah mengelola konflik horizontal. Ditambah isu alternatif lain seperti nasionalisme garis keras (yang memainkan sentimen asing-pribumi) dan islamisme (isu “pemimpin Muslim”), petahana terkesan memainkan kepemimpinan yang sangat bergaya sipil.
Tentu “antitesis”-nya adalah kepemimpinan yang disiplin, nasionalis, dan islamis. Gaya kepemimpinan yang satu selalu digantikan dengan gaya yang berkebalikan. Soekarno (sipil), Soeharto (militer), Gus Dur (sipil-Islam), Megawati (sipil-nasionalis), SBY (militer), hingga Jokowi (sipil).
Apakah siklus semacam ini sehat bagi demokrasi? Siklus politik adalah keniscayaan di pemilu manapun. Persoalannya adalah jika yang selalu dijual sekadar latar belakang figur. Hal ini hanya akan mengulang-ulang pertarungan politik lawas sekaligus mengikis rasionalitas publik. Masyarakat hanya disuguhi pilihan asumtif bahwa karena gaya kepemimpinan yang ada telah gagal, maka gaya kepemimpinan yang sebaliknya patut dicoba.
Terkikisnya rasionalitas publik juga semakin bermasalah karena tingkat elektabilitas melibatkan kerja-kerja media yang membelah masyarakat (konvensional versus alternatif) sebagaimana dijelaskan di atas. Masyarakat dibiasakan saling sinis dan berdebat tanpa sanggup menimbang validitas dan urgensinya.
Di satu sisi konvergensi media membuat jaringan media nasional membuat pemberitaan senada. Di sisi lain media alternatif bak hutan rimba informasi yang sulit dipertanggungjawabkan. Masyarakat lagi-lagi hanya jadi kantong suara.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.