tirto.id - Oktober lalu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dibuat geram. Jawabannya dalam wawancara khusus di iNews TV dipelintir dan dipotong. Berita bohong itu pun menyebar luas di media sosial. Mahfud buru-buru melakukan klarifikasi melalui akun Twitter-nya.
“Saya perlu mengklarifikasi. Beberapa media online dan medsos telah memelintir pernyataan saya tentang status Ahok yang sudah jadi tersangka,” kata Mahfud, 11 November lalu.
Mahfud memang diundang dalam wawancara khusus di iNews mengenai proses hukum Ahok pada 16 November, hari yang sama ketika Basuki Tjahaja Purnama ditetapkan tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri. Ahok diusut pidana karena dianggap menodai agama dengan mengutip Surat Al-Maidah 51. Mahfud menyampaikan pandangannya ketika dia diwawancara presenter iNews.
Isi wawancara yang tersebar tidak sesuai dengan rekaman asli. Pandangan Mahfud dipotong menjadi beberapa bagian. Bahkan ada penyataan yang tak pernah diucapkannya. (Salah satunya “Mahfud MD: Ahok harus ditahan”.) Mahfud memberi klarifikasi: “Itu juga bohong. Saya bilang, 'Tak ada keharusan bagi polisi menahan Ahok.'”
Karena kejadian itu, Mahfud masih emoh melayani wawancara media. Reporter Tirto.id pekan lalu meminta pandangannya mengenai proses persidangan Ahok, tapi Mahfud menolak.
“Saya minta maaf. Tak bicara dulu, biar tak tambah ribut. Ikuti proses hukum,” katanya, 8 Desember lalu.
Potongan wawancara tokoh tersohor mengenai isu tertentu memang belakangan sering beredar dalam bentuk berita di linimasa. Tiga bulan belakangan, suhu politik di Jakarta mendidih. Kondisi itu kemudian dimanfaatkan untuk menyebarkan berita bohong. Tujuannya, mengajak orang lain percaya dengan informasi itu. Sebagaimana pameo: bila kebohongan terus-menerus dihadirkan maka sangat mungkin dicerna menjadi kebenaran.
Wisnu Prasetya Utomo, peneliti Remotivi, mengamati bagaimana dampak dari sebaran berita palsu atau hoax. Menurutnya, sebaran berita hoax kini mengarah bentuk nyata, yaitu kekerasan. Dia mencontohkan, berita boikot Metro TV berujung pada kekerasan pekerja media milik Surya Paloh itu ketika melakukan peliputan demonstrasi anti-Ahok yang disebut “Aksi Bela Islam II”, 4 November. Kekerasan itu kemudian menular kepada jurnalis Tirto.id, Reja Hidayat sehari sebelum “Aksi Bela Islam III” di Markas FPI, Petamburan. Reja dipukul oleh anggota Laskar FPI.
“Efek paling buruk, menurut saya, bisa memprovokasi orang dengan informasi palsu,” ujar Wisnu via telepon. Dia mengatakan, provokasi berbentuk kekerasan itu mulai terlihat.
Kebencian yang Terus Disebarkan
Kemunculan berita hoax yang lantas tersebar meluas bukan kebetulan. Tingkat pengguna internet di Indonesia tahun 2016 menurut data Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) mencapai 132 juta orang, dan 100 jutanya pengguna telepon pintar. Ia menjadi musim panen di media sosial dalam memetik kabar bohong dengan cepat. Mayoritas pengakses internet ini dari kota-kota besar di Pulau Jawa termasuk Jakarta yang dinilai sebagai ibukota media sosial.
Lahan telah tersedia. Perkakas informasi bohong tinggal digarap dengan memindai emosi pembaca berdasarkan keyakinan agama, etnis, maupun politiknya.
M Yamin El Rust, direktur eksekutif Yayasan Nawala, mengamati bagaimana berita hoax itu kini jadi ladang bisnis. Menurutnya, berita hoax kini mulai berpindah haluan. Jika dulu kabar bohong dijadikan bahan lelucon, kini sebaran itu berubah jadi sebuah “berita” yang memuat kebohongan dengan maksud tertentu.
“Kalau sekarang tujuannya berubah. Memberitakan selama ini yang diyakini benar,” ujar Yamin via telepon, Rabu (14/12). Dia menegaskan, sebaran berita hoax sejatinya sudah ada dari dulu di Indonesia. Namun, belakangan kini jadi ujaran kebencian.
“Sudah mau mengubah keyakinan,” ucapnya.
Berita hoax berdampak secara psikologis terhadap penerimanya. Apalagi jika berita itu dibaca berulang-ulang.
Anindito Aditomo, peneliti dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, mengatakan dampak psikologis itu bisa diamati di media sosial maupun orang-orang yang kita kenal secara langsung.
“Secara afektif, hoax seringkali memicu emosi negatif seperti marah, cemas, dan takut,” kata Anindito kepada Tirto.id, 15 Desember kemarin. Dalam konteks situasi politik di Indonesia yang sedang panas saat ini, ujarnya, berita hoax dipakai untuk mendiskreditkan seorang tokoh atau kelompok yang bersebrangan.
“Karena itu berita hoax biasanya mengaitkan tokoh atau kelompok tertentu dengan konsekuensi atau kejadian negatif yang menakutkan,” kata psikolog dari Universitas Surabaya ini.
Anindito mencontohkan, berita hoax mengenai pekerja asing yang diam-diam masuk ke Indonesia bikin orang-orang cemas dan marah, terutama bagi mereka yang secara ekonomi miskin dan bernasib malang.
“Hoax juga bisa menimbulkan kemarahan dan kesedihan jika ditujukan pada tokoh atau figur yang jadi idola atau panutan.”
Wisnu mengatakan berita hoax memanfaatkan sentimen emosi pembaca. Si penyebar mengajak orang yang membacanya agar sepaham dengannya. Karena sentimen emosi ini menjadi bensin bagi berita hoax cepat terbakar dan menyebarkan asap kebencian.
“Karena sentimen emosi, maka masalahnya tidak berhubungan dengan tingkat pendidikan seseorang,” ujar Wisnu.
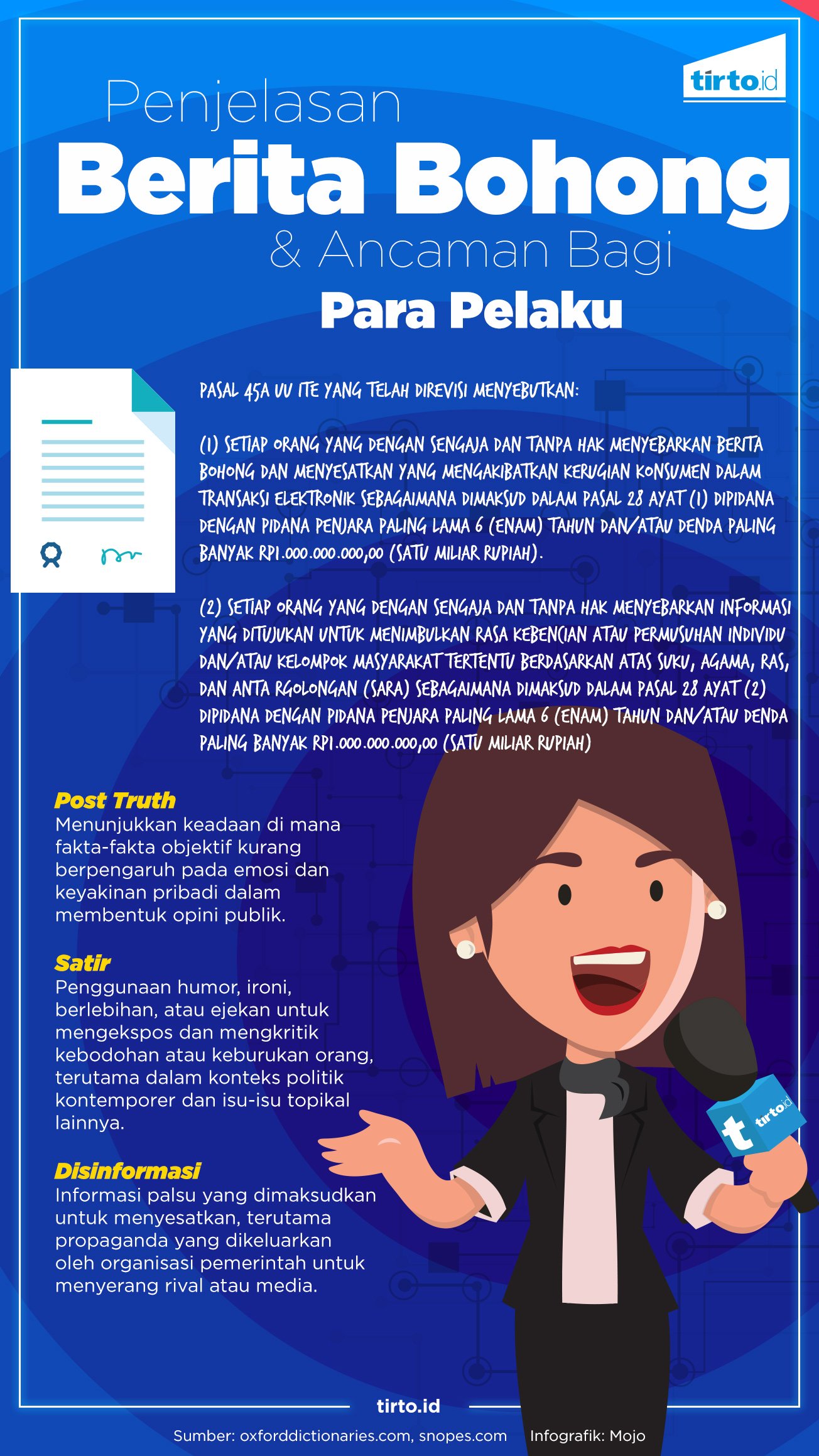
Menangkal Hoax dengan Literasi
Menurut Wisnu, solusi buat menangkal berita hoax yang kini sebarannya semakin meluas dan sistematis adalah dengan menggencarkan budaya membaca.
“Jadi bisa saja, orang lulusan S3 atau profesor, tapi karena yang disasar itu emosinya, maka berita hoax itu mudah saja tersebar lewat tangannya,” ujar Wisnu.
Tidak semua orang mampu membaca berita, menurut Wisnu. “Bukan hanya sentimen. Kadang, orang-orang berusia 50 tahun ke atas, misalnya, ketika membaca berita di media sosial itu kan gagap, ya. Tetapi sering kali mereka membaca media itu, dan merasa cemas, 'Ini benar atau tidak, ya?'”
Jadi, solusinya bukan jangka pendek seperti yang dilakukan pemerintah saat ini dengan pemblokiran. Tetapi jangka panjang: literasi media. Mengenali mana berita palsu dan mana berita jurnalisme.
Hasil penelitian Connecticut State University tahun ini menyebut Indonesia di urutan 60 dari 61 negara berdasarkan tingkat literasi membaca. Indonesia belum menunjukan performa dalam uji keterampilan membaca di level internasional. Bahkan 50 persen pelajar Indonesia berusia 15 tahun tidak memiliki keterampilan dasar membaca. Soal tidak melek media dan informasi ini ditambah dengan kemajuan teknologi digital.
Wisnu mengatakan, kesadaran pemerintah untuk membuat terobosan menangkal berita hoax jauh lebih efektif dibanding dengan melakukan pemblokiran situs.
“Nah bicara soal ini, harusnya bisa dimasukan ke kurikulum pendidikan. Kalau kita mau menangkal berita hoax, solusinya adalah bagaimana orang membaca dengan kritis,” kata Wisnu.
Penulis: Arbi Sumandoyo
Editor: Fahri Salam
















