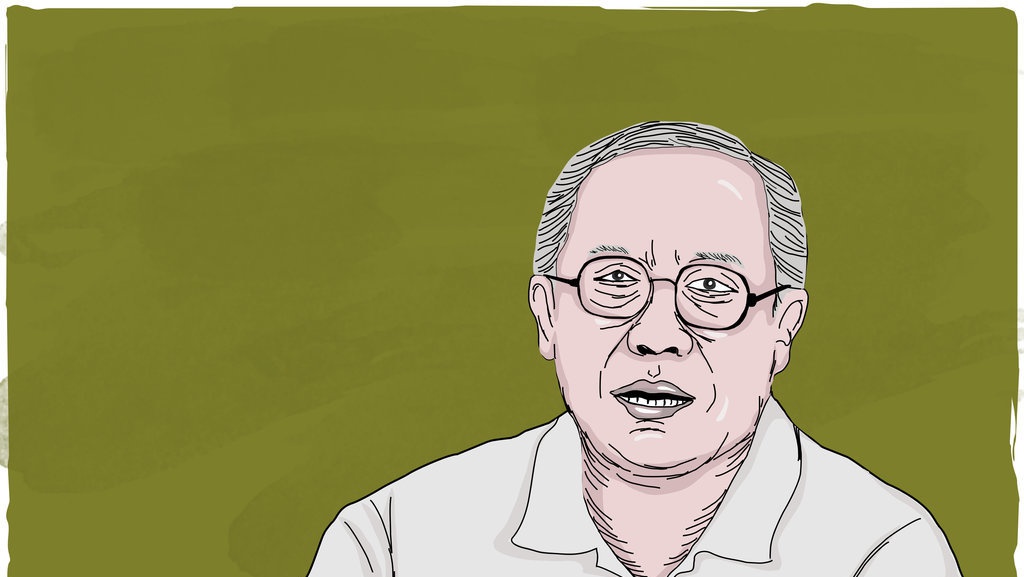tirto.id - Ketika para pembuat film hari ini dididik di sekolah film, para maestro film Indonesia dari dekade 1970-an rata-rata otodidak. Karier mereka berawal dari menyutradarai lakon panggung, menulis novel, atau jadi kacung produksi.
Generasi yang lebih awal memulai karier dari kelompok-kelompok sandiwara pada era pendudukan Jepang, atau lebih lawas lagi, dari panggung-panggung peranakan Tionghoa. Pada dekade-dekade setelahnya, tatkala film Indonesia berjaya di bioskop, magang menjadi saka guru pendidikan film.
Pada 1990-an, angka produksi film nasional anjlok. Situasi ini beriringan dengan boom televisi swasta yang membuat orang-orang film hijrah ke televisi. Segelintir yang masih bertahan membuat film-film seksploitasi, atau bersiasat dengan bermain di gelanggang festival internasional—Garin Nugroho, misalnya.
Antara 1999-2001, Petualangan Sherina, Ada Apa dengan Cinta, dan Jelangkung meledak di pasaran dan dirayakan sebagai momentum kebangkitan film Indonesia. Para kreatornya didapuk sebagai pembaharu dan latar belakang mereka menandai situs-situs baru tempat pengetahuan tentang produksi audio-visual berkembang: Industri iklan, video musik, dan sekolah film.
Windu Jusuf dari Tirto menemui JB Kristanto, kritikus film senior dan penulis Katalog Film Indonesia 1926-2007 (1995). Pada 2011, Om Kris—demikian panggilan akrabnya—dan beberapa kawan muda menggagas Film Indonesia, suatu platform digital berisi data, kajian, dan katalog film Indonesia yang pernah ia terbitkan dalam bentuk buku. Meski telah berhenti beroperasi beberapa waktu lalu, situs itu tetap menyuguhkan data penonton teranyar, film terlaris, dan film-film yang segera rilis. Ditemui di kediamannya, Om Kris sedang menunggu laporan dari jejaring bioskop-bioskop besar untuk diunggah ke situs.
Dalam perbincangan selama satu jam, ia membahas sutradara, sekolah film, regenerasi yang kerap kali terputus, serta sulitnya film Indonesia membicarakan masyarakat.
Sebelum marak sekolah film seperti sekarang, bagaimana para pembuat film Indonesia dari generasi terdahulu dididik?
Sekolah film yang resmi itu dulu, kan, cuma ada satu: IKJ (Jurusan Film dan Televisi, Institut Kesenian Jakarta). Sekarang ISI (Institut Seni Indonesia) Yogyakarta buka jurusan media rekam. ISI Solo, saya enggak yakin betul ada apa enggak. Ini yang formal-formal.
Tapi juga, seingat saya, IKJ baru mulai tahun 1970-an dan baru menghasilkan alumni 5-6 setelahnya. Itu pun tidak banyak pengaruh. Artinya, ia menyumbang tenaga, teknisi. Tapi tidak banyak berpengaruh. Sistem yang lebih besar yang berlaku pada “industri” film sejak 1930 adalah magang.
Maksudnya tidak berpengaruh pada kualitas film-film yang dihasilkan?
Iya. Dan juga tidak berpengaruh pada industri itu sendiri. Tidak banyak yang memberi warna baru di penyutradaran. Kalau teknisinya lain. Mereka, kan, ikut aja. DOP [Director of Photography], editor, art director, tidak terlalu berpengaruh dalam memberi warna atau memberi pemikiran.
Sampai tahun 1990-an, orang belajar bikin film lewat magang, jadi asisten sutradaranya Wim [Umboh], jadi asisten sutradaranya Sjuman [Djaja], Teguh [Karya], Arifin [C. Noer]. Saya lupa ya asisten-asistennya Wim itu ada yang jadi apa enggak. Tapi dari Wim, ada beberapa: Bobby Sandy, misalnya. Dari Teguh jelas ada Slamet [Rahardjo]. Dari Sjuman ada beberapa: ada Jasso Winarto. Ada juga yang seperti Edo [Edward Pesta Sirait] yang jadi asisten beberapa sutradra: ya Sjuman, ya Wim, dan seterusnya.
Enggak seperti Jepang. Jepang itu kalau kamu sudah ikut satu sutradara, kamu akan ikut terus. Misalnya Kurosawa, sampai kamu jadi sutradara, ya kamu akan terus ikut Kurosawa. Di sini enggak seketat itu. Sjuman, kan, ganti-ganti asisten. Dia enggak punya grup. Tapi kalau Teguh Karya, dia punya sanggar: Nano [Riantiarno], Slamet Rahardjo, George Kamarullah. Jadi sistemnya seperti itu.
Lalu pernah di KFT (Karyawan Film dan Televisi) dibikin semacam seleksi. Asisten yang mau jadi sutradara harus memenuhi syarat. Misalnya lima kali jadi asisten. Kalau mereka mau jadi sutradara, mereka harus bilang ke KFT: “Gue mau jadi sutradara, nih.” Lalu diuji oleh KFT. Salah satu ujiannya, tiga film yang pernah dia asisteni diputar, terus dia ditanya-tanya. Kalau boleh ya boleh. Kalau enggak ya enggak.
Seketat itu metode seleksinya?
Ada periodenya. Tahun 1980-an kalau enggak salah. Nah, sampai tahun 1990-an, saya tidak melihat ada sumbangan dari IKJ. Lalu tiba-tiba muncul Garin (Nugroho). Garin ini kayak jadi pembatas, antara angkatan di bawahnya dan angkatan sesudahnya.
Maksud anda pembatas antara angkatan magang dan angkatan sekolahan?
Garin enggak pernah magang. Sebelum dia bikin film cerita, dia bikin film dokumenter, bikin film pendek. Sejak awal sudah sutradara. Makanya dia jadi pembatas betul. Garin itu juga memberi warna. Bukan hanya karena sekolahnya, tapi karena orangnya, sih. Kan selalu ada yang kayak gitu. Bukan karena sistem.
Setelah Garin, muncul generasi yang pernah saya tulis secara pendek: generasi yang enggak ada hubungannya lagi dengan angkatan sebelumnya. Generasi 2000, yang kira-kira mulai berkarya tahun 1995. Tradisi mereka sama sekali lepas dari angkatan sebelumnya.
Apa penyebabnya? Apa karena film-film Indonesia sedang lesu dan orang-orang film pindah ke televisi?
Betul. Jadi televisi itu bersisian dengan film. Tahun 1988 stasiun tivi swasta lahir. Waktu itu masih pakai dekoder. Terus tahun 1993, SCTV, TPI, dan seterusnya muncul bareng. Ini yang bikin orang-orang film pindah. Terus ada juga jaringan bioskop XXI, yang kalau enggak salah berdiri tahun 1986, tapi mulai mencengkeram kuat tahun 1990-an. Bersamaan dengan itu pada 1991, 1992, produksi film drop dan membuat orang-orang film pindah ke televisi.
Pada waktu yang sama, XXI mulai mencengkeram. Ia mulai dengan monopoli distribusi film impor. Dengan monopoli itu ia bisa mendikte: “Lu mau ikut gue apa enggak?” Lama-lama bioskop-bioskop daerah mulai rontok. Apalagi di XXI, ada kualifikasi tertentu, kursinya harus kayak gini, layarnya harus kayak gini, dan seterusnya. Sehingga bioskop-bioskop di kota kabupaten (Dati II), yang tidak bisa memenuhi syarat-syarat itu, gulung tikar. Padahal di situlah wilayah pasarnya film Indonesia. Jadi itu semua saling pengaruh.
Lucunya, sekarang ini semuanya jadi terbalik. Orang-orang yang lari ke tivi sekarang balik ke film. Sebabnya, orang-orang di televisi bikin in-house production sendiri. Multivision, MD, Starvision dulu raja sinetron. Sekarang malah mereka yang menguasai film. Karena mereka sudah enggak punya ladang lagi di televisi.
RCTI dan SCTV, misalnya, bikin anak perusahaan yang mensuplai sinetronnya sendiri. Ini yang menurut saya menarik. Karena waktu mereka jadi supplier televisi, mereka dipaksa menjadi industri, frame of thingking-nya, sistem kerjanya. Penulis skenario dikontrak untuk sekian tahun, sekian judul. Supaya produksinya secure. Kalau enggak, nanti di tengah jalan sinetronnya bubar.
Keterbiasaan mereka dengan industri sekarang diterapkan ke film. Tadinya film itu kayak industri rumahan. Setahun produksi 1, 2, atau 3 film. Sekarang, Starvision bisa (produksi) sepuluh film per tahun. Jadi meskipun pelopor kembalinya film indonesia itu Mira [Lesmana], tapi yang berjaya ya bukan Mira.
Mengapa bisa begitu? Mengapa struktur industri ala Hollywood di sini—kita sebut saja begitu—justru dimulai dari sinetron?
Karena dipaksa. Dan mereka enggak tahu pilihan lainnya. Tahunya cara begini yang bener. Kalau saya lihat data-data penonton, Parwez (Chand Parwez Servia, pemilik Stravision) yang paling produktif, setahun bisa delapan atau sepuluh, kadang-kadang 100 ribu, 200 ribu penonton, tapi tiba-tiba Cek Toko Sebelah dapat 2,5 juta penonton. Nah, itu berarti jackpot-nya dapet.
Resepnya Parwez begini: Asal lu produksi kontinyu, lu enggak rugi secara keseluruhan. Jangan lihat judul per judul. Karena kalau dapat 200 ribu penonton, paling cuma dapat Rp3 milyar. Tapi kalau pun dia dapat tiga milyar dari tiket di bioskop, dengan 200 ribu penonton, dia masih punya hak jual untuk stasiun televisi. Itu sekitar satu milyar.
Bagaimana dengan pendapatan dari DVD?
DVD malah sepi, ya. Sudah dianggap bukan pasar lagi. Yang dianggap pasar sekarang televisi dan kanal-kanal internet: Netflix, Iflix. TV kabel seperti Astro juga.
Nah, kalau kembali ke soal pendidikan tadi, maka orang-orang setelah generasi Garin, seperti Mira dan Riri [Riza] juga jadi pembatas. Setelah Garin ada Riri dan Mira. Di luar mereka ini, ternyata banyak lagi yang sekolah di luar negeri. Mereka sekolah sekitar pertengahan 90-an dan generasi ini bener-bener putus dari generasi sebelumnya. Dari IKJ sekarang hampir kita enggak dengar, ya. Tapi teknisi tetap dari situ: DOP, editor, sound. Tapi sutradara enggak.
Bagaimana dengan Edwin Babibuta?
Artinya, kan, cuma Edwin di IKJ. Tapi sekarang muncul generasi yang juga bukan sekolahan. Lumayan-lumayan, lho. Makassar, Yogya. Dari Belitung ada, dari Batam ada, dari Pontianak ada. Tapi yang bunyi dua: Makassar dan Yogya. (Edwin, sutradara Babi Buta yang Ingin Terbang)
Yang bunyi sampai ke Jakarta?
Katakanlah bunyi secara nasional. Dan lucunya dua tempat ini punya sikap yang bertolak belakang. Yang Makassar orientasinya komersial, mainstream. Film-filmnya sebisa mungkin populer. Bahkan ada satu judul Uang Panai' itu sampai 500 ribu penonton. Silariang dapat 226 ribu penonton. Hitung-hitungannya, untuk satu produksi yang dikerjakan oleh orang Makassar sendiri, pasti sudah untung. Pernah ada satu-dua judul dulu di tahun 1970-an tapi enggak banyak. Yang sekarang di Makassar itu dari komunitas.
Ini beda dengan di Yogya. [Ismail] Basbeth, Yosep [Anggi Noen], Siti, Turah … mereka punya orientasi beda sama sekali. Tapi orang-orang ini, katakanlah Ifa [Isfansyah], dia yang paling komersial, tapi dia sekarang bantu teman-temannya di Four Colours.
Saya tanya, Siti itu untung. Anggaran produksinya 150 juta. Dapatnya di atas 200 juta. Yang menarik Turah ini. Dia diputar di komunitas-komunitas. Targetnya Ifa, sampai lebaran nanti ada 50 titik pemutaran. Harga karcis Rp20 ribu. Saya tanya ke Ifa: Duit masuk? Masuk, katanya. Itu menarik buat saya. Jadi, apa yang dulu dimulai oleh Konfiden, komunitas-komunitas film pendek—itu kan sekolahan juga—hasilnya baru kerasa sekarang.
Tapi ada problem klasik film Indonesia, yang sampai sekarang masih terlihat termasuk dalam film-film ini. Saya baru lihat setengah Turah. Tema sih, OK. Tapi masalah pengolahan tema itu jadi masalah. Keberatan saya terhadap Siti, Ziarah dan secara umum pada film Indonesia adalah masalah kedalaman. Ini juga kritik saya kepada anak-anak IKJ, dan kepada orang-orang yang sekolah di luar negeri. Mereka terampil membuat film, tapi tidak terampil berolah pikiran. Tidak cukup dibekali metodologi riset. Dulu sampai sekarang kelemahannya tetap itu. Tapi saya akan support betul orientasi Yogya. Karena, tanpa mereka, yang berani membuat film-film di luar arus utama, industri akan mati, harus dipelihara orang-orang ini supaya tetap hidup.
Lalu ada contoh menarik juga. Ernest Prakarsa. Dia enggak sekolah di mana-mana. Persinggungan dia dengan medium film sebelumnya sebagai bintang. Tapi giliran dia jadi sutradara, ngagetin itu anak. Apa yang ingin disampaikan film itu, nyampe semua. Memang masih banyak bolongnya secara teknis. Masih kagok di sana-sini. Cek Toko Sebelah kadang-kadang mau ngelucu tapi leluconya malah lebih kental dari alur utamanya. Nyimpang dulu baru balik lagi. Tapi di luar itu, Ernest menguasai medium sehingga dia bisa mengungkapkan apa yang dia mau. Sumbangan dia sama dengan sumbangan dia di stand-up comedy. Ngeledek Cina, karena dia Cina. Apa yang dianggap “eksklusif” dari kultur orang Cina, jadi lebih umum dipahami orang dengan cara itu. Menurut saya itu sumbangan. Dan itu nyampe. Ernest ini fenomena sendiri. Dia enggak dari mana-mana. Dia enggak sekolah film. Kalau udah begini, perlu enggak sih sekolah film? Perlu-perlu enggak, ya. Untuk teknisi ya perlu.
Bagaimana dengan sutradara dan penulis skenario?
Kalaupun sudah terlanjur masuk sekolah, ya, mungkin mesti lebih belajar metodologi riset, filsafat, logika, belajar sosiologi. Itu, kan, kritik saya terhadap Siti. Semua elemen dalam film itu jalan. Tapi saya tidak melihat ada satu masyarakat di balik itu. Saya tidak melihat interaksi cerita dengan lingkungan masyarakat. Turah juga begitu. Dia nemu satu desa atau satu wilayah yang dikuasai tuan tanah, tapi semua dia ungkapkan secara verbal. Struktur sosial dalam masyarakat itu enggak kita tangkap.
Ya, kalau kita mau contoh yang baik, coba lihatlah Godfather (Coppola, 1972). Itu semua struktur politik, ekonomi bisa kita lihat. Bukan berarti, untuk saya, film itu harus realis. Kamu mau surealis, kamu mau absurd silakan. Tapi kalau kamu punya pemahaman terhadap masalah betul-betul, lain jadinya.
Apa ini artinya film-film kita belum berhasil menawarkan imajinasi sosial tentang masyarakat Indonesia?
Jadi imajinasi sosial dalam film kita bisa dibilang imajinasi pembuatnya. Bukan yang riil. Ini penyakit yang sama dengan film-film tahun 1970-an. Karena itu enggak memahami masyarakat.
Film-film 70-an yang mana?
Film-film pop. Kecuali beberapa seperti Sjuman, ya. Di tangan Sjuman, film-film populer bisa lain jadinya. Kabut Sutra Ungu di tangan Sjuman, itu film cinta-cintaan. Tapi ada polisinya lah, korupnya lah. Apapun bentuknya, imajinasi yang riil dan yang tidak riil, dalam tanda petik riil. Kita bisa membaca masyarakat dari situ.
Salah satu kelemahan sekarang juga di film-film mainstream: enggak ada lagi hubungan sastra dan teater. Buku-buku sastra yang “baik”, katakanlah standarnya adalah sastra pemenang DKJ, tidak pernah dilirik oleh produser. Lucunya juga tidak pernah dilihat oleh anak-anak Yogya ini. Ya mungkin ada persoalan uang juga. Katakanlah novel Saman (Ayu Utami, 1998). Diangkat ke film mungkin akan jadi mahal. Kalau mau murah, ya jangan novel itu. Jadi saya enggak bisa nyalahin juga.
Tapi maksud saya begini: Pergaulan antara orang film dan orang sastra juga enggak ada. Padahal dari sejak zaman Usmar [Ismail, 1921-1971], sejak zaman Nyak Abbas Acup [1932-1991], sejak zaman Sjuman [1934-1985], dua komunitas itu akrab. Nyak Abbas itu nongkrongnya di TIM. Sjuman memang sastrawan juga sebelum jadi orang film. Dia termasuk seniman Senen. Misbach [Yusan Biran, 1933-2012]… Asrul [Sani, 1927-2004]… Ini kan orang-orang Perfini semua. Dikumpulin sama Usmar. Generasi yang paling baru ini kayaknya sudah lepas dari sastra dan teater. Bagaimanapun sastra dan teater itu, bukan hanya harus difilmkan, tapi kamu juga bisa menimba estetikanya. Kalau kamu akrab dengan itu, itu akan berpengaruh dalam diri kamu. Itu yang saya maksud.
Saya enggak yakin generasi filmmaker sekarang juga baca. Karena kalau baca, kok, enggak ada baunya, ya? Tapi secara pergaulan juga enggak. Garin orang terakhir yang pergaulannya masih luas. Dia ambil tradisi tari ke film, dia bergaul dengan filsuf-filsuf Indonesia. Tapi di luar Garin, kan, enggak ada. Kita boleh enggak suka dengan film Garin. Saya juga belum tentu suka semua film Garin. Tapi, kan, kelihatan ada pemikiran dan apa yang ada di balik filmnya.
Apa mungkin karena banyak dari angkatan 2000-an memulai karier sebagai pembuat video klip atau iklan?
Mungkin saja. Tapi, kan, itu soal teknis, bukan pemikiran. Yang saya persoalkan adalah pemikiran.
Bukan karena sastra yang dibaca lain?
Ya sastra pop. Yang jelas bukan sastra kanon.
Kembali lagi ke sutradara klasik. Teguh Karya besar di teater populer. Ada banyak pemainnya juga dari sana. Apakah di era itu komunitas sastra atau film juga berperan sebagai “sekolah”?
Menurut saya iya. Karena pergaulan, ya. Teguh, Rendra, Arifin. Itu tiga besar teater. Setelah itu muncul Putu [Wijaya], lalu Ikranagara. Tahun 1970-an Teguh, Rendra, Arifin saling bersaing dan saling bersahabat. Mereka anggota Dewan Kesenian Jakarta semua. Sebelum menulis naskah sendiri, Teguh mementaskan Ibsen, Tennessee Williams, naskah-naskah teater klasik dunia, sesuai dengan mazhab dia, mazhab realis, yang diteruskan oleh Jim Lim di Studiklub Teater Bandung. Bukan hanya sastra, tapi juga musik. Atau seni rupa. Tahun 2000-an seni rupa kita, kan, booming. Perkembangannya luar biasa. Tapi kok kayak enggak ada pengaruhnya ke film.
Perbedaan kelas juga penting. Mira dan Riri dari kelas menengah, seperti Garin juga. Tapi, kan, bukan kelas menengah atas. Rudi Soedjarwo, Nia Dinata, nah itu kelas menengah atas. Kalau kita lihat Arisan, film Nia Dinata, penggambaran kelas sosial di film itu tidak mungkin dilakukan oleh generasi 1970-an, yang melihat orang kaya dari jauh. Sehingga mereka kadang mikir, “Wah, orang kaya begini nih. Makanya pasti roti nih.”
Tapi bukannya Sjuman pada waktu itu juga membuat film-film dengan representasi kelas yang baik?
Betul. Karena dia bergaul dengan orang-orang itu. Dan Sjuman pun juga kelas menengah. Wim? Kacung. Betul-betul kacung. Memang dia akhirnya masuk ke kelas itu. Tapi, kan, kelihatan bedanya. Siapa lagi di luar itu? Ami Prijono? Dia memang kelas atas. Anak menteri. Arifin enggak pernah sih bikin film-film kayak gitu. Coba kalau bikin. Pasti kagok dia.
Dan ini generasi yang sekarang besar melalui sekolah film?
Nah, sekarang siapa sih yang bisa nyekolahin anaknya di jurusan film? Dan membiarkan anaknya sekolah film? Bayangin! Secara keterampilan, ya, mereka terampil. Tapi apakah mereka menyumbang pada Indonesia?
Di tahun 1940-an ada banyak sutradara yang lahir dari teater Jepang. Bagaimana dari tahun 1930-an?
Dari tahun 1930-an ada Anjar Asmara. Dari era The Teng Chun [pendiri Java Industrial Film, 1902-1977] dia udah ikut. Klub sandiwara lokal direkrut ke film. Ada The Teng Chun dan peranakan Cina lain yang memulai “industri film” di Indonesia.
Klub-klub sandiwara ini hanya memasok pemain saja atau juga teknisi?
Kalau teknisi waktu itu dari Tiongkok. Dari Shanghai. Ada juga yang pernah ikut produksi film di Hollywood. Tahun 1930-an itu film Indonesia banyak mengadaptasi novel-novel peranakan. Njai Dasima [Lie Tek Swie, 1929], Boenga Roos dari Tjikembang [Kwee Tek Hoay, 1927], Si Tjonat [Nelson Wong, 1929], itu semua kan dari novel peranakan yang muncul awal abad, jamannya Tirto Adhi Soerjo, Mas Marco. Lalu dari legenda-legenda Cina. Ti Pat Kay, Ular Putih. Nah produser-produser besar keturunan Cina ini sekarang habis.
Sejak kapan?
Sejak 2000-an ini. Mereka mungkin enggak siap dengan industri. Mungkin mereka enggak siap dengan industri, enggak ikut berbondong-bondong masuk ke televisi.
Penulis: Windu Jusuf
Editor: Fahri Salam
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id