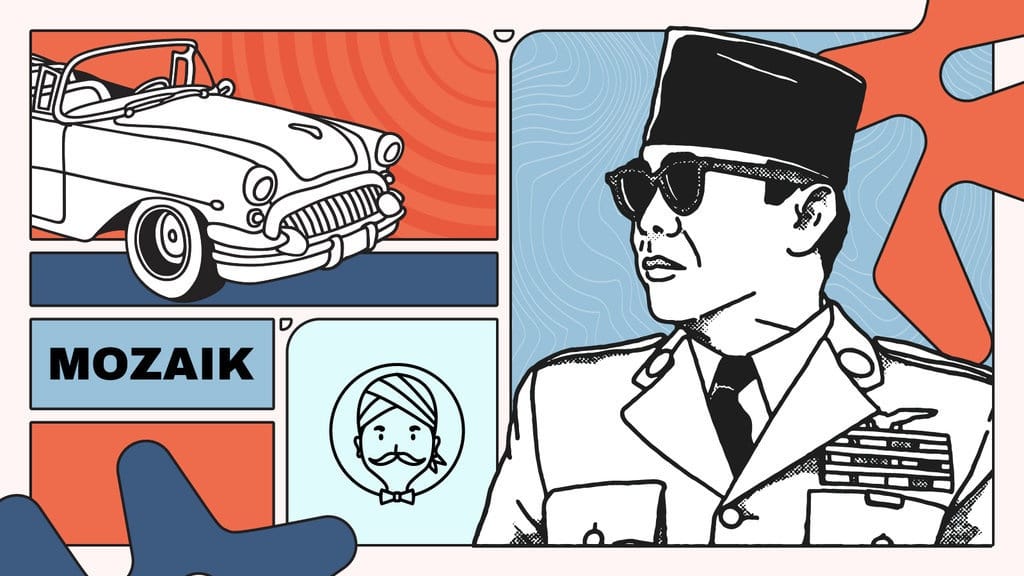tirto.id - Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia langsung melakukan hubungan dengan negara lain sebagai salah satu pondasi penting negara berdaulat.
Menurut Ida Anak Agung Gde Agung, Raja Gianyar sekaligus mantan Perdana Menteri Negara Indonesia Timur dan Menteri Luar Negeri Indonesia dalam Twenty Years Indonesia Foreign Policy 1945-1965 (1973), negara pertama yang melakukan hubungan dengan Indonesia adalah Inggris, lewat utusan yang dikirim dari Singapura.
Utusan itu adalah Jenderal Philip Christison, Panglima Tertinggi Sekutu (Commander of the Allied Forces), beserta serombongan pasukan bersenjata yang tiba di Jakarta pada Oktober 1945.
Dalam kedatangannya, seturut Ida, Christison meminta kepada para pemimpin Republik untuk membantunya dalam menjalankan tugasnya melucuti persenjataan Jepang.
"Ia (Christison) menganggap otoritas Pemerintah Republik Indonesia bertanggung jawab penuh atas administrasi dan ketertiban hukum di wilayah tersebut,” imbuhnya.
Ida menambahkan, tak jelas apakah Pemerintah Inggris tahu dengan tindakan yang dilakukan jenderalnya itu, yang kelas sikap Jenderal Christison bisa diartikan telah mengakui kekuasaan de facto Pemerintah Republik Indonesia.
Sayangnya, karena rombongan pasukan militer yang dibawa Jenderal Christison mengikutsertakan beberapa pasukan Belanda, hal ini tak diindahkan para pemimpin Republik, malahan menggiring terjadinya konflik bersenjata.
Pondasi yang Dibangun Sjahrir dan Hatta
Sadar bahwa pergerakan nasional Indonesia tak bisa dibendung, Pemerintah Inggris akhirnya mendorong Pemerintah Belanda untuk berunding soal Indonesia di Chequers (tempat tinggal Perdana Menteri Inggris di akhir pekan) pada 27 Desember 1945.
Pertemuan itu menyepakati bahwa Pemerintah Belanda harus mengakui hak rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka. Pertama-tama dengan melakukan perundingan damai Belanda-Indonesia untuk menyelesaikan sengketa .
Sebagai pemimpin Indonesia, Sukarno dicanangkan sebagai perwakilan Indonesia dalam perundingan damai yang disponsori Inggris. Namun, karena Sukarno memiliki riwayat hubungan baik dengan Jepang, maka beberapa pemimpin Republik tak sepakat.
Dimotori Sutan Sjahrir, sejumlah pamflet disebar dengan tulisan, “Revolusi kita harus dipimpin kelompok revolusioner dan demokratis, bukan oleh kelompok-kelompok nasional yang membiarkan diri mereka digunakan sebagai kaum fasis, baik kaum fasis kolonial Belanda maupun kaum fasis militer Jepang.”
Situasi ini membuat Sukarno mengalah dan mendaulat Sjahrir sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri sejak 14 November 1945.
Diwakili Sjahrir, perundingan tersebut dilaksanakan. Dan di tangan Sjahrir pula hubungan diplomatik pertama dilakukan Indonesia, yakni dengan India—kala itu tengah berjuang memperoleh kemerdekaan dari Inggris.
Hal ini tak lepas dari hubungan manis antara Mohammad Hatta dan Jawaharlal Nehru yang mulai terjalin sewaktu keduanya tinggal di Eropa untuk menimba ilmu dan sama-sama menghadiri League of Oppressed Nationalities di Brussels, Belgia, pada 1927.
Sjahrir yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, akhirnya menjadi sosok utama di balik pembangunan prinsip-prinsip hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain.
Dalam pidatonya di India, Sjahrir mengimbau bangsa-bangsa Asia yang dipersatukan oleh kepentingan bersama untuk menjalin persahabatan dengan bangsa-bangsa lain, agar visi Satu Dunia dapat terwujud.
Hal ini menurut Sjahrir hanya dapat dicapai dengan hidup berdampingan secara damai, dan upaya semua bangsa untuk memelihara perdamaian dengan memperkuat ikatan yang ada di antara berbagai ras dan bangsa di dunia.
"Dari pernyataan tersebut dapat diambil petunjuk awal mengenai prinsip-prinsip dasar politik luar negeri Indonesia, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk yang lebih positif, dikenal sebagai non-alignment demi melakukan pencarian perdamaian yang positif,” tulis Ida.
Namun, karena kekuasaan Sjahrir jatuh pada Juli 1947, prinsip dasar diplomatik Indonesia berubah menjadi lebih kiri seiring naiknya Amir Sjarifuddin sebagai Perdana Menteri.
Tak lama kemudian, prinsip hubungan luar negeri Indonesia kembali ke prinsip lama dengan sedikit perubahan setelah Amir Sjarifuddin jatuh dan digantikan Mohammad Hatta.
Dalam pidato bertajuk "Mendajung di Antara Dua Karang", Hatta menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia berpandangan posisi yang harus diambil adalah tidak boleh menjadi pihak yang pasif dalam kancah politik internasional, melainkan harus menjadi agen aktif yang berhak menentukan pendiriannya sendiri.
"Politik [luar negeri] Republik Indonesia bukanlah politik netral, karena ia dibangun bukan untuk negara-negara yang berperang, tetapi bertujuan memperkuat dan menegakkan perdamaian. Indonesia tidak memihak antara dua blok yang berseberangan dan mengambil jalannya sendiri dalam menghadapi berbagai masalah internasional,” tegasnya.
Di tangan Hatta, politik luar negeri non-alignment akhirnya bertransformasi menjadi politik luar negeri bebas dan aktif.
Simpati Negara Sahabat dan Haluan yang Bergeser ke Kiri
Sebagai turunan dari prinsip yang dicanangkan Sjahrir, Indonesia berupaya membentuk perwakilan politik di sejumlah negara untuk memperoleh legitimasi dan pengakuan lebih kuat di panggung dunia.
Langkah ini di antaranya dengan mengirim Sudarsono ke India sebagai duta besar, Usman Sastroamidjojo ke Australia, Idham ke Pakistan, dan Haji Rashidi ke Mesir untuk menjadi perwakilan di negara-negara Jazirah Arab.
Pengiriman sejumlah duta besar ini akhirnya membuat Indonesia memperoleh bantuan untuk mempertahankan kemerdekannya. India misalnya, tak segan membuka kedutaan di Yogyakarta yang berfungsi juga sebagai "kantor pos" untuk mengirim dan menerima segala kebutuhan Indonesia dari dan menuju luar negeri.
Dari bantuan India pula, diselenggarakan kanal radio khusus untuk menyebarkan informasi tentang Indonesia kepada dunia.
Melalui prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, PBB akhirnya turun tangan dalam menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda yang dianggap sebagai kemenangan dalam dunia diplomatik Indonesia.
Melalui campur tangan PBB, muncul pernyataan "You are what you are" dari Frank Graham sebagai perwakilan Amerika Serikat dalam komite bentukan PBB. Ini adalah petunjuk bahwa Indonesia merupakan negara berdaulat.
Prinsip politik luar negeri ini terus-menerus dipraktikan Indonesia hingga beberapa tahun usai penyerahan kedaulatan pada 1949.
Namun, karena penyerahan kedaulatan tak mengikutsertakan Papua Barat sebagai bagian integral Indonesia, Sukarno akhirnya mengambil alih seluruh kekuasaan Indonesia dalam kerangka Demokrasi Terpimpin. Sejak itu, Sukarno menjadi satu-satunya kekuatan yang tak tertandingi di panggng politik Indonesia.
Sukarno, seturut Ida Anak Agung Gde Agung dalam Twenty Years Indonesia Foreign Policy 1945-1965 (1973), kemudian menyusun formula politik luar negeri Indonesia dan menyebabkan penyimpangan secara bertahap meski prinsip dasarnya tetap bertahan.
Tindakan Sukarno mengambil alih kekuasaan secara mutlak dilakukan karena pasca kebijakan luar negeri dikendalikan Hatta, para penerusnya yakni Natsir (1950), Sukiman (1951) dan Wiloppo (1952) dianggap tidak bisa berdiplomasi dengan apik dalam persoalan Papua Barat untuk kepentingan Indonesia.
Tidak ingin masalah Papua Barat tenggelam dalam perbincangan dunia dan Indonesia tertinggal memainkan peran internasional, Sukarno akhirnya bertindak. Dalam "Navigating a Turbulent Ocean" (Asian Perspective, Vol. 31 2007) yang ditulis Paige Johnson Tan disebutkan, arah politik luar negeri ala Sukarno lebih memihak pada Blok Timur, pada Uni Soviet, dengan selubung non-Blok.
"Sukarno memandang kekuatan komunis di negara berkembang sebagai kekuatan yang paling progresif secara global,” tulis Tan.
Sukarno hendak menjadikan Indonesia sebagai mercusuar dari Negara Ketiga.
Terlebih, langkah ini dilakukan karena Amerika Serikat sebagai kekuatan utama Blok Barat, setelah kekuasaan berpindah tangan kepada Presiden Dwight D. Eisenhower, menjadi kurang simpatik terhadap Indonesia.

Internasionalisme dan New Emerging Forces
Sebelum kekuasaan mutlak benar-benar digenggamnya, usaha Sukarno menjadikan Indonesia mercusuar Dunia Ketiga dilakukan dengan bersafari ke negara-negara yang sepaham dengan Indonesia.
Pada 1950, ikhtiar ini dilakukan dengan mengunjungi India untuk bertemu Nehru. Lalu dilanjutkan ke Pakistan dan Myanmar, dan berakhir pada 1952 dengan mengunjungi Filipina. Dalam kunjungan ini tercipta kesepahaman bersama bertajuk Treaty of Frienship.
Kesepahaman bersama ini kemudian berlanjut dengan terciptanya asosiasi kerja sama antara negara-negara Asia dan Afrika. Pada 1955, kerja sama ini diteruskan dalam bentuk Konferensi Asia-Afrika di Bandung.
Sadar bahwa Indonesia terlalu penting untuk dicampakkan, sementara haluan politik luar negerinya lebih condong ke kiri, maka sebagaimana ditulis Robert Alden dalam "Bung Karno Pays Us a Visit" (arsip The New York Times, 13 Mei 1956) Amerika Serikat hendak menjinakkannya.
Lewat John Foster Dulles, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Sukarno diajak mengunjungi Paman Sam pada 1956, yang menjadi awal dari rangkaian perjalanan presiden ke luar negeri pada tahun-tahun berikutnya.
Sukarno kemudian mengunjungi Rusia, Cekoslovakia, Yogaslavia, dan China.
Memasuki dekade baru, Sukarno melanjutkan kunjungannya ke Afrika, tepatnya ke Maroko dalam rangka meresmikan nama jalan sharia Al-Rais Ahmed Sukarno. Juga memberikan bantuan senilai $10.000 untuk korban gempa yang mengguncang negara tersebut.
Pada 1961, kunjungan berlanjut ke Belgrade, Serbia, dalam upaya lebih jauh yakni pendirian organisasi pesaing PBB, Conference of New Emerging Force (CONEFO). Kala itu, bagi Sukarno PBB sudah tidak relevan terutama karena membiarkan Inggris membentuk "boneka" bernama Malaysia.
Saat berkunjung ke Belgrade, jalinan Indonesia dan negara-negara Afrika yang lebih dalam terbentuk, misalnya dengan Ethiopia yang kala itu dipimpin Kaisar Haile Selassie.
Setelah pembentukan CONEFO, Sukarno lalu bersafari mengunjungi 14 negara di Timur Tengah dan Afrika, dalam rangka menggelorakan Indonesia sebagai mercusuar Negara Ketiga, mencoba merebut status yang dimiliki India.
Menurut Roekmito Hendraningrat, mantan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Jepang, dan Pakistan, dalam "Some Aspect of Indonesia Foreign Policy" (Pakistan Horizon, Vol. 18 1965), politik luar negeri Indonesia kemudian bertransformasi menjadi internasionalisme.
Maka itu, Indonesia mencoba ikut serta menyelesaikan masalah-masalah dunia, misalnya soal krisis Suez, Hungaria melawan pendudukan Rusia, dan Perang Korea.
Di luar kegagalannya menengahi konflik Hungaria dan Rusia, safari Sukarno ke negara-negara Afrika berhasil memaksa Benua Hitam bersuara nyaring soal Perang Korea dan Terusan Suez guna mendorong dunia internasional lebih peka dan gesit mengurus masalah ini.
Prinsip internasionalisme, seturut Roekmito, kemudian memunculkan konsep New Emerging Forces sebagai landasan yang kokoh bagi hubungan internasional yang dirancang untuk mendukung terbentuknya tatanan dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id