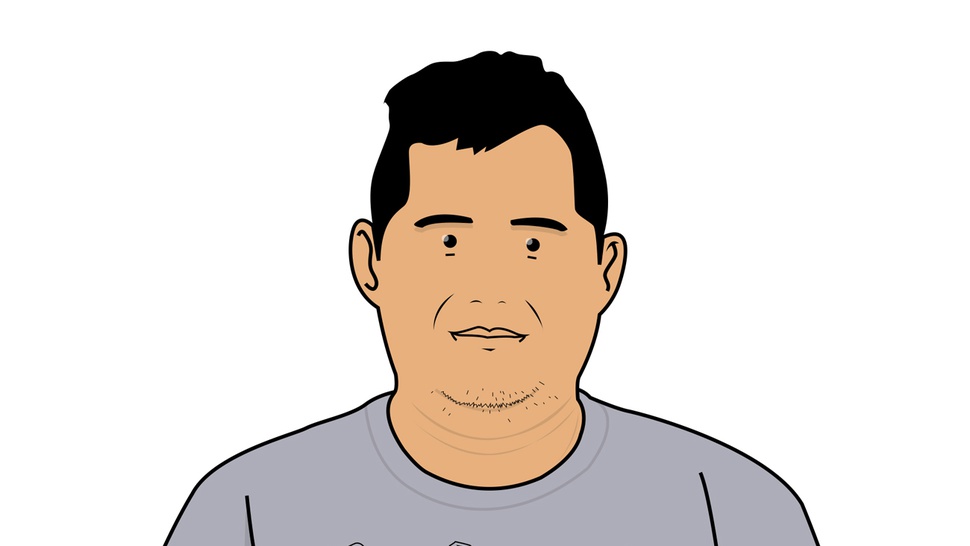tirto.id - Usai Trump terpilih sebagai presiden, wajah keberagaman Amerika dirundung mendung, muram, dan tak berwarna. Kelompok minoritas seperti LGBTQ, imigran Suriah, Hispanik, Afrika-Amerika, dan Muslim menjadi takut. Siar kebencian dan gelombang ancaman kebijakan rasis, yang dipertontonkan Trump selama kampanye, bikin mereka resah.
Serangan dan ujaran kebencian itu meningkat, dan tambah mengerikan karena tak cuma menyasar kelompok minoritas, melainkan pula terhadap mereka yang menolak menunjukkan kebencian. Orang-orang Demokrat dipojokkan; mereka kerap mengalami diskriminasi, verbal maupun fisik. Swastika ditorehkan di dinding rumah dan taman, serta kelompok minoritas diserang. Apakah Amerika diam saja? Tentu tidak. Banyak kelompok masyarakat sipil yang kemudian bergerak, melindungi mereka yang ditindas.
Beberapa pejabat Amerika yang paling awal merespons ketakutan ini adalah wali kota New York Bill de Blasio dalam satu acara resmi pada 21 November lalu. Di hadapan perwakilan masyarakat termasuk kelompok imigran, LGBTQ, dan Muslim, ia mengatakan bahwa Kota New York akan menjadi model dan pionir dalam melawan kebencian. De Blasio, seorang Demokrat, bersumpah akan membuat perlawanan legal apabila pemerintah federal mewujudkan rencana pendataan umat Muslim. Ia berjanji melindungi setiap keluarga imigran yang akan dideportasi. Ia bersaksi bahwa kebijakan yang menindas kelompok minoritas takkan pernah dibuat di kotanya.
Gubenur New York, Andrew M. Cuomo, sehari sebelumnya di Manhattan, di hadapan Gereja Baptis Abyssinian, juga mengungkapkan bakal membuat unit khusus untuk merespons dan menginvestigasi tiap laporan kejahatan berlatar kebencian terhadap kelompok minoritas. Ia juga berjanji mengembangkan regulasi dan jaminan perlindungan hukum yang berpihak pada kemanusiaan.
Pada 8 Juli di Texas, kelompok masyarakat sipil segera bergerak saat masjid dan pusat pendidikan Islam setempat mendapatkan ancaman. Sehari sebelumnya lembaga Islam itu menerima serangan senjata api dari orang asing. Pelbagai orang dengan bermacam latar belakang datang; ada yang berkulit putih, hitam, Hispanik, Asia, dan warna-warni keyakinan. Mereka mengelilingi lokasi tersebut. Mereka membentuk tembok manusia untuk melindungi umat Muslim yang menjalankan salat Jumat.
Mengapa mereka, kelompok mayoritas di Amerika ini—yang bukan Muslim, bukan Hispanik, dan bukan imigran—perlu membuat peraturan yang melindungi kelompok minoritas?
Jawabannya mungkin bisa kita temukan dalam risalah klasik pemikiran Islam. Kalifah keempat Imam Ali bin Abi Thalib berkata: “Mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan.” Wali kota dan gubenur New York bukanlah Muslim; mereka mungkin tak mengenal Imam Ali, tetapi apa yang mereka lakukan mencerminkan apa yang diperjuangkannya. Itu adalah nilai toleransi yang lahir dari kemanusiaan.
Ini bukan yang pertama. Di Swedia, masyarakatnya punya cara sendiri merespons kebencian. Saat kelompok masyarakat Muslim di negara itu diancam dan mengalami diskriminasi, penduduk Swedia datang dengan dukungan membela kaum minoritas. Kertas berbentuk hati ditempelkan di pintu masuk masjid di Uppsala beberapa hari setelah rumah Allah itu coba dibakar. Di antara masyarakat yang menunjukkan solidaritas adalah Ardalan Shekarabi, Menteri Pelayanan Publik Swedia. Ia menjelaskan bahwa semua warga di Swedia berhak mengalami rasa aman tanpa memandang keyakinannya.
Setelah Swedia, mari kita mundur dua tahun di Palestina. Bagi seorang warga Gaza bernama Mahmud Khalaf, tak pernah sebelumnya ia membayangkan bakal melaksanakan salat di bawah pandangan patung Yesus. Tetapi itu terjadi, dan itu pengalaman yang aneh sekaligus ambigu. Mengapa? Sejak peperangan di Gaza, ia tak punya pilihan selain melaksanakan ibadah di gereja. Mahmud, seperti ratusan warga Muslim lain di kota itu, menjadi pengungsi dan berlindung di gereja. Pengalaman ini membuka matanya tentang umat Kristen.
Seperti kebanyakan orang yang terlahir sebagai Muslim, Mahmud punya persepsi personal terhadap umat dari agama lain. Ketika orang yang dianggap kafir ini memberikan tempat berlindung dan beribadah, pandangannya tentang konsep kafir berganti. Gereja Santo Porphyrius di Kota Gaza dihayati secara berbeda. Jika sehari-hari lingkungan sekitar gereja saling menyapa dengan ucapan marhaban, ucapan Assalamualaikum pun menjadi hal lazim. Baik Kristen maupun Muslim saling mendoakan satu sama lain.
Tidak hanya mengizinkan untuk menunaikan salat lima waktu, pihak gereja di Gaza mengizinkan rumah ibadahnya sebagai tempat melaksanakan Idul Fitri. Mereka beribadah di bawah dentuman bom dan serangan Israel, sekaligus membayangkan di suatu tempat korban-korban berjatuhan. Perayaan Idul Fitri atau Natal tidaklah berjalan ekslusif milik satu umat. Muslim dan Kaum Kristen saling mengucapkan harapan dan menjalani hari raya itu dengan perasaan berkabung terhadap para martir akibat serangan Israel. Betapapun kontrasnya, pemandangan itu tentu memberikan harapan.
Di Gaza, diperkirakan hanya ada sekitar 1.500 umat Kristen, sebagian adalah penganut Ortodoks Yunani. Sementara pengikut Islam aliran Sunni mencapai 1,7 juta. Tapi apakah kali itu saja umat minoritas Kristen melindungi dan mengayomi umat Muslim di Gaza? Ketika pemerintah Israel berencana merilis aturan pelarangan azan, masyarakat Kristen dan gereja-gereja di Palestina dan Israel merespons dengan cara paling anggun. Alih-alih membunyikan lonceng, gereja-gereja ini menyuarakan azan sebagai bentuk protes atas rencana Israel.
Di Yerusalem Timur, umat Kristen dan Muslim di bawah kendali Israel adalah kelompok yang sama-sama direpresi. Meski tidak sesusah dan seblangsak nasib umat Islam, kelompok Kristen di Yerusalem berkomitmen untuk saling membantu umat Muslim. Di Nazareth, kota suci bagi umat Kristen, pada satu hari usai larangan azan dikeluarkan, azan merdu pun dikumandangkan. Bisakah kita membayangkan ini di Indonesia?
Yousef Sa’ada, uskup gereja Katolik di Nablus, memprotes keras usaha Israel membungkam azan. Ia menyebut usaha itu sebagai tanda kebangkrutan etik dan moral serta politis pemerintah penjajah. Azan-azan di gereja itu dilengkapi spanduk bertuliskan “Menara kami tak akan pernah bisa dibungkam.” Solidaritas lahir tak hanya dari kelompok Kristen tapi juga masyarakat Yahudi yang menganggap Yerusalem adalah kota suci bagi semua agama Samawi.
Contoh lain. Kaum Muslim yang tinggal di London mendapatkan bantuan dari orang yang tidak terduga. Polisi terlatih berlatar belakang Yahudi ultra-ortodoks menawarkan bantuan untuk menjaga masjid-masjid mereka. Pada 2013, banyak masjid di London mengalami ancaman dan serangan. Inggris menjadi negara tidak ramah Muslim sejak ISIS naik dan banyak sentimen Islamofobia yang lahir dari retorika fasis.
Tapi apakah itu penting? Di Indonesia, negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, semakin hari semakin menunjukkan wajah mengerikan: penyerangan terhadap kelompok minoritas, pembubaran ibadah, dan secara eksplisit menunjukkan sentimen anti-toleransi. Umat Islam bahkan kerap kali lupa pada sejarah soal bagaimana Nabi memperlakukan orang yang berbeda keyakinan. Beberapa kali saya mencontohkan dan mencatat interaksi Nabi dengan kelompok non-Muslim lewat berbagai literatur dan sejarawan.
Karen Armstrong, sejarawan dan penulis agama-agama monoteisme dunia, pernah berkata bahwa Kanjeng Nabi Muhammad selepas membebaskan Mekkah dari kaum kafir, menghancurkan seluruh berhala di sekitar Kakbah. Beliau meminta umat Muslim yang hadir saat itu untuk mengganti seluruh kain dan mencucinya. Semua simbol keyakinan non-Islam dihilangkan kecuali gambar Bunda Maria di dalam Kakbah.
Banyak orang tak percaya atas klaim Armstrong itu dan menganggapnya pembohongan sejarah. Tapi bukan hanya Armstrong yang menceritakan kisah itu. Martin Lings, mualaf dan penulis biografi terbaik Nabi Muhammad, juga mengatakan bahwa saat peristiwa penaklukan Mekkah, seluruh gambar dan patung-patung yang berkaitan dengan berhala dihancurkan, kecuali gambar Bunda Maria dan bayi Yesus serta gambar yang diperkirakan perwujudan Nabi Ibrahim.
Martin Lings merujuk sumber kitab susunan Al-Waqidi berjudul Kitab al-Maghazi, dan menyandarkan diri pada kitab susunan Azraqi berjudul Akhbar Makkah. Azraqi adalah sejarawan awal Kakbah terkemuka. Kitab Azraqi jadi salah satu rujukan kalangan sejarawan yang ingin bicara tentang Mekkah dan khususnya Kakbah. Tetapi beberapa ulama terbaik Islam mengatakan bahwa Al Waqidi adalah orang yang tidak dapat dipercaya dan klaim-klaim yang ia berikan itu palsu, meski setidaknya ada dua penulis dunia dengan kredibilitas mumpuni yang mengutip kisah ini.
Saya acapkali berpikir: Mengapa kita susah sekali percaya dan kerap meragukan kebaikan Nabi Muhammad terhadap umat di luar Islam? Kisahnya yang menunjukkan toleransi kerap kali dipertanyakan kekuatan hadisnya, sahih atau daif. Namun bila ada cerita-cerita yang menunjukkan sebaliknya, materi kisah ini kerap disebarkan, tanpa ada upaya memahami konteks ayat atau hadis itu. Misalnya tentang perintah memerangi, menjauhi, dan tidak memilih teman dari kelompok non-Muslim. Ia jadi bahan yang seketika ditelan bulat-bulat tanpa ada usaha kritis dalam membaca.
Dalam kisah Sirah Nabawiyah atau Sejarah Hidup Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad mengizinkan para utusan Kristen Najran untuk melaksanakan salat di masjid. Lantas apa hak kita melarang orang lain beribadah di tempat lain?
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.