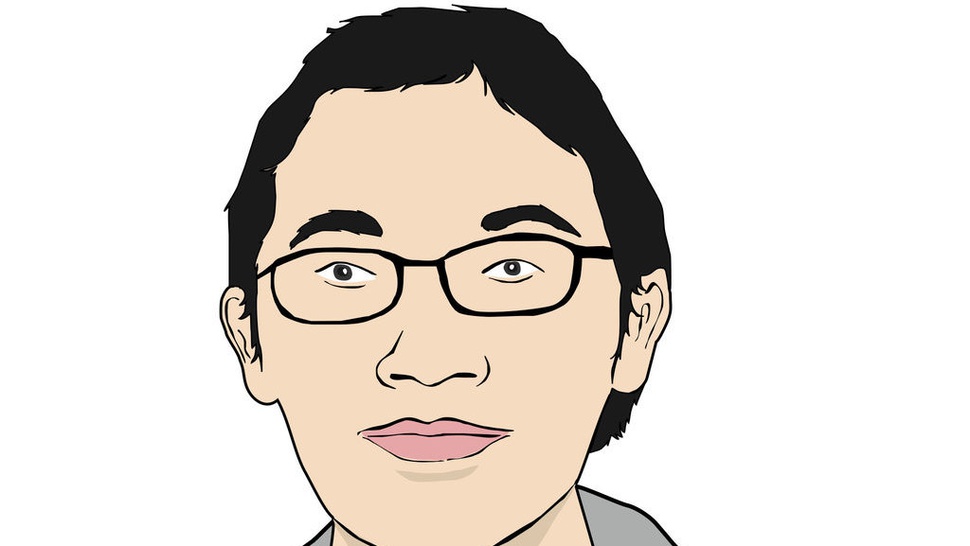tirto.id - Pada 1 Mei 2017, Yance Wenda, wartawan Tabloidjubi.com dan Koran Jubi, dipukul dan digiring aparat keamanan ke Kantor Polisi Resort Jayapura, Sentani, Kabupaten Jayapura.
Wenda sejak setahun belakangan ini adalah kontributor tetap Jubi di wilayah Sentani, yang ditugaskan menulis berita-berita seputar pendidikan dan kesehatan. Liputan-liputannya banyak menyoroti peristiwa menarik sehari-hari di masyarakat Papua yang luput dari perhatian publik.
Hari itu ia ditugaskan meliput kegiatan publik Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sebuah kelompok politik pro-kemerdekaan, yang memperingati 'Hari Aneksasi Papua' oleh Indonesia.
Namun nahas, saat ia memantau para anggota KNPB yang dibawa masuk ke kantor Polres Jayapura, sambil makan pinang dari sebuah kios, seorang polisi menghampiri dan menghardiknya.
Kacamatanya dibuka paksa, ditanya-tanya dengan nada intimidasi, tidak menghiraukan ketika Wenda menjelaskan bahwa ia wartawan dan berupaya menunjukkan surat tugas pers di dalam tasnya. Malah tas tersebut direbut.
Wenda digiring paksa ke kantor polisi, disuruh buka baju, dipukuli hingga memar di bagian belakang dan pelipisnya.
"Tiba di Polres, saya diperiksa. Disuruh bukan baju. Mereka tanya saya, saya bilang saya wartawan. Mereka periksa tas saya dan menemukan surat tugas saya," kata Wenda kepada Jubi.
Setelah mendapati surat tugas wartawan di dalam tasnya, baru kemudian Wenda dilepas. Ia ditahan kurang lebih 4 jam dari pukul 8.30 hingga 13.14.
Kapores Jayapura Gustav Urbinas membenarkan Wenda ikut ditahan, yang disebutnya "diamankan" karena, katanya, Wenda datang bersama simpatisan massa KNPB lain yang ingin mengecek rekan-rekan mereka yang telah terlebih dahulu "diamankan" di Polres.
Gelombang Penangkapan atas Aksi Politik Damai
Yang dialami Yance Wenda sebetulnya tidak terlalu mengejutkan bagi sebagian wartawan Jubi, khususnya wartawan asli Papua, baik saat bertugas di lapangan dan meliput langsung peristiwa aksi-aksi maupun kegiatan publik lain yang dilakukan oleh KNPB.
Wilayah Sentani adalah salah satu wilayah paling miskin peliputan dan pemberitaan jika sudah menyangkut aksi-aksi KNPB.
Setahun sebelumnya, 2 Mei 2016, hampir 2.000 simpatisan KNPB digiring ke Markas Komando Brimob Kota Jayapura saat menggelar aksi dukungan terhadap keanggotaan penuh United Liberation Movement for West Papua, organisasi pro-kemerdekaan Papua, di negara pelopor Melanesia (Melanesian Spearhead Group/ MSG).
Saya baru tiba sekitar 4 hari di Jayapura, dan langsung antusias untuk meliput peristiwa tersebut. Dalam pikiran saya, akan banyak sekali sisi-sisi berita yang tak mesti bombastis tapi bisa menunjukkan peristiwa apa adanya bagi pembaca di luar Papua yang tidak mengetahui situasi.
Belum kantongi kartu pers, hanya bermodal surat tugas, saya bersama B, seorang wartawan Jubi lain, berangkat dengan sepeda motor menuju titik aksi Sentani.
Dalam perjalanan menuju Sentani dari arah Abepura, kami berhenti di persimpangan Yoka saat melihat belasan truk tentara membawa ratusan massa KNPB. Sementara di titik itu juga sebagian aksi sedang berlangsung dan dikepung aparat keamanan.
Saya segera mengambil gambar dan mendekat ke arah massa sambil menyaksikan bagaimana aparat kepolisian menghampiri beberapa pemuda di sekitar aksi yang sedang memegang kamera dan mengambil gambar. Mereka meminta gambar-gambar itu dihapus, bahkan ada yang memaksa membuka tas dan merampas kamera.
Saya pikir, karena melakukan tugas-tugas jurnalisme sesuai hukum, maka saya akan aman. Tapi, sesaat menjelang meninggalkan tempat tersebut dengan sepeda motor, rombongan intel menghentikan kami. Beberapa di antara mereka saya ingat memang mengamati gerak-gerik saya saat beraktivitas tadi.
“Ambil gambar apa? Mana? Mana? Sini HP-nya,” ujar seorang di antaranya yang datang mengelilingi kami. Mencoba tetap tenang, saya jelaskan bahwa kami dari Tabloidjubi.com sambil saya menunjukkan surat tugas dan kawan saya menyodorkan kartu pers.
Namun mereka tidak peduli.
“Apa itu Jubi? Ini surat, bisa tandatangan palsu. Mana fotonya? Hapus. Hapus. Hapus,” kata salah seorang diikuti teriakan provokatif dari yang lain, memaksa menghapus foto-foto yang kami ambil.
Kami berupaya menunjukkan Koran Jubi yang kami bawa agar mereka melihat nama kami di dalamnya. Tetapi upaya itu sia-sia di tengah kerumunan yang, dari gelagat mereka, tidak memerlukan upaya dialog.
Saya tidak tahan untuk tidak merespons perlakukan mereka. Saya bilang: “Terus saja bapak-bapak lakukan ini, kami akan tulis, dan orang-orang akan baca begini perilaku aparat kepolisian di Papua pada wartawan. Tindakan bapak-bapak semua sedang disoroti di internasional, jadi harus mengerti bagaimana berdialog dan mendengarkan apa yang kami katakan.”
Untung saja, ada seorang intel polisi, orang asli Papua yang masih tampak cukup muda, datang dan melonggarkan kerumunan. Ia tampak menguasai keadaan dan mengatakan: “OK. Sudah. Sudah. Ade-ade jalan sudah. Jangan lagi di sini. Lain kali tidak perlu ambil gambar terlalu lama. Seperlunya saja. Sudah. Silakan jalan. Hati-hati."
Lalu kami pergi dan mengucapkan terimakasih kepada si polisi muda yang melerai itu.
Di Markas Brimob Jayapura, tempat ribuan aktivis KNPB ditangkap, kami mencoba meliput penangkapan itu. Namun kembali aparat mengatakan, “tidak bisa, wartawan tidak boleh masuk karena perintah atasan,” tanpa petugas tersebut menjelaskan apa yang dimaksud sebagai perintah itu.
Kami bertemu lagi dengan anak muda petugas intel asli Papua itu di Mako Brimob. Ia tersenyum dan saya ingat ia mengatakan: “Ade, sudah pulang saja. Tidak bisa. Nanti berbahaya buat Ade kalau memaksakan diri. Ini ditangani dari atas,” ujarnya pelan sambil melambaikan tangan.
Kami tidak lantas pulang. Tetap melanjutkan perjalanan ke Sentani, sesuai rencana. Di sekitar wilayah Pasar Lama, saya menyaksikan aparat keamanan sudah memblokade aksi KNPB dan bersiap mengangkut mereka ke truk kepolisian.
Saya ingin sekali menghampiri pusat demonstrasi tersebut dan melihat dari dekat. Namun seorang polisi berpangkat cukup tinggi yang sejak awal mengamati saya, segera menghampiri dan mengatakan: “Mbak, kalau mau meliput di sini saja. Tidak usah dekat. Tidak aman.” Ia berkata dengan nada dingin tanpa menjelaskan apa yang dimaksud sebagai "tidak aman."
Sejak peristiwa itu, saya menjadi paham bahwa aparat kepolisian di lapangan seringkali tidak senang terhadap wartawan yang mengambil gambar kegiatan aksi-aksi pro-kemerdekaan, sekalipun kami sudah menggunakan kartu pers.
Tatapan aparat sama sekali tidak nyaman (kalau tidak mengancam) saat wartawan memilih untuk mendekati kerumunan demonstrasi dan bertanya kepada para demonstran. Seakan-akan posisi yang disebut "aman" bagi wartawan adalah bersama aparat keamanan yang berjaga, dibanding bersama peserta aksi.
Sepanjang 2016, saya tetap berusaha di lapangan saat KNPB melakukan kegiatan-kegiatan publik.
Sebagai editor di Tabloidjubi.com dan Koran Jubi untuk rubrik Nasional, saya memang tidak punya kewajiban langsung untuk turun ke lapangan meliput peristiwa-peristiwa faktual. Namun, peristiwa penangkapan aktivis KNPB pada 2 Mei itu membuat saya memilih sebisa mungkin untuk hadir bila ada aksi politik damai dari KNPB.
Bagi saya, rasanya cukup aneh bahwa aksi-aksi yang melibatkan ribuan orang, dan kerap disertai penangkapan serta jadi berita di media-media asing, justru tidak serius diliput di negeri sendiri. Bukankah kegiatan jurnalisme salah satunya untuk mengangkat fakta dari peristiwa aktual menjadi berita?
Pada aksi KNPB, 15 Juni 2016, saya dan kawan B kembali meliput ke Sentani. Dan penangkapan, atau yang disebut polisi "pengamanan," kembali dilakukan kepada para aktivis KNPB. Kami ada di lapangan saat polisi mengangkut massa ke truk dan membawa mereka dari arah Pos 7 Sentani.
Saya berada di sisi jalan dan mengambil gambar penangkapan tersebut. Seorang polisi Sabara, yang tampak seperti komandan, memberhentikan mobil Sabara dan menghardik saya sambil melihat kartu pers yang saya kenakan.
“Tidak boleh meliput, mengerti tidak? Jubi ... Jubi apa itu?” kata dia.
Kami mengikuti massa hingga ke kantor Polres Jayapura. Saya hendak mengonfirmasi Kapolres soal penangkapan ini. Namun, di depan kantor polisi, kami bertemu kembali dengan polisi Sabara itu dan, tanpa basa basi, ia memerintahkan aparat membawa kami sambil mengatakan, “Ini dari tadi terus ambil gambar! Bawa lapor ke dalam dulu.”
Saya dan B dibawa ke dalam Polres, dan disuruh menunggu. Tampaknya, petugas tidak mengerti harus melakukan hal apa terhadap kami. Lalu Humas Polres Jayapura Imam Rubianto menemui kami. Ia meminta KTP saya untuk difotokopi.
Kami berbicara cukup lama. Ia menjelaskan semua wartawan di wilayahnya "terkoordinasi" dengan Polres, dan ia tidak mengenal kami. Saya jelaskan bahwa tugas saya di Jubi sebagai redaktur Nasional dan berhak melakukan peliputan di mana saja sesuai kebutuhan pemberitaan media kami.
Tidak ada peraturan yang mengharuskan kami melaporkan diri atau berkoordinasi, kata saya.
Kami kemudian dipersilakan pulang. Dalam perjalanan, saya jadi ingat dalam dua kali pemantauan saya terhadap aksi-aksi KNPB di Sentani, tidak tampak ada wartawan yang datang meliput.
Privilese sebagai Wartawan Melayu di Papua
Minimnya peliputan terhadap aktivitas terbuka mereka membuat saya cukup heran dan tertantang. Padahal aksi–aksi sepanjang tahun itu berlangsung sangat tertib, dengan massa ribuan yang jauh lebih teratur dibanding aksi-aksi di Ibukota Jakarta.
Selain itu saya juga merasa sedikit memiliki privilese sebagai jurnalis Melayu yang berstatus pendatang di Papua. Dari pengalaman selama setahun itu, saya menilai aparat kepolisian jauh lebih 'ramah' kepada saya ketimbang teman-teman seprofesi yang kebetulan orang asli Papua. Yance Wenda tidak 'seberuntung' saya.
Satu kali, bersama Arnold Belau, redaktur Suarapapua.com (yang diblokir oleh Kementerian Kominfo), saya meliput penggerebekan sekretariat KNPB Pusat pada 19 Desember 2016. Saya ditanya oleh seorang aparat kepolisian yang berpangkat cukup tinggi, yang mengamati kami mengambil gambar. “Tidak takut meliput bersama ‘orang gunung’?” ujarnya.
Waktu itu saya hanya memandangnya balik tanpa menjawab.
Di banyak kesempatan meliput aksi-aksi tersebut, saya merasa aparat memberi saya keleluasaan lebih ketimbang Yance Wenda, misalnya, atau kawan saya B dan Arnold Belau, yang ketiganya adalah wartawan asli Papua. Saya masih bisa berdialog cukup panjang dengan para sumber resmi, terutama dari aparat keamanan, di lapangan saat aksi-aksi berlangsung. Saya juga lebih mudah meminta komentar mereka melalui telepon terkait beberapa peristiwa kekerasan.
Beberapa di antara mereka sering memperingatkan saya untuk berhati-hati dan menjauhi dari massa demonstrasi. Padahal, sepanjang peliputan saya di lapangan, yang sering membuat gentar saya justru perilaku aparat keamanan terhadap wartawan, bukan sebaliknya.
Seorang simpatisan KNPB yang dibawa truk polisi pada aksi 15 Juni di Sentani menyaksikan saya mengambil gambar dari pinggir jalan. Posisi kami cukup dekat karena jalan dari Pos 7 cukup sempit. Tatapan matanya sama sekali tidak senang saat saya mengambil gambar itu. Namun saya tetap memotret.
Saya terus ingat tatapan itu ... hingga truk membawanya berlalu.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.