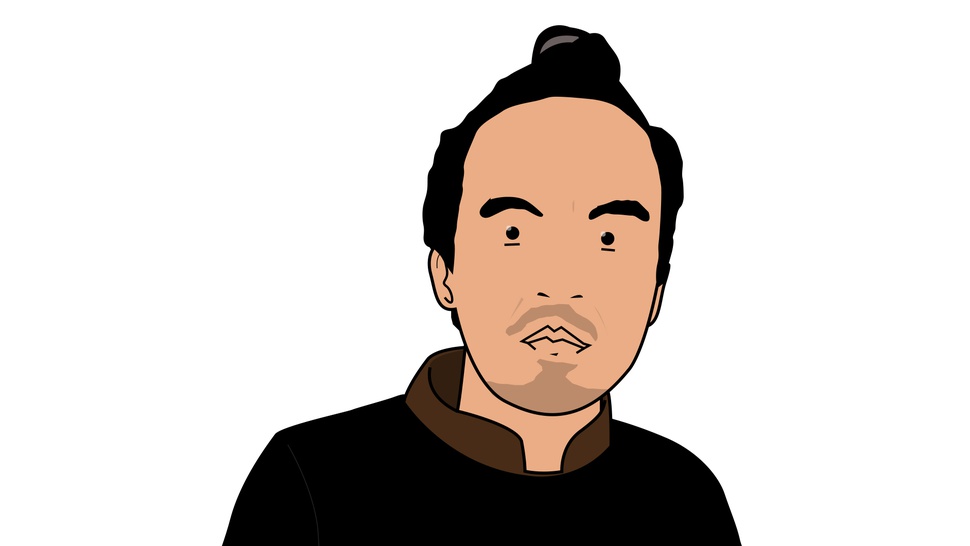tirto.id - desa ditumpas
traktor meremuk palawidja
pembesar mana akan berkabung?
Agam Wispi, “Latini”, Matinja Seorang Petani (Badan Penerbitan Lembaga Kebudajaan Rakjat, 1962, hlm 8)
Akhirnya, setelah bertarung habis-habisan selama bertahun-tahun di sawah, di jalan, dan di pengadilan, petani yang mengekalkan hidup dalam koloni Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah, keluar sebagai pemenang.
Mahkamah Agung pada 5 Oktober 2016 memenangkan gugatan perkara yang mereka ajukan lewat jalan Peninjauan Kembali (PK) setelah kalah di Pengadilan Negeri Semarang. Segala hal yang heroik yang dibayangkan orang dalam “negara-damai” sudah mereka lakukan: melawan tentara sewaan korporasi semen berbulan-bulan dalam tenda, melakukan long march ke pengadilan di Kota Semarang dan sekaligus memperlihatkan caping perlawanan kepada gubernur dari partai (baca PDIP) dengan ideologi marhaen yang makin ke sini makin aneh. Bahkan, di depan Istana Negara yang dihuni presiden dari partai yang menjadikan petani sebagai jualan ideologinya, sembilan perempuan petani ini menggelar “atraksi pertunjukan” dengan, ya Allah, mengikat kaki dengan cor semen.
Saya melihat kemenangan petani Kendeng itu menjadi alarm bahaya bagi partai yang mencampakkan substansi ideologi tani untuk semata meraih kekuasaan reguler di semua tingkatan. Sukarno menamai ideologi partai untuk hidup bersama kepentingan petani dan mengajeni orang miskin dengan marhaenisme. Oleh Sukarno, kaum ini disebut dengan penuh kebanggaan: Sokoguru Revolusi. Partai Nasionalis Indonesia digadang Sukarno menjadi rumah yang teduh bagi tani.
Di abad Mega, jauh setelah Sukarno tumbang dan PNI marhaenisme dikerdilkan oleh Jenderal Besar Soeharto, “marhaenisme” yang subversif itu bermetamorfosis menjadi "wong cilik" dalam satu pengertian yang sama dengan marhaen. Ideologi inilah yang terus-menerus dijejal-transimisikan ke semua kader di semua tingkatan pengaderan.
Namun, petani Kendeng mengonfirmasi seluruh bangunan ideologi itu dalam realitas praktiknya di lapangan. Bagaimana mungkin gubernur di Jawa Tengah yang menjadi "pangeran" dari wong cilik dan sokoguru revolusi ini alih-alih membela mereka, justru berada di sisi "netral", untuk tak menyebut berada di posisi korporasi. Bersikap netral dan membiarkan raksasa korporasi memakan lingkungan tani adalah kejahatan dan penistaan marhaenisme warisan Sukarno.
Bukan hanya itu, jika wong cilik dan marhaenisme adalah penisbahan pada mereka yang papah secara struktural, maka berada dalam barisan kepentingan kaum yang berada dalam rantai masyarakat terlemah ini adalah keniscayaan dan semestinya begitu.
Kenyataannya tidak. Bukan saja melempem dan bisu, justru wong cilik ini berhadapan vis a vis dengan partai ini dalam konteks perebutan hak hidup di banyak tempat; bukan hanya di Jawa Tengah, tapi juga Yogyakarta, Jakarta, Lampung, Jambi, Medan, hingga di banyak titik Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Memang, ada buntalan harapan menggelembung di dada tatkala Eva Susanti Bande dari Desa Bumi Harapan, Kecamatan Toili Barat, Banggai, Sulawesi Tengah, mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo setelah 61 hari berkuasa. Simak baik-baik kata-kata Presiden Joko Widodo di Gelanggang Olahraga Ciracas, Jakarta, Timur, pada 22 Desember 2014: “Jangan sampai ada lagi aktivis perempuan yang memperjuangkan haknya dan hak rakyat malah justru akhirnya masuk ke tahanan atau sel. Jangan ada lagi hal seperti itu.”
Jangan ada lagi, sebagaimana kata Presiden, berarti ada “moratorium” kekerasan atas para petani. Kenyataannya? Dalam catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2015 atau setahun setelah kekuasaan politik dipegang, konflik agraria malah makin stabil. Petani berhadapan dengan traktor-traktor infrastruktur dan keserakahan tambang dan perkebunan. Bukan hanya petani masuk bui, tapi juga menyerahkan nyawanya demi hak dan tanah, sebagaimana kematian Salim Kancil di Desa Selo Awar-Awar, Pasirian, Lumajang, Jawa Timur.
Kenyataan yang menggiring wong cilik berada ke titik suram itu tepat saat isu agraria dan kebijakan perkotaan kiwari menghempaskan mereka atas nama norma keindahan, pendapatan daerah, dan hukum formal. Mereka yang masih ingat dengan Perjanjian Marhaen yang ditandatangi Joko Widodo 138 hari sebelum dilantik menjadi Presiden RI itu mesti geleng-geleng kepala dengan peristiwa dalam larik puisi penyair Agam Wispi (1962: 7), "jika datang traktor, bikin gubuk hantjur". Negara harus hadir di setiap konflik, demikian salah satu butir Perjanjian Marhaen itu, menjadi omong-kosong ketika negara hadir justru—pinjam diksi penyair—sebagai traktor dan pelor bagi petani.
Ditempat keringat tertumpah
kaum tani membela tanah
Stop! padi ini api njawaku
djagung ini darah djantungku
kenallah aku, lebih teguh dari traktor
kenallah aku, lebih badja dari pelor
S. Anantaguna, “Jang Mempertahankan Tanah”, 1962, hlm 37
Bagaimana bisa evolusi ideologi marhaenisme yang diusung partai pewaris ajaran Sukarno ini mengalami pemajalan absurd yang dalam kenyataannya justru berada dalam satu sekutu dengan traktor dan pelor seperti ini?
Mabuk Kuasa: Ketika Partai Lupa Petani
Mabuk jenis ini betul-betul sangat berbahaya dari seluruh jenis mabuk. Oleh agama, mabuk kuasa ini terselenggara jika tiga karakter ini duduk semeja dan buka tutup botol bersama: karakter Firaun (kekuasaan eksekutif), Karun (korporasi/pengusaha serakah), dan Balam (ulama, cendekia, akademisi).
Ada tendensi jika partai yang menjual isu petani secara kasar dan rendah ini tak mendapatkan kekuasaan, galaknya luar biasa. Isu agraria dioplos untuk menunjukkan ke mana pendulum pemihakan.
Dalam kondisi “tanpa-kuasa” ini juga PDIP kita bisa catat dengan tinta bagus sebagai salah satu motor lahirnya UU Desa. Dana besar untuk pertama kalinya dalam sejarah sejak Reformasi dialirkan ke desa-desa. Namun, anak sungai uang masuk desa itu sama menggelegaknya dengan konflik agraria di dalamnya yang tak juga memperlihatkan arus surut. Nah, dalam arus pasang konflik tanah melibatkan marhaen itu, butir Perjanjian Marhaen bahwa negara (dan partai) hadir di sana menjadi anakronisme yang menyedihkan.
Demikianlah, mabuk kuasa mendorong orang menjadi galak kalau sedang paceklik kuasa politik dan berubah watak bila mendapatkan hak privelese mengatur hajat hidup orang banyak. Ketika fakir kuasa dalam ketiak militerisme Soeharto, partai ini berada dalam front perjuangan para petani; ia mendapatkan privelese sosial menjadi rumah ratu adil bagi pencari keadilan. Mulai dari Kedungombo, Nipah, Jenggala, hingga banyak pergelaran perlawanan di kantong-kantong orang miskin kota besar yang dialami buruh dan aktivis-aktivis kritis, partai wong cilik yang kemudian memakai embel-embel “perjuangan” di namanya agar bisa ikut pemilu tahun 1999 selalu ada dalam barisan.
Dan piramida besar wong cilik yang menjadi kurban politik Orde Baru menghadiahkannya sabuk juara saat palagan pemilu 1999. Partai ini merebut kemenangan dengan suara terbanyak karena rakyat tahu bagaimana membalas pembelaan, pemihakan, dan pemberi harapan hidup perbaikan takdir sosial atas diri mereka.
Pragmatisme yang kawin dengan keserakahan membuat ideologi marhaenisme majal di tangan para gadungan. Petani di Pegunungan Kendeng di Rembang dan sekitarnya yang dengan caranya sendiri justru memperlihatkan bagaimana korporasi dan petugas partai gadungan yang menjadi makelar marhaenisme berada dalam satu paket “si pemabuk kuasa” yang layak dilawan secara terbuka. Mendudukkan Gubernur Jawa Tengah satu paket “setan lingkungan” dengan pabrik semen dan dengan para akademisi di kampus adalah pemberitahuan bahwa menista petani dan wong cilik adalah penghinaan atas keadilan dan melempar ajaran Sukarno dalam kubangan busuk.
Lalu kita pun dengan sangat cemas menunggu datangnya apa yang disebut penyair T. Iskandar A.S. dengan “Traktor Maut” di Bumi Papua. Presiden Jokowi pada medio 2015 menjadikan Merauke sebagai “pusat pertanian pangan berbasis teknologi modern pertama di Indonesia”. Luas lahan yang disiapkan untuk proyek “kedaulatan pangan” itu 4,6 juta hektar yang mana 1/3 lahan tersebut diperuntukkan sebagai lahan sawah padi.
Demi kesejahteraan marhaen? Tunggu dulu. Lima bulan setelah pencanangan “pusat pertanian pangan berbasis teknologi modern pertama di Indonesia” itu, Presiden Jokowi melakukan perjalanan bisnis ke Amerika Serikat. Dan di sinilah, nama “Traktor Maut” itu muncul. Monsanto dan Cargill, dua nama “Traktor Maut” itu, digandeng Presiden Jokowi untuk “membereskan” tanah-tanah marhaen. Tahu atau pura-pura bego bahwa benih genetik, pestisida, agro-kimia, dan keseluruhan budaya agrokultural perusahaan Monsanto di seluruh dunia adalah alarm sangat berbahaya bagi harapan hidup sebuah generasi.
traktor itu datang lagi
atas suruhan tangan durdjana
melindasi ladang petani
T. Iskandar A.S., “Traktor Maut”, 1962, hlm 38
Traktor-traktor itu datang makin sering; bahkan secara resmi dipanggil petugas-petugas partai dalam kekuasaan. Penyair bilang, ada suruhan tangan "durdjana melindasi ladang petani". Sukarno lebih telengas menyebutnya: "marhaen gadungan".
Maka, ketika disebutkan nama politisi paling senior yang lahir dari trah Sukarno, sastrawan Pramoedya Ananta Toer yang menyerahkan afiliasi politiknya kepada Sukarno di tahun 60-an, hanya menggelengkan kepala dan mengibaskan tangan. Kata dia, “Jangankan membela kami ini (pendukung Sukarno dan peneguh marhaenisme), membela (kehormatan) bapaknya saja tidak bisa!”
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.